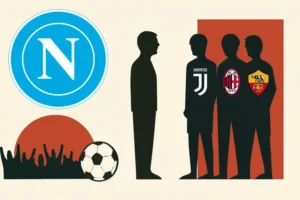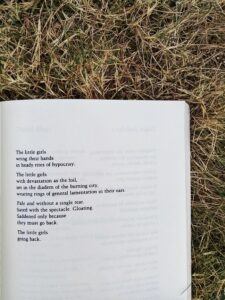Negara Mengarang: Ketika Sejarah Butuh Editor

Ada satu kalimat agung yang sering dikutip para pejabat ketika bicara tentang sejarah: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.” Kalimat ini begitu suci, sampai-sampai tak ada yang berani membantahnya. Namun dalam praktiknya, tampaknya kita justru bangsa besar yang senang menyunting sejarah. Barangkali kita terlalu menghargainya—hingga ingin memperbaikinya.
Kini, sejarah Indonesia tengah memasuki fase paling dramatis dalam siklus hidupnya: fase “penulisan ulang”. Pemerintah, melalui lembaga-lembaga berwibawa, memutuskan untuk memperbarui narasi sejarah nasional. Alasannya: ada banyak “lubang”, “distorsi”, dan “titik buta” dalam buku sejarah yang selama ini beredar. Bahkan, beberapa tokoh terkesan lebih berperan dari yang seharusnya, sementara tokoh lain tenggelam seperti data yang tak terarsipkan di Dapodik.
Apakah kita sedang membongkar kebohongan masa lalu? Ataukah kita sekadar mengganti aktor utama dan menulis ulang naskah lakon agar sesuai dengan selera zaman? Sejarah, sebagaimana kita tahu, adalah kisah tentang masa lalu—namun ditulis oleh pemenang. Kini, pemenangnya berganti, dan pena sejarah pun berpindah tangan.
Selamat datang di Republik Naratif: tempat di mana masa lalu tidak tetap, dan kebenaran bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan strategis nasional.
Mengapa Menulis Ulang Sejarah? Karena Bisa.
Tidak semua negara diberkahi dengan kemampuan seperti ini. Hanya negara-negara tertentu—yang memiliki kombinasi sempurna antara amnesia institusional, optimisme birokrasi, dan stamina wacana—yang mampu menulis ulang sejarah nasionalnya setiap beberapa dekade.
Di Indonesia, alasan penulisan ulang sejarah bisa beragam: untuk koreksi ilmiah, untuk kepentingan kurikulum merdeka, untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan, atau, yang paling jujur: untuk mengamankan narasi.
Banyak pihak mengklaim bahwa penulisan ulang ini penting agar generasi muda “tidak salah paham terhadap bangsanya sendiri.” Yang dikhawatirkan, tentu saja, bukan generasi mudanya, tetapi bangsanya sendiri. Karena sejarah yang terlalu jujur bisa membuat anak-anak sekolah bertanya, “Mengapa yang ini dipuja, padahal catatannya…”
Lalu, karena tak nyaman, sejarah pun harus sedikit didandani. Bukan dibohongi, tentu saja. Hanya dipoles. Seperti ketika seorang tokoh yang pernah dituduh korupsi disebut sebagai “sosok visioner yang menghadapi tantangan fiskal dengan cara-cara non-konvensional.”
Sejarah: Antara Versi dan Versus
Salah satu tantangan dalam menulis ulang sejarah adalah menentukan siapa yang layak ditulis, dan siapa yang sebaiknya dilupakan secara elegan. Seperti memilih foto keluarga yang layak dipajang di ruang tamu, sejarah pun harus selektif.
Masalahnya, setiap rezim punya selera estetika yang berbeda.
Di masa Orde Baru, sejarah kita bertema “kemuliaan negara” dan “bahaya laten”. Setiap musuh ideologi dipinggirkan, setiap perlawanan dimaknai sebagai ancaman. Namun kini, sejarah hendak direvisi: tokoh-tokoh yang dulu dicoret mulai dikembalikan dengan narasi yang lebih simpatik. Tapi ironisnya, pengembalian itu tidak disertai permintaan maaf kepada mereka yang sejarahnya sempat dihapus.
Sebaliknya, tokoh-tokoh yang sempat ditinggikan, kini mulai disorot dengan lampu yang lebih dingin. Kata-kata seperti “otoriter”, “anti-demokrasi”, dan “melanggar HAM” mulai bermunculan, meski masih dalam catatan kaki buku pelajaran.
Begitulah sejarah di negeri ini: bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang sedang memegang pena.
Guru Sejarah: Antara Bingung dan Berimprovisasi
Ketika kurikulum berubah, maka buku pelajaran pun berubah. Ketika buku berubah, maka guru sejarah berada dalam posisi pelik: apakah ia mengajar sesuai buku, atau sesuai arsip pribadi yang selama ini ia kumpulkan dengan penuh cinta?
Bayangkan seorang guru sejarah yang sudah 30 tahun mengajarkan peristiwa G30S dengan versi lama. Kini, versi baru memintanya untuk menekankan bahwa “sejarah adalah konstruksi.” Ia pun harus mengajar dengan gaya multiverse: “Anak-anak, versi yang dulu menyebut bahwa…, tapi versi revisi menyebutkan bahwa…, dan menurut sumber non-pemerintah…, sedangkan menurut novel sejarah populer….”
Murid pun bingung. Mereka mulai curiga: apakah sejarah ini semacam skrip sinetron yang berganti sutradara setiap lima musim?
Dalam kondisi ini, guru sejarah berubah menjadi semacam stand-up historian—bercerita dengan gaya jenaka, membandingkan versi, dan berharap murid tidak terlalu tersesat.
Sejarah Lokal: Ketika Pahlawan Tak Punya Sponsor
Penulisan ulang sejarah nasional sering kali menabrak sejarah lokal. Banyak pahlawan daerah yang namanya tidak masuk dalam buku sejarah nasional karena tidak cukup dikenal di Jakarta atau tidak memiliki dokumentasi audiovisual yang menarik.
Pahlawan yang viral lebih mudah masuk buku sejarah dibanding mereka yang hanya hidup dalam tradisi lisan.
Ada cerita tentang seorang pemimpin lokal yang melakukan perlawanan luar biasa terhadap penjajah, tapi karena tak ada foto resmi dan tidak pernah masuk film dokumenter, maka namanya tersisih dari daftar. Sementara tokoh lain yang punya dokumentasi lengkap, meski kontribusinya ambigu, justru diberi porsi dua halaman penuh.
Begitulah sejarah kita: siapa yang terdokumentasi, dia yang eksis. Ini bukan soal jasa, tapi soal siapa yang punya angle kamera terbaik.
Sejarah Sebagai Alat Listrik Negara
Ada anggapan bahwa sejarah hanya digunakan ketika ada krisis legitimasi. Ketika rakyat mulai bertanya, “Kenapa pemerintah begini?”, maka jawaban idealnya adalah, “Karena begitulah yang diajarkan sejarah kita.”
Sejarah menjadi semacam PLN: dipakai untuk menerangi kebijakan gelap. Ketika satu kebijakan terasa tidak masuk akal, maka dijelaskan dengan narasi sejarah. Misalnya: “Kebijakan penggusuran ini sejalan dengan semangat pembaruan ala Tan Malaka,” atau “Kenaikan harga ini mengikuti spirit kemandirian ekonomi Soekarno.”
Jadi, sejarah menjadi semacam ATM justifikasi. Ditarik sesuai kebutuhan. Tentu saja, tidak semua setuju. Tapi karena suara sejarah terdengar dari ruang-ruang resmi, maka versi alternatif hanya menjadi suara lirih di perpustakaan komunitas atau utas Twitter yang sepi.
Menulis Sejarah Masa Kini: Kegiatan Futuristik
Lucunya, penulisan ulang sejarah sering dilakukan saat luka sejarah belum sepenuhnya sembuh. Kita menulis tentang reformasi 1998, padahal banyak pelakunya masih hidup dan beberapa bahkan masih menjabat. Kita menulis tentang konflik 1965, padahal rekonsiliasi belum tuntas. Kita menulis tentang Orde Baru, padahal sisa-sisa polanya masih terdistribusi dengan baik di birokrasi.
Menulis sejarah masa kini adalah kegiatan futuristik: kita menulis masa lalu dengan struktur masa depan yang belum stabil.
Tentu ini bukan kesalahan penulis sejarah. Mereka hanya mengikuti pesanan. Yang menyedihkan, mungkin, adalah kenyataan bahwa kita lebih tertarik pada pengendalian narasi ketimbang penyembuhan trauma.
Solusi Nasional: Buatlah Sejarah yang Bisa Diperbarui
Mengingat betapa cairnya sejarah kita, maka sebaiknya pemerintah menciptakan buku sejarah nasional dalam format digital yang bisa diperbarui secara berkala. Seperti aplikasi e-commerce: ada update versi 1.2.3, patch revisi narasi Trikora, atau bug fix pada kronologi Malari 1974.
Dengan begini, setiap rezim bisa menyesuaikan narasi tanpa harus mencetak ulang buku dan membuang anggaran negara.
Guru sejarah cukup menekan update, lalu masuk ke mode pengajaran terbaru. Tidak perlu canggung atau merasa bersalah. Lagipula, ini zaman fleksibel. Anak-anak muda sudah terbiasa dengan istilah “versi beta”. Jadi sejarah versi beta pun tak akan mengejutkan mereka.
Tapi Kita Tak Sepenuhnya Sinis
Meskipun nada tulisan ini penuh satire, kita tahu bahwa ada upaya tulus dalam menulis ulang sejarah. Banyak sejarawan yang dengan jujur ingin menampilkan sejarah yang lebih inklusif, memberi ruang bagi suara yang selama ini dibungkam. Mereka bekerja di balik layar, meraba-raba arsip, menggali dokumen, dan mencari narasi alternatif yang selama ini ditutup.
Namun tantangannya jelas: selama sejarah ditulis dalam bingkai kekuasaan, maka netralitas hanyalah ilusi. Dan selama narasi nasional harus tunduk pada kepentingan politik jangka pendek, maka sejarah akan terus menjadi korban pengeditan tanpa akhir.
Sejarah sebagai Proyek Nasionalisme Estetis
Kebijakan menulis ulang sejarah Indonesia adalah cermin dari ambivalensi nasionalisme kita. Di satu sisi, kita ingin bangga terhadap masa lalu. Di sisi lain, kita malu terhadap beberapa bagian dari masa lalu itu. Maka, cara terbaik adalah: poles saja.
Namun sejarah bukan salon. Ia tak bisa terus-menerus dipermak agar tampak menarik.
Jika kita sungguh ingin membangun bangsa yang besar, maka sejarah seharusnya tidak ditulis untuk membenarkan, tapi untuk memahami. Tidak untuk membela tokoh, tapi untuk menjelaskan kompleksitas. Tidak untuk memperkuat penguasa, tapi untuk memberdayakan warga.
Sampai saat itu tiba, biarlah kita hidup di negara yang sedang terus mengedit sejarahnya. Negara yang percaya bahwa masa lalu bisa direvisi, dan kebenaran bisa ditunda sampai anggaran siap.
Selamat menikmati pelajaran sejarah.