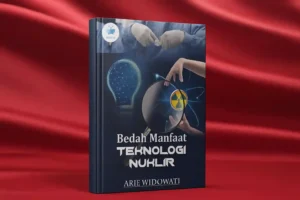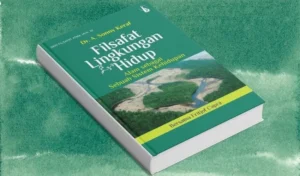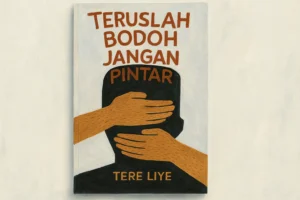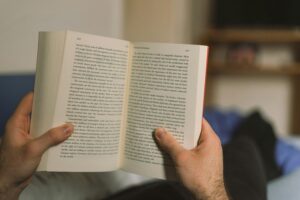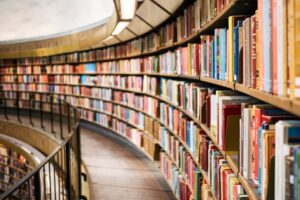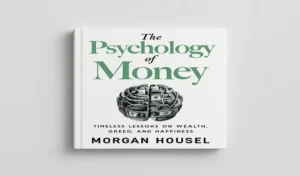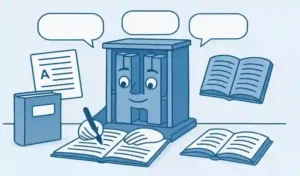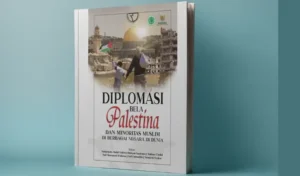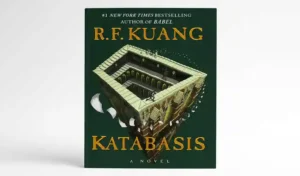Visi Pembaharuan Nurcholish Madjid dalam Bilik-Bilik Pesantren
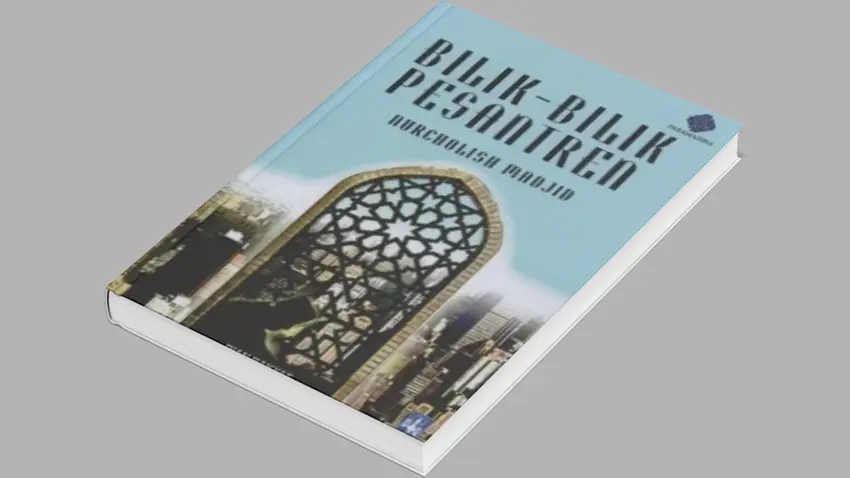
Bilik-Bilik Pesantren karya Nurcholish Madjid, atau yang akrab disapa Cak Nur, merupakan sebuah karya monumental yang tidak hanya menjadi refleksi kritis, tetapi juga sebuah manifesto visioner tentang peran dan masa depan institusi pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Ditulis berdasarkan observasi sekitar tahun 1970-an, buku ini menyajikan telaah mendalam yang mengurai tantangan, mengidentifikasi kelemahan, dan merumuskan ulang cita-cita ideal bagi pesantren agar tetap relevan dan berkontribusi secara signifikan di tengah gelombang modernisasi dan pembangunan nasional. Inti dari argumen Cak Nur adalah seruan untuk melakukan pembaruan yang bersifat fundamental, dimulai dari aspek non-fisik—sikap jiwa keseluruhan—sebelum beranjak ke masalah struktural.
Merumuskan Kembali Cita-Cita Pendidikan Pesantren
Kritik utama Cak Nur terhadap kondisi pesantren tradisional terletak pada orientasi dan visinya. Ia menyoroti adanya kecenderungan di mana tujuan pendidikan sering kali diserahkan kepada proses yang berjalan apa adanya, bukan melalui perumusan yang sadar dan terencana. Hal ini ia tegaskan sebagai, “Kekurangan pertama adalah terletak pada lemahnya visi dan tujuan yang dibawa pendidikan pesantren.” (hal. 19).
Dalam pandangan Cak Nur, kelemahan visi ini disebabkan oleh adanya kecenderungan tujuan pesantren diserahkan pada proses yang terbentuk dari kondisi yang ada. Akibatnya, alih-alih menjadi lembaga yang proaktif dalam menjawab tantangan zaman, pesantren justru dinilai sebagai “’fosil’ masa lampau yang cukup jauh untuk bisa memainkan peranannya sebagaimana kita harapkan.” (hal. 19).
Untuk mengatasi hal ini, Cak Nur menyerukan perlunya perumusan kembali tujuan pendidikan yang bergeser dari fokus ritualistik semata menuju penghayatan nilai-nilai keagamaan yang lebih fungsional. Dalam konteks hubungan antara manusia dengan Tuhan, ia berargumen agar pembahasan tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan ubudiyah (ritus) saja, melainkan harus membahas dan menanamkan keinsyafan yang mendalam tentang makna nilai-nilai keagamaan seperti “taqwa, taqarrub, tawakkal, ikhlas, dan seterusnya.” (hal. 26). Ritus, dalam kerangka ini, dipandang sebagai sarana edukatif bagi terbentuknya kualitas-kualitas spiritual tersebut dalam jiwa manusia. Visi yang luas ini juga mencakup kesadaran manusia akan alam dan hubungan ideal dengannya, yang memiliki “bahannya” dalam kitab suci al-Qur’an dan sangat relevan dengan pola kehidupan modern (hal. 26).
Sistem Nilai dan Kontinuitas Tradisi Pesantren
Secara kelembagaan, sistem nilai yang digunakan oleh kalangan pesantren berakar kuat pada tradisi Islam, yang mereka namakan sebagai “Ahlu Sunnah wal-Jama’ah” (hal. 36). Dalam teologi, pesantren mengikuti madzhab Sunni, yang dirumuskan oleh Abu Hassan al-Asy’ari, dengan rumusan terkenal tentang dua puluh sifat Tuhan yang dihafal mati oleh para santri (hal. 36).
Namun, Cak Nur mengingatkan bahwa pemeliharaan tradisi juga harus dibarengi dengan kehati-hatian, terutama dalam aspek spiritual dan mistis (tasawuf). Meskipun penting untuk memelihara unsur kedalaman rasa keagamaan Cak Nur menekankan perlunya peningkatan taraf kecerdasan umat Islam pada umumnya sebagai “suatu tantangan baru yang harus diselesaikan oleh pesantren-pesantren kita.” (hal. 62). Hal ini sejalan dengan perlunya thariqah (jalan spiritual) memagari diri dengan menekankan kesatuan mutlak antara syari’ah, thariqah, ma’rifah, dan haqiqah (hal. 62), sehingga unsur kedalaman tidak terjerumus pada praktik-praktik superstitious yang menyimpang dari ajaran ortodoks.
Kesenjangan dan Masalah Kelembagaan Pesantren
Salah satu bagian terpenting dari analisis Cak Nur adalah peninjauan objektifnya terhadap “Kesenjangan antara Pesantren dengan Dunia Luar” (hal. 72). Ia secara tegas mengakui adanya semacam “ketidakcocokan antara dunia pesantren dan dunia luar yang dinilai sebagai ‘ashry’, ‘menzaman’ atau modern.” (hal. 74). Ketidakcocokan ini tidak hanya menyentuh aspek filosofis, tetapi juga kondisi fisik dan lingkungan yang jauh dari modernitas.
Cak Nur memberikan ilustrasi yang cukup tajam tentang keadaan pesantren yang dianggap “lagging behind the time”. Kondisi lingkungan pesantren yang merupakan hasil pertumbuhan tak berencana digambarkan secara rinci, seperti pengaturan tata kota yang sporadis, kamar asrama yang sempit, tidak higienis, dan minimnya peralatan (hal. 75). Selain itu, ia menyoroti fasilitas sanitasi (kamar mandi dan kakus) yang tidak sebanding dengan jumlah santri, bahkan ada yang tidak menyediakan fasilitas ini, membuat santri mandi dan buang air di sungai (hal. 75).
Secara kelembagaan, pesantren juga menghadapi masalah dalam pola kepemimpinan dan manajemen. Pola kepemimpinan yang bertumpu pada figur seorang kiai (otoritarianistik), sementara di satu sisi melahirkan kekayaan kultural dalam setiap pesantren, di sisi lain membuat pembaruan menjadi sangat sulit dan “kurang prospektif bagi kesinambungan pesantren bagi masa depan,” sebab banyak pesantren populer hilang begitu saja ketika sang kiai meninggal dunia (hal. 89).
Ironi terbesar, menurut Cak Nur, adalah bahwa kesadaran akan kehilangan relevansi sosial ini justru disadari oleh tokoh pesantren sendiri. Ia mengamati kecenderungan para kiai di kota-kota besar yang lebih percaya menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah umum, terutama di bidang paling produktif seperti “ekonomi, kedokteran, dan teknik,” (hal. 81) daripada di pesantren sendiri. Sebuah pengamatan yang menyindir, “Seolah-olah mereka berkata: ‘Cukuplah aku saja, anakku jangan!’” (hal. 81). Kenyataan ini menunjukkan dilema batin tokoh pesantren antara mempertahankan tradisi untuk basis massa dan mengejar kemajuan materiil-profesional untuk anak kandungnya.
Amanat Ganda dan Ekspansi Fungsional
Menanggapi tantangan dan kesenjangan yang ada, Cak Nur menawarkan solusi ideal, yaitu agar pesantren mengambil posisi sebagai pengembang “amanat ganda (duo mission) yaitu amanat keagamaan atau moral dan amanat ilmu pengetahuan.” (hal. 86). Dua amanat ini harus dilakukan serentak dan proporsional untuk mencapai keseimbangan yang diharapkan.
Penerimaan amanat ganda ini menuntut pesantren untuk melakukan efisiensi, terutama dalam penggunaan waktu, dana, dan daya yang harus “dipergunakan dua kali lebih efektif daripada yang ada sekarang ini.” (hal. 86). Hal ini juga menyangkut perubahan dalam metodologi pengajaran, atau streamlining, yang menekankan pengintensifan segi-segi pembentukan watak dari penciptaan suasana keagamaan.
Dalam perkembangannya, pesantren memang telah merespons modernisasi melalui ekspansi fungsional. Respons ini meliputi pembaruan substansi dengan memasukkan subyek-subyek umum dan vocational, pembaruan metodologi seperti sistem klasikal dan penjenjangan, pembaruan kelembagaan melalui diversifikasi dan sistem yayasan, serta pembaruan fungsi dari sekadar kependidikan menjadi fungsi sosial-ekonomi (hal. 13).
Institusi ini menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Melalui penyesuaian dan akomodasi, pesantren tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mengembangkan diri dan menempatkan diri pada posisi penting dalam sistem pendidikan nasional (hal. 13). Ekspansi ini tidak hanya terjadi secara fisik, dengan munculnya gedung-gedung dan fasilitas yang lebih megah (hal. 13), tetapi juga secara geografis, dari rural based institution menjadi lembaga pendidikan urban di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Medan (hal. 13).
Kesimpulan Nurcholish Madjid adalah optimisme yang dibalut realisme. Dengan merangkul amanat ganda, pesantren dapat menghindari nasib buruk, yaitu lenyap tak berbekas, dan sebaliknya menjadi sesuatu yang “berguna untuk umat manusia maka akan tetap menghujam di Bumi,” sebuah peringatan yang ia kutip dari al-Qur’an (hal. 87). Bilik-Bilik Pesantren bukan sekadar kritik nostalgia, tetapi sebuah cetak biru untuk transformasi kelembagaan yang memastikan bahwa tradisi Islam Indonesia, yang diwakili oleh pesantren, dapat terus menjadi mata air kearifan dan agen pembangunan di tengah pusaran zaman modern.
Identitas Buku
Judul: Bilik-bilik Pesantren
Penulis: Nurcholis Madjid
Penerbit: Paramadina dan Dian Rakyat
Tahun Terbit: 1997
Halaman: 1-105