Sound Horeg dari Kaca Mata Sosiolog

Fenomena sound horeg merebak bagai gelombang suara yang tak terbendung. Ia tak sekadar dentuman audio raksasa yang mengguncang jalan-jalan desa, melainkan simbol kompleks tentang ekspresi budaya rakyat, teknologi rakitan, sekaligus polemik sosial yang memecah masyarakat. Di satu sisi, sound horeg menjadi panggung tempat kreativitas lokal memekik bebas. Di sisi lain, ia juga menjadi sumber ketegangan, pertentangan moral, bahkan ancaman terhadap kesehatan dan ketertiban umum.
Di tengah pawai-pawai desa atau konvoi malam hari, kita kerap mendengar suara yang mengguncang dada, memantul ke tembok rumah, menggetarkan kaca jendela hingga berderak. Truk-truk terbuka yang dimodifikasi menjadi panggung berjalan, membawa speaker raksasa, lampu disko, dan kadang-kadang bahkan panggung tari, melintasi kampung-kampung dengan dentuman musik remix EDM yang menggema jauh melebihi batas akustik wajar. Inilah sound horeg, sebuah fenomena sosial dan teknologi yang menjangkau hampir setiap pelosok Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir. Istilah “horeg” sendiri merupakan turunan dari kata Jawa yang menggambarkan getaran, guncangan, sensasi fisik yang intens.
Tak ada yang bisa menafikan bahwa sound horeg adalah buah dari kreativitas rakyat. Tak sedikit teknisi desa yang menghabiskan waktu berbulan-bulan merakit perangkat audio, memodifikasi speaker, menciptakan rangkaian lampu dan efek cahaya, hingga menyusun playlist musik remix mereka sendiri. Nama-nama seperti Thomas Alva Edi Sound, tokoh lokal yang dijuluki demikian karena inovasi audio rakitannya, menjadi ikon tersendiri di jagat sound horeg. Beberapa dari mereka bahkan mengklaim telah menghabiskan dana hingga satu miliar rupiah hanya untuk membangun satu unit truk sound system yang lengkap. Ratusan usaha persewaan sound system tumbuh, menyerap tenaga kerja lokal dari teknisi hingga operator, menjadikan fenomena ini bagian dari industri kreatif akar rumput yang menghidupi banyak orang.
Namun ketika kreativitas ini keluar dari batas ruang ekspresi yang sehat dan masuk ke ruang publik tanpa pengaturan, konflik pun tak terelakkan. Masyarakat mengeluhkan polusi suara yang ekstrem, bahkan mencapai tingkat 135 desibel, melebihi suara mesin jet saat lepas landas. Anak-anak terbangun tengah malam, lansia terganggu istirahatnya, dan beberapa warga melaporkan sakit kepala dan gangguan pendengaran ringan akibat intensitas suara tersebut. Tak sedikit pula rumah yang retak atau kaca jendela yang pecah karena dentuman bass yang terus menerus selama berjam-jam.
Di Malang, Bondowoso, dan beberapa kota lain di Jawa Timur, protes warga mulai menguat. Ketegangan antara penyelenggara sound horeg dan warga yang terganggu semakin membesar, bahkan di beberapa titik menimbulkan bentrokan fisik. Pemerintah daerah pun turun tangan. Di Malang, polisi resmi melarang kegiatan sound horeg tanpa izin, dan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pemerintah menetapkan batasan maksimal jumlah speaker serta melarang aksi panggung dengan pakaian minim di ruang publik. Langkah ini mencerminkan betapa sound horeg telah menjadi persoalan yang tidak lagi bisa dianggap sebagai hiburan biasa.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur bahkan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa sound horeg termasuk haram, khususnya jika menimbulkan mudarat lebih besar daripada manfaat. Fatwa ini didasari pertimbangan moral, kesehatan masyarakat, serta pemborosan sumber daya. Dalam pandangan mereka, sound horeg bukan lagi bentuk hiburan yang membahagiakan, tapi justru menciptakan kerusakan dan ketidaktertiban. Sebuah kemewahan audio yang tidak beradab, yang melukai tetangga tanpa menyentuh nurani.
Namun bukan berarti fenomena ini harus dipadamkan begitu saja. Banyak pihak menyarankan pendekatan yang lebih bijak. Daripada melarang total, lebih baik fenomena ini diatur dengan regulasi yang realistis dan edukatif. Misalnya, menetapkan jam tayang terbatas, pembatasan volume, dan rute konvoi yang aman dan tidak mengganggu warga. Di sisi lain, para pelaku sound horeg juga perlu diberikan pelatihan tentang etika audio publik, hak cipta musik, serta aspek keamanan teknis dalam penggunaan perangkat berskala besar. Pendekatan semacam ini tak hanya akan menyelamatkan ruang publik dari kebisingan, tapi juga mengangkat martabat komunitas kreatif lokal.
Di balik semua itu, terdapat pertanyaan besar tentang bagaimana masyarakat kita memahami batas antara ekspresi budaya dan penghormatan terhadap hak orang lain. Apakah kebebasan menciptakan dan merayakan teknologi audio ini harus dibayar dengan kesehatan publik? Apakah kesenangan sebagian kelompok harus ditoleransi meskipun mengorbankan ketenangan mayoritas warga?
Sound horeg seharusnya menjadi ruang dialog, bukan arena benturan. Ini bukan sekadar tentang siapa yang punya speaker lebih besar, atau siapa yang bisa membuat bass paling dalam. Ini tentang bagaimana suara, dalam artian harfiah maupun metaforis, digunakan dalam kehidupan sosial kita. Apakah suara itu meneguhkan kebersamaan, atau justru merusak simpul-simpul harmoni?
Dalam perspektif Emile Durkheim, fenomena seperti sound horeg dapat dibaca sebagai manifestasi solidaritas mekanik, di mana kesadaran kolektif masyarakat masih terikat pada ekspresi komunal yang seragam dan tradisional. Konvoi sound horeg bukan sekadar parade kendaraan bersuara keras, melainkan ritual sosial yang memperkuat rasa kebersamaan. Dalam masyarakat yang masih mempertahankan ikatan mekanik, bentuk-bentuk kolektif semacam ini menjadi penanda identitas, bahkan menjadi sarana untuk memperbarui solidaritas komunitas. Namun, seperti yang Durkheim juga peringatkan, setiap ritus atau bentuk ekspresi kolektif harus berada dalam batas yang memperkuat integrasi sosial, bukan merusaknya.
Ketika sound horeg justru menciptakan konflik, ketegangan, dan fragmentasi sosial, maka ritual ini telah kehilangan fungsinya sebagai perekat. Ia menjadi bentuk anomi—keadaan ketika norma sosial gagal mengatur perilaku individu atau kelompok. Sound horeg yang tak diatur mencerminkan kekosongan norma: semua bisa dilakukan, semua sah, asalkan viral. Di titik ini, suara tak lagi menjadi medium komunikasi atau kebersamaan, tapi simbol disintegrasi dan kebisingan yang memekakkan tatanan sosial. Durkheim mungkin akan menyebutnya sebagai kegagalan masyarakat dalam memperbarui solidaritasnya ke arah bentuk yang lebih organik, yakni ketika diferensiasi sosial menuntut adanya koordinasi dan kompromi.
Dalam pandangan Max Weber, fenomena sound horeg bisa dibaca dari aspek tindakan sosial yang berorientasi pada pemaknaan subjektif. Bagi para pelaku dan komunitas sound horeg, tindakan membangun dan memamerkan audio raksasa bukan sekadar kesenangan, tapi memiliki nilai simbolik: sebuah bentuk dominasi estetika, prestise sosial, dan klaim atas ruang publik. Tindakan itu bisa bersifat instrumental-rasional—yakni demi eksistensi, bisnis, atau pengaruh media—namun juga bisa bersifat afektif, sebagai ledakan emosi kolektif yang mewujud dalam bentuk suara dan cahaya. Dalam perspektif Weberian, kita melihat bagaimana nilai dan makna individu atau kelompok terhadap aktivitas sound horeg dapat berbeda jauh dari tafsir masyarakat umum. Konflik pun lahir dari ketidaksinkronan makna antara aktor dan lingkungan sosialnya.
Pierre Bourdieu akan melihat sound horeg sebagai arena pertarungan simbolik dalam ranah budaya populer. Para pelaku sound horeg mengakumulasi modal simbolik melalui kekuasaan estetika—semakin keras, semakin unik, semakin atraktif, semakin tinggi posisi dalam hierarki komunitas. Sound horeg menjadi bentuk habitus baru: serangkaian kebiasaan yang tertanam dalam tubuh sosial, dibentuk oleh sejarah komunitas dan internalisasi simbol-simbol kekuasaan bunyi. Bourdieu akan mencatat bagaimana sound horeg menciptakan ranah tersendiri di mana modal ekonomi, simbolik, dan kultural berinteraksi. Tapi ia juga akan menyoroti dominasi budaya—di mana yang punya akses ke teknologi suara besar mendominasi ruang publik dan menundukkan yang tidak punya pilihan selain diam atau terganggu.
Alfred Schutz, dengan pendekatan fenomenologinya, akan melihat sound horeg dari perspektif makna intersubjektif yang dibentuk oleh pengalaman bersama. Bagi komunitas penggemarnya, sound horeg adalah dunia kehidupan (lifeworld) yang memiliki logika sendiri: kegembiraan, kekompakan, kesenangan tubuh, dan pengakuan dari sesama. Dalam dunia mereka, bunyi bukanlah gangguan, tapi sarana komunikasi dan ekspresi eksistensial. Konflik muncul ketika dunia kehidupan ini berhadapan dengan lifeworld lain—mereka yang menginginkan ketenangan, istirahat, dan keteraturan. Schutz akan menekankan pentingnya memahami makna-makna yang dibentuk oleh pengalaman sehari-hari, dan bagaimana interpretasi atas realitas sosial tidak pernah tunggal.
Ironisnya, banyak komunitas sound horeg mengaku tak pernah berniat mengganggu. Mereka ingin membangun hiburan alternatif di tengah desa yang miskin pilihan rekreasi. Mereka ingin menunjukkan bahwa teknologi bukan milik kota besar semata, bahwa kreativitas tak harus bergantung pada label atau sponsor. Tapi tanpa kesadaran sosial dan etika kolektif, niat baik itu bisa melenceng menjadi bencana akustik yang merusak relasi antarwarga.
Dalam tinjauan fisika, resonansi bunyi dan interferensi gelombang suara menjelaskan mengapa sound horeg terasa mengguncang tulang. Pantulan bunyi dari tembok rumah atau bangunan sempit menyebabkan efek akustik yang memperkuat dentuman, menciptakan getaran yang bukan hanya terdengar, tapi dirasakan. Kombinasi ini membuat pengalaman sound horeg tak terlupakan—baik bagi mereka yang menyukai, maupun yang tersiksa karenanya.
Dalam realitas hukum, undang-undang tentang gangguan lingkungan hidup, hak atas ketenangan, dan kebebasan berekspresi harus berjalan beriring. Tak boleh ada dominasi satu pihak. Negara mesti hadir sebagai fasilitator kompromi: membuka ruang bagi kreativitas lokal, tapi tegas dalam melindungi warga dari kekerasan akustik yang tak perlu.
Fenomena sound horeg adalah cermin kompleks dari wajah masyarakat kita. Ia memperlihatkan potensi teknologi akar rumput yang luar biasa, tapi juga mencerminkan minimnya kesadaran kolektif tentang batas-batas kebebasan. Dalam era di mana segala hal bisa viral, kita justru perlu lebih sadar tentang dampak sosial dari tiap tindakan. Bukan hanya soal bisa atau tidak bisa membuat dentuman sekuat mungkin, tapi apakah kita mau menyalakan suara yang membangun peradaban, atau justru menggelegarkan kehancuran.
Jika kita bisa mengatur dan mendidik komunitas ini dengan baik, sound horeg bisa menjadi industri lokal yang mendunia. Bukan tidak mungkin Indonesia dikenal dunia bukan hanya karena dangdut koplo dan angklung, tapi juga karena teknologi audio rakitan desa yang membanggakan. Tapi jika dibiarkan, sound horeg hanya akan menjadi simbol lain dari ironi: kebisingan yang lahir dari kreativitas, tapi memekakkan nurani dan membelah masyarakat.



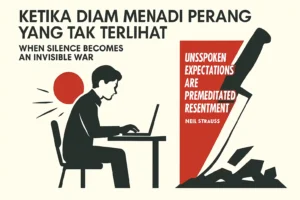


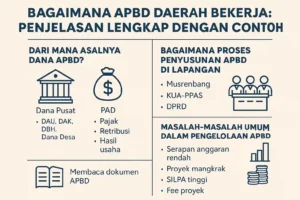


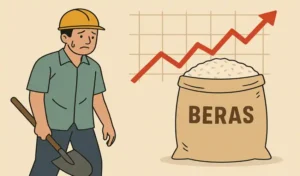
Sound horeg.. sambil ngopi membuat gelas kopi ku loncat-loncat..kudapan loncat.. bahkan otakku ikutan loncat-loncat.. hhihihh
Agak bahaya, yaa 🤣
Antara iya dan tidak pak😂🙏