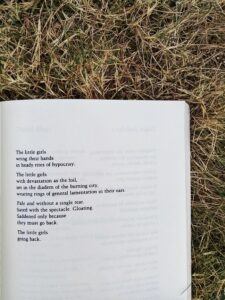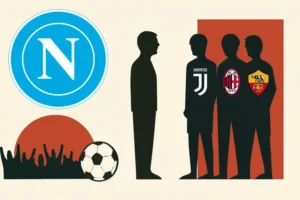Republik dan Kerajaan dalam Budaya Hukum dan Partisipasi Publik
Budaya suatu negara sering kali tercermin dari bagaimana masyarakatnya memandang hukum, pemerintahan, serta jenis simbol politik yang dipelihara. Indonesia dan Inggris, dengan format negara yang berbeda—republik dan monarki konstitusional—menampilkan perpaduan paradoks yang menarik.
Di Indonesia, indeks Rule of Law 2023 dari World Justice Project mencatat skor 0,53 (skala 0–1), stabil sejak 2015. Indonesia menempati peringkat ke‑66 dari 142 negara dan ke‑9 di ASEAN, dengan indikator “ketertiban dan keamanan” satu‑satunya yang relatif tinggi (0,71), tapi aspek absennya korupsi, hak dasar, dan peradilan pidana berada di bawah 0,58. Skor -0,15 (dalam rentang -2,5 hingga 2,5) juga sekaligus peringkat ke‑99 secara global dalam World Bank Rule of Law Index. Hal ini menunjukkan bahwa meski Indonesia berbentuk republik, budaya hukum belum berkembang optimal—banyak aspek formal belum diimbangi praktik keadilan substansial.
Persepsi publik yang tercatat oleh Transparency International pada 2023 menunjukkan skor CPI 34/100, naik menjadi 37/100 pada 2024, namun tetap berada di peringkat ke‑115 hingga ke‑99 dari 180 negara. Survei WEF dan TI memperlihatkan bahwa sekitar 90% warga menilai korupsi sebagai hambatan utama, dan 30% pengakses layanan publik pernah memberi suap dalam setahun terakhir. Problema sistemik ini mendorong persepsi bahwa hukum lebih menjadi alat kekuasaan ketimbang penegakan keadilan.
Di sisi lain, Inggris menunjukkan prestasi lebih baik dalam budaya hukum. Dalam World Justice Project Index 2023, Inggris memperoleh skor 1,4 (dalam rentang -2,5 hingga 2,5), berada di peringkat ke‑22 secara global—lebih tinggi daripada banyak negara G20.
Statistics (ONS) 2023 memperlihatkan bahwa 62% warga mempercayai pengadilan, 56% mempercayai polisi, dan hanya 27% mempercayai pemerintah. Sementara kepercayaan terhadap partai politik bahkan hanya 12%. Meskipun kepercayaan terhadap politisi rendah, warga Inggris tetap mempercayai institusi teknokratis dan objektif seperti statistik nasional (ONS: 85–87%).
Ketidakpercayaan terhadap politik di Inggris merupakan efek dari skandal politik dan ketidakstabilan pemerintahan (misalnya masa pemerintahan Johnson dan Truss), bukan karena penghancuran budaya hukum. Survei Financial Times 2024 menunjukkan 45% warga jarang mempercayai pemerintah bertindak demi kepentingan nasional, dan 58% meragukan kejujuran politisi. Namun hal ini tidak merambat ke sistem hukum atau birokrasi.
Dalam konteks partisipasi publik, 70% warga Inggris merasa warga pada umumnya dapat dipercaya, dan 44% pernah mengikuti aktivitas politik dalam setahun terakhir. Keterlibatan ini meliputi memilih, menghadiri diskusi lokal, atau aksi kampanye, yang menunjukkan civic engagement lebih kuat dibandingkan banyak negara demokratis modern.
Di ranah pendidikan, perbedaan antara sistem republik dan monarki terlihat lebih tajam bukan pada bentuk kelembagaan, tetapi dalam arah pengembangan nilai-nilai warga negara. Indonesia, dengan kurikulum nasional yang silih berganti sejak 2004 hingga Kurikulum Merdeka pada 2022, menghadapi tantangan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara konsisten. Menurut laporan Kemdikbudristek, indeks literasi nasional Indonesia tahun 2022 berada pada angka 61,6 dari skala 100. Sedangkan survei UNESCO menunjukkan bahwa tingkat minat baca Indonesia berada di bawah rata-rata global, yakni sekitar 0,001 — artinya hanya 1 dari 1000 penduduk Indonesia yang gemar membaca buku secara rutin.
Sementara itu, Inggris melalui Office for Standards in Education (Ofsted) melaporkan pada 2023 bahwa 89% sekolah negeri dinilai “baik” atau “sangat baik” dalam pengajaran nilai warga negara, literasi, dan multikulturalisme. Bahkan sejak 1988, melalui National Curriculum, Inggris telah mewajibkan pelajaran Citizenship yang mencakup pemahaman terhadap hukum, HAM, pemerintahan, dan partisipasi sipil. Hasilnya, tingkat literasi fungsional Inggris menurut OECD PISA 2022 menempatkan mereka dalam 10 besar dunia, dengan skor literasi membaca 504, jauh di atas rata-rata OECD (476)l.
Dalam konteks simbolisme negara, Inggris memelihara institusi monarki sebagai simbol kontinuitas sejarah dan stabilitas politik. Ratu Elizabeth II, dan kini Raja Charles III, tidak memerintah secara eksekutif, namun memegang peran simbolik yang kuat. Masyarakat Inggris tidak merasa bertentangan antara demokrasi dan monarki karena peran raja/ratu tidak menghambat kekuasaan rakyat. Bahkan dalam survei YouGov 2023, sekitar 58% warga Inggris masih mendukung keberlanjutan monarki, meskipun ada tren penurunan sejak 2015. Simbolisme kerajaan hidup dalam budaya populer, parade tahunan Trooping the Colour, serta struktur bangsawan yang masih memiliki tempat di House of Lords.
Berbeda halnya dengan Indonesia yang menanggalkan seluruh atribut kerajaan pascakemerdekaan 1945 dan memilih simbol-simbol negara yang egaliter seperti bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, dan konsep “kedaulatan di tangan rakyat”. Namun ironisnya, sistem politik lokal dan pusat kadang mewarisi gaya feodalistik—dengan elite politik berperan laiknya “raja kecil” yang sulit dikritik dan cenderung membentuk dinasti politik. Penelitian Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 100 kepala daerah di Indonesia memiliki hubungan keluarga langsung dengan pejabat atau elite politik nasional. Ini menunjukkan paradoks antara semangat republik dan realitas budaya politik Indonesia yang masih sarat loyalitas patron-klien.
Multikulturalisme menjadi isu sentral yang menarik di kedua negara. Inggris dengan sejarah kolonialnya memiliki populasi imigran yang besar. Data ONS (2021) menunjukkan bahwa sekitar 14,4% populasi Inggris lahir di luar negeri, dan 18% berasal dari kelompok etnis non-kulit putih. Kota-kota seperti London, Birmingham, dan Manchester memiliki warga keturunan Asia Selatan, Karibia, dan Afrika dalam jumlah signifikan. Pemerintah Inggris menerapkan kebijakan multikulturalisme terbuka sejak 1970-an, meskipun sempat dikritik setelah peristiwa kerusuhan 2011 dan Brexit. Masyarakat Inggris secara umum menerima keberagaman, meskipun tetap ada tantangan rasisme struktural dan integrasi sosial.
Indonesia, di sisi lain, mewarisi keberagaman sebagai bagian dari sejarah internalnya sendiri—dengan lebih dari 1.300 suku, 718 bahasa daerah, dan enam agama yang diakui negara. Namun, penerimaan terhadap keberagaman tidak selalu linier. Dalam laporan Wahid Foundation (2021), lebih dari 30% responden menyatakan pernah mengalami diskriminasi berbasis agama atau suku. Selain itu, kebijakan afirmasi untuk Papua, komunitas adat, atau minoritas agama belum sepenuhnya diimplementasikan secara merata. Diskursus politik identitas juga terus mengemuka dalam Pilkada atau Pemilu, menandakan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika belum sepenuhnya menjadi budaya yang hidup dalam praktik demokrasi Indonesia.
Perbedaan yang lebih dalam terletak pada cara kedua bangsa ini memahami peran rakyat dalam pengambilan keputusan. Inggris, meski kerajaan, memiliki sejarah panjang dalam tradisi perwakilan—dimulai dari Magna Carta 1215 hingga sistem parlemen modern. Demokrasi Inggris stabil meski tanpa konstitusi tertulis, karena norma politik dan hukum berkembang melalui common law dan konvensi. Sementara Indonesia sebagai republik dengan konstitusi formal kerap menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya—UUD 1945 sering menjadi arena tafsir politis, dan Mahkamah Konstitusi pernah tercoreng oleh kasus suap.
Demokrasi di Inggris tidak sempurna, namun partisipasi politik cenderung berbasis kesadaran warga. Sementara di Indonesia, partisipasi politik sering kali bersifat mobilisasi, terutama menjelang pemilu. Survei LIPI dan CSIS menunjukkan bahwa 60% pemilih muda Indonesia hanya mengikuti politik saat menjelang pemilu dan tidak aktif setelahnya. Ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya tumbuh sebagai budaya, melainkan sebagai peristiwa lima tahunan yang dibingkai secara ritualistik.
Di ujung narasi ini, kita tidak sedang menempatkan republik lebih unggul dari kerajaan, atau sebaliknya. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana budaya politik, hukum, dan sosial dibentuk oleh institusi dan praktik jangka panjang. Republik Indonesia membawa cita-cita egaliter, tetapi kadang terjebak dalam praktik kekuasaan yang menyerupai kerajaan tanpa mahkota. Sementara Inggris yang mempertahankan simbol kerajaan justru menampakkan stabilitas hukum dan partisipasi sipil yang lebih mapan.
Maka yang penting bukan apakah sebuah negara berbentuk republik atau kerajaan, melainkan apakah nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman benar-benar hidup dalam praktik harian warganya. Bentuk negara hanya kerangka. Jiwa demokrasinya lah yang membuatnya bernyawa.