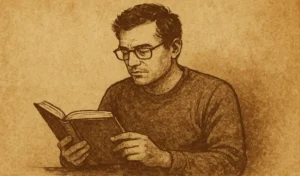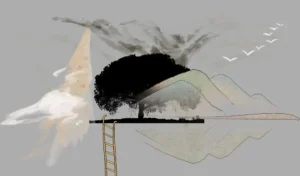Mojokerto: Kota Batu Bata dan Kenangan yang Tak Selesai
“Budaya Mojokerto adalah mosaik dari banyak hal: dari batu bata sejarah sampai gorengan pagi hari, dari candi yang sepi sampai warung kopi yang ramai, dari jalan berlubang sampai tawa warga yang tetap tulus.”

Mojokerto adalah kota yang tidak bisa selesai hanya dalam satu kali kunjungan. Kota ini semacam mantan yang, walau sudah ditinggal, tetap saja muncul dalam obrolan tengah malam dengan teman lama. Kadang muncul sebagai tawa, kadang sebagai perih. Mojokerto bukan hanya sekadar titik di peta Jawa Timur, tapi semacam perasaan yang membatu, mewujud dalam arca dan candi, tapi hidup di dalam warung kopi dan percakapan ibu-ibu PKK.
Sebagai kota yang menyandang julukan “Bumi Majapahit,” Mojokerto tampaknya punya semacam beban moral untuk terus bersikap arkeologis: menggali yang lama, menata ulang, memoles ulang, lalu memasang papan nama dari dinas pariwisata. Tapi jangan salah, di balik tatanan batu bata merah yang konon peninggalan Hayam Wuruk itu, tersimpan budaya warga yang lebih ajaib dari naskah Nagarakretagama: budaya cuek, budaya sambat, budaya ngopi, dan tentu saja—budaya bertahan hidup di tengah janji politik yang seperti jalan rusak: diperbaiki lima tahun sekali.
Budaya Batu Bata dan Makna yang Retak-retak
Mari mulai dari hal yang paling membatu: candi. Mojokerto adalah kota yang jumlah candinya hampir mengalahkan jumlah rest area di tol Trans Jawa. Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Bajang Ratu, semuanya berdiri tegak sebagai pengingat bahwa dulu kita pernah besar. Pernah menjadi pusat kekuasaan. Pernah disegani. Kini, kita lebih sering disegani oleh debt collector dan tengkulak daripada oleh negara tetangga.
Yang lucu, meski tiap tahun ribuan siswa SD diseret oleh guru IPS ke situs sejarah itu sambil pegang lembar LKS, sangat sedikit dari mereka yang kemudian tumbuh dewasa dengan cita-cita menjadi arkeolog. Lebih banyak yang ingin jadi YouTuber atau admin TikTok Pemkab. Entah siapa yang gagal: sistem pendidikan, semangat lokal, atau mungkin kita semua yang lebih tertarik memotret candi untuk Instagram daripada memaknai warisan yang sesungguhnya.
Budaya batu bata ini tak hanya hadir dalam bentuk fisik, tapi juga mentalitas. Di Mojokerto, banyak yang hidup dengan prinsip “pelan tapi ngoyo.” Seperti batu bata: tampak diam, tapi ketika disusun bisa jadi pondasi bangunan besar. Masalahnya, kadang kita terlalu sibuk jadi batu bata sampai lupa bahwa seharusnya kita yang membangun rumah, bukan cuma jadi dindingnya.
Budaya Ngopi: Kopi Saset dan Diskusi Filosofis
Di Mojokerto, ngopi bukan cuma aktivitas, tapi semacam ritual. Warung kopi di pojok gang bisa menjadi tempat lahirnya analisis politik yang lebih tajam dari debat capres. Dari warung kopi, kita bisa tahu siapa yang bakal nyalon lurah, siapa yang barusan diciduk KPK, dan siapa yang digosipkan selingkuh dengan anggota DPRD.
Kopi yang diminum? Jangan bayangkan kopi single origin dari Ethiopia atau Gayo yang diseduh dengan French press. Di sini, kopi artinya kopi hitam sasetan yang disajikan dengan gorengan dan obrolan pahit-pahit lucu. Kadang ada aroma robusta, kadang ada aroma patah hati. Tapi yang pasti, selalu ada rasa ingin tahu yang mengepul.
Di warung kopi ini, budaya Mojokerto menemukan tempatnya: antara serius dan santai, antara sambat dan syukur. Orang Mojokerto bisa mengeluh soal banjir sambil tertawa. Bisa mengkritik bupati sambil main catur. Bisa menghina sistem birokrasi sambil minta tolong surat rekomendasi RT.
Budaya Jalan Rusak dan Aspal yang Filosofis
Mojokerto adalah kota yang jalannya kadang seperti nasib mahasiswa tingkat akhir: banyak lubangnya. Tapi jangan salah, jalan rusak di sini bukan sekadar masalah teknis. Ia adalah metafora. Tentang hidup yang tak selalu mulus. Tentang janji-janji pemimpin yang menunggu musim pemilu. Tentang motor Supra yang tetap bisa lewat meski harus miring-miring seperti film laga Thailand.
Ada budaya unik yang lahir dari kondisi ini: budaya saling mengingatkan. Warga akan saling teriak, “Awas lobang!” saat ada pengendara lain di belakangnya. Kalimat yang sederhana, tapi penuh solidaritas. Di kota besar, mungkin orang akan sibuk update status di medsos tentang jalan rusak. Di Mojokerto, kita cukup teriak dan melambai tangan.
Di sinilah lirisnya hidup orang kampung: tidak banyak protes, tapi selalu ada daya tahan. Tidak banyak fasilitas, tapi ada saling peduli. Lubang-lubang itu memang menyebalkan, tapi mereka juga mengajarkan kita tentang pentingnya melihat ke depan—dan sedikit ke bawah.
Budaya Kesenian yang Setia Menunggu Penonton
Mojokerto punya kesenian tradisional yang luar biasa. Tari remo, gamelan, wayang, ludruk, dan tentu saja jaranan. Tapi semua itu seperti acara TVRI: tetap tayang meski tidak banyak yang menonton. Sering kali, kesenian ini hanya muncul saat ada event dari dinas, lengkap dengan tenda biru dan spanduk berlogo APBD.
Yang menyedihkan, para seniman lokal kadang lebih dihargai ketika mereka tampil di luar kota. Di Mojokerto sendiri, mereka seperti kaset lama di rak warung—ada, tapi jarang diputar. Padahal, kesenian ini bukan cuma soal estetika, tapi soal identitas. Tentang bagaimana kita ingin diingat dan diwariskan.
Budaya Mojokerto adalah budaya yang setia. Meski tidak dipuja-puji, dia tetap hadir. Seperti ibu-ibu yang terus menanak nasi meski anak-anaknya lebih suka makan mie instan. Seperti petani yang tetap menanam padi meski harga gabah naik-turun seperti sinyal WiFi di pinggir sawah.
Budaya Pemerintahan yang Kadang Lupa Turun ke Jalan
Satu hal yang khas dari Mojokerto adalah gaya pemerintahannya yang, bagaimana ya, sering kali seperti menara air: tinggi, jauh, tapi penting. Program-program dijalankan dari balik meja, tanpa banyak jalan-jalan ke lapangan. Padahal kalau mau jujur, banyak urusan yang selesai hanya dengan nongkrong di warung dan ngobrol dengan warga.
Ada budaya formalitas yang kental. Rapat, apel, dan seremoni digelar dengan rapi. Tapi implementasi seringkali seperti wifi gratis di alun-alun: lambat dan suka putus nyambung. Sementara warga harus cari cara sendiri agar bisa bertahan. Kadang dengan kreativitas, kadang dengan nekat. Tapi yang jelas, Mojokerto tidak pernah kekurangan akal.
Budaya Anak Muda: Antara TikTok dan Tradisi
Anak muda Mojokerto sekarang sudah melek teknologi. Banyak yang jadi content creator, selebgram lokal, bahkan penjual online yang sukses. Tapi di sisi lain, mereka juga mewarisi budaya lokal yang kuat. Di banyak desa, anak-anak muda masih terlibat dalam kegiatan desa: jadi panitia tasyakuran, ronda malam, atau lomba 17-an. Ini paradoks yang indah: satu tangan menggenggam HP, tangan lain memegang kentongan.
Budaya anak muda di sini tidak selalu bisa didefinisikan dalam kategori klasik. Mereka bukan generasi rebahan total, tapi juga bukan pejuang revolusi. Mereka adalah generasi Mojokerto: tahu sejarah, tapi juga tahu filter Instagram yang paling cocok buat selfie di depan candi.
Yang membanggakan, meski hidup di era digital, banyak anak muda Mojokerto yang tetap punya rasa lokalitas. Mereka tidak malu berbicara dalam logat khas, tidak gengsi ikut kegiatan desa, dan tidak alergi makan tahu petis di pinggir jalan.
Budaya Pasar Tradisional: Tempat Semua Kabar Bersilang
Pasar tradisional di Mojokerto adalah tempat yang lebih informatif daripada media lokal. Di sana, harga cabai dan harga diri bisa naik turun secara bersamaan. Budaya di pasar adalah budaya paling jujur. Tidak ada basa-basi. Jika tempe keras, ya dibilang keras. Kalau beli tapi tidak jadi, ya disebut “gak jadi, Bu.” Tapi tetap dengan senyum.
Pasar bukan cuma tempat jual beli. Ia adalah tempat di mana kabar tentang pernikahan, perceraian, banjir, pembangunan jembatan, dan gosip lurah menyatu dalam irama teriakan pedagang. Pasar adalah radio komunitas yang tak pernah mati.
Budaya pasar ini mengajarkan bahwa hidup bukan hanya soal efisiensi seperti di minimarket, tapi soal relasi. Tentang tawar-menawar, tentang saling kenal, dan tentu saja tentang utang yang bisa dicicil minggu depan.
Mojokerto, Kota yang Tak Pernah Selesai Dicintai
Budaya Mojokerto adalah mosaik dari banyak hal: dari batu bata sejarah sampai gorengan pagi hari, dari candi yang sepi sampai warung kopi yang ramai, dari jalan berlubang sampai tawa warga yang tetap tulus. Ia adalah kota yang tidak sempurna, tapi justru karena itu ia indah. Karena kita tidak butuh kota sempurna. Kita hanya butuh tempat untuk pulang dan merasa diterima, meski dengan jalanan berlubang dan kopi yang terlalu manis.
Mojokerto adalah kota yang tak pernah selesai dicintai, karena ia terus tumbuh dan berubah. Tapi dalam setiap perubahan itu, ada budaya yang tetap diam-diam menjaga kita: budaya bersahaja, budaya ramah, dan tentu saja—budaya mojok.
Dan di ujung hari, saat langit mulai oranye dan suara adzan maghrib bersahutan, orang-orang Mojokerto kembali ke rumahnya. Meletakkan beban di kursi bambu, menyeduh kopi murah, lalu tersenyum. Karena mereka tahu, di kota ini, hidup memang tidak gampang, tapi selalu ada yang bisa disyukuri. (*)