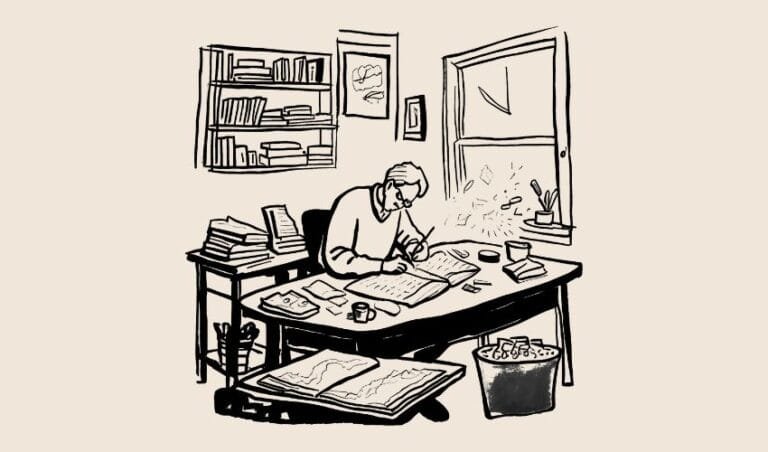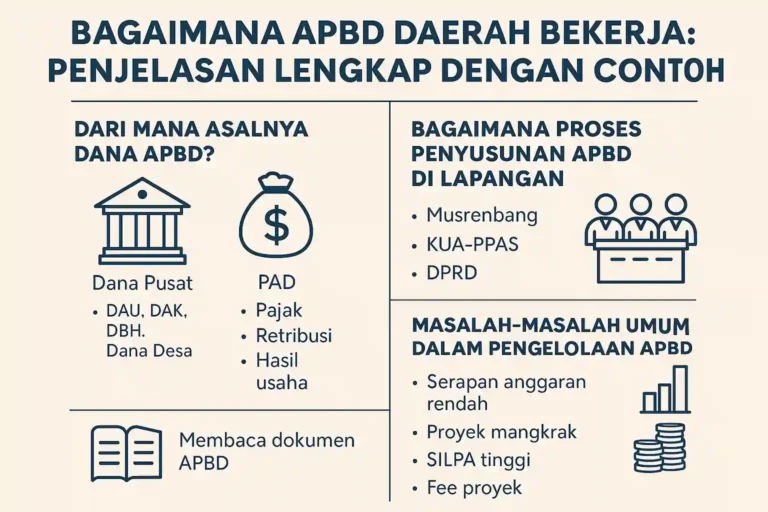Menyoal Dominasi Lembaga Fatwa di Indonesia Pasca-Orde Baru (Bagian II)

Di panggung pasca-otoritarianisme Indonesia, fatwa telah bertransformasi dari sekadar nasihat keagamaan menjadi instrumen kekuasaan yang tajam. Ia menjelma menjadi penanda batas ideologis, alat klaim otoritas, dan justifikasi bagi tindakan sosial-politik. Dalam arena pertarungan wacana keislaman ini, tiga raksasa institusional—Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah—berdiri sebagai arsitek utama, masing-masing dengan cetak biru fatwa yang merefleksikan watak ideologis dan pertarungan internal mereka. Analisis ini melanjutkan penelusuran kritis terhadap bagaimana ketiga lembaga ini, melalui mekanisme fatwanya, tidak hanya menafsirkan agama, tetapi secara aktif merekayasa lanskap sosial dan politik keagamaan di Indonesia.
MUI dan Konservatisme Religius: Antara Otoritas Moral dan Instrumen Ideologi
Runtuhnya rezim Orde Baru ternyata tidak serta-merta mengantarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuju ruang netralitas ideologis; sebaliknya, ia melepaskan MUI menjadi sebuah kekuatan semi-otonom yang dahsyat. Ironisnya, kemandirian yang baru diraih ini justru dikonsolidasikan untuk membangun benteng konservatisme keagamaan yang kokoh. Sebagaimana diungkap oleh Pradana (2017), MUI bermetamorfosis dari sekadar perpanjangan tangan “ulama negara” yang terkontrol menjadi agen ideologi yang mandiri dan berpengaruh.
Fondasi konservatisme ini adalah obsesi terhadap apa yang mereka definisikan sebagai “kemurnian” akidah Islam. Obsesi ini secara agresif termanifestasi dalam fatwa-fatwa yang melaknat pluralisme, liberalisme, dan sekularisme (PLS) sebagai paham terlarang, serta vonis sesat yang dijatuhkan kepada kelompok minoritas seperti Ahmadiyah (2005) dan Syiah (yang berulang kali disuarakan, terutama oleh MUI Jawa Timur). Meskipun dibungkus dengan retorika perlindungan keutuhan umat, dampak nyata dari fatwa-fatwa ini, seperti dicatat Pradana (2017), adalah terbukanya pintu bagi pengucilan sistematis, stigmatisasi, dan bahkan justifikasi kekerasan.
Fatwa-fatwa tersebut bukanlah sekadar teks normatif yang pasif, melainkan berfungsi sebagai instrumen ideologis yang efektif untuk memaksakan ortodoksi Islam versi mayoritas Sunni. Dalam kerangka ini, MUI lebih berperan sebagai “penjaga gerbang” (gatekeeper) hegemonik yang memiliki kuasa untuk menentukan diskursus keislaman mana yang sah dan mana yang harus diberangus, ketimbang sebuah majelis musyawarah para ulama.
Kekakuan ideologis ini tercermin pula dalam mekanisme internalnya. Proses pengambilan keputusan fatwa jauh dari deliberasi yang partisipatif. Alih-alih, ia didominasi oleh segelintir elite, khususnya yang berafiliasi dengan gagasan salafi atau neo-konservatif, yang membuat prosesnya cenderung tertutup dan resisten terhadap perbedaan pandangan. Secara metodologis, MUI kerap berlindung di balik pendekatan fikih klasik yang literalistik, dengan penekanan berlebihan pada prinsip sadd al-dzari’ah (menutup jalan menuju kemungkaran) dan amar ma’ruf nahi munkar, tanpa kepekaan yang memadai terhadap realitas kebhinekaan dan kompleksitas konteks sosial-politik Indonesia.
Relasi MUI dengan negara adalah sebuah potret ambivalensi yang strategis. Di satu sisi, ia bersedia menjadi state-sponsored religious authority yang memberikan stempel legitimasi keislaman bagi kebijakan pemerintah, mulai dari kampanye vaksinasi hingga keuangan syariah. Di sisi lain, MUI tak ragu memainkan peran sebagai polisi moral yang galak, mengkritik keras pemerintah terkait isu pornografi atau legislasi yang dianggap tidak selaras dengan syariah.
Dengan demikian, MUI terus beroperasi dalam sebuah dilema permanen: menjadi representasi negara atau pemegang otoritas umat. Posisi dilematis inilah yang membuatnya sangat strategis sekaligus problematik, terutama ketika kepentingan negara dan agenda ideologisnya tidak sejalan. Tak heran jika dominasi MUI menuai kritik tajam dari kelompok Islam progresif, LSM, dan akademisi, yang menyoroti bagaimana fatwa-fatwanya lebih sering menjadi alat untuk mempersempit ruang ekspresi keagamaan daripada merawat pluralisme. Kendati MUI berkelit bahwa fatwanya tidak mengikat secara hukum, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya: fatwanya kerap menjadi rujukan penyusunan perda syariah dan pembenar bagi aksi-aksi kekerasan oleh kelompok vigilante.
Untuk melepaskan diri dari citra sebagai penafsir ortodoksi semata dan memainkan peran yang lebih transformatif, reformasi internal di tubuh MUI adalah sebuah keniscayaan. Hal ini menuntut peningkatan inklusivitas dalam komisi fatwa, penguatan metodologi istinbath hukum yang lebih kontekstual, serta kemitraan otentik dengan akademisi. Tanpa langkah-langkah ini, MUI akan terus terperangkap dalam perannya sebagai penjaga kemurnian ideologis, bukan pelayan kemanusiaan.
Nahdlatul Ulama: Paradoks Tradisionalisme Kritis
Nahdlatul Ulama (NU) menampilkan sebuah paradoks yang menarik. Sebagai organisasi Islam terbesar, ia mengklaim tradisionalisme yang berakar pada warisan klasik (turats) melalui forum prestisiusnya, Lajnah Bahtsul Masail (LBM). Namun, tradisionalisme NU bukanlah entitas yang beku. Ia secara dinamis berupaya meramu kesetiaan pada kitab kuning dengan tuntutan modernitas, melahirkan sebuah corak pemikiran yang bisa disebut sebagai tradisionalisme kritis.
Pradana (2017) menggarisbawahi bahwa sekalipun LBM berpegang teguh pada metodologi fikih klasik, terdapat celah-celah inovasi, khususnya pada isu-isu sosial. Contohnya adalah fatwa yang memperbolehkan Keluarga Berencana (KB) atas nama kemaslahatan atau imunisasi demi menjaga kehidupan (hifdz al-nafs). Ini membuktikan bahwa di balik kepatuhannya pada mazhab Syafi’i, NU menyisakan ruang bagi ijtihad yang berorientasi pada maqashid syariah.
Metodologi kolektif melalui LBM menjadi ciri khasnya, melibatkan tiga tahapan: tahqīq al-manāth, takhrīj al-manāth, dan fatwa kolektif. Kekuatan utamanya terletak pada proses deliberatif dan akuntabilitas keulamaan. Namun, di balik fasad deliberatif ini, tersembunyi sebuah kelemahan struktural: hegemoni otoritas kiai senior yang, sebagaimana diamati oleh Bruinessen (2002), cenderung bersikap konservatif dalam isu-isu sensitif seperti relasi gender dan pluralisme agama.
Daya tarik NU terletak pada kemampuannya menjadi benteng bagi keragaman praktik keagamaan lokal—seperti tahlilan, yasinan, dan maulid—yang kerap diserang oleh kelompok puritan. Dalam narasi ini, NU memposisikan diri sebagai pembela “Islam Nusantara” yang ramah budaya. Akan tetapi, narasi besar ini tidak selalu selaras dengan produk fatwanya. Dominasi intelektual di forum LBM masih dipegang oleh tokoh-tokoh pesantren tradisional yang sangat berhati-hati terhadap perubahan sosial yang dianggap terlalu radikal.
Pradana juga mengkritisi terbatasnya partisipasi perempuan, generasi muda, dan perspektif minoritas dalam forum LBM. Arena ini masih dikuasai oleh senioritas dan pola pikir tekstual yang kaku, sehingga menghambat adopsi pendekatan hermeneutik baru atau analisis interdisipliner. Untuk menjadi kekuatan progresif yang sesungguhnya, revitalisasi LBM menjadi krusial. Forum ini harus lebih membuka diri terhadap ilmu-ilmu sosial, studi gender, dan riset lapangan yang otentik.
Pada akhirnya, NU merepresentasikan model fatwa yang unik: terjebak di antara konservatisme dan reformisme. Tradisionalisme kritisnya memang mampu menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, tetapi ia masih membutuhkan dorongan metodologis yang kuat agar fatwanya benar-benar berdampak. Potensi NU sebagai penengah polarisasi sosial-keagamaan hanya akan terwujud jika ia mampu mensintesakan otoritas tradisi dengan semangat tajdid yang inklusif dan kontekstual.
Muhammadiyah: Dilema Modernisme Revivalis
Muhammadiyah, sejak kelahirannya pada 1912, adalah personifikasi dari semangat tajdid (pembaruan) dalam Islam modernis. Semangat ini terinstitusionalisasi melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, sebuah lembaga yang bertugas merumuskan panduan keagamaan melalui ijtihad kolektif yang mengandalkan rasionalitas dalam mendekati sumber primer Islam, Al-Qur’an dan Sunnah. Ini adalah antitesis dari pendekatan fikih klasik yang dianut NU; Muhammadiyah justru mengedepankan akal, logika ilmiah, dan simplisitas hukum.
Fatwa-fatwa Majelis Tarjih adalah cerminan dari orientasi modernisme-revivalis: sebuah upaya ganda untuk memurnikan ajaran Islam dari anasir non-Islam sekaligus merespons tantangan zaman. Keterbukaannya terhadap ilmu pengetahuan tampak jelas dalam fatwa-fatwa terkait sosial-ekonomi, kesehatan, hingga teknologi. Contoh paling ikonik adalah penggunaan metode hisab hakiki wujudul hilal untuk penentuan awal bulan kamariah. Pendekatan astronomis ini menawarkan kepastian hukum, sebuah ciri modernis, namun pada saat yang sama sering kali menjadi sumber perpecahan dalam perayaan hari besar keagamaan nasional.
Di sisi lain, semangat purifikasi Muhammadiyah termanifestasi dalam penolakannya yang tegas terhadap praktik-praktik yang dianggap bid’ah, seperti tahlilan atau perayaan maulid. Bagi Muhammadiyah, pemurnian akidah adalah prasyarat kebangkitan umat. Namun, proyek puritanisme ini tak jarang membenturkannya dengan realitas kultural masyarakat tradisional dan menimbulkan resistensi.
Pradana (2017) menyoroti adanya ketegangan inheren dalam fatwa Muhammadiyah: antara idealisme progresif yang diusung oleh para elite intelektualnya dan tuntutan konservatif yang datang dari basis massanya. Misalnya, sementara Majelis Tarjih telah mengeluarkan panduan yang relatif inklusif mengenai peran perempuan, implementasinya di tingkat akar rumput, sebagaimana dicatat oleh Hooker (2008), masih menghadapi hambatan budaya dan struktural yang kuat.
Secara struktural, Majelis Tarjih bekerja secara efisien dan terpusat. Produknya, Himpunan Putusan Tarjih (HPT), menjadi rujukan doktrinal yang seragam di seluruh cabangnya. Keunggulannya adalah konsistensi dan kepastian hukum. Namun, sentralisme ini memiliki sisi gelap: ia mengebiri ruang dialektika lokal dan menjadikan proses ijtihad bersifat elitis, hanya untuk para pakar terpilih.
Meskipun menyandang predikat pelopor pendidikan dan kesehatan modern, fatwa-fatwa Muhammadiyah ironisnya belum sepenuhnya mengadopsi perspektif interdisipliner. Pertimbangan hukumnya masih sangat didominasi oleh logika tekstual dan formal, dengan sedikit ruang bagi pendekatan empiris atau dialog mendalam dengan masyarakat terdampak. Hal ini berisiko membuat fatwa-fatwanya menjadi normatif dan formalistik, namun kurang efektif dan sulit diterima secara sosial.
Dengan demikian, Majelis Tarjih dan Tajdid adalah representasi dari dilema modernisme Islam: mengejar rasionalitas, konsistensi, dan purifikasi, namun terkadang gagap dalam menghadapi pluralitas dan dinamika sosial. Agar tetap relevan, Muhammadiyah ditantang untuk memperluas cakrawala tarjih-nya dengan membuka partisipasi yang lebih inklusif, mengakomodasi keragaman budaya lokal, dan menjadikan riset sosial-keagamaan sebagai pilar dalam pengambilan fatwa. Hanya dengan cara itu, fatwanya bisa bertransformasi dari sekadar produk hukum formal menjadi solusi responsif bagi realitas umat.
Editor: Muhammad Farhan Azizi