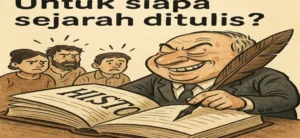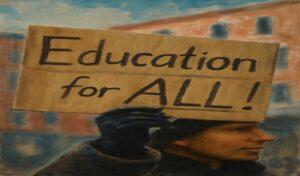Menemukan Kembali Kebebasan Berpikir

Saya selalu teringat pada sebuah pagi di kampus ketika seorang dosen—dengan senyum tipis yang menyiratkan jarak hierarkis—menjelaskan bahwa “apa pun yang tertulis di buku teks itu sudah benar, tugas kalian hanya menyerap.” Ucapan itu, diiringi ketukan ringan spidol pada papan tulis, terasa bagai gong pembuka pertunjukan besar: pertunjukan tentang bagaimana para mahasiswa, yang tumbuh dengan idealisme dan rasa ingin tahu, perlahan‑lahan dilatih untuk patuh, diam, dan—tanpa disadari—menjadi penonton pasif di ruang kelas mereka sendiri.
Dalam kisah kebudayaan kampus kita, posisi dosen sering kali tidak sekadar pengampu mata kuliah, melainkan penentu kebenaran mutlak. Mahasiswa yang mempertanyakan dianggap kurang ajar, sementara yang “ruwet” dicap sok kritis. Maka terciptalah budaya “mahasiswa lugu”—bukan karena mereka bodoh, melainkan karena kultur akademik memaksa mereka memilih sikap tunduk demi harmoni, IPK, dan kelulusan yang lancar.
Sejak masa orientasi, sebuah narasi halus ditanamkan: “hormati dosen, jangan banyak tanya, ikuti petunjuk.” Narasi ini tampak wajar—bukankah sopan santun adalah bagian dari kebudayaan timur? Namun, di baliknya tersembunyi mekanisme kekuasaan yang efektif. Dosen, sebagai pemegang otoritas nilai, memiliki kuasa menentukan nasib akademik.
Para mahasiswa yang lugu kerap kali menegosiasi diri: apakah sepadan merisikokan nilai hanya untuk mendebat argumen lemah di kelas? Kebanyakan memilih diam. Kebisuan itu, dari waktu ke waktu, menumpuk jadi kesadaran kolektif: lebih baik mengangguk daripada meragukan, lebih aman mencatat daripada mempertanyakan. Akhirnya, ruang kelas kehilangan gema diskusi; yang tersisa hanyalah monolog sang dosen—seperti panggung tunggal yang tak butuh penonton aktif.
Ada sebuah pengalaman yang pernah dibagikan oleh seorang teman–yang tidak perlu disebutkan namanya. Kala itu, ia mengenal salah satu dosen yang reputasinya disegani. Oleh dosennya, ia diajak menggarap artikel ilmiah yang kemudian dipublikasi di suatu jurnal. Lalu, alih-alih berdagang, jurnal itu kemudian dijadikan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) di Fakultas. Semua mahasiswa Fakultas diwajibkan membeli jurnal untuk bisa mengikuti UAS, sementara tidak semua program yang ada di Fakultas itu beririsan dengan isi artikel jurnal.
Akhirnya ia pun menginisiasi aksi penolakan membeli jurnal. Alih-alih mencari keadilan ia dibungkam, sementara temannya yang lain menelan pelajaran bisu. Budaya kultural ini melahirkan mahasiswa yang mudah “dibodoh‑bodohi”. Bukan karena kurang kecerdasan, melainkan karena kecerdasan mereka tidak diizinkan beroperasi. Dosen, dengan wibawa formal, memosisikan diri sebagai satu‑satunya sumur pengetahuan—padahal hakikat ilmu justru tumbuh dalam adu argumen.
Fenomena ini diperparah oleh sistem evaluasi. Tugas reflektif yang seharusnya mendorong daya kritis berujung pada format “ringkasan bab” atau “resume kuliah.” Kreativitas diukur lewat kesamaan perspektif dengan dosen. Demikianlah modus kekuasaan bekerja—menjinakkan potensi kritis melalui mekanisme penilaian. Kebudayaan akademik di kampus, alih‑alih merayakan pertentangan ide justru merawat kepatuhan demi stabilitas administrasi.
Namun budaya “keluguan” mahasiswa tak lahir secara sepihak. Ada faktor internal: kebutuhan akan rasa aman, motivasi memperoleh gelar, dan tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, banyak dari para mahasiswa pun terperangkap kontradiksi. Di satu sisi, idealisme menuntut ruang kritis; di sisi lain, beban finansial—UKT, SPP, DPP, biaya hidup, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya—membisikkan urgensi lulus tepat waktu.
Akibatnya, kompromi menjadi strategi bertahan: diskusi keras dilakukan di kafe, bukan di kelas. Ada semacam skizofrenia intelektual—di luar ruang kuliah kita garang, di hadapan dosen kita tunduk. Budaya ini perlahan menormalisasi diri: ketimpangan kuasa diterima sebagai kodrat, bukan problem struktural yang perlu dirombak.
Kebudayaan kampus sesungguhnya bisa menjadi ruang latihan demokrasi intelektual, tempat dosen dan mahasiswa berdialektika setara. Sayangnya, tradisi feodal masih mengakar. Bahasa tubuh dosen—dari cara duduk di podium hingga sapaan “kalian belum apa‑apa”—menegaskan jarak.
Lalu lahirlah ritual komunikasi yang timpang: ketika dosen bertanya “ada pertanyaan?”, ruangan hening bukan karena semuanya paham, melainkan karena takut salah. Di titik inilah saya menyadari, kebudayaan “mahasiswa lugu” tidak lahir dari satu sumber; ia diproduksi oleh jaringan aturan tak tertulis, norma sosial, dan kepentingan institusi yang membutuhkan mahasiswa patuh sebagai bukti kesuksesan program.
Meski demikian, perlawanan tetap muncul, walau sering diperlemah labelisasi. Mahasiswa kritis kerap distigma radikal, nakal, bahkan “pengacau.” Stigma ini efektif mengisolasi dibandingkan argumen substantif.
Saya pernah menyaksikan seorang mahasiswa diancam drop out karena mencoba terlibat aktif sebagai agent of social control–menjadi korlap aksi “Tolak RUU TNI”. Alih‑alih dimintai keterangan, maksud dan tujuan atau penjelasan lanjut, ia dituduh “tidak menghormati” ilmu, urakan, setan, bahkan dajjal. Stigma ini kemudian menjadi alat kultural untuk mempertahankan status quo, sebab yang diserang bukan gagasan, melainkan identitas pribadi. Efeknya, mahasiswa lain ciut, kembali ke mode aman: lugu, manut, dan siap “dibodoh‑bodohi” logika institusi.
Namun lugu tidak identik dengan bodoh. Di balik citra pasif, para mahasiswa sebenarnya menyimpan kecerdasan sosial—kemampuan membaca situasi, memilih medan perlawanan, dan merancang siasat belajar alternatif. Surat kabar mahasiswa, diskusi daring, dan komunitas kajian mandiri menjadi ruang tandingan.
Di sana, teori justru diulik secara kritis, jauh dari tatapan dosen. Ironisnya, kualitas percakapan di ruang informal sering melampaui kuliah formal. Artinya, “bodoh‑bodohi” di ruang kelas tak berarti mahasiswa tereliminasi dari pencarian ilmu; mereka hanya memindahkan locus belajar ke wilayah kurang terpantau.
Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya kampus yang menindas daya kritis tak mampu membungkam rasa ingin tahu—ia hanya memaksa mahasiswa menemukan jalur tersendiri.
Pada titik ini, tanggung jawab juga terletak pada dosen. Kekuasaan bisa digunakan untuk membuka ruang, bukan menutupnya. Saya teringat satu pengajar tamu yang memulai kuliah dengan kalimat, “Saya juga belajar dari kalian.”
Setelah itu, diskusi meluncur bebas; kami berdebat keras, ia menanggapi setara. Tak ada ancaman nilai; yang ada hanya argumentasi. Kuliah dua jam terasa singkat, tetapi mengubah cara kami memandang kelas: ia bukan lagi ruang pengukuhan hierarki, melainkan laboratorium ide. Saya percaya, contoh semacam itulah benih kebudayaan akademik yang sehat. Dosen bukan menara gading, melainkan fasilitator yang memancing kegelisahan intelektual.
Menulis esai ini membuat saya bertanya: bagaimana menggeser budaya “mahasiswa lugu dibodoh‑bodohi” menuju budaya “mahasiswa kritis berdaulat”? Pertama, perlu reformasi sistem penilaian—dari penekanan hafalan menuju penghargaan atas argumentasi. Kedua, institusi harus melindungi hak mahasiswa mengkritik tanpa takut sanksi. Ketiga, dosen perlu latihan pedagogi dialogis, agar otoritas ilmiah diimbangi kerendahan hati intelektual. Keempat, mahasiswa mesti menyadari bahwa ke‑lugu‑an bukan sifat alamiah, melainkan konstruksi kultural yang bisa dirobohkan lewat solidaritas dan keberanian bersuara. Institusi pendidikan harus menyadari konsekuensi logis dari sebuah pencerahan diri seorang berpengetahuan, mereka tak mungkin diam melihat kedzaliman.
Pada akhirnya, kampus adalah miniatur masyarakat. Jika di dalamnya kritik dibungkam dan pengetahuan dimonopoli, bagaimana kita berharap masyarakat luas menjadi demokratis? Kultur “mahasiswa lugu” mungkin tampak remeh, tetapi dampaknya meluas: lulusan yang terbiasa diam akan menjadi profesional yang enggan bertanya, warga negara yang alergi diskusi publik, intelektual yang sekadar mengekor arus. Oleh karena itu, menggugat budaya ini bukan sekadar perjuangan internal kampus, melainkan upaya membangun kecerdasan kolektif bangsa.
Saya ingin menutup refleksi ini dengan satu keyakinan: mahasiswa tak pernah benar‑benar bodoh, mereka hanya disuruh percaya bahwa keheningan adalah emas. Saat keheningan itu pecah—entah lewat diskusi, tulisan, atau aksi—kita akan melihat betapa dalam reservoir gagasan yang selama ini tersembunyi. Dan ketika dosen berhenti merasa berkuasa mutlak, ruang kelas akan berubah menjadi arena pertarungan ide yang menggembirakan. Di sanalah, akhirnya, lugu berganti luwes, patuh berganti partisipasi, dan kebudayaan akademik kita menemukan kembali jiwa yang semestinya: kebebasan berpikir. (*)