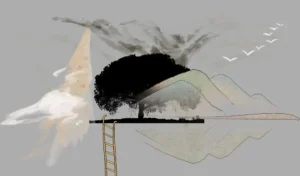Cara Menerima Kenyataan Hidup yang Tolol dan Mengesalkan

Ada satu hal yang tak pernah gagal membuat manusia kesal: kenyataan. Ia hadir tanpa diundang, tanpa permisi, dan sering kali dengan wajah tolol yang menyebalkan. Seolah-olah hidup ini adalah panggung sandiwara murahan, di mana aktor-aktornya bermain setengah hati, naskahnya ditulis dengan ceroboh, dan sutradaranya tampak absen. Kita dipaksa memainkan peran yang kadang kita benci, lalu tetap harus berdiri tegar meski tepuk tangan tak kunjung datang.
Betapa sering kita menemukan hal-hal yang terasa absurd. Orang yang malas justru mendapat keuntungan, sementara yang bekerja keras digilas keadaan. Orang yang licik melesat naik, sementara yang jujur tertinggal. Orang yang bodoh menguasai panggung, sementara yang cerdas hanya menonton dari bangku penonton. Dan dunia, dengan wajah tanpa rasa bersalah, menatap kita sambil berkata: “Ya, begitulah kenyataan. Mau apa?”
Di sinilah kita mulai bertanya: bagaimana cara menerima kenyataan hidup yang tolol dan mengesalkan ini? Apakah cukup dengan sabar? Apakah cukup dengan pasrah? Atau perlu ada cara lain yang lebih manusiawi—lebih masuk akal—untuk tidak sekadar menerima, tetapi juga bisa tetap hidup tanpa kehilangan kewarasan?
Mari kita menelusuri jawabannya pelan-pelan.
Ketololan Hidup Sebagai Realitas
Logika mengatakan, jika kita rajin belajar, nilai kita akan bagus. Jika kita bekerja keras, kita akan berhasil. Jika kita berbuat baik, kita akan menuai kebaikan. Namun, betapa sering hidup menampar wajah kita dengan kenyataan sebaliknya. Nilai bagus justru sering dibeli dengan uang. Kesuksesan datang kepada mereka yang punya jalur istimewa. Kebaikan dibalas dengan pengkhianatan.
Di titik ini kita sadar, hidup tidak tunduk pada hukum logika semata. Ia punya jalannya sendiri, jalur absurd yang penuh belokan aneh dan tikungan licin. Kita boleh marah, boleh protes, boleh mengutuk, tetapi dunia tidak peduli.
Kebodohan dalam hidup bukan sekadar soal individu, tetapi juga soal sistem. Lihatlah birokrasi: tumpukan kertas, tanda tangan berlapis, dan prosedur berbelit. Semua itu sering kali tidak ada hubungannya dengan efisiensi, melainkan sekadar mempertahankan absurditas. Aturan yang dibuat tidak untuk memudahkan, tetapi justru untuk mempersulit.
Bukankah tolol namanya jika mengurus sesuatu yang sederhana justru dibuat rumit? Tetapi anehnya, orang-orang terbiasa. Mereka pasrah, menerima kebodohan itu sebagai normalitas.
Lebih parah lagi, ketololan hidup sering diwariskan turun-temurun. Kita dibesarkan dengan nasihat klise: sabar saja, ikhlas saja, jangan melawan. Padahal kenyataan tidak berubah dengan sekadar nasihat kosong. Sering kali, yang diwariskan hanyalah pola pasrah tanpa daya. Akibatnya, kita terbiasa menerima kebodohan sebagai takdir.
Mengapa Hidup Mengesalkan?
Sumber utama rasa kesal adalah ekspektasi. Kita berharap dunia berjalan sesuai logika, lalu kecewa ketika yang terjadi justru sebaliknya. Kita mengira kebaikan akan selalu menang, padahal sering kali kalah. Kita percaya kerja keras akan dihargai, padahal banyak yang diabaikan.
Ekspektasi adalah jebakan manis. Ia membuat kita merasa berhak, padahal kenyataan tidak pernah janji apa pun.
Manusia tidak bisa lepas dari kebiasaan membandingkan. Kita melihat orang lain yang lebih sukses, lebih dihargai, lebih bahagia, lalu merasa kesal pada hidup sendiri. Kita lupa bahwa setiap orang berjalan dengan jalan tololnya masing-masing. Perbandingan hanya mempertebal rasa iri dan sakit hati.
Kesal juga lahir dari ego. Kita merasa berhak mengendalikan segalanya, padahal kendali kita sangat terbatas. Ego menuntut dunia tunduk pada keinginan kita, dan ketika dunia menolak, yang tersisa hanyalah kekecewaan.
Cara Menerima Kenyataan yang Tolol dan Mengesalkan
Di sinilah pertanyaan besar muncul: bagaimana cara menerima kenyataan itu? Jawabannya tentu bukan sekadar “ikhlas” atau “sabar.” Kata-kata itu sudah terlalu sering diucapkan, tetapi jarang benar-benar membantu.
Mari kita gali lebih dalam.
Langkah pertama adalah mengakui bahwa hidup memang sering tolol. Jangan menutup mata dengan kalimat manis atau harapan kosong. Jika hidup menyebalkan, katakan saja: ya, memang menyebalkan. Pengakuan ini penting agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam penyangkalan.
Seperti menghadapi orang bodoh: jika kita sadar ia bodoh, kita berhenti berharap ia akan bersikap cerdas. Demikian pula dengan hidup.
Kebodohan hidup, jika ditanggapi terlalu serius, akan melumat habis kewarasan. Karena itu, belajar menertawakan absurditas adalah bentuk perlawanan. Tawa menjadi senjata untuk menjaga hati tetap ringan.
Menertawakan bukan berarti menyepelekan. Ia adalah cara untuk berkata: “Aku tidak akan ikut tenggelam dalam kebodohan yang sama.”
Hidup penuh hal-hal di luar kendali kita. Cuaca, keputusan orang lain, keberuntungan, bahkan hasil dari usaha kita sendiri—semua itu tidak bisa kita atur sepenuhnya. Yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap dan pilihan kita sendiri.
Daripada mengutuk kenyataan, lebih baik mengatur langkah kita. Fokus pada hal-hal kecil yang masih bisa kita genggam.
Rasa kesal jangan dibuang. Ia bisa diolah menjadi energi. Banyak orang besar lahir karena muak dengan kenyataan. Mereka menjadikan kekesalan sebagai dorongan untuk bergerak, mencipta, memperbaiki.
Kesal bisa membuat kita menulis, berjuang, atau bahkan sekadar bertahan lebih lama. Dalam dunia yang tolol, bertahan dengan kepala tegak saja sudah bentuk kemenangan.
Humor adalah kunci bertahan hidup. Lihatlah orang-orang yang bisa tertawa meski hidupnya berantakan. Mereka mungkin tidak kaya, tidak punya jabatan, tetapi mereka punya senjata yang ampuh: kemampuan menertawakan luka.
Humor tidak menghapus derita, tetapi membuat derita lebih bisa ditanggung.
Contoh-Contoh dalam Kehidupan
Seorang karyawan bekerja keras, tetapi promosi justru jatuh ke tangan rekan yang pandai menjilat. Situasi ini jelas tolol dan mengesalkan. Apa yang bisa dilakukan? Marah? Keluar? Atau tetap bekerja sambil mengumpat dalam hati?
Cara yang lebih sehat adalah menerima kenyataan bahwa dunia kerja tidak selalu adil. Lalu fokus pada apa yang bisa dikendalikan: meningkatkan keahlian, mencari peluang baru, atau bahkan menertawakan kebodohan sistem yang lebih mementingkan pencitraan daripada kualitas.
Ada kalanya kita bertemu orang-orang yang logikanya jungkir balik. Mereka marah tanpa alasan, menyalahkan kita atas hal-hal yang bukan kesalahan kita, bahkan menyebarkan gosip tanpa dasar. Apakah kita harus ikut gila?
Tidak. Kadang lebih bijak untuk mengangguk sambil tersenyum, lalu menertawakan kebodohan itu dalam hati. Karena jika semua diladeni dengan serius, hidup kita hanya penuh dengan amarah.
Kadang kita sendiri yang membuat hidup tolol. Rencana gagal, uang hilang, cinta kandas. Kita marah pada diri sendiri, menyesali, menyalahkan. Tetapi pada akhirnya, semua itu bagian dari absurditas hidup.
Belajar memaafkan diri sendiri adalah bagian dari menerima kenyataan. Kita pun manusia, penuh salah, penuh kekonyolan.
Filosofi Menerima
Para filsuf Stoa mengajarkan: jangan resah pada hal-hal di luar kendali kita. Kendalikan hanya pikiran dan sikap. Filosofi ini cocok untuk menghadapi dunia tolol. Saat orang bodoh naik jabatan, katakan: itu di luar kendaliku. Saat dunia tidak adil, katakan: tugasku hanya mengatur diriku sendiri.
Filsuf eksistensialis seperti Camus melihat hidup sebagai absurditas. Hidup memang tidak punya makna yang jelas, maka tugas manusia adalah menciptakan makna sendiri. Dalam absurditas itu, kita punya kebebasan untuk menentukan sikap.
Dengan cara ini, ketololan hidup bukan ancaman, melainkan panggung untuk kita berimprovisasi.
Dalam budaya kita, ada ungkapan: “Urip mung mampir ngombe” (hidup hanya mampir minum). Ungkapan ini mengingatkan bahwa hidup sementara. Maka, kalaupun tolol dan mengesalkan, untuk apa terlalu serius? Nikmati saja sebisanya.
Hidup Sebagai Komedi Absurd
Pada akhirnya, hidup memang tidak selalu indah. Ia tolol, ia mengesalkan, ia kadang membuat kita ingin menyerah. Tetapi justru di situlah tantangannya. Menerima hidup bukan berarti berhenti berjuang, melainkan menyadari bahwa perjuangan itu sendiri sudah bernilai.
Hidup adalah komedi absurd, dan kita adalah aktornya. Alih-alih mengutuk naskah yang buruk, lebih baik kita belajar improvisasi. Siapa tahu, dari ketololan itu justru lahir kisah paling jujur dan paling manusiawi.
Jadi, bagaimana cara menerima kenyataan hidup yang tolol dan mengesalkan? Dengan sadar, dengan tertawa, dengan bertahan, dan dengan terus melangkah meski dunia tampak tidak masuk akal. Karena pada akhirnya, mungkin justru di situlah makna hidup tersembunyi: dalam kemampuan kita bertahan di tengah ketololan yang tak pernah usai.