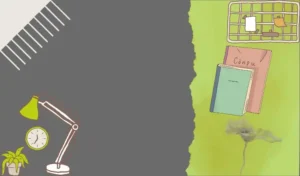Batas Tipis antara Kebijakan, Kelalaian, dan Kriminalisasi dalam Kasus Tom Lembong

Kasus hukum yang menjerat Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menimbulkan respons publik yang luas. Ia adalah mantan Menteri Perdagangan Indonesia yang dikenai vonis pidana dalam kasus impor gula. Proses hukum ini memancing banyak opini karena tokoh yang terlibat dikenal luas sebagai profesional dengan reputasi baik. Diskursus publik pun menjadi dinamis antara pembelaan dan kritik.
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pemberian izin impor gula oleh pihak swasta pada tahun 2015–2016. Menurut Kejaksaan, izin tersebut diberikan tanpa rekomendasi teknis dari kementerian terkait dan bertentangan dengan kebijakan nasional. Kerugian negara dihitung berdasarkan selisih harga jual dan harga pokok dari gula yang diimpor swasta. Meski tidak ada bukti keuntungan pribadi, Tom tetap dijatuhi hukuman karena kelalaian dalam proses.
Vonis terhadap Tom Lembong menuai banyak komentar. Sebagian mendukung langkah hukum sebagai bentuk akuntabilitas pejabat publik. Namun sebagian lain menyebutnya terlalu berat dan dipenuhi nuansa politis. Perdebatan ini wajar terjadi dalam masyarakat demokratis. Yang penting adalah membedakan antara persepsi dan fakta hukum.
Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan lima penyimpangan administratif dalam kebijakan impor gula saat itu. Di antaranya adalah ketiadaan rapat koordinasi antar kementerian dan pemberian izin kepada swasta, bukan kepada BUMN. Hal ini dianggap sebagai penyebab utama kerugian negara. Audit tersebut menjadi landasan Kejaksaan untuk menjerat Tom.
Namun, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2018 menunjukkan bahwa tidak ada kerugian negara akibat impor tersebut. Ini menunjukkan adanya dua pandangan teknokratik yang berbeda. Perbedaan ini menjadi bahan perdebatan yang valid. Dalam konteks hukum, penting untuk menjelaskan mengapa satu audit dipilih dan yang lain diabaikan.
Aspek penting lain dalam kasus ini adalah konteks pengambilan keputusan. Saat menjabat, Tom Lembong berada dalam tekanan untuk menjaga stabilitas harga dan stok bahan pokok. Impor merupakan salah satu cara cepat untuk mengatasi krisis pasokan. Keputusan itu tidak diambil secara pribadi, melainkan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah.
Namun demikian, ada prosedur hukum dan administratif yang harus diikuti. Jika memang terbukti izin dikeluarkan tanpa rekomendasi kementerian teknis, maka itu merupakan pelanggaran prosedural. Dalam hukum administrasi, kelalaian juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Meski tidak ada niat jahat, unsur kesalahan tetap relevan secara hukum.
Pada titik ini, debat publik muncul karena penilaian atas niat dan akibat. Ada yang menilai Tom sekadar melakukan kesalahan administratif. Ada pula yang menilai bahwa ia telah melampaui wewenang dan menimbulkan kerugian negara. Perbedaan persepsi ini perlu dikaji dengan pendekatan hukum dan etika administrasi negara.
Beberapa pengamat hukum menilai pasal yang digunakan terlalu longgar. UU Tindak Pidana Korupsi memungkinkan penjatuhan pidana hanya berdasarkan kerugian negara yang “potensial”. Konsep ini masih menjadi perdebatan dalam ilmu hukum. Hal ini memberi ruang besar bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan perbuatan.
Dalam praktiknya, banyak pejabat lain yang juga mengambil kebijakan serupa tanpa dijerat hukum. Ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum. Mengapa hanya Tom yang diproses? Jika alasan hukum murni digunakan, maka pejabat lain dengan tindakan serupa juga harus ditindak. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan kecurigaan.
Aspek lain yang juga mencuat adalah kemungkinan muatan politik. Tom dikenal mendukung pasangan oposisi dalam Pilpres 2024. Oleh karena itu, beberapa pihak menduga kasus ini memiliki dimensi politis. Namun, tuduhan ini sulit dibuktikan tanpa data kuat. Maka, penting untuk bersikap netral dan menilai berdasarkan fakta hukum.
Kejaksaan Agung sendiri membantah adanya motif politik. Mereka menyatakan kasus ini murni hasil penyelidikan atas laporan masyarakat dan audit keuangan negara. Jaksa juga menegaskan bahwa Tom tidak dijerat karena afiliasi politiknya. Hal ini patut dihormati sebagai pernyataan resmi, kecuali ada bukti sebaliknya.
Di sisi lain, simpati publik terhadap Tom cukup besar. Banyak kalangan menilai ia adalah figur reformis dan profesional. Ia dikenal vokal dalam menyuarakan transparansi dan reformasi birokrasi. Maka, publik merasa janggal jika tokoh semacam itu dijerat karena kesalahan administratif. Rasa kejanggalan inilah yang memicu empati.
Netizen di media sosial, khususnya di Reddit dan X, banyak yang mendiskusikan kasus ini dengan nada skeptis. Beberapa menyebutnya sebagai bentuk kriminalisasi. Yang lain menyebut ini sebagai pembelajaran bahwa kelalaian administratif bisa berdampak besar. Diskusi ini memperlihatkan bahwa publik mulai sadar akan pentingnya prosedur.
Sebagai negara hukum, Indonesia harus mengedepankan asas due process dan keadilan. Hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan. Jika seseorang tidak mengambil keuntungan pribadi dan tidak berniat merugikan negara, maka hukum harus mempertimbangkan faktor tersebut. Ini bukan berarti membebaskan, tapi menilai secara adil.
Di sisi lain, pejabat publik harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tanda tangan kebijakan bukan sekadar formalitas. Ia punya dampak hukum dan ekonomi yang besar. Kasus Tom menjadi pelajaran bahwa jabatan publik penuh risiko jika prosedur dilanggar.
Dalam ilmu administrasi publik, ada konsep “administrative liability”. Ini berarti pejabat bisa bertanggung jawab tanpa adanya niat jahat. Hal ini digunakan untuk menjaga akuntabilitas birokrasi. Namun, penerapannya harus dengan standar yang jelas agar tidak menjadi alat politik.
Penting pula untuk mengkaji kembali mekanisme koordinasi lintas kementerian. Jika memang tidak ada sistem peringatan atau review atas kebijakan yang menyimpang, maka kesalahan akan terus berulang. Kasus ini menunjukkan pentingnya sistem pengawasan internal di pemerintahan.
Ke depan, penegakan hukum harus dilakukan dengan standar yang konsisten. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum digunakan untuk menekan lawan politik. Namun, tidak pula boleh memberi kekebalan bagi pejabat yang melakukan kesalahan. Keseimbangan inilah yang menjadi inti negara hukum.
Tom Lembong sendiri menyatakan akan menempuh upaya banding. Ini adalah hak hukum yang sah dan harus dihormati. Pengadilan tingkat lebih tinggi diharapkan memberi penilaian yang lebih objektif. Proses ini juga menjadi ajang uji integritas sistem hukum kita.
Penting pula bagi publik untuk tidak serta-merta menyimpulkan tanpa membaca dokumen hukum yang lengkap. Informasi di media sosial seringkali terbatas. Penilaian harus berbasis pada putusan, bukti, dan argumentasi hukum yang utuh. Sikap kritis harus dibarengi dengan kehati-hatian.
Bagi kalangan profesional dan pembuat kebijakan, kasus ini menyampaikan pesan bahwa integritas saja tidak cukup. Kepatuhan terhadap prosedur adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Bahkan niat baik pun bisa berujung pada pidana jika prosedur dilanggar.
Dari sisi lembaga negara, ini juga menjadi bahan refleksi. Apakah sistem birokrasi sudah cukup kuat dalam mencegah pelanggaran prosedur? Apakah sistem peringatan dini berjalan baik? Jika tidak, maka perlu reformasi kelembagaan yang lebih sistemik.
Masyarakat pun belajar bahwa hukum administrasi bukan hanya soal aturan teknis. Ia punya dampak nyata terhadap kebijakan publik dan kehidupan rakyat. Maka, partisipasi publik dalam mengawasi proses pemerintahan harus terus ditingkatkan.
Sebagai kesimpulan, kasus Tom Lembong adalah contoh kompleksitas hubungan antara kebijakan publik, prosedur hukum, dan persepsi masyarakat. Tidak mudah menilai siapa benar atau salah secara mutlak. Namun, dengan pendekatan ilmiah dan objektif, kita bisa memetakan masalah secara adil.
Kita perlu menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Semua pejabat harus bertanggung jawab, tetapi dengan ukuran yang proporsional dan adil. Tidak boleh ada impunitas, tapi juga tidak boleh ada kriminalisasi.
Kasus ini adalah ujian bagi hukum, pemerintahan, dan masyarakat sipil Indonesia. Bagaimana kita merespons akan menentukan arah demokrasi dan keadilan kita ke depan. (*)