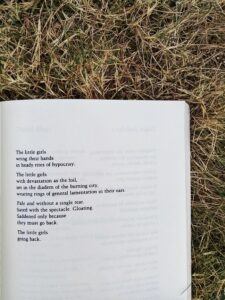Antara Musik yang Mengguncang dan Rumah yang Bergetar

Saya bukan bagian dari komunitas sound horeg. Saya hanya seorang pembaca buku musik. Tapi akhir-akhir ini, setiap membuka berita daring atau media sosial, yang muncul justru bukan diskusi tentang harmoni atau instrumen, melainkan tentang sound horeg. Istilah itu, yang dulu mungkin terasa asing, kini menjadi topik nasional. Di satu sisi, ia dipuja sebagai pesta rakyat yang meriah. Di sisi lain, ia dituding merampas hak dasar warga untuk beristirahat.
Kasus-kasus yang muncul membuat saya tak bisa hanya menontonnya sebagai penonton pasif. Di Malang, misalnya, sebuah karnaval sound horeg pada pertengahan Juli berujung ricuh. Seorang warga yang anaknya sedang sakit protes karena rumahnya bergetar hebat. Suaranya, yang mungkin hanya berupa permintaan sederhana agar sedikit dikecilkan, berubah jadi perdebatan panas. Peserta karnaval tersulut, lalu terjadi dorong-dorongan yang hampir berakhir dengan adu jotos. Polisi akhirnya turun tangan, memfasilitasi mediasi, dan persoalan selesai dengan kompensasi uang. Tetapi bagi warga yang rumahnya terguncang, apakah masalah benar-benar selesai dengan rupiah?
Di Kediri, cerita lain muncul. Seorang warga bernama Eko Mariyono sejak lama menolak kehadiran sound horeg. Bukan karena ia anti musik, tapi karena menurutnya suara itu sudah melampaui batas toleransi manusia. Protesnya justru berbuah tekanan. Rombongan sound horeg sengaja berhenti di depan rumahnya, menyalakan volume keras berjam-jam seolah menantang. Lebih jauh lagi, fotonya bersama keluarga tersebar di media sosial, dijadikan bahan intimidasi. Di sini kita melihat bukan sekadar persoalan kebisingan, melainkan persoalan sosial: sebuah komunitas merasa terancam oleh kritik, dan warga yang bersuara balik merasa terintimidasi.
Cerita lain datang dari Surabaya. Seorang ibu muncul dalam video viral, meminta peserta sound horeg menghentikan dentuman karena kaca rumahnya hampir pecah. “Kalau pecah siapa yang ganti?” katanya dalam rekaman. Video itu terasa jujur, sederhana, dan membuat saya merenung: sejak kapan musik—yang seharusnya membawa keindahan—berubah jadi sumber ketakutan di ruang domestik?
Namun tentu tidak adil jika hanya melihat sound horeg sebagai ancaman. Bagi banyak anak muda desa dan kota kecil, acara ini adalah panggung kebanggaan. Operator sound system merasa kreativitas mereka teruji ketika dentuman bass mampu “mengguncang bumi”. Di balik pengeras suara raksasa itu, ada ekonomi rakyat: tukang sewa, penjual makanan, pengrajin kayu untuk box speaker, hingga remaja yang mendapat hiburan murah. Bagi sebagian orang, sound horeg adalah ekspresi kebebasan, bahkan identitas kultural. Menyalahkan mereka secara total sama artinya menutup telinga terhadap kegembiraan komunitas.
Pemerintah daerah, menyadari kontroversi yang kian panas, akhirnya mengeluarkan surat edaran dan membentuk tim khusus. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melibatkan kepolisian, dokter THT, ahli hukum, hingga Majelis Ulama Indonesia. Tim ini dimaksudkan untuk menyusun aturan yang adil: bukan melarang total, tapi mencari batas wajar antara kebebasan berekspresi dan hak atas ketenangan. Bagi saya, langkah ini penting, meski surat edaran pada tahap awal sering terasa abstrak. Apalah artinya larangan jika tidak ada standar teknis yang jelas—berapa desibel maksimal, berapa lama durasi, dan di mana lokasi yang diperbolehkan?
Saya teringat teori tentang eksternalitas dalam kebijakan publik. Ketika seseorang menikmati manfaat privat, tapi dampaknya menimbulkan biaya sosial, negara biasanya turun tangan. Seperti pabrik yang menimbulkan polusi udara, atau kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi. Sound horeg berada di ranah serupa. Operator dan penikmat mendapat kesenangan, ekonomi lokal ikut bergerak, tetapi warga di sekitarnya menanggung kerugian: kaca bergetar, bayi terbangun, bahkan kesehatan telinga jangka panjang bisa terancam. WHO pernah menegaskan bahwa paparan suara di atas 85 desibel dalam jangka lama bisa menimbulkan gangguan pendengaran permanen. Artinya, ini bukan sekadar “ribut” atau “tidak sopan”, melainkan persoalan kesehatan publik.
Namun saya juga paham, kebijakan yang lahir tanpa empati bisa menjadi pisau yang tumpul atau bahkan menyakiti. Melarang secara total tanpa memberi ruang bagi komunitas untuk menyalurkan kreativitas hanya akan melahirkan resistensi. Apalagi di era media sosial, larangan bisa dibaca sebagai penindasan budaya lokal. Itulah sebabnya solusi yang paling masuk akal bukan hitam putih, melainkan abu-abu yang lentur: zonasi yang jelas, batas waktu yang ketat, kompensasi jika ada kerusakan, dan tentu saja ruang dialog yang setara.
Di tengah hiruk pikuk ini, suara warga biasa sebenarnya sangat berharga. Di Reddit Indonesia, misalnya, muncul komentar yang sederhana tapi tajam: “Semoga kebiasaan buruk ini segera punah.” Ada juga yang berkata, “Kalau tidak bisa dilarang, setidaknya diatur, karena bisa membahayakan bayi, lansia, dan orang dengan penyakit jantung.” Kalimat-kalimat semacam itu, meskipun terdengar keras, sebenarnya mencerminkan kegelisahan sehari-hari. Warga tidak sedang berteori tentang musik atau kebijakan publik. Mereka hanya ingin tidur nyenyak, merawat orang tua tanpa dentuman, atau menjaga anak kecil tanpa takut kaca jendela pecah.
Saya membayangkan jika diskusi ini diubah menjadi forum nyata. Komunitas sound horeg duduk bersama warga yang rumahnya bergetar, pemerintah hadir sebagai mediator, dokter menjelaskan dampak kebisingan, dan operator sound system diberi kesempatan menunjukkan inovasi mereka tanpa harus merusak lingkungan sosial. Bayangan itu mungkin terasa idealis, tetapi bukan mustahil. Bukankah seni sejatinya bertujuan mempertemukan, bukan memisahkan?
Pada akhirnya, bagi saya, sound horeg adalah cermin kecil dari bagaimana masyarakat kita mengelola perbedaan. Apakah kita memilih jalan adu jotos di Malang, intimidasi di Kediri, dan kaca bergetar di Surabaya? Atau kita bisa menemukan cara agar musik dan kedamaian berdampingan?
Sebagai pecinta buku musik, saya percaya suara memiliki dua wajah: ia bisa menjadi harmoni yang mengikat, atau kebisingan yang memisahkan. Pilihan wajah mana yang muncul bukan ditentukan oleh teknologi speaker atau besar kecilnya amplifier, melainkan oleh sikap manusia yang menggunakannya. Jika kita mau mendengar tidak hanya dentuman bass, tetapi juga keluhan warga dan tangisan bayi, maka musik bisa kembali pada hakikatnya: membahagiakan, bukan menakutkan.
Saya ingin tetap melihat anak-anak muda merayakan kreativitas mereka. Saya juga ingin tetap melihat orang tua bisa beristirahat tanpa resah. Dua keinginan itu tidak perlu saling meniadakan. Yang dibutuhkan hanya kesepakatan: bahwa meriah dan nyaman bukanlah dua hal yang bertolak belakang, melainkan dua sisi dari sebuah kehidupan sosial yang sehat.