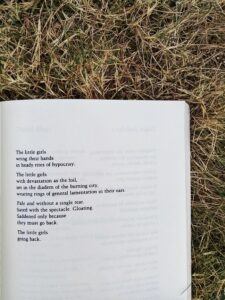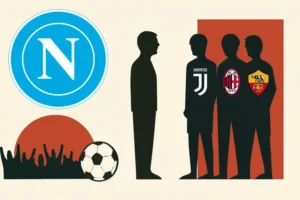Hari Museum Nasional: Sekadar Seremoni Tahunan atau Titik Pijak Transformasi?

Setiap tanggal 12 Oktober, kalender kultural Indonesia akan ditandai dengan satu perayaan: Hari Museum Nasional. Spanduk-spanduk akan terpasang, beberapa museum mungkin akan menggratiskan tiket masuk, dan para pejabat akan merilis pernyataan pers yang berisi harapan-harapan luhur tentang pentingnya museum sebagai penjaga memori bangsa. Sebuah ritual tahunan yang khidmat, namun terasa semakin hampa di tengah deru zaman yang tak lagi bisa menunggu.
Di usianya yang ke-63 sejak Musyawarah Museum se-Indonesia (MUSEMIA) pertama kali digelar di Yogyakarta pada 1962—yang menjadi cikal bakal penetapan hari bersejarah ini—kita patut mengajukan sebuah pertanyaan fundamental yang sedikit menusuk: Apakah Hari Museum Nasional masih memiliki relevansi substantif? Ataukah ia telah tereduksi menjadi sekadar seremoni kosong, sebuah perayaan artifisial untuk institusi yang sebagian besar justru sedang berjuang melawan ketertinggalan dan krisis identitas?
Peringatan ini seharusnya menjadi momen introspeksi nasional, sebuah audit kebudayaan besar-besaran terhadap kondisi museum kita. Namun yang sering terjadi adalah euforia sesaat yang menguap begitu tanggal 13 Oktober tiba, meninggalkan museum kembali dalam kesunyiannya, bergelut dengan atap yang bocor, vitrin yang berdebu, dan narasi yang beku.
Paradoks Kekayaan Sejarah dan Kemiskinan Presentasi
Indonesia adalah sebuah paradoks yang berjalan. Negara ini adalah tambang emas bagi para kurator, sejarawan, dan antropolog. Dari fosil Homo floresiensis hingga prasasti-prasasti kerajaan maritim, dari keris pusaka yang sarat filosofi hingga arsip revolusi kemerdekaan yang dramatis. Secara koleksi, kita adalah raksasa. Namun, dalam hal presentasi, inovasi, dan manajemen, banyak museum kita yang—harus diakui—masih kerdil.
Masuk ke banyak museum milik pemerintah di daerah (dan bahkan beberapa di pusat) seringkali terasa seperti melakukan perjalanan waktu ke era 1980-an. Tata cahaya yang temaram dan seadanya, label artefak yang diketik dengan font kaku dan penjelasan yang kering, serta alur pameran yang terasa acak dan tanpa narasi yang menggugah. Pengalaman yang didapat seringkali bukan pencerahan, melainkan kebosanan.
Stigma museum sebagai “gudang barang antik” atau “tempat penyimpanan benda kuno” bukanlah isapan jempol. Stigma itu lahir dari pengalaman nyata jutaan siswa yang diwajibkan datang dalam rombongan studi tur, hanya untuk berjalan dari satu vitrin ke vitrin lain tanpa mendapatkan percikan inspirasi. Mereka datang karena kewajiban, bukan karena ketertarikan. Setelah itu, mereka mungkin tidak akan pernah kembali lagi seumur hidupnya, kecuali untuk bernostalgia tentang betapa membosankannya kunjungan itu.
Inilah krisis pertama dan paling mendasar: kegagalan museum kita untuk bercerita. Sebuah museum modern bukanlah gudang, melainkan panggung. Artefak bukanlah benda mati, melainkan aktor utama dalam sebuah drama sejarah yang epik. Kurator adalah sutradaranya. Namun, yang kita saksikan seringkali adalah panggung yang gelap dengan aktor-aktor bisu tanpa sutradara yang mampu menghidupkan cerita mereka.
Disrupsi Sektor Swasta dan Tamparan bagi Status Quo
Di tengah potret yang agak suram ini, muncullah beberapa oase yang mengejutkan. Kehadiran museum-museum yang dikelola swasta atau yayasan independen seperti Museum MACAN di Jakarta, atau bahkan museum-museum butik yang lebih kecil namun dikelola dengan sangat profesional, telah menjadi sebuah disrupsi. Mereka datang dengan arsitektur yang memukau, kurasi kelas dunia, strategi marketing yang agresif di media sosial, dan kemampuan untuk menjadikan museum sebagai ruang publik yang “keren” dan relevan bagi generasi milenial dan Gen Z.
Museum MACAN, misalnya, tidak hanya memamerkan karya seni. Ia menjual sebuah pengalaman. Pengunjung datang bukan hanya untuk melihat lukisan Affandi atau instalasi Yayoi Kusama, tetapi juga untuk menjadi bagian dari sebuah peristiwa budaya. Mereka berfoto, mengunggahnya ke Instagram, dan secara tidak langsung menjadi agen pemasaran gratis bagi museum tersebut. Museum ini memahami bahwa di era digital, pengalaman visual dan partisipasi audiens adalah segalanya.
Keberhasilan museum-museum swasta ini adalah sebuah tamparan keras sekaligus cermin bagi museum-museum pemerintah. Tentu, kita tidak bisa membandingkan secara apel-ke-apel sumber daya finansial mereka. Museum swasta didukung oleh korporasi atau filantropi besar, sementara museum pemerintah bergantung pada APBN/APBD yang seringkali menempatkan pos anggaran kebudayaan di urutan bawah.
Namun, masalahnya tidak melulu soal uang. Ini soal visi, mentalitas, dan kemauan politik. Museum swasta dijalankan dengan etos profesionalisme, kelincahan, dan fokus pada pengunjung. Sementara banyak museum pemerintah masih terperangkap dalam jerat birokrasi yang kaku, di mana kepala museum adalah seorang pejabat struktural yang mungkin tidak memiliki latar belakang permuseuman, dan inovasi dianggap sebagai anomali yang merepotkan.
Anggaran yang terbatas seringkali menjadi kambing hitam. Tapi pertanyaannya, apakah anggaran yang ada sudah digunakan secara efektif dan kreatif? Apakah ada upaya untuk menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, komunitas kreatif, atau universitas? Seringkali, jawabannya adalah tidak.
Menuju Museum 4.0: Empat Pilar Transformasi yang Mendesak
Hari Museum Nasional 2025 ini harus menjadi titik balik. Bukan dengan perayaan yang lebih meriah, tetapi dengan komitmen yang lebih serius untuk melakukan transformasi fundamental. Ada setidaknya empat pilar yang harus menjadi fondasi bagi “Museum 4.0” di Indonesia.
# 1 Revolusi Narasi dan Kuratorial
Museum harus berhenti menjadi kamus visual yang statis. Saatnya beralih ke pendekatan tematik dan naratif. Alih-alih hanya memajang “Keris dari Abad ke-15”, ceritakan kisah di baliknya: Siapa empunya? Dalam pertempuran apa ia digunakan? Apa filosofi di balik pamornya? Bagaimana ia merefleksikan kosmologi masyarakat saat itu?
Kurator harus berani menafsirkan ulang koleksi, menghubungkannya dengan isu-isu kontemporer yang relevan bagi anak muda. Misalnya, pameran tentang jalur rempah bisa dikaitkan dengan isu perdagangan global, diplomasi budaya, dan bahkan perubahan iklim. Pameran tentang surat-surat Kartini bisa menjadi platform diskusi tentang feminisme dan kesetaraan gender hari ini. Museum harus menjadi ruang dialog, bukan ruang monolog.
#2 Transformasi Digital yang Holistik
Di era pasca-pandemi, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun, digitalisasi bukan sekadar memindai koleksi dan mengunggahnya ke situs web yang jarang diperbarui. Transformasi digital yang holistik harus dimulai dengan pengalaman interaktif di tempa. Manfaatkan teknologi Augmented Reality (AR) untuk “menghidupkan” artefak. Bayangkan mengarahkan ponsel ke sebuah arca dan melihat rekonstruksi 3D candi aslinya, atau mendengarkan suara gamelan kuno hanya dengan memindai fotonya.
Selain itu, tur virtual 360 derajat yang berkualitas tinggi, koleksi online yang mudah diakses dan dicari, serta pameran-pameran khusus digital yang dirancang dari awal untuk platform online juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Dan, yang pasti, museum harus aktif di platform seperti Instagram, TikTok, dan X, tidak hanya untuk promosi, tetapi untuk edukasi mikro dan membangun komunitas. Buat konten yang menarik, informatif, dan mudah dibagikan.
#3 Museum sebagai Ruang Publik dan Pusat Komunitas
Masa depan museum adalah sebagai community hub atau ruang publik ketiga (setelah rumah dan tempat kerja/sekolah). Hentikan citra museum sebagai bangunan angker yang sunyi. Integrasikan kafe yang nyaman, toko suvenir yang kreatif, ruang kerja bersama (co-working space), perpustakaan, dan area terbuka untuk pertunjukan seni, lokakarya, atau diskusi publik.
Jadikan museum sebagai tempat orang ingin datang dan menghabiskan waktu, bahkan jika tujuan utama mereka awalnya hanya untuk minum kopi. Dengan menjadi pusat kegiatan komunitas, museum akan secara organik menarik audiens baru dan menanamkan rasa kepemilikan pada masyarakat sekitar.
#4 Reformasi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Reformasi kelembagaan dan SDM adalah pilar yang paling sulit namun paling krusial. Perlu ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan anggaran, depolitisasi dan profesionalisasi manajemen, serta investasi SDM.
Alokasi dana yang layak untuk pemeliharaan, riset, akuisisi, dan terutama untuk program-program publik. Posisi kepala museum dan kurator harus diisi oleh para profesional dengan rekam jejak dan keahlian yang teruji di bidang museologi, sejarah, atau manajemen seni, bukan oleh birokrat karier. Menciptakan program pelatihan, sertifikasi, dan studi lanjut bagi para pengelola museum, kurator, konservator, dan edukator. Kualitas sebuah museum ditentukan oleh kualitas orang-orang di dalamnya.
Sebuah Panggilan untuk Bertindak
Hari Museum Nasional adalah pengingat tahunan tentang harta karun memori yang kita miliki. Namun, memiliki harta karun saja tidak cukup. Kita butuh juru kunci yang andal, pencerita yang ulung, dan arsitek pengalaman yang visioner untuk membuatnya bermakna bagi generasi masa kini dan masa depan.
Jika kita terus terjebak dalam pendekatan seremonial, maka setiap 12 Oktober kita hanya akan merayakan sebuah ilusi—ilusi bahwa kita peduli pada sejarah, padahal kita membiarkan wadah penyimpanannya rapuh dan tak berdaya.
Sudah saatnya kita berhenti menepuk dada tentang kekayaan masa lalu dan mulai bekerja keras untuk memastikan masa lalu itu memiliki masa depan. Transformasi museum bukan sekadar proyek renovasi gedung, melainkan proyek pembangunan jiwa bangsa. Mari jadikan Hari Museum Nasional tahun ini sebagai hari pertama dari sebuah gerakan kebangkitan, bukan sekadar hari terakhir dari sebuah perayaan yang terlupakan. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hanya memiliki sejarah, melainkan bangsa yang tahu bagaimana cara menghidupkan kembali sejarahnya setiap hari.