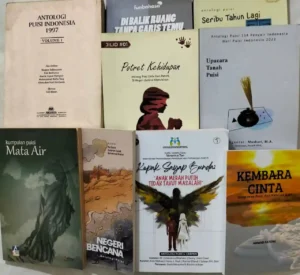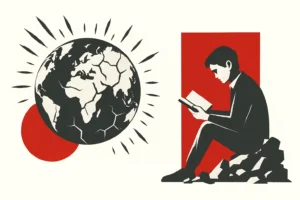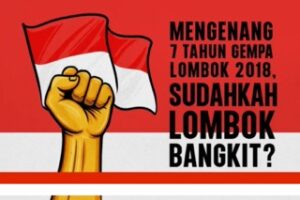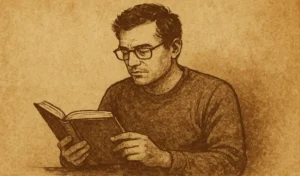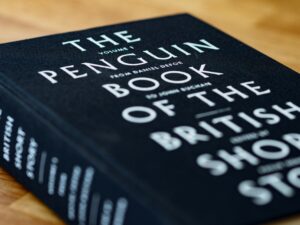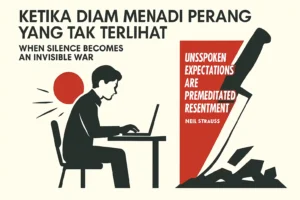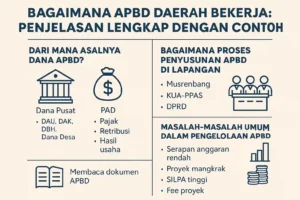Inspirasi Literasi dari Dee Lestari: Saat Menulis Menyembuhkan Para “Puan”

Berbicara tentang perempuan, seperti membuka sebuah buku tua yang aromanya masih menyimpan musim-musim luka. Di setiap halamannya, tergores kisah panjang ketertindasan, berabad-abad lamanya, menyeberangi benua, hinggap di negeri ini. Luka itu tak hanya lahir dari tindakan yang membelenggu, tetapi juga dari kata-kata yang membisu di ranah wacana. Maka, melawan ketertindasan bukan semata soal turun ke jalan, tapi juga menanamkan kata di ladang pengetahuan, menumbuhkan narasi yang memulihkan martabat, bahkan membalik arah angin sejarah yang selama ini jarang memihak.
Sastra dan perempuan merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Sastra, sebagai sebuah karya tulis (literature), menjadi penanda periode masyarakat sejarah yang literat, karena ada banyak temuan yang jika disimpulkan menempatkan sastra bersama retorika hadir lebih dahulu sebelum ada filsafat. Jika filsafat dianggap sebagai ibu bagi ilmu pengetahuan, maka nenek dari ilmu pengetahuan itu adalah karya sastra.
Sastra juga mengandung komposisi antara “komposisi amanat” (shas-) dan “komposisi alat” (-tra) yang fungsinya tidak hanya sebagai penghibur, tetapi juga menjaga ingatan, memperbaiki akal, dan menajamkan kritik pada fenomena sosial-budaya. Dalam “kebudayaan pasca-filsafat”, yang mempopulerkan dialog terus-menerus antara sains, sastra, seni, teknologi, agama, dan lain-lain, sastra menjadi pelengkap untuk menciptakan “jalan baru yang lebih baik, lebih menarik, lebih berbuah”.
Lalu, apa kaitan sastra dengan perempuan? Ellie Norman, dalam Beyond Sisterhood: The Complex Terrain of Female Relationships in Literature (2025), menulis bahwa sastra dan perempuan diikat oleh medium yang merangkai keindahan sekaligus getir menjadi perempuan. Dari kacamata teori budaya dan feminisme, hubungan itu adalah pertemuan antara kuasa dan perlawanan terhadap patriarki—sekaligus ruang penyembuhan dari luka-luka yang diwariskan dunia.
Dengan sastra, perempuan bisa bicara melampaui usia tubuhnya; kata-katanya hidup lebih lama dari suaranya yang kerap dipadamkan. Di Indonesia, meski sastra sering dibiarkan berjalan sendiri tanpa perhatian negara, banyak perempuan tetap menulis. Mereka merajut ulang peta persepsi publik yang masih terperangkap keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah—bukan karena kodrat, melainkan karena budaya yang merendahkannya. Salah satu di antara mereka adalah Dee Lestari.
Dengan Sastra Melampaui Batasan
Dee Lestari bukan nama asing di dunia sastra dan musik Indonesia. Perjalanan kreatifnya, yang melintasi dua ranah seni yang berbeda, bukan sekadar transisi karier, melainkan sebuah pencarian makna yang mendalam. Dalam dunia sastra, karya-karya Dee Lestari seperti Supernova, Aroma Karsa, Perahu Kertas, dan Rapijali berhasil menggambarkan dinamika dunia perempuan melalui narasi yang kaya akan perspektif budaya dan feminisme.
Dee sering menampilkan tokoh perempuan yang kompleks, seperti Elektra dalam Supernova yang memiliki kemampuan unik sambil menghadapi tantangan epilepsi, atau Ping dalam Rapijali yang mencari jati diri di tengah keterbatasan lingkungan. Dalam Aroma Karsa, tokoh seperti Raras Prayagung dan Tanaya Suma digambarkan berjuang menunjukkan eksistensi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial di tengah kondisi ketidaksetaraan gender yang memunculkan marginalisasi, stereotip, dan beban ganda.
Bagi Dee Lestari, yang akrab disapa Mbak Dee dan memiliki nama lengkap Dewi Lestari Simangunsong, menulis adalah napas panjang yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Hal ini diungkapkannya saat mengisi seminar sastra bersama Ratih Kumala dalam Festival Literasi Singaraja bertajuk “Kisah-Kisah yang Ajaib dan Menyembuhkan” pada 26 Juli 2025. Menurutnya, menulis memungkinkan kita untuk menuangkan dan meluapkan perasaan melalui rangkaian kata-kata.
Meskipun pada awalnya menulis tidak langsung mengantarkan seseorang pada puncak keberhasilan dan bahkan dapat terasa membosankan, dengan pendekatan trial and error yang berulang, kualitas tulisan dapat terus meningkat hingga disukai banyak orang. Dee Lestari sendiri mulai menulis sejak kelas 5 SD, di usia belia ketika anak-anak lain lebih fokus pada permainan, ia justru asyik menjelajahi dunia batinnya. Baginya, menulis bukanlah pilihan yang terencana, melainkan kebutuhan yang tumbuh secara alami dari dalam diri.
Dee menjelaskan, “Saya menulis karena merasa membutuhkan banyak hal dalam kehidupan dan cara menjalani kehidupan.” Ungkapan ini menjadi kunci untuk memahami perjalanan kreatifnya. Menulis adalah cara Dee memproses emosi, memahami kompleksitas dunia, dan menemukan cara terbaik untuk menjalani hidup, yang baginya menjadi semacam kompas spiritual. Menulis juga memungkinkannya “bertemu dengan alam inspirasi”, terutama bagi perempuan yang suaranya kerap ditekan oleh dunia patriarkal, sehingga batin dan raga seakan bukan lagi milik mereka sendiri.
Menulis sebagai Upaya Penyembuhan
“Menulis itu adalah penyembuhan bagi diri sendiri,” kata Dee. Ungkapan ini menjadi sangat relevan dalam konteks Bali yang sedang mengalami masalah kesehatan mental yang berujung pada peningkatan bunuh diri (ulah pati). Apalagi banyak temuan psikologis yang membenarkan dampak menulis bagi kesehatan mental, salah satunya temuan dari James Pennebaker di tahun 1980 yang menyatakan bahwa menulis 15 menit sehari tentang trauma yang kita alami dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental.
Terkhusus bagi perempuan, perempuan yang menulis pada dasarnya adalah perempuan yang bertindak secara progresif, karena mereka menciptakan kemungkinan-kemungkinan baik bagi perempuan lainnya di tengah tekanan sosial. Di tengah dunia yang menuntut segalanya terbuka—hingga batas pribadi dan publik kabur—menulis menjadi tempat untuk kembali pulang pada diri sendiri.
Jadi, ruang privat dalam menulis bukan sekadar pelarian, melainkan arena refleksi yang memungkinkan perempuan untuk menghadapi kegundahan batin, merangkai narasi otentik, dan melawan keterasingan yang ditimbulkan oleh struktur sosial, yang berdampak pada upaya-upaya untuk memberdayakan agar merebut kembali agensi atas pikiran dan perasaan mereka dalam dunia yang serba transparan namun sering kali opresif.
Editor: Ihya Ulumuddin