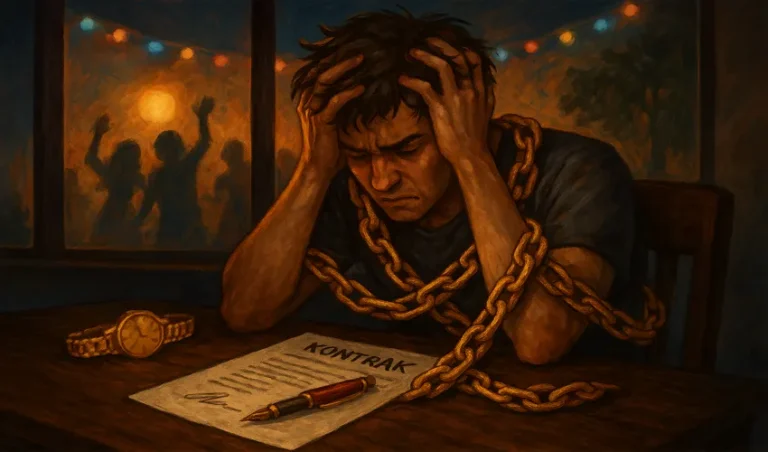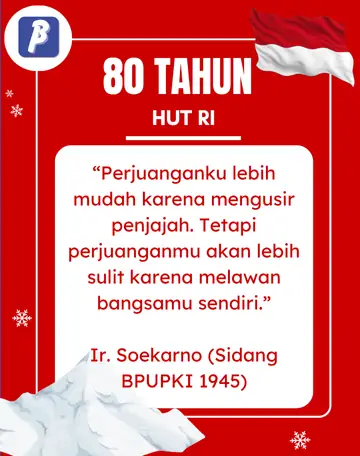Menanti Nasi Sisa dan Puisi Lainnya

Surat dari Anak Tak Terdaftar
Ibu, aku ingin sekolah bukan karena aku ingin pintar,
tapi karena aku ingin tahu mengapa hidup begini berat?
aku membaca nama-nama yang tertempel di papan pengumuman sekolah,
nama mereka tertulis jelas sebagai penerima beasiswa
bahkan dari dua program punya pemerintah,
sedangkan namaku salah tulis pun tak ada
“maaf, namamu tak ada dalam data” kata salah seorang petugas
apakah aku anak hilang?
atau, anak yang sengaja dihilangkan?
di kelas, teman-temanku belajar tentang demokrasi dan Pancasila,
sementara aku belajar cara menahan lapar sampai jam dua siang
aku duduk di emper toko membaca koran bekas
—berita tentang menteri yang korupsi beasiswa
seolah-olah masa depanku hanya angka yang bisa dijual
Ibu, aku dengar negara ini katanya kaya,
tapi mengapa tak cukup untuk membeli satu bangku untukku?
aku tidak minta iPad, tidak minta laptop
aku hanya ingin seragam yang bisa kupakai
tanpa dijadikan simbol bantuan sosial
di malam hari,
aku belajar dari bayangan lampu jalan
setiap kali angin berembus,
huruf-huruf di kepalaku ikut bergetar
Ibu, kalau aku tidak bisa sekolah,
bolehkah aku menjadi puisi saja?
agar aku bisa dibaca meskipun tanpa ijazah.
Pacet, 28 Juni 2025
—
Menanti Nasi Sisa
di republik ini,
ada orang makan sampai lupa mengunyah, dan
ada orang mengunyah sampai lupa rasa
seorang lelaki tua duduk di trotoar kota,
bukan untuk meminta-minta,
melainkan menanti nasi sisa yang jatuh
dari tangan orang yang duduk manis
di dalam gedung-gedung tinggi
ia menyeka mulutnya dengan koran pagi:
berita tentang surplus beras, dan citra
kepala daerah yang sedang menyapa rakyat di depan kamera
tangannya yang kurus seperti batang korek kayu,
menyulut api di dada yang sudah lama dingin
di dekatnya, tukang sampah
memungut botol plastik bermerk
perusahaan yang mensponsori seminar kemiskinan
sesekali ia tertawa
sebab menyaksikan menu rapat DPR
lebih mahal dari makanannya selama sebulan
katanya:
“aku bagian dari anggaran yang tak pernah dicairkan
seperti janji masa lalu yang dibumihanguskan bersama kotak suara”
bocah-bocah lewat mengangguk hormat,
seolah-olah ia pahlawan
padahal, ia hanya rakyat yang tak sempat
mati dengan terhormat
28 Juni 2025
—
Hening di Dalam Masjid
di masjid megah itu marmernya dingin
lebih dingin dari tangan rakyat yang tak sempat memberi sedekah
imam membaca ayat dengan suara yang menggelegar,
sementara di luar masjid seorang nenek mencari sandal yang dicuri waktu salat Jumat
di dindingnya tertulis: “wakaf dari dermawan besar”
namanya dipahat emas, tapi orang miskin tak bisa membaca kemewahan
AC menyala, sajadah harum seperti hotel
tapi bau lapar tak bisa diusir dari saf belakang
anak-anak kecil di luar pagar bermain dengan sepatunya yang bolong,
mereka menunggu ibunya selesai salat—bukan untuk berdoa
—tapi untuk sisa kurma dari kotak amal.
di rak buku, kitab-kitab tebal tersusun rapuh,
berdebu oleh waktu,
sementara di kepala jamaah
hanya hafal potongan ayat yang cocok untuk ceramah bisnis.
langit-langit masjid itu tinggi,
tapi tak cukup tinggi
untuk menampung jeritan buruh
yang tak sempat bersujud.
28 Juni 2025
—
Baju Seragam untuk Siapa?
di meja kecil itu seorang ibu menyetrika seragam
dengan tangan gemetar, tapi bukan karena lelah—
karena tak ada lagi yang akan memakainya
anaknya sudah pergi dengan wajah yang belum sempat dewasa,
pergi di antara peluru dan teriakan yang dikira teror
di lemari masih tersimpan topi sekolah dan buku tulis yang hanya terisi satu halaman:
gambar matahari dan rumah dengan dua jendela
di kelas, bangkunya kosong tapi gurunya tetap absen,
mungkin berharap arwahnya masih hadir di tengah ujian
ibunya menjahit nama pada saku baju itu,
dengan benang luka dan jarum kehilangan
di luar rumah, orang-orang bicara tentang stabilitas,
tentang keamanan, tentang negara hukum
tapi ibu itu hanya ingin tahu:
kenapa anaknya harus mati karena bertanya?
28 Juni 2025
—
Aku Menyamar Jadi Sunyi
aku menyamar jadi sunyi karena bicara tak lagi aman,
karena kata-kata bisa dikriminalisasi dan bisikan bisa jadi laporan
aku menyelinap ke lorong tempat suara rakyat dikecilkan,
diredam mikrofon, ditutupi musik dan iklan
aku bersembunyi di balik spanduk yang robek oleh hujan,
di bawah baliho tokoh yang menjanjikan perubahan tapi lupa alamat rakyat
aku menyamar jadi sunyi karena ribuan orang telah hilang
hanya karena berteriak dengan kalimat yang terlalu jujur
di sekolah, guru mengajarkan diam sebagai bentuk kepatuhan, bukan kebijaksanaan
di televisi, suara-suara diseleksi, hanya yang lucu, yang dramatis, atau yang bisa dijual
aku menyamar jadi sunyi karena suara rakyat sudah terlalu lelah mendaki gedung wakilnya sendiri
aku bukan pemberontak aku hanya suara yang dibungkam sebelum tumbuh
aku bukan penyusup aku adalah gema dari kata yang tak sempat lahir
dan jika suatu hari kalian mendengar sunyi menangis
di lorong-lorong itulah aku—yang pernah kalian bisukan.
28 Juni 2025
Penulis: Muhammad Farhan Azizi