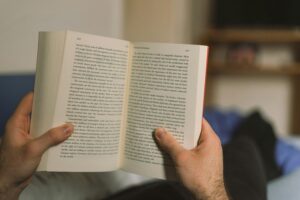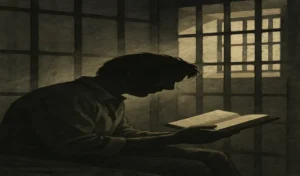Hijrah di Tengah Gemuruh Zaman: Muharram dan Tafsir Kultural atas Waktu Suci

Balai Pikir – Saya ingin memulai catatan ini bukan dengan semacam adagium moral tentang hijrah atau kemuliaan Muharram. Saya ingin mulai dengan sesuatu yang lebih purba, lebih metafisik, lebih awal dari semua itu: kesadaran bahwa waktu bukan sekadar urutan peristiwa, melainkan pengalaman ruhani.
Muharram, dalam kesadaran Islam klasik, bukan sekadar angka pertama dalam kalender Hijriyah, melainkan “sakralitas waktu”—dimensi di mana sejarah dan eskatologi bertemu dalam satu simpul yang menggugah batin.
Kita hidup dalam zaman yang barangkali tak banyak memberi ruang untuk merenung tentang waktu. Segalanya bergerak cepat. Klik. Swipe. Scroll. Tapi Muharram, seperti oasis sunyi di tengah sahara digital ini, menawarkan kesempatan untuk bertanya secara filosofis: apa arti awal? Apa makna berpindah, berhijrah?
Di sinilah, saya kira, penting untuk kembali membaca Muharram bukan hanya sebagai produk sejarah Nabi, tetapi sebagai teks kultural yang terbuka untuk tafsir. Tafsir bukan dalam arti sempit filologis, tetapi dalam semangat yang diungkapkan Hans-Georg Gadamer: dialog abadi antara masa lalu dan kini.
Hijrah: Bukan Pelarian, Tapi Peradaban
Hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah adalah peristiwa yang luar biasa ambigu. Ia tampak seperti pelarian, tetapi ia sesungguhnya adalah deklarasi politik dan spiritual. Nabi tidak sekadar berpindah dari tempat yang menindas ke tempat yang ramah. Ia sedang merintis sebuah kota ideologis, sebuah Madinah yang dalam bahasa Thomas More barangkali setara dengan utopia—kota yang ditopang oleh hukum, etika, dan welas asih.
Inilah titik di mana Muharram menjadi penting. Kita tidak memperingati hijrah karena momentum geografisnya. Kita memperingatinya karena ia adalah lompatan epistemik, bahkan eksistensial.
Di tangan Umar bin Khattab—yang oleh sejarah sering digambarkan sebagai rasionalis par excellence dalam Islam—Muharram dipilih sebagai awal kalender Islam. Mengapa bukan Ramadan, atau bulan lahir Nabi, atau bulan kemenangan di Badar? Mungkin karena Umar menyadari: transformasi tidak dimulai dari kemenangan, tetapi dari keberanian melangkah di tengah ketidakpastian.
Muharram, Asyura, dan Luka Kultural yang Tak Kunjung Sembuh
Tentu, Muharram bukan hanya tentang awal dan hijrah. Ada juga luka sejarah yang tak bisa dilewatkan: tragedi Karbala. Husain, cucu Nabi yang mulia itu, mati di padang gersang, tubuhnya tercabik, darahnya membasahi tanah. Bagi banyak orang—terutama kalangan Syiah—Muharram adalah bulan berkabung.
Tapi bahkan bagi Sunni seperti saya, sulit untuk tidak merasakan duka itu. Kita bisa saja berdalih ini isu sektarian. Tapi siapa pun yang membaca sejarah dengan jujur akan merasa: Karbala adalah cermin pahit dari apa yang terjadi ketika agama dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Husain bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah simbol perlawanan terhadap tirani yang dibungkus simbol agama.
Karenanya, Muharram mengajarkan kita bahwa waktu suci pun tak steril dari pertumpahan darah. Ia adalah bulan suci yang menyimpan tragedi. Dalam sufisme, ini disebut al-jam‘ bayna al-diddain—persatuan paradoks: suci tapi luka, awal tapi penuh duka.
Waktu dan Tafsir Sufistik: Muharram sebagai Ruang Kesunyian
Muharram, dalam tradisi tasawuf, adalah bulan sunyi. Ia adalah ruang bagi yang ingin merintis jalan menuju Allah dengan meluruhkan ego. Di sini saya teringat kata-kata Ibnu ‘Atha’illah dalam al-Hikam:
“Sebaik-baik amal adalah amal yang disertai dengan fana’ dari dirimu sendiri.”
Hijrah, dalam tafsir sufi, bukan soal berpindah tempat. Ia adalah proses menafikan “aku” yang palsu, menuju “aku” yang sejati: yang sadar bahwa dirinya hanya cermin dari kehadiran Tuhan. Dalam konteks ini, Muharram bukan bulan seremoni, tetapi bulan untuk kembali menjadi hamba.
Puasa Asyura, misalnya, bisa dilihat sebagai latihan spiritual untuk merasakan ketidakberdayaan: lapar, haus, hampa. Ini bukan puasa biasa. Ini adalah fasting of soul, bukan sekadar lambung.
Muharram dalam Konteks Nusantara: Antara Islam dan Kebudayaan
Indonesia, seperti kita tahu, tidak pernah mengalami Islam secara steril. Islam di sini datang bersama budaya, bahasa, dan imajinasi lokal. Muharram di Jawa disebut Suro. Ia dirayakan dengan tirakat, laku prihatin, dan kadang ritual yang oleh kaum salafi dicurigai sebagai bid‘ah. Tapi saya kira, pendekatan seperti itu terlalu sempit.
Mengapa tidak kita baca saja praktik itu sebagai ekspresi kultural dari kerinduan pada kesucian? Suro bukan sekadar warisan Hindu. Ia adalah tafsir lokal atas waktu sakral. Di Pariaman, Tabuik dilarung ke laut sebagai simbol penghormatan terhadap Husain. Di Banten, orang berkumpul untuk zikir dan haul. Semua itu menunjukkan bahwa Islam di Nusantara tahu caranya menghormati waktu melalui budaya.
Apakah itu salah? Tidak. Justru di sinilah letak kekayaan Islam Nusantara. Muharram menjadi panggung di mana memori sejarah bertemu dengan ekspresi artistik dan spiritual lokal.
Refleksi Etis: Apa Hijrah yang Kita Butuhkan Hari Ini?
Setelah semua ini, pertanyaan yang penting diajukan adalah: hijrah macam apa yang kita perlukan saat ini? Jawabannya bisa sangat personal, tapi izinkan saya mengusulkan beberapa hal.
Pertama, hijrah dari sekadar identitas ke substansi. Terlalu banyak di antara kita yang sibuk mempersoalkan baju, jenggot, niqab, atau kerudung tanpa menyentuh persoalan akhlak, empati, dan tanggung jawab sosial.
Kedua, hijrah dari kemarahan ke kasih sayang. Kita hidup dalam ekosistem digital yang penuh amarah. Media sosial menjadi medan tempur, bukan ruang dialog. Bisakah kita hijrah menuju adab? Menuju kata-kata yang membawa kesejukan?
Ketiga, hijrah dari apatisme ke kepedulian. Dunia terbakar oleh perang, krisis iklim, dan kemiskinan struktural. Apa gunanya berpuasa Asyura kalau kita tetap abai pada anak-anak di Gaza atau hutan di Kalimantan yang terbakar?
Menutup Waktu, Membuka Jiwa
Akhir tahun Hijriyah dan datangnya Muharram adalah peristiwa psiko‑spiritual. Kita menutup satu fase, membuka yang baru. Dalam satu hadis, Nabi menganjurkan membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Sebagian menyebut ini hadis dha‘if, tapi saya pribadi lebih tertarik melihatnya sebagai ekspresi budaya spiritual: manusia butuh momen, jeda, simbol.
Muharram adalah jeda itu. Ia bukan sekadar tanggal. Ia adalah peluang. Peluang untuk berhenti, untuk bernapas, dan untuk mendengarkan kembali suara hati yang lama tenggelam dalam kebisingan algoritma.
Hijrah sejati bukan soal berapa banyak kajian yang kita hadiri. Tapi seberapa banyak kesadaran yang tumbuh dari pertemuan kita dengan waktu yang suci.
Muharram dan Masa Depan Etika Islam
Jika umat Islam ingin berkontribusi dalam dunia modern, kita harus mengembangkan “etik hijrah”: etika berpindah menuju yang lebih baik, tanpa menyingkirkan yang berbeda. Dunia tidak kekurangan fatwa. Yang ia butuhkan adalah welas asih. Dan Muharram, saya kira, adalah musim yang tepat untuk memulainya.
Maka, seperti Jalaluddin Rumi mengatakan dalam Masnawi:
“Why do you stay in prison, when the door is so wide open?”
Muharram mengajak kita keluar dari penjara diri, menuju ruang cahaya. Hijrah adalah panggilan, bukan kewajiban administratif. Ia adalah perjalanan tanpa peta, tetapi penuh harapan.
Selamat Tahun Baru Hijriah. Semoga setiap langkah kita adalah hijrah menuju kedalaman, bukan sekadar perpindahan lokasi.
Penulis: Muhammad Farhan Azizi