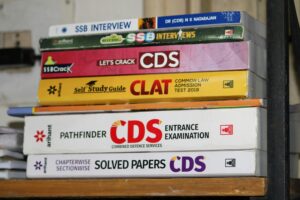Wajah Baru Pesantren Indonesia

Sejak abad ke-17, denyut nadi pesantren berpacu di antara suara lantang membaca kitab kuning dan suara ketukan sendok di dapur pesantren. Namun dewasa ini denyut itu berpacu cepat, seirama dengan transformasi sosial, ekonomi, dan digital.
Perubahan paling terasa bermula pada Oktober 2019, saat Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pesantren disahkan. Regulasi tersebut mengakui pesantren sebagai pilar setara sekolah formal, lengkap dengan hak atas ijazah yang diakui, akses anggaran, serta otonomi kurikulum. Mengubah “lembaga tradisi” menjadi “lembaga strategis”.
Di bawah regulasi baru, Kemenag era presiden Jokowi mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Program inkubasi yang dikemas sebagai Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) berhasil memantik 432 badan usaha—dari konveksi sampai pertanian organik—dengan total penerima manfaat sebesar 3.576 pesantren.
Di Pesantren Al‑Mahmudiyah, Lumajang, misalnya, kolam nila dan kebun pepaya menjadi laboratorium kewirausahaan santri. Dengan begitu, santri dapat belajar fikih muamalah sambil praktik neraca laba rugi.
Transformasi lain terpancar lewat klik. Pada Januari 2024, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meluncurkan aplikasi “Pegon Virtual Keyboard” dan “Rumah Kitab”—dua platform yang mempertemukan aksara pegon warisan Walisongo dengan cloud server Jakarta.
Tak hanya itu, pesantren juga bernegosiasi dengan gelombang moderasi beragama. Hal ini bisa kita lihat makala kepala BNPT bertandang ke Pondok Tebuireng, Jombang untuk menandatangani nota kesepahaman literasi antiradikalisme. Di aula pesantren pendiri NU itu, nasionalisme dan silaturahmi dipertautkan dalam sesi bedah kurikulum.
Sementara itu, angka masuknya investasi pengetahuan terasa dari peningkatan izin pendirian Ma’had Aly, setara perguruan tinggi pesantren. Pada Februari 2025, Kemenag menerbitkan 43 SK kepada lembaga baru, menegaskan bahwa tradisi ta’liq syariah bersanding sah dengan standar akademik nasional.
Namun, modern bukan berarti lepas dari romantika lumbung ilmu tradisional. Di Pesantren Salafiyah di Tegal, lampu minyak masih dinyalakan ketika listrik padam. Santri menadah kitab usang, dengung sholawat bergaung di emper mushala. Pesantren tipe “salaf” ini bertahan di tengah gelombang “khalaf”—berpegang pada kurikulum murni kitab klasik.
Fenomena lain ialah santripreneur: kampanye pemerintah, lembaga filantropi, hingga korporasi menumbuhkan jaringan digital preneur. Program Santri Berseri, yang digagas perusahaan swasta, menargetkan dua juta santri di 17 provinsi belajar higienitas sekaligus pemasaran konten.
Di Pesantren Darunnajah, Jakarta, sekelompok santri putri mengelola kanal YouTube Cooking with Barokah, meramu resep bakso santri dan tips eco‑enzym. Dalam sepekan, video itu ditonton ratusan ribu kali, memicu pesanan katering daring yang menopang dapur pesantren.
Meski geliat ekonomi bergema, persoalan kesejahteraan guru diniyah tetap membayang. Banyak ustaz digaji sebatas uang saku. Sehingga beberapa pondok memutar kas koperasi dan bisnis ritel internal demi menambah insentif.
Tantangan lain adalah ketimpangan fasilitas. Pesantren elit di kota besar mampu membangun smart classroom, sementara di pedalaman Kalimantan, santri masih belajar di bilik papan. Skema Dana Abadi Pesantren senilai Rp 250 miliar dialokasikan untuk beasiswa dan sarana, tetapi realisasi kerap terhambat birokrasi dan minim pendampingan.
Meski demikian, program kemandirian ekonomi diharap menutup kesenjangan itu lewat jejaring antar‑pesantren. Kita bisa mencontoh Pesantren Al‑Zaytun. Sekalipun pernah menuai kontroversi, model pertanian terpadu pesantren itu, mulai padi organik hingga bioflok ikan patin, bisa menjadi contoh bagi pesantren lain. Di mana mereka mencangkok gagasan botani ke dalam fikih siyasah dan leadership pesantren, menawarkan alternatif kemandirian di tengah fluktuasi harga beras nasional.
Tak kalah penting ialah peran perempuan. Di Pesantren Mambaul Ulum, Mataram, program halaqah nyai mengajarkan tafsir gender, kesehatan reproduksi, dan kepemimpinan komunitas. Santriwati di sana menulis bunga rampai cerpen tentang pengalaman ngaji sambil merawat desa terdampak kekeringan. Beberapa diterbitkan majalah daring Santri Literasi, membuktikan bahwa pesantren bukan monastik pria semata, melainkan ruang kolaboratif lintas gender.
Di tengah semua geliat, pesantren masih menjadi rumah persaudaraan lintas kelas. Tengok malam Ramadan di Pesantren Langitan: ribuan warga desa tumpah ruah berbuka bersama, dari petani cabai hingga pegawai kecamatan.
Masuk 2025, kementerian mencanangkan Pesantren Go Green, sebuah gerakan penanaman sejuta pohon trembesi di lingkungan pondok dan program bank sampah berbasis santri. Di Pesantren Luhur Malang, santri menukar botol plastik dengan kupon makan siang. Narasi ekologi ini berkelindan dengan ajaran khilafah fil ardh—kewajiban manusia memakmurkan bumi.
Fenomena pesantren hari ini menyerupai sungai besar berarus majemuk. Di hulunya, tradisi kitab kuning, sholawatan, dan tirakat masih mematangkan karakter. Di mutlanya, arus digital, startup, dan modal usaha memperlebar tapak santri di panggung nasional. Di muaranya, pesantren menjelma simpul peradaban—memasok tenaga ulama, ilmuwan, wirausahawan, pegiat lingkungan, dan penjaga toleransi.