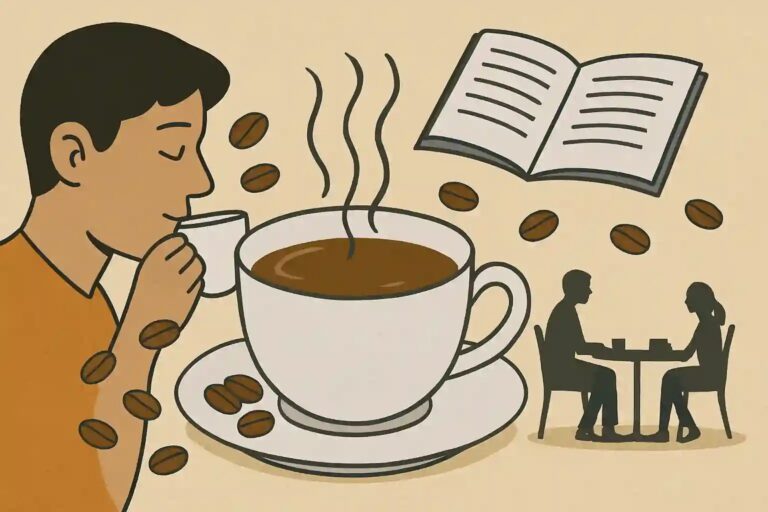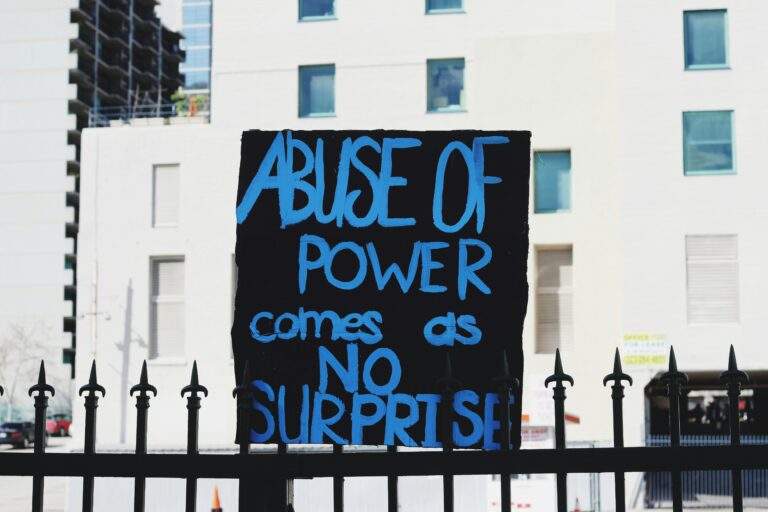Teknologi dan Perubahan Sosial: Antara Konektivitas dan Keterasingan

(unsplash.com/@marpicek)
Teknologi, terutama dalam bentuk digital, telah mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia. Dari cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, hingga membentuk identitas sosial, teknologi menyusup ke dalam relung-relung terdalam kehidupan sosial. Namun, perubahan ini tidak serta merta bersifat positif atau negatif. Ia menghadirkan paradoks: di satu sisi meningkatkan efisiensi, akses informasi, dan konektivitas global; di sisi lain juga menyumbang pada keterasingan sosial, kesenjangan digital, dan fragmentasi komunitas. Dalam memahami dampak ini, teori-teori sosiologi klasik dan kontemporer memberikan kerangka reflektif untuk menimbang sejauh mana teknologi membentuk struktur dan interaksi sosial manusia modern.
Menurut Manuel Castells, seorang sosiolog kontemporer terkemuka dalam kajian masyarakat informasi, dunia saat ini tengah mengalami apa yang ia sebut sebagai network society—masyarakat yang struktur sosialnya terbentuk oleh jaringan digital. Dalam bukunya The Rise of the Network Society (1996), Castells menjelaskan bahwa transformasi teknologi komunikasi telah menciptakan bentuk baru kehidupan sosial yang sangat tergantung pada jaringan dan informasi. Hubungan antarmanusia kini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan dimediasi oleh teknologi jaringan seperti internet dan media sosial. Namun, konektivitas digital ini bukan tanpa konsekuensi. Castells memperingatkan bahwa meskipun jaringan digital meningkatkan partisipasi dan komunikasi, ia juga menciptakan “ruang aliran” (space of flows) yang dapat menyingkirkan identitas lokal dan komunitas berbasis tempat.
Di sisi lain, teori alienasi dari Karl Marx bisa digunakan untuk memahami sisi gelap dari kehidupan sosial yang dimediasi oleh teknologi. Marx berbicara tentang keterasingan manusia dalam sistem kapitalisme industri, tetapi dalam konteks kekinian, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana individu terasing dari makna sosial yang otentik akibat mediasi teknologi. Dalam masyarakat digital, hubungan sosial seringkali tereduksi menjadi angka: likes, views, shares, followers. Individu mulai mengukur eksistensinya berdasarkan metrik algoritmik yang dikendalikan oleh perusahaan teknologi raksasa. Interaksi yang dulu terjadi secara langsung dan penuh konteks kini berpindah ke ruang virtual yang serba cepat dan dangkal. Hal ini berisiko menumbuhkan alienasi emosional dan psikologis, terutama di kalangan remaja dan pengguna intensif media sosial.
Studi empiris mendukung keprihatinan ini. Sebuah penelitian oleh Twenge et al. (2017) yang diterbitkan dalam Clinical Psychological Science menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan smartphone dan media sosial berkorelasi dengan peningkatan depresi dan kesepian pada remaja di Amerika Serikat. Studi ini menemukan bahwa mereka yang menghabiskan lebih dari lima jam per hari di perangkat digital memiliki kemungkinan dua kali lipat mengalami gejala depresi dibandingkan dengan mereka yang menggunakan perangkat kurang dari satu jam. Meski korelasi tidak berarti kausalitas, temuan ini menegaskan bahwa teknologi bukan sekadar alat netral, melainkan memiliki implikasi psikososial yang signifikan.
Namun, tidak semua pandangan tentang teknologi bersifat pesimistis. Anthony Giddens, seorang sosiolog Inggris yang terkenal dengan teorinya tentang strukturasi, menyatakan bahwa manusia tidak pasif dalam menghadapi teknologi. Dalam The Consequences of Modernity (1990), Giddens menjelaskan bahwa modernitas—yang sangat terkait dengan kemajuan teknologi—menghasilkan disembedding mechanisms, yaitu pelepasan hubungan sosial dari konteks lokal menuju sistem yang lebih luas dan abstrak. Teknologi memungkinkan individu untuk membentuk komunitas lintas batas geografis dan identitas yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Dalam konteks ini, media sosial, forum daring, dan komunitas virtual dapat menjadi ruang aktualisasi dan solidaritas baru, terutama bagi kelompok minoritas yang sering terpinggirkan dalam masyarakat konvensional.
Contoh konkret dari gagasan ini dapat dilihat dalam gerakan sosial digital seperti #MeToo atau #BlackLivesMatter. Melalui platform digital, individu yang tersebar di berbagai belahan dunia dapat membentuk jaringan solidaritas, berbagi pengalaman, dan mendorong perubahan sosial yang nyata. Teknologi, dalam hal ini, menjadi alat pemberdayaan yang melampaui keterbatasan fisik dan politis. Dalam kerangka Habermas, ini dapat dilihat sebagai bentuk baru dari ruang publik digital, di mana diskursus rasional dapat tumbuh meski tetap harus dikritisi mengenai siapa yang mengendalikan platform dan bagaimana algoritma memfilter informasi.
Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang memiliki akses yang setara terhadap teknologi. Fenomena yang dikenal sebagai digital divide atau kesenjangan digital menjadi tantangan besar dalam keadilan sosial di era teknologi. Data dari International Telecommunication Union (ITU) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 2,6 miliar orang di dunia masih belum memiliki akses ke internet. Di Indonesia, meski angka penetrasi internet mencapai lebih dari 78%, ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial masih nyata. Wilayah-wilayah terpencil, masyarakat adat, serta warga miskin perkotaan kerap tertinggal dalam mengakses layanan dan manfaat dari teknologi informasi. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kesenjangan ini mencerminkan distribusi modal simbolik dan modal kultural yang tidak merata, yang pada akhirnya mereproduksi ketimpangan sosial yang ada.
Masalah lain yang muncul dari dominasi teknologi dalam kehidupan sosial adalah surveillance capitalism, sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Shoshana Zuboff dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism (2019). Ia menggambarkan bagaimana perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook memanen data pribadi pengguna, kemudian mengolah dan menjualnya demi keuntungan ekonomi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan etis tentang privasi, kontrol atas informasi pribadi, dan kebebasan individu dalam ruang digital. Masyarakat, dalam konteks ini, menjadi objek pengawasan dan eksploitasi data, bukan sekadar pengguna teknologi. Sosiolog Michel Foucault sudah jauh-jauh hari mengingatkan melalui konsep panopticon, bahwa teknologi dapat menjadi alat kekuasaan yang bekerja secara halus namun efektif dalam mengawasi dan mendisiplinkan masyarakat.
Sementara itu, pada tataran mikro, interaksi sehari-hari antarindividu juga mengalami transformasi. Erving Goffman, dalam kerangka dramaturginya, menjelaskan bahwa kehidupan sosial adalah serangkaian pertunjukan, di mana individu memainkan peran tertentu tergantung pada audiensnya. Media sosial memperluas panggung ini. Setiap unggahan adalah semacam performa sosial yang dikurasi untuk membentuk kesan tertentu di hadapan publik digital. Fenomena ini dapat memperkuat tekanan sosial untuk tampil “sempurna”, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kesehatan mental dan hubungan interpersonal. Penelitian oleh Pew Research Center (2022) mencatat bahwa banyak pengguna media sosial, khususnya generasi muda, merasa tertekan untuk menampilkan kehidupan yang ideal secara online, meski kenyataan di balik layar berbeda jauh.
Namun demikian, tidak adil jika kita menyimpulkan bahwa teknologi sepenuhnya merusak tatanan sosial. Dalam bidang pendidikan, misalnya, teknologi telah membuka akses belajar yang lebih luas melalui platform daring seperti Coursera, Khan Academy, dan Ruangguru. Di bidang kesehatan, telemedicine memungkinkan konsultasi jarak jauh yang menyelamatkan nyawa selama pandemi COVID-19. Dalam konteks sosial, platform seperti WhatsApp dan Zoom membantu menjaga relasi keluarga yang terpisah jarak dan waktu. Dengan demikian, teknologi adalah alat yang memiliki potensi emansipatif, tergantung bagaimana dan oleh siapa ia digunakan.
Penting bagi masyarakat untuk mengembangkan literasi digital kritis, yaitu kemampuan untuk tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga memahami logika di baliknya: siapa yang membuatnya, untuk tujuan apa, dan bagaimana dampaknya terhadap diri dan lingkungan sosial. Pendidikan formal dan non-formal harus memasukkan perspektif ini ke dalam kurikulum agar generasi muda tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen dan pengkritiknya. Pemerintah, dalam hal ini, memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan yang melindungi warga dari dampak negatif teknologi sekaligus mendorong inklusivitas digital.
Dalam konteks Indonesia, langkah-langkah seperti Gerakan Literasi Digital Nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo adalah inisiatif yang patut diapresiasi. Namun, upaya ini harus diiringi dengan perbaikan infrastruktur digital di daerah tertinggal dan pengawasan ketat terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pihak swasta maupun negara.
Pada akhirnya, dampak teknologi terhadap kehidupan sosial manusia adalah medan tarik-menarik antara potensi pembebasan dan kemungkinan dominasi. Teknologi bukan entitas netral; ia membawa nilai, kekuasaan, dan arah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor sosial dan politik. Oleh karena itu, tugas kita sebagai warga, akademisi, pembuat kebijakan, dan pengguna adalah memastikan bahwa teknologi tidak menggerus nilai-nilai kemanusiaan, tetapi justru memperkuat solidaritas, keadilan, dan otonomi manusia.
Referensi
- Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Blackwell.
- Marx, K. (1844). Economic and Philosophic Manuscripts of 1844.
- Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Polity Press.
- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.
- Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Vintage.
- Twenge, J. M., et al. (2017). “Increases in Depressive Symptoms, Suicide-Related Outcomes, and Suicide Rates Among U.S. Adolescents After 2010.” Clinical Psychological Science.
- Pew Research Center. (2022). Teens, Social Media and Technology.
- ITU. (2023). Measuring Digital Development: Facts and Figures.
- Bourdieu, P. (1986). “The Forms of Capital.” In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education.
- Kominfo. (2023). Gerakan Nasional Literasi Digital.