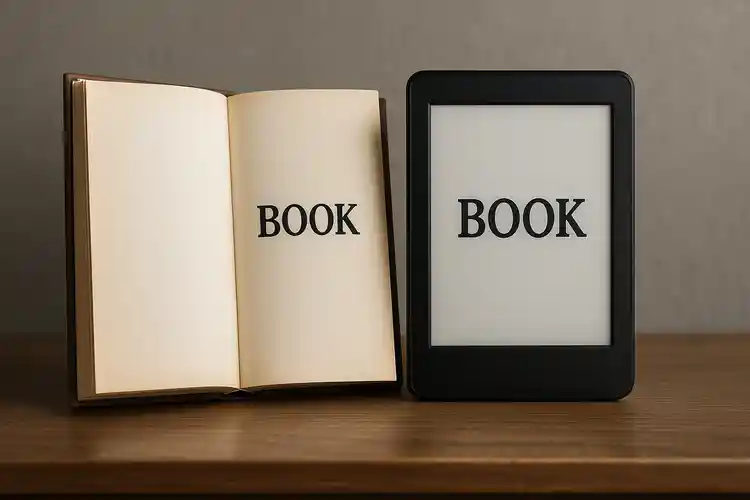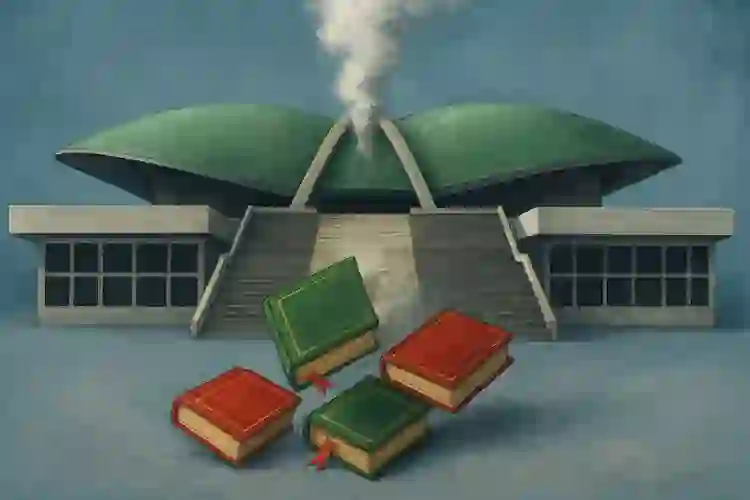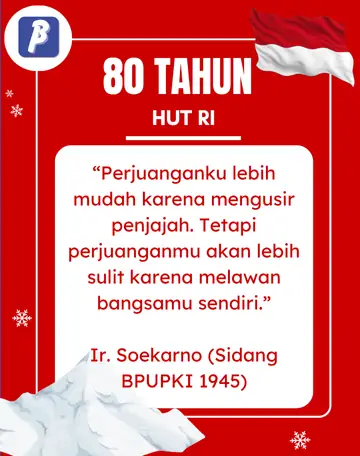Sibuk Sekolah Lupa Belajar

Pendidikan, sejak awal Republik ini diproklamasikan, selalu menempati ruang batin yang paling dalam dari cita-cita kebangsaan kita. Ia hadir bukan sekadar sebagai rangkaian gedung sekolah, kurikulum, dan angka-angka statistik, melainkan sebagai nadi kebudayaan yang memompa darah bernama pengetahuan ke seluruh sendi masyarakat.
Namun, tujuh dasawarsa lebih setelah cita luhur itu diikrarkan, kebijakan pendidikan Indonesia masih saja terperangkap di antara labirin regulasi, dinamika politik anggaran, dan kepentingan pragmatis yang sering melupakan esensi: memerdekakan manusia.
Di sinilah, opini ini bermaksud menelisik sekaligus menggugat—dengan nada yang lebih sebagai ajakan bersoal jawab ketimbang sekadar kecaman—tentang bagaimana kebijakan pendidikan kita kerap bergerak cepat tetapi jarang menjejak mantap pada akar persoalan.
Romantisme Pembangunan
Fenomena pertama yang menyeruak adalah romantisme “pembangunan fisik”—semangat yang, sejak Orde Baru, menjelma obsesif. Gedung-gedung baru didirikan, seragam diseragamkan, dan papan nama sekolah dipoles agar berkilau.
Tetapi, di balik dinding beton itu, guru masih tenggelam dalam birokrasi administrasi, murid terkekang dalam target nilai, dan kurikulum berganti lebih cepat ketimbang musim panen. Ironisnya, tiap pergantian menteri kerap disambut dengan peluncuran jargon baru, seakan mengganti nama, sama dengan menyalakan obor revolusi.
Padahal, di desa-desa terpencil, seminar kerap terdengar bak dongeng: sinyal internet terseok, listrik padam saban hujan, buku referensi tinggal kumpulan lembar kusam, dan guru honorer menunggu kabar pengangkatan layaknya menanti undian nasib. Di titik inilah, kebijakan terasa lebih akrab pada ruang-ruang konferensi berpendingin udara daripada kelas-kelas beratap seng.
Beranjak ke ranah anggaran, Pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen keempat dengan tegas mengamanatkan 20 persen APBN/APBD bagi pendidikan. Dari sisi hitungan makro, angka itu memang menempatkan Indonesia dalam jajaran negara dengan alokasi relatif tinggi di kawasan. Namun, ketika kita menengok peta rincian, terlihat bahwa sebagian besar dana tersedot untuk belanja pegawai dan operasional rutin.
Dalam teori politik anggaran, belanja semacam itu tak keliru; negara memang berkewajiban menjamin kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Masalahnya, porsi untuk riset, pelatihan kompetensi, literasi digital, dan investasi mutu pembelajaran justru merana. Alhasil, kita memompa dana besar tetapi hasil PISA tetap stagnan, literasi membaca jalan di tempat, dan kesenjangan antar‑wilayah masih menganga.
Beralih ke kurikulum, wacana Merdeka Belajar hadir dengan nuansa progresif: otonomi sekolah diperluas, asesmen nasional dirancang mengganti ujian berbasis hafalan, dan paradigma kompetensi abad 21 serta profil pelajar Pancasila digadang-gadang sebagai kompas. Tapi saat implementasi, guru di kelas kerap bimbang: perangkat ajar belum tuntas, pelatihan daring penuh materi abstrak, dan administrasi digital menuntut perangkat mahal beserta kuota internet.
Sementara itu, di kota‑kota besar, sekolah berlabel “favorit” segera beradaptasi, memasang layar sentuh interaktif, menggandeng startup edtech, dan menambah program coding. Kesenjangan teknologi pun kian tebal; murid di pelosok hanya mengenal robotik lewat iklan televisi, sedangkan teman sebayanya di kota memenangi lomba internasional dengan prototipe kecerdasan buatan. Merdeka belajar, tanpa kesetaraan sarana, cenderung menjadi merdeka bagi yang sudah mapan dan tetap terpenjara bagi yang papa.
Kita kemudian dihadapkan pada dilema evaluasi. Asesmen Nasional berbasis komputer dipuji karena menilik literasi, numerasi, dan lingkungan belajar, bukan lagi rangking angka semata. Tetapi survei banyak guru mengeluhkan minimnya sosialisasi mendalam; pelatihan kilat via gawai tidak cukup mengubah paradigma mengajar yang puluhan tahun berorientasi pada lembar kerja siswa dan buku paket.
Apalagi, hasil asesmen tidak lagi menentukan kelulusan. Paradigma anyar ini mulia, tetapi ketika balik ke kelas, guru tetap menghadapi orangtua dan masyarakat yang menuntut rapor berderet angka sembilan. Di sinilah, kebijakan terasa bagaikan orkestra yang instrumentasinya belum seirama: regulator meniup trompet reformasi, tetapi penonton masih mengharap lagu lama yang akrab.
Sementara itu, isu kesejahteraan guru honorer menjadi nyeri berkepanjangan. PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer sudah berusia dua dekade, berganti nomenklatur dan skema PPPK, namun di lapangan, cerita tragis tetap terulang: gaji tak kunjung setara UMR, status menggantung, dan peluang peningkatan kompetensi terhambat birokrasi seleksi.
Kebijakan afirmatif rekrutmen guru di daerah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar—memang ada, tetapi tanpa dukungan transportasi, perumahan, dan pengakuan sosial, banyak guru muda enggan bertahan. Akhirnya, disparitas mutu pengajar menjadi lingkaran setan: daerah maju berlimpah guru ber‑sertifikasi dan bertitel magister, sedangkan wilayah terpencil disandarkan pada dedikasi segelintir pahlawan tanpa tanda jasa.
Persoalan tidak berhenti pada ranah sekolah dasar dan menengah. Perguruan tinggi pun terjebak kompetisi peringkat global. Lembaga pemeringkat internasional memakai indikator publikasi jurnal, reputasi akademik, dan jejaring penelitian. Maka, kebijakan kita pun ramai mendorong dosen menerbitkan artikel Q1, mengikuti konferensi internasional, dan mengejar paten. Konsekuensinya, ruang pengabdian masyarakat yang kontekstual kerap terpinggirkan.
Lebih ironis lagi, riset dasar bidang humaniora—yang merawat jiwa bangsa—dianggap kurang “menghasilkan impact factor”. Kementerian, via skema pendanaan riset, sudah mencoba menyeimbangkan, tetapi pola penilaian tetap menomorsatukan kuantifikasi. Di sinilah letak paradoks: kita berbicara pendidikan karakter, tetapi indikator kebijakan justru mendorong perlombaan angka sitasi.
Pada saat bersamaan, dunia industri mengeluhkan kesenjangan keterampilan (skill gap). Kebijakan link and match—dipopulerkan sejak era Menteri Wardiman Djojonegoro tahun 1990 an—masih menjadi mantra, kini dibungkus kemasan Kampus Merdeka dan SMK Pusat Keunggulan. Namun, praktik magang sering kali hanya seremonial; mahasiswa ditempatkan di kantor tetapi minim proyek konkret.
Industri pun memilih jalur pelatihan internal pasca‑rekrutmen karena dianggap lebih efektif ketimbang menuntut perubahan kurikulum perguruan tinggi yang menghabiskan waktu. Akhirnya, lulusan baru terjebak antara teori kampus dan realitas pasar, sementara negara sibuk membuat skema sertifikasi berlapis yang kadang membingungkan calon tenaga kerja.
Di level dasar, isu literasi dan numerasi masih menghantui. Beragam studi menunjukkan ketidakmerataan kualitas bacaan anak; sebagian masih gagap mengeja di kelas empat sekolah dasar. Program Gerakan Literasi Sekolah digagas, buku bacaan tambahan dikirim, dan pojok baca dibuat.
Namun, tanpa budaya membaca di rumah, sinergi perpustakaan desa, dan dukungan publik, upaya sekolah laksana menimba air dengan keranjang bocor. Lagi‑lagi, kebijakan seolah rindu popularitas: peluncuran buku digital nasional, festival literasi, atau rekor membaca massal dipublikasikan, tetapi pemeliharaan jangka panjang terabaikan. Saat kegiatan usai, pojok baca menjadi rak berdebu.
Tak kalah krusial, kebijakan pendidikan inklusif masih tertatih. Undang‑Undang Disabilitas 2016 menjamin hak pendidikan setara, tetapi hanya sebagian sekolah negeri menyediakan guru pendamping khusus. Kebutuhan sarana aksesibel—ramp, toilet khusus, dan media pembelajaran braille—belum merata.
Mirisnya, kebijakan zonasi PPDB yang pada niat awal ingin menghapus kasta sekolah justru kerap meminggirkan anak berkebutuhan khusus jika sekolah terdekat belum siap. Hukum yang progresif pun terhambat implementasi minimalis.
Bersamaan dengan itu, disrupsi teknologi kecerdasan buatan (AI) memasuki ruang kelas. Kebijakan pemerintah merespons dengan rencana modul AI di kurikulum, pelatihan guru, dan kolaborasi dengan perusahaan teknologi. Akan tetapi, diskusi etika, keamanan data, dan potensi bias algoritma masih tipis.
Tanpa kesadaran kritis, peserta didik bisa menjadi konsumen pasif, sekadar belajar mengklik tombol, bukan memahami epistemologi di baliknya. Kebijakan harus memandu transformasi ini agar AI menjadi alat pembebasan, bukan reproduksi ketimpangan digital.
Pada ranah kebijakan makro, perundang‑undangan—mulai dari UU Sisdiknas 2003 hingga berbagai Peraturan Pemerintah—mengarahkan sistem pendidikan formal, non‑formal, dan informal. Namun, implementasi kerap terfragmentasi karena koordinasi antarkementerian belum solid.
Kewenangan PAUD berada di direktorat berbeda, pendidikan vokasi dipegang kementerian lain, sementara riset dan teknologi sempat berpindah kementerian dalam waktu singkat. Struktur birokrasi yang dinamis memang mencerminkan adaptasi, tetapi terlalu sering berpindah nomenklatur membuat program kehilangan kontinuitas, data tercerai‑berai, dan evaluasi jangka panjang terhambat.
Publik Merespon
Orang tua, sebagai pemangku kepentingan langsung, terpecah antara harapan ideal dan beban finansial. Sekolah negeri unggulan membatasi pendaftar lewat zonasi, sedangkan sekolah swasta berkualitas membebankan biaya tinggi. Program Indonesia Pintar (PIP) menyalurkan bantuan, tetapi persyaratan administrasi dan data kependudukan kadang membuat keluarga marginal terlewat. Maka, “inovasi” muncul: bimbel daring murah, pinjaman pendidikan, dan kelas privat. Pasar melihat peluang, namun negara harus mawas agar kesenjangan tidak makin lebar.
Dalam lanskap global, Indonesia menghadapi bonus demografi: 70 juta pemuda memasuki usia produktif. Tanpa kebijakan pendidikan yang visioner, bonus ini berubah menjadi beban. Negara seperti Korea Selatan, Finlandia, dan Vietnam menunjukkan bahwa loncatan kualitas pendidikan butuh keberanian melakukan reformasi struktural, fokus pada kualitas guru, dan pembudayaan riset yang konsisten.
Indonesia punya modal budaya gotong royong, kearifan lokal, serta semangat Pancasila yang menyeimbangkan ilmu dan budi. Sayangnya, modal itu belum diolah dalam kerangka kebijakan yang berkesinambungan. Pergantian rezim politik menata ulang prioritas, dan orientasi jangka pendek mendominasi.
Jalan Keluar
Pertama, reformasi governance: kementerian dan pemerintah daerah perlu satu peta jalan 25 tahun yang tidak berubah karena kalender politik. Di dalamnya, indikator keberhasilan harus menitikberatkan pada kualitas proses—seperti rasio guru terlatih, keterlibatan komunitas—bukan sekadar angka kelulusan. Kedua, investasi pada guru sebagai garda depan. Skema beasiswa magister terapan, insentif riset tindakan kelas, dan platform kolaborasi digital wajib diperluas. Ketiga, pemerataan infrastruktur digital dengan skema afirmatif untuk wilayah 3T, termasuk satelit internet berbiaya terjangkau dan penyediaan perangkat secara bertahap. Keempat, penyederhanaan regulasi kurikulum agar guru punya ruang kreasi, tetapi tetap ada kerangka mutu nasional yang ketat. Kelima, pembentukan badan independen evaluasi pendidikan lintas rezim, mirip Ofsted di Inggris, untuk menjamin akuntabilitas tanpa intervensi politik jangka pendek.
Akhirnya, marilah kita kembali ke gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang tiga pusat pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kebijakan pendidikan yang sehat adalah yang mampu menautkan ketiganya dalam tarian selaras. Negara menyediakan panggung, tetapi keluargalah yang menanam benih karakter; sekolah menyirami dengan sains dan seni; masyarakat memanen nilai dalam tindakan sosial nyata. Tanpa harmoni itu, kebijakan apa pun hanya akan menjadi dokumen menawan yang berdebu.
Apakah kita masih punya harapan?
Sejarah bangsa ini—dengan segala jatuh bangunnya—menunjukkan ketahanan luar biasa. Bila gelombang pandemi Covid‑19 mampu kita lampaui, seharusnya transformasi pendidikan pun bisa kita gelar. Tetapi syaratnya jelas: keberanian meninggalkan politik seremonial, komitmen membumikan keadilan akses, dan kesediaan mendengar suara akar rumput, terutama guru, siswa, dan orang tua. Mereka bukan objek, melainkan subjek utama pendidikan.
Penutup opini ini bukan sekadar simpulan melankolis, melainkan seruan agar kita menghargai pendidikan sebagai napas kemanusiaan. Kebijakan harus menjadi jembatan antara mimpi dan realitas—bukan menara gading yang berdiri megah tetapi sunyi.
Dengan merawat substansi, bukan kemasan; mengutamakan keberlanjutan, bukan popularitas singkat; serta menegakkan etika, bukan sekadar mengejar peringkat, kita memperkukuh janji konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita mungkin belum tiba di puncak, tetapi kompas moral dan rasional itu telah terhampar.
Tugas generasi kini adalah meluruskan arah, melintasi kabut kepentingan, dan menapaki jalan terjal dengan tekad bahwa setiap anak Indonesia—di puncak gunung maupun di tepi pantai—berhak pada pendidikan bermutu yang memerdekakan jiwa. (*)