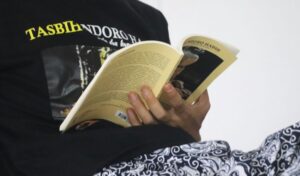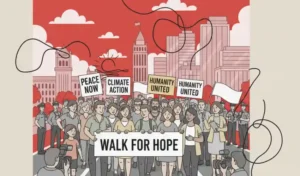Royalti Pemutaran Lagu, Menghargai Pencipta Bukan Menutup Pintu bagi Pendengar
Kafe, restoran, dan ruang publik lainnya selama ini memainkan peran penting dalam memperluas akses terhadap musik lokal. Mereka bukan sekadar pengguna, tapi juga kurator tak resmi yang memperkenalkan lagu-lagu baru ke audiens yang lebih luas.

Isu pemutaran lagu berbayar di kafe memang memantik pro-kontra tajam. Di satu pihak, pencipta lagu sebagai seniman berhak atas penghargaan finansial. Karya mereka dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang memberi hak eksklusif untuk melakukan penerbitan, penggandaan, pertunjukan, dan pengumuman ciptaan.
Oleh karena itu, pada prinsipnya royalti—berupa pembayaran setiap kali lagu dipakai secara komersial—adalah wajar. Misalnya, PP No.56/2021 mewajibkan setiap penggunaan lagu di restoran, kafe, dan tempat umum komersial lainnya untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dengan aturan tersebut, setiap kursi kafe kini dikenai tarif sekitar Rp120.000 per tahun.
Artinya, kafe mungil dengan 5 kursi harus membayar hampir Rp600.000 setiap tahun hanya untuk memutar musik. Di sinilah muncul persoalan kebijakan: apakah penegakan hukum hak cipta seperti ini berlebihan atau dibutuhkan, dan bagaimana dampaknya bagi pelaku usaha kecil maupun masyarakat luas?
Keterlibatan sejumlah musisi papan atas yang jadi legislator menambah kontroversi. Musisi seperti Anang Hermansyah (mantan anggota Komisi X DPR), Krisdayanti (anggota Komisi IX DPR), dan Ahmad Dhani terlibat dalam merancang atau memengaruhi kebijakan terkait royalti musik.
Misalnya, Anang menyambut positif terbitnya PP 56/2021 dan menyebutnya “angin segar bagi ekosistem musik.” Sementara Krisdayanti menegaskan bahwa pengelolaan royalti harus diserahkan pada LMKN agar hak-hak pencipta tidak terabaikan. Dari sudut pandang pencipta lagu, kejelasan mekanisme pembayaran royalti memang penting agar kesejahteraan seniman terjaga.
Namun, publik mengkritik bahwa aturan yang dibuat dengan suara musisi di DPR tersebut berpotensi menguntungkan segelintir pencipta besar secara politis dan ekonomis. Banyak yang menduga bahwa para legislator-musisi ini sekaligus berkepentingan sebagai penerima royalti, sehingga rawan benturan kepentingan.
Di sisi lain, karya musik jelas diciptakan untuk dinikmati publik, bukan hanya dikunci dalam album eksklusif. Karier Anang dan Krisdayanti berjaya sebagian berkat lagu-lagu mereka diputar luas oleh masyarakat.
Seorang hakim MK, Arief Hidayat, pernah mengkritik keras pendekatan bisnis semacam ini. Ia menyindir bahwa jika interpretasi hak cipta ini diterapkan apa adanya, maka WR Supratman, pencipta lagu kebangsaan “Indonesia Raya,” bakal menjadi orang terkaya di Indonesia.
Analogi ini menyoroti perubahan pemahaman dari semangat gotong royong sosial karya seni menuju kapitalisme individualistis semata. Maksudnya, kini segala aktivitas komunal—menyanyi lagu nasional bersama—diperlakukan sebagai transaksi ekonomi yang menguntungkan pencipta dan ahli warisnya.
Pelaku usaha kecil justru menjadi ujung tombak ketidakpuasan. Sejak aturan ini ramai diperbincangkan, banyak pemilik kafe dan warung kopi mikro merasa sesak dan kebingungan. Mereka khawatir tiba-tiba ditagih royalti oleh lembaga tanpa sosialisasi yang jelas.
Belum lagi, kewajiban membayar royalti berlaku tanpa pengecualian, bahkan bagi pelaku usaha yang berlangganan layanan musik digital seperti Spotify. DJKI menegaskan bahwa langganan platform digital bukan penggugur kewajiban royalti.
Kondisi ini membuat beberapa tempat makan di berbagai kota memutuskan untuk tidak lagi memutar lagu apapun. Kompas TV melaporkan, pemilik kafe dan restoran beralih ke playlist instrumen atau bunyi alam supaya aman dari biaya royalti. Sebagian bahkan mengaku lebih memilih sunyi.
Menggunakan suara alam pun ternyata tak luput dari aturan. Media Disway melaporkan bahwa aturan hak cipta berlaku ketat: lagu populer maupun rekaman bunyi alam komersial sama-sama dikenai royalti jika diputar di tempat usaha.
Bahkan usaha populer seperti Mie Gacoan di Bali sempat tersandera kasus hukum karena tidak membayar royalti terhadap lagu-lagu yang diputar. Direktur Mie Gacoan akhirnya dinyatakan tersangka pelanggaran hak cipta.
Betapa ironi, kafe-kafe itu selama ini justru sudah menjadi media promosi bagi musisi. Seorang pemilik kafe mengakui bahwa memutar lagu-lagu Indonesia sama artinya dengan memberikan iklan gratis bagi pencipta.
Tindakan musisi seperti Ahmad Dhani yang menawarkan izin gratis pemutaran lagu-lagu Dewa 19 di kafe adalah contoh simpati atas situasi ini. Langkah Dhani ini diapresiasi luas oleh para pemilik kafe karena merasa beban mereka sedikit terangkat.
Akhirnya, soal karya seni memang rumit antara hak ekonomi dan fungsi sosial. Undang-undang memang menjamin hak pencipta untuk mendapat imbalan dari penggunaan komersial karya mereka. Namun, apakah segala macam pemanfaatan mesti dijadikan transaksi?
Bukankah musik sejatinya diciptakan untuk dinikmati orang banyak? Jika penafsiran hak cipta terlalu sempit, kita justru mengabaikan peran budaya dalam kehidupan publik. Lagu-lagu rakyat atau daerah semestinya terus hidup menjadi bagian kultur.
Keseimbangan antara menghargai kreator dan menjaga akses budaya publik harus ditemukan. Para pakar hukum kekayaan intelektual menyarankan mekanisme lisensi yang lebih fleksibel untuk UKM atau mekanisme kolektif yang memperhatikan skala usaha.
Dampak ekonomi dari kebijakan royalti ini juga tak sepele bagi masyarakat umum. Untuk pelaku UMKM, pajak tambahan bisa mengurangi modal usaha, bahkan mendorong kenaikan harga jual kopi atau makanan. Teras kafe yang sunyi tanpa musik bisa mengubah pengalaman bersosial. Kehilangan sentuhan lagu-lagu Indonesia membuat ruang publik terasa kurang hidup, padahal musik punya fungsi hiburan dan edukasi budaya.
Kekayaan intelektual harus dilindungi, tetapi penyelesaiannya perlu memperhatikan keadilan sosial. Misalnya, pemerintah bisa menetapkan tarif subsidi untuk usaha kecil, atau LMKN mengelola skema pembayaran yang proporsional dan transparan. Dalam konteks kritis ini, jelas bahwa aturan royalti bagi kafe memunculkan dilema: antara menghargai pencipta dan menjaga keseimbangan sosial-ekonomi. Opini ini menegaskan bahwa kita perlu kebijakan yang lebih adil dan inklusif.
Pendapatan musisi perlu dihargai, tetapi tidak dengan cara membebani UMKM atau membatasi akses masyarakat terhadap karya budaya. Diperlukan dialog terbuka agar musik tetap terdengar di ruang-ruang publik. Musik bukan sekadar komoditas. Ia bagian dari jiwa kolektif bangsa yang harus terus bergema tanpa terkekang selubung profit semata.
Mempertanyakan Distribusi Manfaat dan Keadilan
Kritik terhadap kebijakan royalti di ruang publik tidak semata-mata menolak penghargaan terhadap hak cipta, melainkan mempertanyakan distribusi manfaat dan keadilan penerapannya. Sebab, dalam praktiknya, hanya segelintir musisi besar yang mendapat royalti dalam jumlah signifikan. Sisanya, musisi-musisi independen atau pemula sering kali tidak merasakan dampak ekonomi yang berarti dari sistem ini.
Menurut data LMKN, royalti yang dikumpulkan dari pengguna lagu—termasuk kafe dan restoran—dialokasikan kepada anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan jumlah pemutaran dan popularitas lagu. Ini menciptakan efek “rich get richer,” di mana lagu-lagu yang sudah populer semakin mendominasi distribusi royalti. Musisi baru atau alternatif yang lagunya hanya diputar di ruang-ruang kecil menjadi terpinggirkan dalam distribusi.
Apalagi, sistem pendataan melalui SILM (Songs and Music Information System) masih menghadapi tantangan besar dalam akurasi dan transparansi. Banyak pelaku usaha mengeluhkan bahwa mereka tidak diberi daftar lagu-lagu apa saja yang dikenai royalti atau metode penghitungan yang adil berdasarkan frekuensi pemutaran. Bahkan, ada laporan kafe yang ditagih royalti untuk lagu-lagu yang tidak pernah mereka putar, hanya karena menggunakan layanan streaming yang mencakup katalog luas.
Aspek transparansi menjadi persoalan mendesak. Ketika para pembuat kebijakan juga merupakan musisi yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil royalti, publik wajar mempertanyakan apakah sistem ini dirancang untuk menciptakan keadilan ekonomi atau sekadar memperkaya pemilik lagu-lagu yang sudah dominan. Mekanisme pengawasan independen terhadap LMKN dan LMK perlu diperkuat untuk menghindari konflik kepentingan.
Masalah lainnya adalah pembatasan budaya dalam ruang sosial. Kafe, restoran, dan ruang publik lainnya selama ini memainkan peran penting dalam memperluas akses terhadap musik lokal. Mereka bukan sekadar pengguna, tapi juga kurator tak resmi yang memperkenalkan lagu-lagu baru ke audiens yang lebih luas. Ketika tempat-tempat ini dibebani biaya yang tinggi, mereka terpaksa mengurangi pemutaran musik lokal dan beralih ke musik bebas lisensi atau bahkan diam.
Jika ini berlangsung terus-menerus, maka ekosistem musik Indonesia akan mengalami pembusukan kultural. Musik tidak lagi menjadi bagian dari ruang sosial kolektif, melainkan menjadi produk eksklusif yang hanya bisa dinikmati di ruang-ruang terbatas yang mampu membayar. Padahal, musik adalah bahasa emosional dan kebudayaan. Kehadirannya di ruang publik bukan sekadar hiburan, melainkan media komunikasi, memori kolektif, dan edukasi informal.
Pemerintah seharusnya melihat peluang untuk membangun sistem royalti yang progresif dan adaptif. Misalnya, dengan menerapkan skema progresif di mana tarif royalti disesuaikan dengan pendapatan usaha. Kafe kecil dengan omzet di bawah batas tertentu bisa diberi pembebasan royalti atau cukup membayar kontribusi simbolik. Sebaliknya, pusat perbelanjaan, restoran besar, atau jaringan hotel multinasional bisa dikenakan tarif penuh.
Pemerintah juga dapat mengembangkan platform musik nasional yang memungkinkan pelaku usaha memilih katalog lagu-lagu dari musisi Indonesia yang bersedia dibagi dengan lisensi kolektif dan ringan. Dengan sistem ini, musisi juga bisa memilih lagu mana yang ingin mereka distribusikan untuk publik secara bebas atau berbayar. Ini memberikan fleksibilitas dan kontrol kepada para kreator, sekaligus memberi pilihan legal dan terjangkau kepada pengguna.
Langkah lain adalah menggalakkan edukasi tentang hak cipta sejak dini. Banyak masyarakat dan pelaku usaha belum memahami perbedaan antara mendengarkan musik secara pribadi dan menggunakan musik secara komersial. Sosialisasi yang lebih masif dan inklusif diperlukan agar pelaku UMKM tidak merasa diintimidasi, melainkan diajak menjadi bagian dari ekosistem musik nasional.
Dengan begitu, kita tidak sedang mempertentangkan seniman dan pengusaha kecil, tapi membangun jembatan antara hak eksklusif dan akses kolektif. Royalti semestinya bukan penghalang bagi tumbuhnya budaya, tapi pendorong bagi keadilan dalam ekosistem kreatif.
Saat legislator-musisi mendorong regulasi yang memengaruhi pasar musik, seharusnya mereka tampil sebagai penyeimbang, bukan sebagai penerima manfaat utama. Mereka mesti mendorong sistem yang adil, terbuka, dan memberi ruang kepada musisi-musisi baru untuk hidup dari karya mereka, bukan sekadar memperpanjang dominasi katalog lama. Dalam konteks inilah, fungsi legislatif harus dikembalikan kepada nilai publik, bukan kepentingan pribadi.
Musik tidak semestinya dikunci oleh birokrasi royalti yang kaku. Ia harus tetap menjadi denyut nadi sosial—yang hidup di kafe pinggir jalan, di warung kopi malam hari, di ruang komunitas dan taman kota. Musik adalah suara rakyat. Dan suara rakyat tak boleh dibungkam hanya karena tagihan.
Menghargai Pencipta, Bukan Menutup Pintu Pendengar
Sebagai penutup, penting untuk menegaskan bahwa isu royalti lagu bukan sekadar soal transaksi ekonomi antara pemilik hak cipta dan pengguna, tetapi juga menyangkut posisi musik dalam kehidupan sosial masyarakat. Musik adalah bagian dari kebudayaan yang hidup, berkembang, dan menyatu dalam ruang-ruang publik. Ia tidak lahir dalam ruang hampa dan tidak hanya untuk konsumsi kalangan terbatas.
Ketika regulasi mengatur akses terhadap musik terlalu ketat, dampaknya bukan hanya terasa pada pelaku usaha kecil, tetapi juga mengurangi daya hidup kebudayaan itu sendiri. Musik yang hanya bisa didengar jika dibayar secara eksklusif akan kehilangan esensi sosialnya. Ia menjadi sekadar barang dagangan, bukan lagi bahasa emosi bersama.
Oleh karena itu, reformasi kebijakan royalti sangat diperlukan. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan—termasuk LMKN, LMK, musisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil—perlu membangun sistem yang inklusif dan adil. Sistem yang memberi penghargaan layak kepada pencipta tanpa membebani masyarakat dan UMKM secara berlebihan.
Peninjauan ulang atas skema royalti, transparansi pendataan dan distribusi, serta keberpihakan kepada sektor kecil adalah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan. Di samping itu, keberadaan musisi di lembaga legislatif seharusnya menjadi jembatan untuk mengawal kebijakan yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi menjamin keberlanjutan ekosistem musik nasional secara keseluruhan.
Jika kita ingin musik Indonesia terus bergema, menjadi teman harian rakyat dari Sabang sampai Merauke, maka ia harus tetap hidup di ruang-ruang yang paling sederhana: di teras warung kopi, di dalam kafe kecil, di radio komunitas, dan di acara-acara rakyat. Musik adalah suara kolektif, dan kolektivitas tidak semestinya dikenakan beban yang menghambat peredarannya.
Pada akhirnya, menghargai pencipta bukan berarti menutup pintu bagi pendengar. Sebaliknya, karya seni yang besar adalah yang bisa dinikmati seluas-luasnya. Dari situ, kita membangun ekosistem musik yang bukan hanya adil bagi pencipta, tetapi juga ramah bagi masyarakat. Sebab, sebagaimana puisi, film, dan sastra, musik adalah bagian dari peradaban. Dan peradaban tumbuh ketika akses terhadapnya dibuka seluas mungkin, bukan dikunci dengan tarif yang kaku. (*)