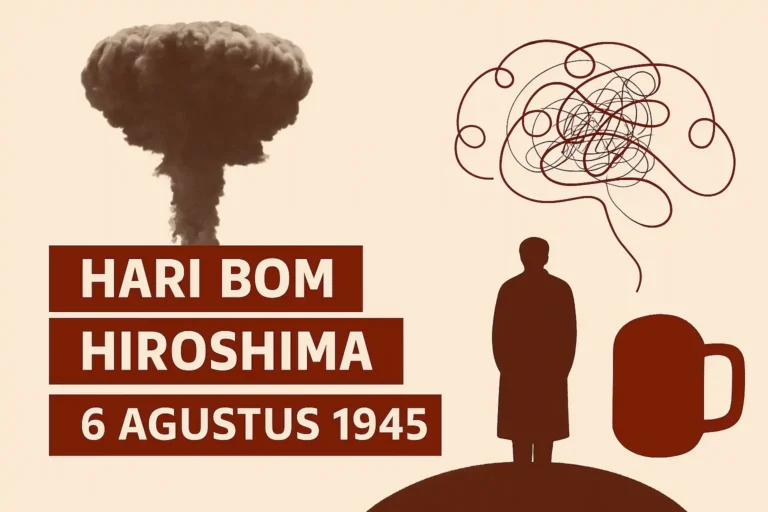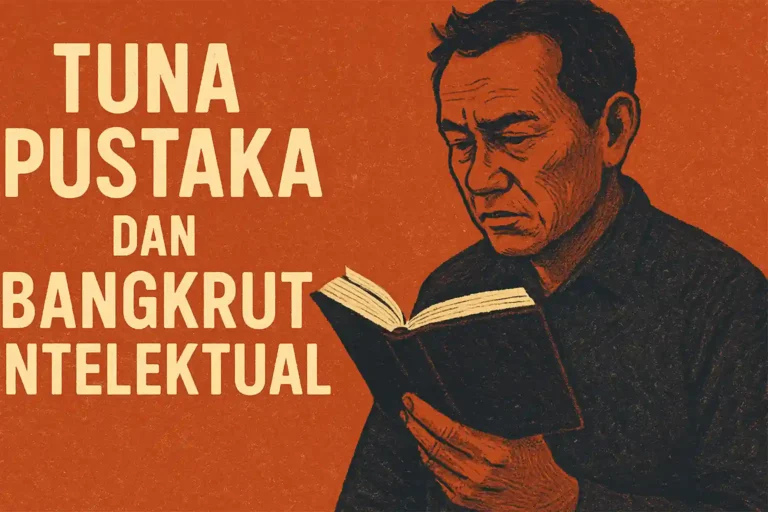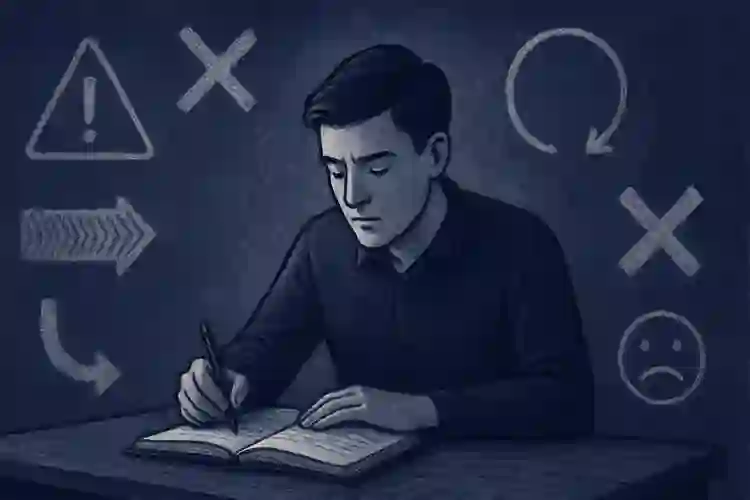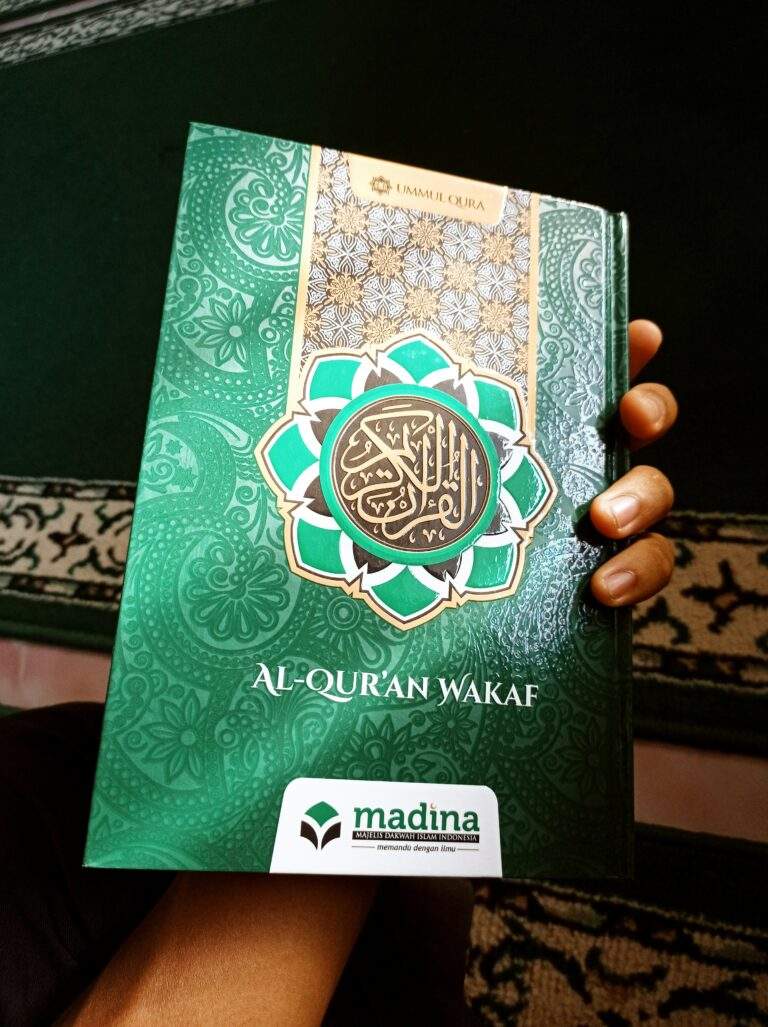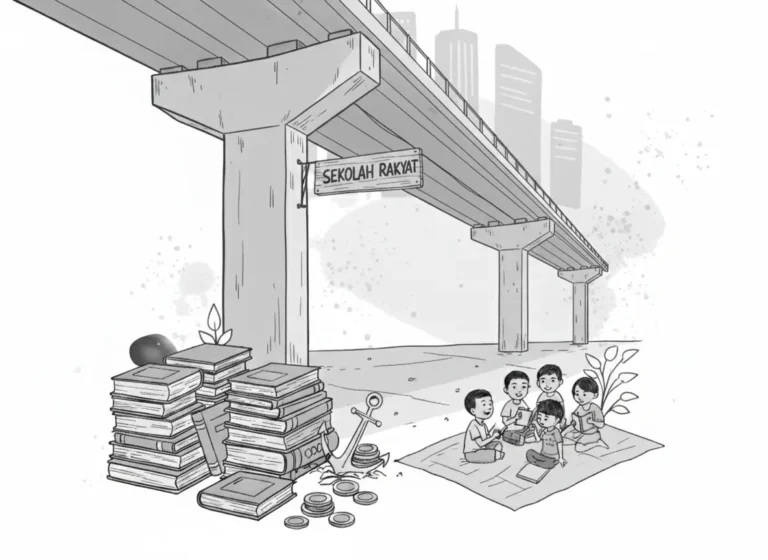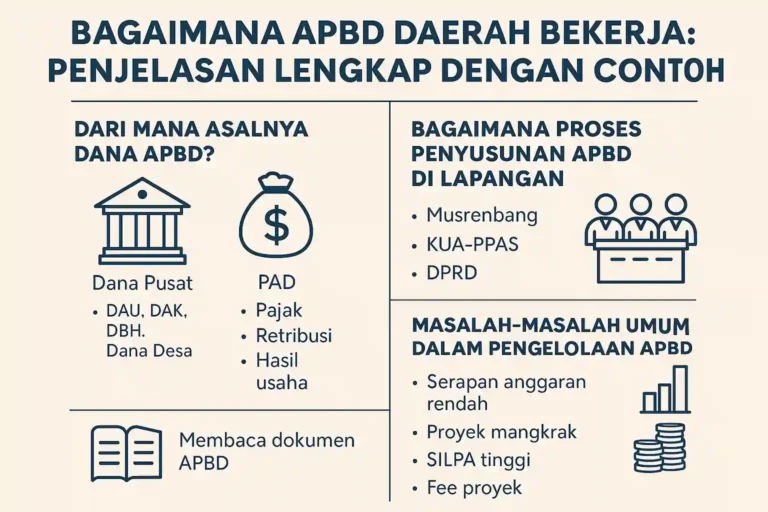Polisi dan Budaya Kuasa: Menelisik Luka Struktural dalam Institusi Kepolisian Indonesia

Ketika masyarakat berbicara tentang institusi penegak hukum, harapan yang muncul biasanya berkaitan dengan rasa aman, keadilan, dan kepercayaan. Namun, dalam konteks Indonesia, kepolisian justru seringkali hadir sebagai sumber ketakutan, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum. Bukan karena publik tidak menghargai peran polisi, tetapi karena lembaga ini kerap gagal mencerminkan semangat demokrasi dan keadilan yang seharusnya menjadi pijakan dalam negara hukum. Dalam kenyataannya, berbagai laporan, riset, hingga investigasi jurnalistik mengungkapkan bahwa polisi Indonesia masih bergulat dengan budaya kekerasan, korupsi, impunitas, dan relasi kuasa yang melukai integritas institusional dan kepercayaan publik.
Menurut laporan tahunan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan atas praktik kekerasan pada tahun 2023. Dari total 472 aduan yang diterima KontraS, polisi menyumbang 213 kasus kekerasan. Jenis kekerasan yang dilakukan beragam, mulai dari kekerasan fisik, intimidasi, kriminalisasi, hingga penyiksaan selama proses penangkapan dan interogasi. Kekerasan ini bukanlah insiden individual belaka, melainkan cerminan dari budaya institusional yang menormalisasi tindakan represif dalam kerangka “menjaga ketertiban”.
Budaya kekerasan ini erat kaitannya dengan warisan militeristik Orde Baru, ketika polisi berada dalam satu tubuh bersama militer dalam ABRI. Meskipun telah dipisahkan secara kelembagaan sejak reformasi 1999, jejak militeristik itu masih membekas dalam cara kerja polisi. Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dalam kajian mereka tentang demokrasi di Indonesia menyatakan bahwa demokratisasi tidak selalu menghapus praktik otoritarianisme di tubuh negara. Dalam hal ini, reformasi Polri tampak lebih kosmetik daripada substansial.
Laporan dari Human Rights Watch (HRW) tahun 2020 mengungkap bahwa polisi Indonesia sering menggunakan kekerasan berlebihan saat mengendalikan massa demonstrasi. Dalam konteks protes omnibus law tahun 2020, misalnya, aparat menggunakan peluru karet, gas air mata, dan pentungan terhadap demonstran yang sebagian besar tidak bersenjata. Bahkan dalam beberapa kasus, para jurnalis dan relawan medis pun turut menjadi korban kekerasan. Praktik ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dipakai untuk menghadapi pelaku kriminal, tetapi juga untuk membungkam ekspresi sipil.
Fenomena impunitas juga menjadi masalah serius. Dalam banyak kasus pelanggaran oleh aparat, hukuman yang diberikan sangat ringan atau bahkan tidak ada sama sekali. Kasus kematian enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek tahun 2020 adalah contoh penting. Komnas HAM menyimpulkan bahwa ada pelanggaran HAM berat dalam insiden tersebut, namun hingga kini proses hukum terhadap anggota polisi pelaku tidak menunjukkan transparansi yang dapat membangun kepercayaan publik. Polri, alih-alih membuka diri terhadap investigasi independen, cenderung bersikap defensif dan tertutup.
Dalam ranah ekonomi, praktik pungli (pungutan liar) dan korupsi di tubuh kepolisian menjadi penyakit yang kronis. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa polisi merupakan salah satu institusi yang paling sering dilaporkan melakukan korupsi, terutama dalam bentuk suap dan pemerasan terhadap masyarakat sipil dan pelaku usaha kecil. Praktik ini marak dalam pengurusan SIM, tilang, bahkan penanganan kasus hukum yang seringkali ditentukan oleh “uang pelicin”. Di level yang lebih tinggi, kasus Irjen Ferdy Sambo menjadi cermin paling telanjang dari problem struktural ini: pembunuhan berencana terhadap sesama polisi, upaya pengaburan fakta, manipulasi TKP, dan keterlibatan puluhan personel dalam menyembunyikan kejahatan. Kasus ini membuka mata publik bahwa kebusukan bukan hanya terjadi di level bawah, melainkan sudah menjangkiti pucuk pimpinan.
Dari sisi budaya kerja, struktur kepolisian Indonesia menampilkan karakter yang sangat hierarkis, maskulin, dan feodalistik. Budaya “asal bapak senang” (ABS) dalam kepolisian menyuburkan praktik loyalitas buta dan menghambat kritik dari dalam. Polisi-polisi muda yang kritis terhadap seniornya cenderung terpinggirkan atau dimutasi. Situasi ini membuat reformasi internal sulit dilakukan secara jujur dan menyeluruh. Bahkan dalam proses rekrutmen, sering muncul keluhan dari calon polisi dan keluarganya tentang mahalnya biaya masuk akademi kepolisian yang bisa mencapai ratusan juta rupiah, sesuatu yang secara implisit membuka peluang bagi mereka yang mampu “membeli” pangkat dan jabatan.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah relasi antara kepolisian dan dunia bisnis-politik. Di banyak daerah, polisi menjadi bagian dari jejaring kekuasaan yang menopang oligarki lokal. Dalam laporan riset yang dilakukan oleh LIPI (kini BRIN), disebutkan bahwa aparat kepolisian kerap dimobilisasi untuk menjaga kepentingan investor, khususnya dalam proyek tambang dan pembangunan infrastruktur. Di banyak konflik agraria—seperti di Wadas, Rempang, Kendeng, dan Papua—polisi tidak hadir sebagai penjaga hukum, melainkan sebagai pelindung proyek kapital. Hal ini memperlihatkan bagaimana hukum tidak dijalankan untuk keadilan, tetapi untuk mengamankan modal dan kekuasaan.
Secara kultural, citra polisi juga terus menurun. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun drastis setelah kasus Sambo mencuat. Dari angka 80% pada pertengahan 2022, kepercayaan turun ke kisaran 60% pada awal 2023. Meskipun Kapolri mencoba membangun kembali citra dengan jargon “Presisi”, langkah-langkah yang diambil masih belum menyentuh akar masalah. Publik melihat bahwa perubahan yang dijanjikan cenderung bersifat simbolik, bukan struktural.
Namun, penting untuk dicatat bahwa kritik terhadap polisi bukan berarti menolak keberadaan institusi ini. Kritik adalah bagian dari upaya membangun negara hukum yang sehat dan akuntabel. Polisi, seperti semua aparatur negara, harus tunduk pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pengawasan publik. Sayangnya, selama ini polisi sering menempatkan diri bukan sebagai pelayan rakyat, tetapi sebagai alat kekuasaan. Ketika polisi merasa lebih tinggi daripada hukum yang seharusnya mereka tegakkan, maka yang muncul adalah negara represif, bukan negara hukum.
Dalam kerangka kebudayaan, kita dapat mengatakan bahwa keburukan polisi Indonesia bukan semata-mata soal individu yang jahat, melainkan tentang sistem yang melestarikan praktik buruk. Ini adalah soal budaya kuasa yang menolak transparansi, soal mentalitas “raja kecil” di setiap pos polisi, soal institusi yang lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki diri. Budaya ini dibentuk oleh sejarah, dikuatkan oleh impunitas, dan dijaga oleh jejaring kuasa yang melibatkan elit politik dan ekonomi.
Jika kita ingin institusi kepolisian yang benar-benar berpihak pada rakyat, maka reformasi tidak bisa setengah hati. Diperlukan pembenahan menyeluruh: dari rekrutmen, kurikulum pendidikan, pengawasan internal dan eksternal, sampai pada restrukturisasi relasi antara polisi dan kekuasaan ekonomi-politik. Tanpa itu semua, jargon “Polri Presisi” akan tetap menjadi slogan kosong yang tak menyentuh akar persoalan.
Dalam kebudayaan Indonesia yang kaya akan nilai gotong royong dan keadilan sosial, institusi kepolisian seharusnya menjadi penegak hukum yang humanis, bukan mesin kekerasan yang arogan. Jika tidak ada perubahan struktural yang signifikan, maka publik akan terus menyimpan luka dan ketakutan setiap kali mendengar kata “polisi”—sebuah ironi besar bagi negara yang mengklaim dirinya demokratis.
Referensi:
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Laporan Tahunan 2023
- Human Rights Watch, Indonesia: Police Violence During Protests, 2020
- Indonesia Corruption Watch (ICW), Laporan Pungli dan Korupsi Polri, 2022
- LIPI/BRIN, Studi tentang Peran Aparat dalam Konflik Agraria, 2021
- Indikator Politik Indonesia, Survei Nasional Kepercayaan Publik terhadap Polri, 2023
- Edward Aspinall & Marcus Mietzner, Democracy for Sale, Cornell University Press, 2019
- Komnas HAM, Laporan Penyelidikan Kasus Km 50, 2021