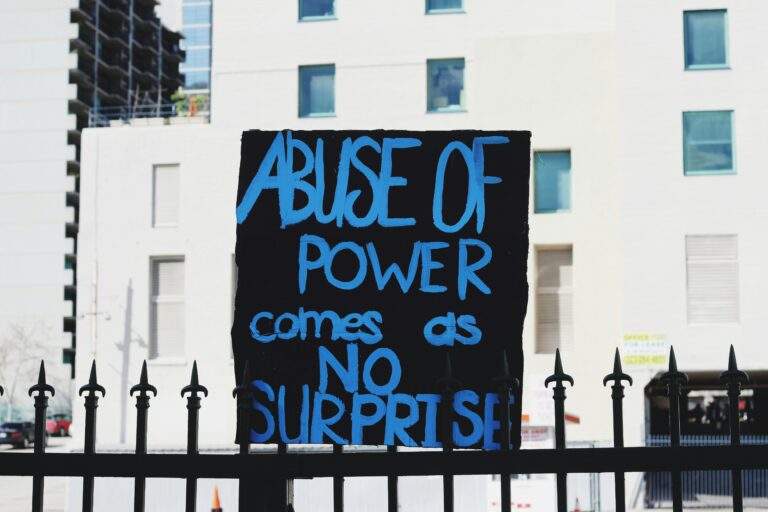Orang Tua Zaman Now, Cemas Tiada Akhir

Jika dahulu orang tua hanya pusing soal harga minyak tanah dan nyari guru ngaji buat anak-anak mereka, maka kini daftar kekhawatiran mereka sudah seperti tabel periodik: kompleks, saling berhubungan, dan bikin kepala migrain. Mulai dari urusan ASI eksklusif, imunisasi, mainan edukatif, tumbuh kembang, screen time, nilai rapor, sampai soal anak mereka bakal jadi barista atau bupati, semua dipikirin.
Inilah zaman di mana menjadi orang tua adalah kombinasi antara jadi detektif, ahli gizi, psikolog, IT support, dan juga ustaz dadakan. Semua demi satu tujuan: agar anak tidak “salah jalan” dan “tidak kalah bersaing”. Tapi di balik mulianya motivasi itu, terselip satu penyakit sosial modern yang sayangnya belum masuk BPJS: parental anxiety alias kecemasan orang tua.
Kecemasan Bukan Cuma Perasaan
Kecemasan orang tua hari ini bukanlah sekadar paranoia. Ia adalah hasil olahan dari berbagai tekanan sosial, ekonomi, budaya digital, dan ekspektasi pendidikan. Data dari UNICEF Indonesia (2021) menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang tua di Indonesia mengaku mengalami stres dalam mengasuh anak selama pandemi, dan kondisi itu tidak serta merta membaik pasca-COVID.
Menurut laporan Save the Children (2023), lebih dari 60% orang tua di Asia Tenggara—termasuk Indonesia—merasa tidak percaya diri dalam membesarkan anak di era digital. Mereka dibanjiri informasi yang sering kontradiktif. Hari ini baca parenting influencer bilang screen time maksimal 30 menit, besok ketemu artikel jurnal Harvard yang bilang 1 jam pun bisa bikin anak obesitas. Belum lagi grup WhatsApp sekolah yang lebih menyeramkan daripada rapat RT, dengan isinya saling pamer: “Anak saya udah hafal Juz 30 lho, padahal baru TK B.”
Ini menciptakan semacam social comparison anxiety, yaitu kegelisahan karena terus membandingkan anak sendiri dengan anak orang lain. Yang membuat ironi bertambah parah adalah: kegelisahan itu dipicu justru oleh sesama orang tua juga.
Dari ‘Tiger Parenting‘ ke ‘Helicopter Parenting‘
Jika dulu kita mengenal konsep “Tiger Mom” seperti Amy Chua (2011), yang percaya anak harus dididik keras agar sukses, maka kini telah bergeser ke bentuk baru: “Helicopter Parenting”, di mana orang tua terus mengawasi setiap detil hidup anak, bahkan sejak mereka bisa merangkak.
Menurut hasil riset dari Journal of Child and Family Studies (2020), orang tua yang terlalu protektif cenderung menyebabkan anak mengalami gangguan kecemasan, kesulitan mengambil keputusan, hingga kesulitan sosial saat dewasa. Anak-anak ini tumbuh dalam atmosfer ketakutan akan gagal karena mereka tak pernah diajari menghadapi kegagalan.
Contohnya sangat nyata: guru-guru SD hingga SMA hari ini sering mengeluh bahwa banyak orang tua langsung “naik pitam” kalau anaknya mendapat nilai jelek. Bukan anaknya yang ditegur, tapi gurunya yang disalahkan. Fenomena ini punya istilah resmi dalam psikologi pendidikan: lawnmower parenting, yakni orang tua yang “membersihkan jalan” agar anak tidak menghadapi hambatan sedikit pun. Padahal, dalam hidup nyata, lubang got tak bisa selalu ditutup.
Kecemasan Ekonomi: Ketika Anak Dianggap Investasi
Kecemasan orang tua tidak lepas dari tekanan ekonomi yang semakin ketat. Laporan Badan Pusat Statistik (2024) mencatat biaya pendidikan meningkat rata-rata 7-10% setiap tahun. Tak heran jika banyak orang tua menganggap anak sebagai “proyek masa depan”. Anak harus sukses, dapat kerja bagus, gaji gede, bisa balikin modal biaya sekolah dari TK sampai S2.
Maka lahirlah tekanan luar biasa dari orang tua agar anak ikut bimbel sejak kelas 1 SD, ikut les coding sejak TK, dan ikut kursus public speaking agar bisa jadi pemimpin masa depan. Orang tua berlomba-lomba memasukkan anak ke sekolah “favorit”, yang sering kali bukan favorit karena mutu pendidikannya, tapi karena gengsi dan harga seragamnya.
Celakanya, semakin besar investasi yang dikeluarkan, semakin besar pula kecemasan. Orang tua akan lebih panik jika anak menunjukkan tanda-tanda “menyimpang dari jalur”, seperti tidak suka matematika, tidak mau ikut olimpiade, atau bahkan sekadar bilang: “Aku mau jadi seniman.” Bagi sebagian orang tua urban yang sudah terjebak dalam sistem meritokrasi, itu seperti mendengar anaknya mau jadi ninja.
Dunia Digital dan Rasa Takut yang Melebar
Masuknya media sosial sebagai bagian dari kehidupan keluarga memperparah rasa cemas ini. Orang tua harus menghadapi dua tantangan sekaligus: menjaga anak dari konten berbahaya, dan menjaga citra keluarganya di dunia maya. Ya, sekarang, keluarga bukan hanya membesarkan anak, tapi juga membangun branding.
Instagram dan TikTok menjadi medan perang baru. Setiap orang tua berlomba memamerkan anaknya: yang sudah bisa baca usia 3 tahun, yang jago main piano, yang jadi model cilik, dan sebagainya. Fenomena ini didukung oleh tren “sharenting” (sharing + parenting), yaitu praktik membagikan kehidupan anak di media sosial secara intens.
Menurut laporan Pew Research (2022), lebih dari 70% orang tua mengunggah foto anak mereka secara rutin, dan 39% dari mereka mengaku melakukannya karena tekanan sosial agar terlihat “menjadi orang tua yang baik”. Maka dari itu, kecemasan orang tua tak lagi hanya soal anak tumbuh baik, tapi juga soal bagaimana publik melihat mereka sebagai orang tua.
Dari Cemas Menjadi Trauma Turunan
Yang paling mencemaskan dari semua kecemasan ini adalah dampak jangka panjangnya. Banyak studi menunjukkan bahwa kecemasan orang tua dapat menjadi warisan psikologis. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah penuh kecemasan cenderung mengalami gangguan emosi, kesulitan mengenali identitas diri, dan cenderung tumbuh sebagai manusia yang takut salah.
Menurut sebuah studi dari American Psychological Association (2021), tingkat kecemasan di kalangan remaja meningkat drastis, dan salah satu pemicunya adalah ekspektasi akademik dan sosial dari orang tua. Bahkan, di Indonesia, data dari Kementerian Kesehatan (2023) mencatat bahwa 1 dari 5 remaja mengalami gangguan kesehatan mental, dan banyak dari mereka mengeluhkan tekanan dari rumah.
Anak-anak ini akhirnya tidak tahu bagaimana menjalani hidup atas nama mereka sendiri. Mereka sibuk mengejar ranking, pujian, validasi, dan takut mengecewakan. Ironisnya, banyak dari mereka tidak tahu kenapa mereka belajar, kerja, atau hidup. Mereka hanya tahu: harus sukses. Harus membanggakan orang tua. Titik.
Lalu, Apa Jalan Tengahnya?
Tentu saja, menjadi orang tua tidak pernah mudah. Ini bukan perkara salah atau benar. Namun, penting bagi orang tua untuk menyadari bahwa terlalu banyak kontrol bisa melumpuhkan anak, dan terlalu banyak kecemasan justru menular.
Psikolog parenting seperti Elizabeth Pantley dan Shefali Tsabary menekankan pentingnya kehadiran emosional daripada pengawasan ketat. Kecemasan harus diubah menjadi keterlibatan yang penuh kesadaran, bukan obsesi. Fokus pada tumbuh kembang anak sebagai manusia utuh, bukan sebagai cermin prestasi orang tua.
Alih-alih sibuk khawatir anak ketinggalan kurikulum atau kalah dari anak tetangga, mungkin lebih baik bertanya: apakah anak kita merasa dicintai tanpa syarat? Apakah mereka merasa aman, bahkan saat mereka gagal? Apakah mereka tahu bahwa mereka boleh punya mimpi sendiri?
Kita Butuh Orang Tua yang Tenang, Bukan Cemas
Di tengah dunia yang semakin gaduh ini, kita tidak butuh orang tua yang perfeksionis. Kita butuh orang tua yang manusiawi, yang bisa bilang ke anaknya: “Nggak apa-apa kamu gagal.” Yang bisa mendampingi bukan hanya di ruang belajar, tapi juga di ruang tangis.
Jadi, buat para orang tua yang hari ini sedang stres lihat anaknya belum bisa baca padahal tetangganya sudah hafal tiga bahasa, tenanglah. Kadang, anak yang hari ini belum lancar membaca, bisa tumbuh jadi orang yang peka, lembut, dan punya empati luar biasa. Dan dunia tidak kekurangan orang pintar, tapi sangat kekurangan orang baik.
Mari berhenti menjadikan anak sebagai proyek. Mereka bukan startup yang butuh valuasi, tapi manusia yang perlu pelukan.