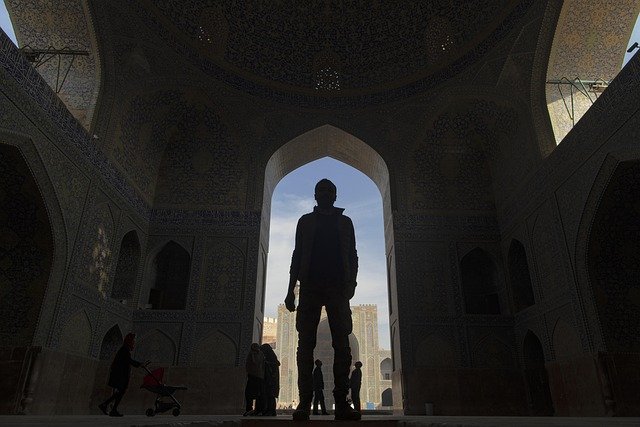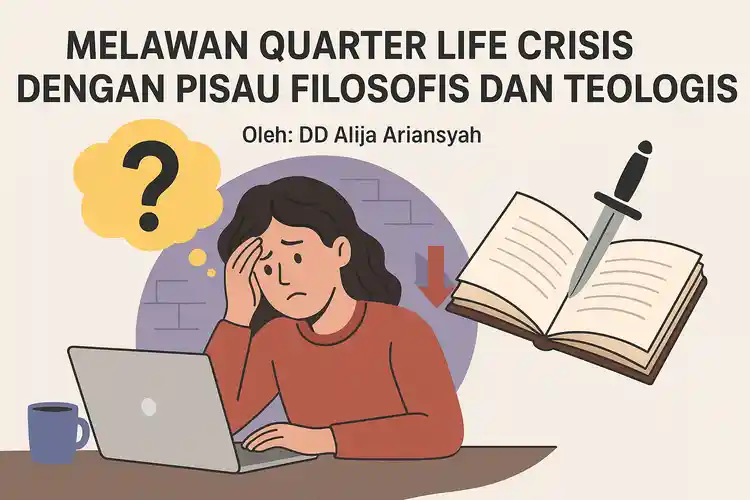Mengubah Mosaik Keberagaman Menjadi Mesin Pembangunan Bangsa
Indonesia sering kali digambarkan sebagai sebuah mosaik raksasa yang indah, tersusun dari ribuan keping suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” menjadi perekat yang menyatukan kepingan-kepingan ini. Namun, terlalu sering, narasi tentang keberagaman berhenti pada tataran romantisme persatuan dan kewaspadaan terhadap potensi konflik. Kita kerap memandangnya sebagai tantangan yang harus dikelola, bukan sebagai aset fundamental yang bisa dieksploitasi untuk kemajuan. Sudah saatnya kita mengubah paradigma: keberagaman budaya dan sosial bukanlah beban, melainkan modal dan mesin pendorong utama bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.
Potensi pertama dan yang paling nyata terletak pada sektor ekonomi, khususnya ekonomi kreatif dan pariwisata. Setiap entitas budaya di nusantara adalah sumber inspirasi produk yang unik dan bernilai jual tinggi. Dari sehelai kain tenun Sumba yang sarat filosofi, gurihnya rendang Padang yang diakui dunia, hingga alunan musik sasando dari Rote, semuanya adalah komoditas ekonomi kreatif. Ketika dikelola dengan baik melalui perlindungan hak kekayaan intelektual, pelatihan kewirausahaan, dan akses pasar, industri ini mampu menciptakan lapangan kerja masif, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat sebagai penjaga utama budaya tersebut.
Di sisi pariwisata, keberagaman adalah daya tarik utama. Wisatawan tidak lagi hanya mencari keindahan alam, tetapi juga pengalaman budaya yang otentik. Upacara adat Rambu Solo di Tana Toraja, festival Lembah Baliem di Papua, atau perayaan Waisak di Borobudur menawarkan pengalaman mendalam yang tidak bisa ditiru oleh negara lain. Ini adalah devisa yang mengalir langsung dari pelestarian budaya. Dengan mengembangkan pariwisata berbasis komunitas, kita tidak hanya menjual destinasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi subjek, bukan sekadar objek pariwisata.
Lebih dari sekadar keuntungan material, keberagaman adalah laboratorium inovasi sosial dan intelektual. Ketika individu dari latar belakang yang berbeda dengan cara pandang, sistem pengetahuan, dan pengalaman hidup yang beragam berkumpul untuk memecahkan suatu masalah, solusi yang dihasilkan cenderung lebih kreatif, komprehensif, dan tangguh. Di dunia bisnis, perusahaan yang menerapkan kebijakan keberagaman dan inklusivitas terbukti lebih inovatif dan profitabel. Prinsip yang sama berlaku di tingkat negara. Kolaborasi antara kearifan lokal, misalnya sistem irigasi Subak di Bali atau pranata mangsa dalam pertanian Jawa, dengan teknologi modern dapat menghasilkan solusi jitu untuk tantangan kontemporer seperti ketahanan pangan dan perubahan iklim.
Keberagaman juga merupakan fondasi bagi ketahanan sosial (social resilience). Masyarakat yang terbiasa hidup berdampingan dengan perbedaan akan memiliki tingkat toleransi, empati, dan kemampuan berdialog yang lebih tinggi. Nilai-nilai seperti gotong royong, tepa selira, dan musyawarah mufakat yang hidup di berbagai komunitas adalah modal sosial tak ternilai. Modal sosial inilah yang membuat masyarakat mampu bertahan dan bangkit dari guncangan, baik itu bencana alam, krisis ekonomi, maupun pandemi. Bangsa yang beragam dan bersatu secara inheren lebih adaptif dan tidak mudah pecah oleh provokasi
Keberagaman bukan hanya kekayaan budaya semata, tetapi juga menjadi pondasi utama bagi ketahanan sosial dalam suatu masyarakat. Ketika individu terbiasa hidup bersama dalam perbedaan baik suku, agama, budaya, maupun pandangan mereka akan terlatih untuk membangun toleransi, memperluas empati, serta meningkatkan kemampuan berdialog secara konstruktif. Dalam konteks ini, nilai-nilai luhur seperti gotong royong, tepa selira, dan musyawarah mufakat yang tumbuh di berbagai komunitas Indonesia menjadi modal sosial yang sangat berharga. Modal sosial tersebut menciptakan ikatan solidaritas yang kuat, memperkuat kohesi sosial, dan mendorong kerja sama lintas kelompok.
Inilah yang menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan baik bencana alam, krisis ekonomi, hingga pandemi global. Ketika terjadi guncangan, masyarakat yang memiliki keberagaman yang harmonis akan lebih cepat bangkit karena sudah terbiasa menghadapi perbedaan secara damai dan solutif. Sebuah bangsa yang majemuk namun bersatu memiliki daya tahan yang lebih besar dan tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu provokatif atau konflik identitas. Oleh karena itu, merawat keberagaman berarti juga memperkuat fondasi bangsa dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan ketidakpastian.
Potensi ini tidak akan terwujud secara otomatis. Mengubah keberagaman menjadi kekuatan pembangunan memerlukan kerja keras dan kebijakan yang sadar. Pertama, diperlukan pendidikan yang berperspektif multikultural. Siswa harus diajarkan untuk tidak hanya mentoleransi, tetapi juga menghargai dan belajar dari perbedaan sejak dini. Kedua, kebijakan pembangunan harus inklusif, memastikan setiap kelompok, terutama minoritas dan masyarakat adat, mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya, layanan publik, dan kesempatan ekonomi. Ketiga, penegakan hukum yang adil harus tanpa kompromi menindak segala bentuk diskriminasi dan ujaran kebencian yang merusak tatanan sosial.
Pada akhirnya, memandang keberagaman budaya dan sosial sebagai potensi pembangunan adalah sebuah pilihan strategis. Ini adalah langkah untuk beralih dari sekadar mengelola perbedaan menjadi secara aktif mengkapitalisasinya. Indonesia tidak akan pernah bisa bersaing di panggung global dengan meniru negara lain yang homogen. Kekuatan super kita justru terletak pada apa yang membuat kita unik: mosaik budaya kita. Dengan merawat, merayakan, dan memberdayakan setiap kepingan mosaik tersebut, kita tidak hanya membangun ekonomi yang kuat, tetapi juga sebuah peradaban bangsa yang adil, tangguh, dan dihormati dunia.
Penulis: Lilis
(Mahasiswa Doktoral Universitas Negeri Jakarta)