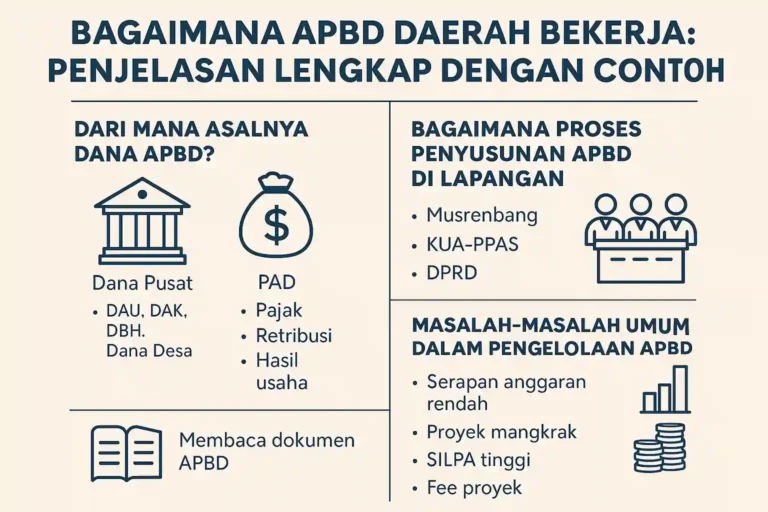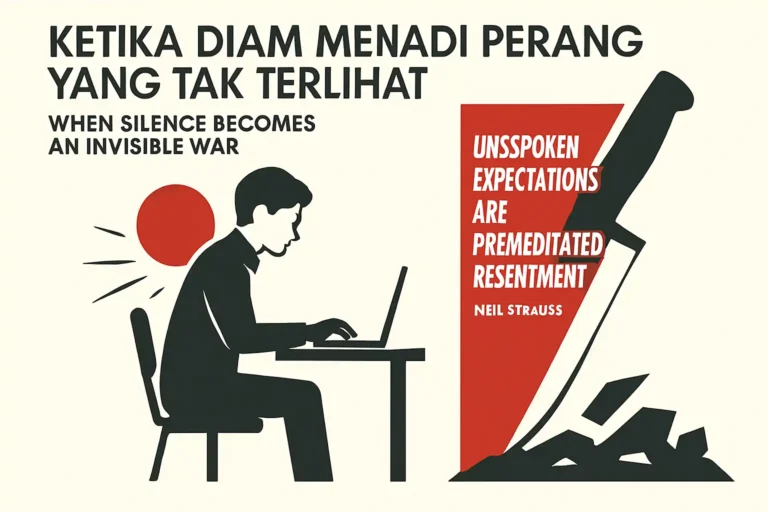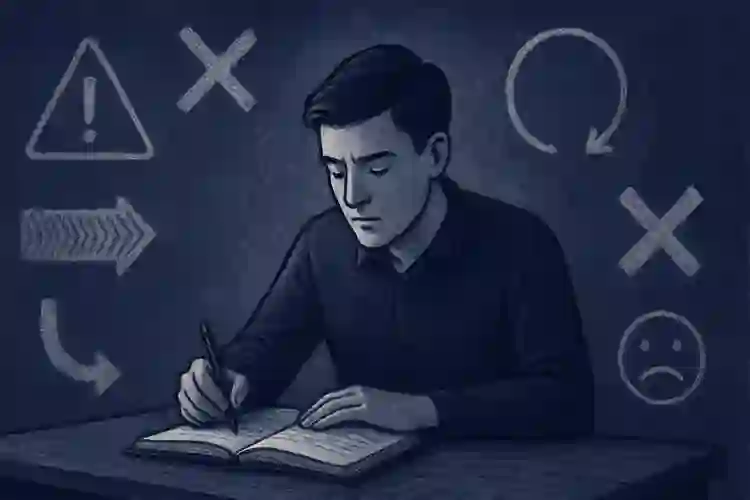Membaca, Aktivitas yang Kian Diujungkan
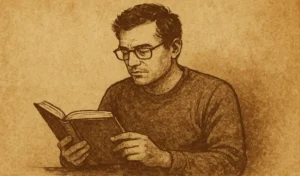
Membaca adalah aktivitas yang seolah sederhana, namun dalam praktiknya tidak pernah sesederhana membalik halaman. Sejak lama, manusia membaca sebagai bagian dari kebudayaan: dari relief batu, dari papirus, dari lembaran-lembaran kitab, hingga dari layar-layar terang yang kita bawa ke mana-mana hari ini. Tetapi perubahan bentuk bukan hanya menggeser media baca. Ia juga menggeser cara berpikir, mempengaruhi apa yang kita anggap sebagai makna membaca itu sendiri.
Dalam satu dekade terakhir, riset dari berbagai lembaga seperti Pew Research Center di Amerika Serikat hingga UNESCO menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan untuk membaca buku (dalam bentuk cetak) terus menurun secara global. Meskipun akses terhadap informasi meningkat drastis berkat internet dan perangkat digital, ini tidak secara otomatis berarti masyarakat membaca lebih banyak dalam pengertian yang substantif. Ada perbedaan besar antara paparan teks dan pemahaman yang mendalam.
Membaca dan Perubahan Media
Revolusi digital membuat akses terhadap teks menjadi sangat mudah. Namun kemudahan ini menimbulkan konsekuensi: perubahan cara kita menyerap informasi. Nicholas Carr dalam bukunya The Shallows (2010) memaparkan temuan dari berbagai studi neurologis bahwa kebiasaan membaca di layar, dengan format yang cenderung terfragmentasi, hiperlink, dan didominasi skimming, membuat otak kita lambat laun kehilangan kemampuannya untuk membaca dalam-dalam dan merenung. Studi serupa oleh Maryanne Wolf menunjukkan bahwa membaca di era digital membentuk struktur perhatian yang lebih pendek, membuat kita terbiasa dengan membaca cepat dan mengurangi kesanggupan berpikir kritis.
Sebagian besar bacaan digital diakses dalam bentuk artikel pendek, ringkasan, atau bahkan hanya judul dan cuplikan. Fenomena ini menghasilkan semacam ilusi literasi. Orang merasa telah membaca karena mereka menerima informasi, padahal yang terjadi hanyalah konsumsi fragmen-fragmen wacana. Akibatnya, pemahaman kontekstual sering kali lemah, dan kemampuan untuk membangun argumen yang utuh ikut terganggu.
Hal ini terlihat dalam perdebatan publik, baik di media sosial maupun di forum akademis. Masyarakat mudah terjebak dalam dikotomi hitam-putih, sulit mencerna kompleksitas, dan cenderung memilih sikap reaktif. Sebuah survei oleh Stanford History Education Group (2016) bahkan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa perguruan tinggi tidak mampu membedakan antara konten editorial dan konten iklan di media digital, menandakan lemahnya literasi kritis.
Dari Literasi ke Literasi Kritis
Membaca bukan hanya soal mengenal huruf dan memahami makna harfiah dari sebuah kalimat. Dalam definisi UNESCO, literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, dan berkomunikasi menggunakan materi cetak, tertulis, dan visual. Di era informasi ini, literasi kritis menjadi sangat penting. Literasi kritis bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan untuk menganalisis, mempertanyakan, dan mengevaluasi informasi.
Sayangnya, penguasaan literasi kritis masih rendah di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2018, skor kemampuan membaca siswa Indonesia berada di peringkat ke-74 dari 79 negara yang disurvei. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun program-program pemerintah mendorong peningkatan minat baca, tantangannya tidak sekadar pada kuantitas bahan bacaan atau akses, tetapi lebih pada kualitas dan pendekatan pembelajaran yang menumbuhkan daya pikir analitis.
Membaca dalam pengertian mendalam menuntut waktu, kesabaran, dan ketekunan. Ketiganya adalah kualitas yang semakin langka di tengah budaya kecepatan dan distraksi. Dalam konteks ini, pertanyaan yang penting diajukan bukan hanya “apakah kita masih membaca?”, tetapi lebih jauh, “apa yang kita harapkan dari membaca?”
Membaca sebagai Aktivitas Kognitif dan Sosial
Aktivitas membaca tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan tindakan kognitif yang sangat kompleks, yang melibatkan interaksi antara memori, logika, emosi, dan imajinasi. Membaca memperkaya kosakata, memperkuat struktur berpikir, dan memungkinkan seseorang membentuk pemahaman yang lebih kaya tentang dunia.
Dalam ranah psikologi pendidikan, studi dari Anne Cunningham dan Keith Stanovich (1998) mengonfirmasi adanya hubungan yang kuat antara kebiasaan membaca dan pencapaian akademik. Mereka menyebutnya “Matthew Effect”—istilah dari perumpamaan Injil yang berarti “yang kaya akan semakin kaya.” Anak-anak yang sering membaca sejak dini akan memperkaya kosakatanya lebih cepat, memahami konsep abstrak lebih dalam, dan akhirnya berprestasi lebih baik secara umum.
Selain dampak kognitif, membaca juga memiliki dimensi sosial. Ia membantu individu memahami perspektif lain, meruntuhkan stereotip, dan menumbuhkan empati. Dalam sebuah studi oleh Raymond Mar dan koleganya di York University, ditemukan bahwa individu yang terbiasa membaca fiksi cenderung memiliki empati lebih tinggi dibanding yang tidak. Ini penting, karena empati adalah prasyarat utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis.
Krisis Waktu dan Perhatian
Namun, hari ini kita menghadapi krisis lain: krisis perhatian. Meskipun banyak orang memiliki akses ke buku dan sumber bacaan lainnya, mereka tidak lagi memiliki cukup waktu dan energi mental untuk benar-benar membaca. Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi mencerminkan kondisi budaya: kita hidup dalam ekosistem yang menuntut kecepatan, keterhubungan tanpa henti, dan produktivitas yang tak pernah selesai.
Platform digital dirancang untuk menarik perhatian dan mempertahankannya selama mungkin, dengan notifikasi, scroll tanpa batas, dan algoritma yang menyodorkan konten berbasis kecenderungan konsumsi. Ini memecah konsentrasi, menjadikan pembacaan mendalam sebagai aktivitas yang sulit dilakukan secara berkelanjutan. Dalam model bisnis ini, perhatian adalah komoditas. Dan membaca panjang adalah ancaman bagi pola konsumsi impulsif.
Bahkan dalam institusi pendidikan, tantangan serupa muncul. Banyak siswa dan mahasiswa mengalami kesulitan membaca teks akademik, bukan karena kurangnya kemampuan teknis, tetapi karena tidak terbiasa dengan kesunyian dan disiplin berpikir yang dibutuhkan untuk menyerap bacaan berat. Dalam beberapa studi, mahasiswa cenderung menghindari sumber primer atau buku teoretis, dan lebih memilih ringkasan video atau konten visual. Tentu ini bukan kesalahan individu. Sistem yang kita bangun bersama ikut menciptakan preferensi ini.
Pendidikan Membaca Kembali
Untuk itu, perlu ada upaya sistemik untuk membangun kembali ekosistem membaca. Ini tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah atau guru, tetapi juga pada keluarga, media, penerbit, dan tentu saja kebijakan publik. Kurikulum harus memperkuat pendekatan literasi kritis, bukan sekadar mengejar hafalan isi buku teks. Perpustakaan perlu dihidupkan kembali, bukan hanya sebagai ruang penyimpanan buku, tapi sebagai ruang pertemuan gagasan.
Di ranah digital, platform membaca berbasis komunitas seperti Goodreads, Wattpad, atau bahkan klub buku daring dapat menjadi ruang alternatif untuk menumbuhkan minat baca. Tapi harus disadari, teknologi hanyalah alat. Tanpa budaya membaca yang kuat, teknologi hanya akan mempercepat apa yang sudah lemah: minat yang dangkal, informasi yang cepat lewat tanpa bekas.
Kebijakan publik juga perlu berani mengalokasikan dukungan nyata terhadap produksi buku bermutu, penerjemahan karya penting, dan distribusi bahan bacaan yang merata hingga ke daerah. Di negara-negara seperti Finlandia, kebijakan literasi menjadi bagian integral dari pembangunan manusia. Membaca bukan dianggap sebagai aktivitas pelengkap, tetapi sebagai fondasi berpikir yang menopang seluruh struktur pendidikan dan demokrasi.
Membaca sebagai Tindakan Sosial dan Politik
Membaca tidak netral. Ia adalah tindakan sosial yang memiliki implikasi politik. Pilihan apa yang dibaca, bagaimana ia dibaca, dan siapa yang memiliki akses untuk membaca menentukan lanskap pengetahuan dalam sebuah masyarakat. Dalam sejarah, penguasa otoriter selalu curiga terhadap bacaan. Buku dibakar, perpustakaan dikendalikan, dan pembaca dikriminalisasi. Sebab mereka tahu, membaca membebaskan.
Hari ini, pembatasan bisa datang dalam bentuk yang lebih halus: sensor algoritmik, monopoli distribusi pengetahuan, hingga dominasi satu bahasa atau satu perspektif wacana dalam produksi konten. Maka membaca dengan kesadaran kritis menjadi semakin penting. Membaca bukan hanya menyerap, tapi juga menimbang, memilih, bahkan menolak.
Di sinilah membaca kembali kepada makna asalnya: bukan sebagai kegiatan privat, tetapi sebagai proses yang melibatkan etika dan tanggung jawab sosial. Di tengah derasnya informasi, membaca yang reflektif dan mendalam adalah satu-satunya cara untuk menjaga agar kita tidak hanyut, tidak mudah diarahkan, dan tidak menjadi korban pasif dari sistem yang membentuk kita.
Kita hidup dalam zaman di mana informasi membanjiri, tetapi makna menjadi langka. Membaca, di tengah kondisi ini, tidak lagi sekadar aktivitas kognitif, tetapi menjadi tindakan resistensi. Ia adalah cara untuk merebut kembali perhatian kita sendiri, memperlambat ritme hidup yang dipercepat oleh mesin, dan membangun ulang fondasi berpikir kritis yang dibutuhkan dalam kehidupan publik.
Membaca tidak menjanjikan solusi instan. Ia tidak menyelesaikan semua masalah. Tapi membaca membuat kita bertanya lebih baik, memahami lebih dalam, dan melihat lebih luas. Dalam dunia yang makin sempit oleh algoritma, membaca adalah pintu yang tetap terbuka menuju ruang kemungkinan.