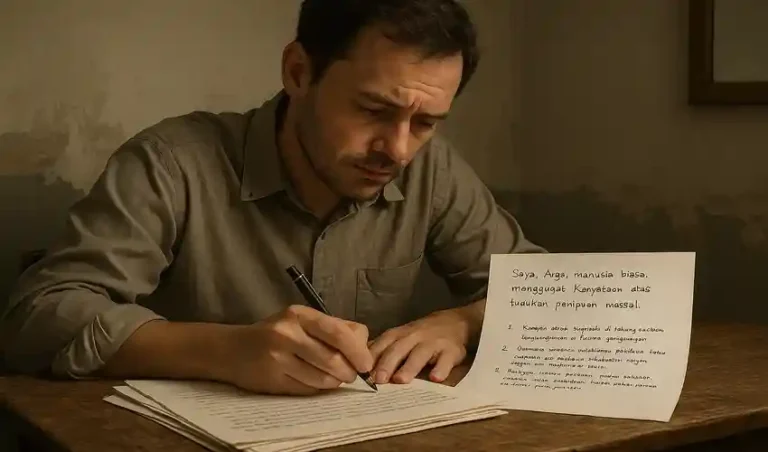Meja Kaki Lima
Hari Saat Langit Terlalu Rendah
Pada hari keempat setelah pembakaran meja, kota itu seperti menggigit lidahnya sendiri. Langit mendung. Bukan karena hujan, tapi karena kabut gas air mata dari demonstrasi yang pecah tak jauh dari pasar. Jalanan dicegat, wartawan ditendang, dan yang paling menyakitkan: meja-meja lain mulai digusur, satu per satu, hingga suara pasar menjadi sunyi seperti museum penuh luka.
Pak Darun tak terlihat.
Orang-orang bilang dia ditangkap. Ada juga yang bilang ia dibawa oleh anaknya ke desa karena penyakit lamanya kambuh.
Tapi sore itu, seorang anak kecil datang. Tubuhnya kurus, bajunya dekil. Ia menarik meja yang baru—bentuknya persis, dengan lima kaki dan puisi yang ditulis tangan gemetar:
“Jika yang besar menindas yang kecil, maka kecil akan tumbuh di celah sempit dan meledak dari bawah.”
Anak itu tak tahu siapa Pak Darun. Ia hanya tahu, ia lapar. Dan katanya, meja itu bisa memberi makan bukan hanya perut, tapi juga kepala.
Tawa yang Tak Bisa Ditertibkan
Hari-hari berikutnya aneh. Pemerintah mengeluarkan peraturan baru: semua pedagang wajib mendaftar ke “Sistem Lapak Nasional” (SILANAS) dan dikenai retribusi digital. Ironisnya, koneksi internet di pasar selalu mati. Sementara Satpol terus berkeliling, menyita yang tak terdaftar.
Namun tiap mereka datang, suara-suara tawa justru terdengar. Tawa getir. Tawa melawan. Tawa yang tak bisa ditertibkan.
Meja Pak Darun—atau yang orang sebut begitu, meski kini sudah tak tahu siapa pemiliknya—menjadi tempat berkumpul para pendengar dan penutur. Di sana, setiap gorengan jadi semacam ayat darurat, dan setiap teh manis jadi semacam perjanjian diam: bahwa rakyat hanya butuh satu hal—dipandang sebagai manusia.
Dan itu, rupanya, lebih mengancam kekuasaan daripada demonstrasi.
Hujan dan Sebuah Selebaran
Suatu hari, hujan turun seperti amarah yang jatuh dari langit. Air menggenang. Meja tergenang hingga setengah kaki. Tapi tetap, kaki kelima itu tegak, mencengkeram bumi seperti janji tak terlupakan.
Di bawah meja, seseorang meninggalkan selebaran lusuh. Isinya hanya satu kalimat:
“Jika kau mencari keadilan di atas kertas, maka kelak kau akan memakan tinta dan bukan nasi.”
Selebaran itu difoto, dibagikan, disalin, ditempel di dinding sekolah, pintu masjid, bahkan tiang listrik.
Pemerintah menyebutnya “ajakan makar.”
Tapi rakyat menyebutnya “pesan lapar.”