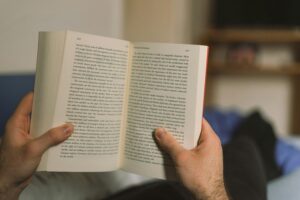Masa Depan Pembangunan Daerah: Responsif dan Berkelanjutan

Perencanaan pembangunan daerah bukan sekadar rangkaian dokumen teknokratis, melainkan fondasi bagi arah dan masa depan sebuah wilayah. Di tengah dinamika nasional dan global yang kian kompleks, kabupaten/kota dituntut untuk tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga memiliki visi pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan berkelanjutan. Sayangnya, banyak perencanaan daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya data perencanaan, hingga intervensi politik yang kerap kali membelokkan arah pembangunan. Dalam konteks inilah, penting untuk merumuskan kembali gagasan tentang perencanaan daerah yang ideal—yang tak hanya legal-formal, tetapi juga substantif dan berbasis bukti.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 3 UU tersebut menyebutkan bahwa perencanaan dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Artinya, setiap kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam menyusun perencanaan yang tidak sekadar menggugurkan kewajiban administrasi, melainkan harus memuat arah pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Mengarusutamakan Dokumen-Dokumen Strategis
Perencanaan daerah yang ideal harus berpijak pada prinsip evidence-based planning yaitu perencanaan yang didasarkan pada data dan bukti empiris yang kuat. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali berbenturan dengan kebiasaan menyusun dokumen rencana berdasarkan asumsi atau copy-paste dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal, seperti yang diungkapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam berbagai forum konsultasi publik, pendekatan berbasis bukti adalah fondasi utama agar perencanaan benar-benar menyentuh akar permasalahan dan potensi daerah. Misalnya, kabupaten yang memiliki karakteristik geografis sebagai daerah pesisir akan memiliki tantangan berbeda dibandingkan daerah dataran tinggi. Tanpa data yang akurat dan diperbarui secara berkala, mustahil menyusun perencanaan yang adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Selanjutnya, partisipasi publik menjadi elemen tak terpisahkan dalam perencanaan daerah yang ideal. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan RPJMD dan RKPD wajib melibatkan pemangku kepentingan melalui mekanisme Musrenbang. Namun, dalam praktiknya, banyak Musrenbang hanya bersifat seremonial dan tidak benar-benar menjadi ruang partisipatif yang substansial. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa atau kelurahan masih rendah, bahkan sering kali hanya menghadirkan tokoh formal tanpa representasi komunitas marjinal. Padahal, keberhasilan perencanaan justru bergantung pada kemampuan menangkap aspirasi akar rumput, bukan semata keputusan elite.
Perencanaan yang baik juga harus selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan indikator utama apakah perencanaan daerah sungguh-sungguh dijalankan atau hanya menjadi formalitas belaka. Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, ditemukan bahwa masih banyak daerah yang tidak konsisten antara dokumen RPJMD dengan realisasi anggaran di lapangan. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah dan masih kuatnya pengaruh non-teknokratis dalam proses implementasi.
Idealnya, perencanaan daerah harus responsif terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi krisis global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan ketimpangan digital. Kabupaten/kota perlu menjadikan isu-isu ini sebagai bagian integral dalam rencana pembangunan mereka. Misalnya, perencanaan pembangunan infrastruktur seharusnya mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup serta risiko bencana. Menurut kajian dari Kementerian PPN/Bappenas dan UNDP (2023), pembangunan berketahanan iklim akan menghemat anggaran pemerintah hingga 30% dalam jangka panjang karena menurunkan risiko kerusakan dan biaya pemulihan pasca bencana. Oleh karena itu, pendekatan perencanaan berbasis risiko dan adaptif perlu segera diarusutamakan dalam dokumen-dokumen strategis daerah.
Menjawab Kebutuhan Lokal, Tanpa Mengabaikan Pembangunan Nasional
Perlu juga digarisbawahi bahwa perencanaan daerah bukan semata soal rumusan teknis, melainkan juga merupakan seni mengelola harapan publik dan membangun arah kolektif jangka panjang. Maka dari itu, peran kepala daerah dan tim perencana menjadi sangat penting dalam memastikan proses ini berlangsung secara inklusif dan transparan. Mereka harus mampu menjadi jembatan antara aspirasi warga, kebutuhan sektoral, dan arahan pembangunan nasional. Kepala daerah yang visioner tidak akan hanya berfokus pada pencitraan atau proyek fisik jangka pendek, melainkan membangun sistem yang berkelanjutan dan menciptakan ekosistem pembangunan yang sinergis.
Di sisi lain, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan menjadi kunci agar proses tidak berhenti pada tahap perumusan. Dalam Permendagri 86/2017 ditegaskan bahwa evaluasi RPJMD harus dilakukan setiap tahun dan hasilnya menjadi dasar penyesuaian arah pembangunan. Sayangnya, di banyak daerah, kegiatan evaluasi cenderung dilakukan sebagai formalitas dan tidak berimplikasi nyata pada revisi strategi pembangunan. Evaluasi semestinya menjadi momen refleksi kolektif: apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang harus diperbaiki. Di sinilah peran DPRD juga penting untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan dengan semestinya, tanpa tergelincir menjadi arena politik transaksional.
Membangun sistem perencanaan yang ideal tentu bukan pekerjaan sehari. Ia menuntut transformasi budaya birokrasi, kapasitas teknis, serta kemauan politik yang sungguh-sungguh. Pemerintah pusat, melalui Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, dapat terus memperkuat kapasitas daerah melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta penyediaan platform data dan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi. Di era digital, penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi alat bantu penting untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan secara elektronik dan real-time. Namun, teknologi hanyalah alat—tanpa komitmen etis dari para pemangku kepentingan, sistem yang canggih pun akan lumpuh oleh kepentingan sempit.
Pada akhirnya, perencanaan daerah yang ideal adalah yang mampu menjawab kebutuhan lokal tanpa mengabaikan arah pembangunan nasional. Ia bukan hanya alat teknokratis, tetapi juga cermin dari kematangan demokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Kabupaten/kota yang mampu merumuskan rencana pembangunan secara partisipatif, berbasis bukti, adaptif terhadap perubahan, dan konsisten dalam pelaksanaan, akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. Sebab, pembangunan sejatinya bukan tentang seberapa banyak yang dibangun, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dan perencanaan adalah langkah pertama menuju cita-cita tersebut.