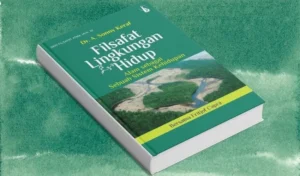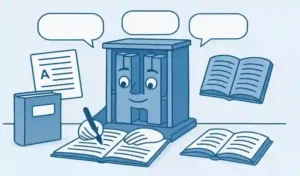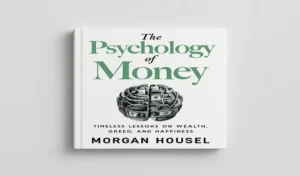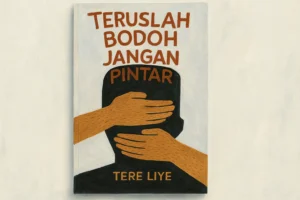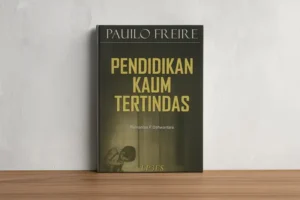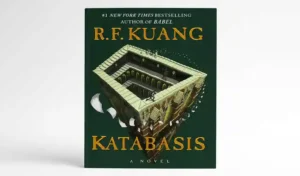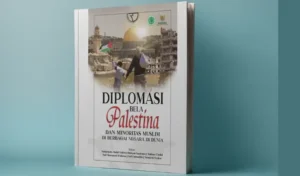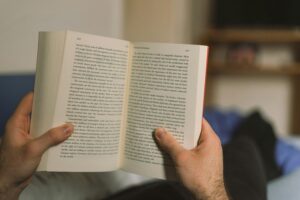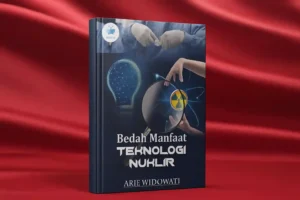Literasi dari Malaysia, Pelajaran bagi Indonesia
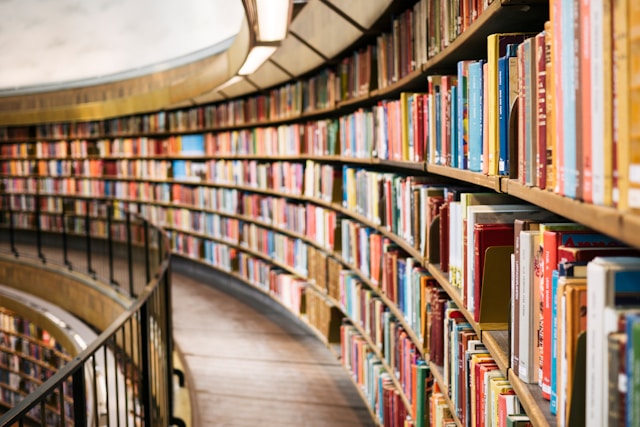
Berita tentang pelajar di Malaysia yang mendapatkan bantuan sekitar Rp 956.000 untuk membeli buku-buku berbahasa Indonesia membawa kita pada sebuah refleksi penting mengenai kondisi literasi dan pendidikan, khususnya jika dibandingkan dengan situasi di Indonesia. Di permukaan, bantuan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya cukup signifikan. Ini bukan sekadar soal uang atau buku, tetapi soal bagaimana sebuah bangsa memperlakukan literasi sebagai fondasi pembangunan generasi muda.
Di Malaysia, pemerintah menyadari pentingnya literasi dan memberikan perhatian konkret dengan menyediakan dana bagi pelajar agar bisa membeli buku sesuai minat mereka. Dengan cara ini, pelajar tidak hanya menerima buku secara seragam, tetapi memiliki kebebasan memilih apa yang ingin mereka baca. Pendekatan ini memungkinkan pengalaman membaca menjadi lebih personal, relevan, dan bermakna. Selain itu, langkah ini menunjukkan bahwa membaca dan mengakses ilmu pengetahuan adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang kritis, kreatif, dan berwawasan luas.
Sementara itu, kondisi di Indonesia terasa berbeda. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu bagi seluruh warga, tetapi akses terhadap buku dan bahan literasi seringkali terbatas, terutama di daerah terpencil. Distribusi buku di Indonesia cenderung seragam dan formal, tanpa memperhatikan minat atau kebutuhan spesifik pelajar. Dampaknya, keinginan membaca bisa menurun karena buku yang diterima tidak relevan atau menarik bagi mereka. Ironisnya, negara yang memiliki bahasa sendiri dan warisan budaya yang kaya justru belum mampu memberikan akses yang memadai kepada generasi mudanya.
Fenomena ini menghadirkan paradoks yang menarik: pelajar di negara tetangga justru lebih mampu menikmati literatur Indonesia daripada pelajar di tanah airnya sendiri. Di Malaysia, mereka bisa membeli buku dan mengenal sejarah, budaya, serta nilai-nilai Indonesia. Sementara di Indonesia, banyak pelajar harus menghadapi keterbatasan akses yang membuat pengalaman dan pemahaman budaya mereka menjadi parsial. Hal ini menjadi peringatan bahwa literasi bukan hanya soal ketersediaan buku, tetapi soal bagaimana sebuah bangsa memastikan anak-anaknya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan memahami dunia serta budayanya sendiri.
Lebih jauh lagi, cara distribusi dan pendekatan terhadap literasi di Indonesia perlu ditinjau ulang. Memberikan ruang bagi pelajar untuk memilih buku sesuai minat mereka terbukti lebih efektif dibandingkan distribusi seragam. Minat membaca tumbuh ketika pembaca merasa relevansi buku dengan kehidupannya. Literasi bukan sekadar membaca teks, tetapi menginternalisasi pengetahuan, mengasah imajinasi, dan membangun kemampuan berpikir kritis. Dengan cara yang lebih fleksibel, pelajar dapat menemukan buku yang memantik rasa ingin tahu, sehingga pengalaman membaca menjadi aktivitas yang menyenangkan dan bermakna.
Berita tentang Malaysia juga menyinggung pentingnya literasi sebagai bagian dari budaya nasional. Pelajar yang membaca buku Indonesia secara tidak langsung mengenal sejarah, tradisi, dan nilai-nilai bangsa. Sementara di tanah air, keterbatasan akses buku membuat sebagian pelajar kehilangan kesempatan itu. Hal ini menunjukkan bahwa akses literasi berkaitan erat dengan pembentukan identitas budaya dan pemahaman sejarah. Anak-anak yang tidak memiliki akses memadai berpotensi tumbuh dengan pemahaman budaya yang terbatas, sehingga rasa memiliki terhadap identitas nasional juga bisa ikut tereduksi.
Selain masalah akses, hal ini juga membuka diskusi tentang prioritas dalam kebijakan pendidikan. Literasi seharusnya ditempatkan sebagai fondasi utama, bukan sebagai program tambahan yang muncul ketika anggaran lebih tersedia. Investasi dalam literasi adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas intelektual, kreativitas, dan daya saing generasi muda. Tanpa perhatian serius, risiko terjadinya generasi yang kurang membaca, kurang memahami budaya, dan minim kemampuan berpikir kritis menjadi nyata. Sebaliknya, ketika literasi mendapat perhatian penuh, anak-anak bisa berkembang menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu memahami dan menghargai warisan budaya mereka.
Fenomena ini juga menyinggung bagaimana sebuah bangsa menilai diri sendiri. Jika pelajar luar negeri lebih mampu mengakses literatur Indonesia dibandingkan pelajar di dalam negeri, hal itu menandakan adanya ketimpangan antara retorika kebanggaan budaya dan realitas akses pendidikan. Sebuah bangsa yang ingin maju tidak hanya perlu menciptakan narasi tentang identitas dan budaya, tetapi juga memastikan generasi mudanya memiliki akses nyata untuk mempelajari, menginternalisasi, dan melanjutkan narasi tersebut.
Selain aspek budaya dan pendidikan, fenomena ini juga berkaitan dengan kesenjangan sosial dan geografis. Di Indonesia, buku-buku berkualitas sering kali hanya tersedia di kota-kota besar. Sementara di daerah terpencil, anak-anak masih harus berjuang untuk mendapatkan buku yang memadai. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa literasi belum menjadi hak yang merata bagi semua anak. Jika pemerintah Malaysia mampu menyediakan bantuan bagi pelajar untuk mengenal budaya tetangga, Indonesia seharusnya mampu melakukan hal yang lebih luas: memastikan semua pelajar, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang setara terhadap literatur dan bahan bacaan.
Dari perspektif ini, program literasi tidak bisa hanya berfokus pada jumlah buku atau gedung perpustakaan. Program literasi harus menekankan kualitas, relevansi, dan kebebasan memilih. Anak-anak perlu memiliki kesempatan untuk menemukan buku yang menarik bagi mereka, untuk membentuk kebiasaan membaca yang berkelanjutan. Literasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga membuka jalan bagi pembelajaran seumur hidup, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas.
Lebih lanjut, berita tentang Malaysia ini menjadi cermin bagi pemerintah Indonesia untuk menempatkan literasi sebagai strategi pembangunan nasional. Literasi adalah fondasi bagi kemampuan anak-anak memahami ilmu pengetahuan, budaya, sejarah, dan kehidupan sosial di sekitar mereka. Tanpa fondasi ini, anak-anak berisiko tumbuh dengan pemahaman yang terbatas, sehingga daya saing dan kemampuan mereka menghadapi tantangan global pun terhambat.
Dengan demikian, ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian serius. Pertama, alokasi dana untuk literasi perlu ditingkatkan, termasuk memberikan stimulus langsung bagi pelajar untuk membeli buku sesuai minat mereka. Kedua, distribusi buku harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pembaca, bukan sekadar jumlah atau keseragaman. Ketiga, literasi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar program tambahan. Keempat, perlu ada perhatian khusus terhadap kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan terpencil.
Kesimpulannya, bantuan yang diberikan di Malaysia bukan hanya kabar positif bagi pelajar di sana, tetapi juga menjadi cermin kritis bagi Indonesia. Akses membaca, ketersediaan buku berkualitas, dan kebebasan memilih bacaan adalah kunci membangun generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap budaya sendiri. Tanpa langkah nyata dan konsisten, peluang itu akan tetap terbatas, sementara negara tetangga telah memulai langkah strategis untuk memanfaatkan literatur sebagai sarana pendidikan dan pengenalan budaya. Indonesia perlu belajar dari hal ini: literasi bukan sekadar membaca, tetapi tentang membentuk masa depan bangsa melalui akses pengetahuan, pengalaman, dan budaya yang merata bagi semua anak.