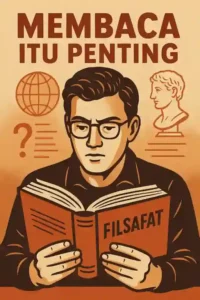Ketika Unjuk Rasa Menggugat Legitimasi Kuasa

Unjuk rasa adalah bahasa terakhir rakyat ketika seluruh pintu dialog tertutup. Saat suara dibungkam di ruang-ruang formal, jalanan berubah menjadi panggung politik rakyat, dan spanduk menjadi lembar gugatan terhadap kekuasaan. Dari Pati, Jawa Tengah, hingga Jakarta, unjuk rasa selalu menjadi barometer relasi kuasa antara rakyat dan penguasa.
Unjuk rasa bukan sekadar aksi turun ke jalan. Ia adalah ekspresi politik rakyat yang merasa diabaikan. Sepanjang sejarah, dari Revolusi Prancis hingga Reformasi Indonesia, unjuk rasa menjadi alat rakyat untuk mendakwa kebijakan penguasa yang dianggap menindas, korup, atau tidak mewakili kepentingan publik.
Momentum unjuk rasa mahasiswa tahun 1998 telah menunjukkan peristiwa krusial yang mengguncang rezim Orde Baru. Krisis ekonomi, korupsi, dan otoritarianisme membuat kepercayaan rakyat pada Presiden Soeharto runtuh. Mahasiswa memimpin gelombang protes nasional, menduduki gedung DPR, dan menyerukan reformasi.
Keberanian mahasiswa dan tekanan publik memaksa Soeharto mundur setelah 32 tahun berkuasa. Saat itu bukan sekadar pergantian rezim, melainkan lahirnya era baru: demokrasi multipartai, kebebasan pers, dan desentralisasi. Unjuk rasa tersebut membuktikan bahwa ketika rakyat bersatu, kekuasaan otoriter pun bisa hancur.
Kini, sejarah itu berulang. Atas nama perjuangan rakyat, mahasiswa kembali turun ke jalan dengan membawa ancaman: bubarkan DPR. Tuntutan mahasiswa bukan tanpa dasar. Dalam persepsi publik, Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi mencerminkan suara rakyat, melainkan berubah menjadi simbol kompromi politik elitis, pelemahan demokrasi, dan pengkhianatan terhadap konstitusi.
Pesan dari Peristiwa Bastille
Salah satu unjuk rasa paling ikonik dalam sejarah dunia terjadi pada 1789 di Prancis. Latar belakangnya jelas: kelaparan, ketimpangan sosial, dan pajak yang menindih rakyat kecil sementara bangsawan hidup dalam kemewahan. Kebijakan Raja Louis XVI yang gagal mengatasi krisis ekonomi memicu kemarahan rakyat.
Saat parlemen hanya melayani raja dan bangsawan, rakyat menuntut perwakilan sejati. Ketimpangan ekonomi dan ketidakpekaan kekuasaan menjadi bara api yang membakar Bastille. Pesan mereka jelas: legitimasi kekuasaan tanpa kepercayaan layak diganti.
Puncaknya adalah penyerbuan Penjara Bastille, simbol tirani kerajaan. Aksi ini tidak hanya memicu runtuhnya monarki absolut Prancis, tetapi juga menyulut gelombang demokratisasi di seluruh Eropa. Rakyat Prancis menyerbu Bastille bukan semata karena kemarahan, melainkan karena ketidakadilan yang mengakar.
Begitu pula di Indonesia tahun 1998. Saat penguasa dan parlemen gagal merespons krisis dan justru mempertahankan status quo, mahasiswa memimpin gerakan yang akhirnya menggulingkan rezim Orde Baru. Gedung DPR bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga panggung bagi rakyat untuk mengambil alih narasi bangsa.
Kini, rakyat yang diwakili mahasiswa kembali meluapkan amarah yang memuncak. Kali ini penyebabnya terutama laporan tentang 580 anggota DPR yang menerima tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sejak September 2024. Angka yang jauh di atas kemampuan ekonomi rakyat ini memicu kemarahan kolektif di tengah masyarakat.
Bukan Sekadar Protes
Unjuk rasa sejatinya bukan sekadar luapan amarah atau gangguan keamanan, sebagaimana sering diklaim penguasa. Ia adalah mekanisme koreksi. Dalam sistem yang sehat, unjuk rasa menjadi saluran aspirasi sekaligus peringatan keras bagi kekuasaan yang bobrok. Sejarah membuktikan, perubahan besar bisa lahir dari langkah massa yang marah namun terorganisir.
Kekuatan unjuk rasa tidak semata pada jumlah massa, melainkan pada kejelasan tuntutan dan daya dorong moral. Ketika rakyat mampu menyuarakan aspirasi secara konsisten dan terorganisir, penguasa—betapapun kuatnya—harus mendengar atau jatuh di bawah desakan massa. Kekuasaan bukanlah takdir. Ia bisa ditantang, dibentuk, bahkan dijatuhkan oleh rakyat yang bersatu dalam kemarahan.
Tuntutan mahasiswa membubarkan DPR bukan sikap sembrono, melainkan bentuk frustrasi terhadap lembaga yang dianggap kehilangan arah. Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan pengesahan undang-undang kontroversial yang lebih menguntungkan elite ketimbang rakyat, rendahnya transparansi legislasi, minimnya partisipasi publik, serta politikus yang lebih sibuk menari di panggung politik daripada memperjuangkan aspirasi pemilihnya.
Dalam iklim politik Indonesia yang kian elitis dan hedonis, tuntutan pembubaran DPR bukan sekadar retorika emosional. Ia adalah kritik sistemik: masih pantaskah lembaga ini disebut perwakilan rakyat? Jika tidak, legitimasi moralnya runtuh sehancur-hancurnya. Dan ketika legitimasi runtuh, wajar jika rakyat menuntut perombakan total—sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah.
Peringatan dari Jalanan
Seperti gerakan mahasiswa 1998, unjuk rasa hari ini mempertegas bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahun sekali. Demokrasi adalah integritas, akuntabilitas, dan keterwakilan yang tulus. Bila rakyat tidak lagi merasa terwakili, demokrasi hanyalah ilusi.
Unjuk rasa mahasiswa tidak lahir dari apatisme. Sebaliknya, mereka memahami akar masalah dan berani menantang sistem yang gagal. Tuntutan mereka—sekeras apa pun bunyinya—berangkat dari semangat perbaikan. Mereka tidak menolak demokrasi, justru ingin menyelamatkannya dari kerakusan dan kemunafikan.
Tentu, pembubaran DPR bukan langkah ringan. Secara konstitusional, hal ini membutuhkan proses panjang dan kompleks. Namun yang harus diingat, tuntutan tersebut adalah simbol dari krisis kepercayaan publik yang sudah akut. Jika pemerintah dan elite politik terus mengabaikannya, potensi instabilitas akan semakin meluas.
Jika kekuasaan memilih menutup telinga, merespons dengan represif atau sinis, maka yang lahir hanya ketegangan yang lebih besar. Sebaliknya, kekuasaan yang mau mendengar dan berubah dapat menghindari krisis berkepanjangan.
Unjuk rasa mahasiswa kali ini bukanlah akhir, melainkan peringatan. Peringatan bahwa demokrasi tidak akan pernah berjalan tanpa kepercayaan. Bahwa rakyat tidak akan tinggal diam saat lembaga yang seharusnya mewakili mereka justru berubah menjadi alat kekuasaan yang menjauh dari akarnya.
Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah cermin yang mengingatkan: kekuasaan yang mengabaikan rakyat, pada akhirnya akan ditinggalkan rakyat.
Editor: Muhammad Farhan Azizi