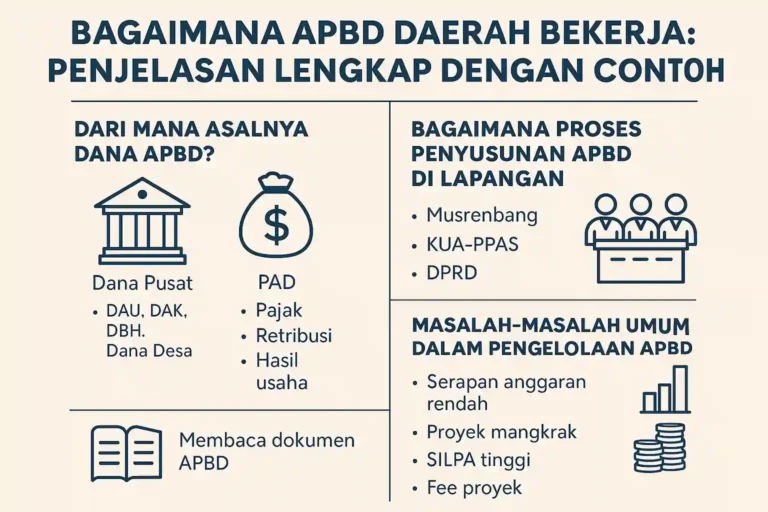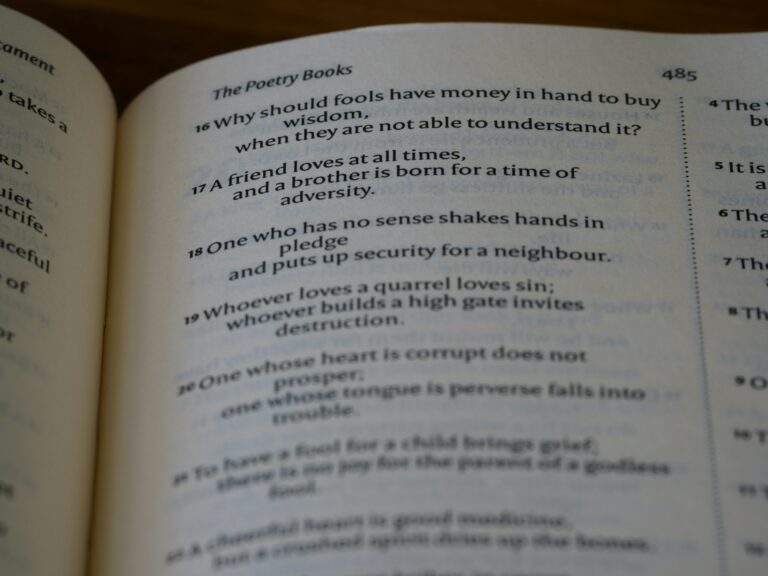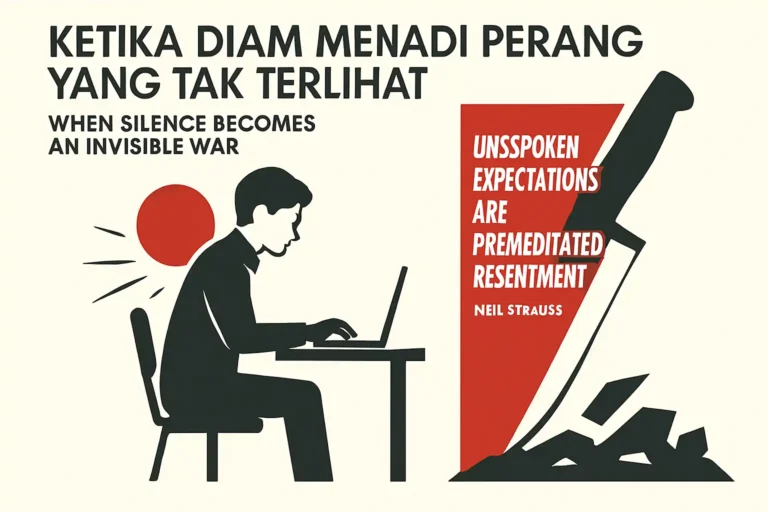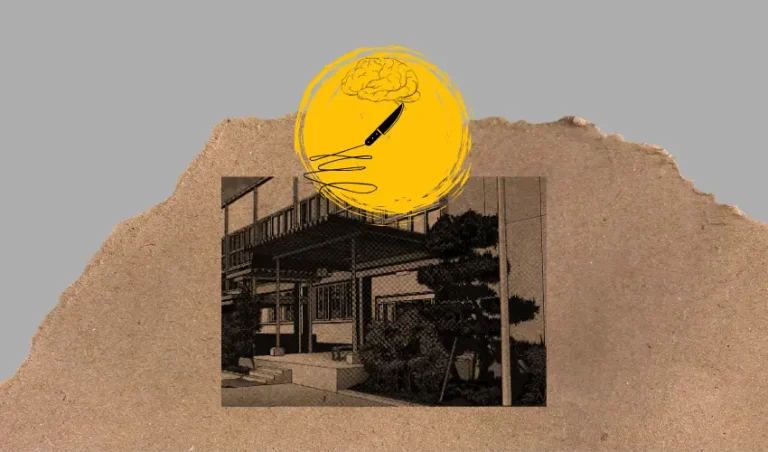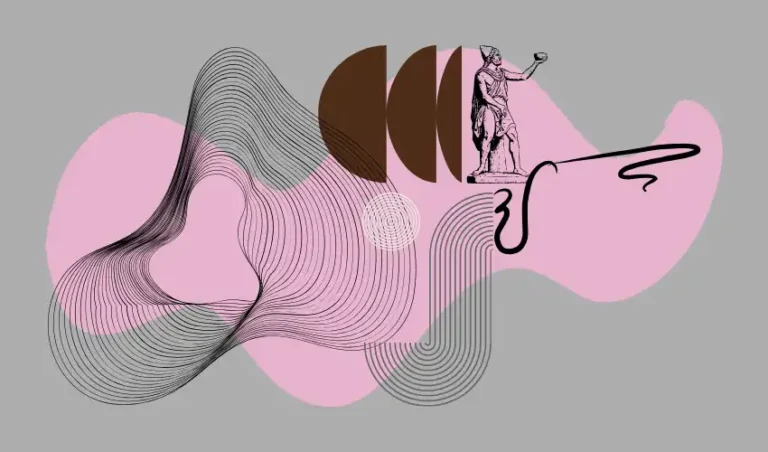Kerja Keras vs Harga Beras: Siapa yang Menang?

Di atas mimbar-mimbar kekuasaan, para pemimpin merayakan kerja seperti doa yang telah dikabulkan. Mereka mengumandangkan pembangunan dengan gegap gempita dan memuji pertumbuhan ekonomi seolah langit telah menyentuh bumi. Grafik menanjak tampil sebagai jubah kebanggaan, menggambarkan kesuksesan bangsa yang konon dinikmati oleh semua.
Namun di bawah langit yang sama, rakyat kecil justru memanggul beban hidup seperti Atlas yang tak pernah disebut dalam pidato kenegaraan. Mereka melangkah setiap hari di atas karpet ekonomi yang mewah, tetapi hanya berperan sebagai debu di sela-selanya.
Setiap hari, seseorang mengayuh becak dari subuh hingga larut malam. Orang lain berdiri berjam-jam di balik etalase toko, bahkan saat hari libur. Di tempat lain, petani menggenggam cangkul di tanah kering yang tak menjanjikan penghasilan layak. Mereka semua bekerja keras—namun tetap lapar.
Mereka bukan penganggur, tetapi negara enggan menghitung mereka sebagai bagian dari kesejahteraan. Mereka termasuk working poor—hantu-hantu statistik yang membuat angka pengangguran tampak rendah, tetapi tak pernah muncul dalam peta kemakmuran.
Negara ini mengagungkan pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan peluh para pekerja yang perlahan menguap seperti embun di pagi hari. Pembangunan menjulang tinggi bak menara gading, tetapi fondasinya bertumpu pada punggung mereka yang tak pernah diundang masuk.
Angka Statistik dan Wajah Keseharian
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sekitar 9,1%. Mayoritas penduduk miskin tinggal di pedesaan, namun banyak pula yang bertahan hidup di kota besar dengan segala paradoksnya. Di tengah gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan mewah, dan kafe-kafe estetik, realitas pahit justru tersembunyi: banyak pekerja keras tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Meski memiliki pekerjaan tetap, mereka tetap kesulitan mencukupi kebutuhan hidup. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menunjukkan bahwa di banyak provinsi, upah minimum hanya menutup 75–80% kebutuhan dasar seorang pekerja lajang. Apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga—beban hidupnya jauh lebih berat.
Struktur biaya hidup di kota justru memperparah keadaan. Harga sewa rumah melonjak, tarif transportasi meningkat, dan harga pangan terus menanjak. Sementara itu, kenaikan upah berjalan lamban. Akibatnya, para pekerja tinggal di hunian sempit dan tidak layak, berbagi ruang dengan beberapa anggota keluarga, serta menggunakan air dari sumber yang kualitasnya meragukan.
Lebih buruk lagi, mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mencapai tempat kerja karena tak mampu tinggal di dekat pusat kota. Ironisnya, mereka membangun dan menjalankan kota, tetapi tak memiliki tempat di dalamnya.
Pekerjaan Tidak Selalu Menjamin Kemakmuran
Sering kali kita terjebak dalam narasi usang: siapa pun yang bekerja otomatis keluar dari kemiskinan. Nyatanya tidak demikian. Banyak pekerja di sektor informal—seperti buruh bangunan, petugas kebersihan, atau pengemudi ojek daring—menghadapi pendapatan fluktuatif dan tidak menentu.
Di sektor formal pun, gaji minimum gagal mencukupi kebutuhan. Maka, banyak dari mereka berutang ke koperasi, rentenir, atau layanan pinjaman online dengan bunga tinggi. Mereka bukan mengejar gaya hidup mewah, tetapi berutang demi bertahan hidup: membayar sekolah anak, membeli obat, atau sekadar makan sampai akhir bulan.
Studi dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) menyebutkan bahwa rumah tangga miskin yang tetap bekerja umumnya memiliki lebih dari satu pinjaman, dan sebagian besar dipakai untuk kebutuhan pokok, bukan barang tersier.
Dengan kata lain, bekerja tidak selalu berarti bebas dari jerat kemiskinan. Bagi sebagian orang, pekerjaan justru menjadi satu-satunya alasan mereka bisa berutang untuk bertahan hidup.
Dampak Sistemik dari Kemiskinan Pekerja
Kemiskinan yang menjerat pekerja tidak berhenti pada masalah ekonomi. Dampaknya menjalar ke pendidikan anak-anak mereka. Sekolah memang gratis, namun biaya tak langsung seperti seragam, buku, dan transportasi menyulitkan banyak keluarga. Anak-anak pun terpaksa berhenti sekolah atau menerima pendidikan dengan kualitas rendah.
Lingkaran kemiskinan pun terus berputar. Anak-anak dari keluarga miskin sulit naik kelas sosial karena tidak memiliki bekal pendidikan dan jaringan. Kemiskinan menjadi warisan yang turun-temurun.
Tekanan ekonomi juga merusak kesehatan mental. Rasa cemas karena pendapatan tak cukup, kerja tanpa henti, serta tekanan sosial menciptakan stres kronis. Sayangnya, layanan kesehatan mental masih jauh dari jangkauan dan terlalu mahal. Padahal, gangguan kesehatan mental menurunkan produktivitas dan memperburuk kualitas hidup.
Ironisnya, bantuan sosial dari negara jarang menjangkau mereka. Pemerintah hanya menyasar kelompok miskin ekstrem tanpa penghasilan. Sementara para pekerja miskin—yang sebenarnya sangat membutuhkan—tidak termasuk dalam kategori penerima karena masih memiliki pekerjaan.
Jalan Keluar
Kondisi ini seharusnya menyadarkan semua pihak bahwa solusi kemiskinan tidak cukup hanya dengan membuka lapangan kerja. Kualitas pekerjaan perlu diperkuat: upah layak, jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan harus tersedia.
Pemerintah perlu merevisi standar kebutuhan hidup layak sebagai acuan upah minimum. Revisi ini wajib mempertimbangkan kondisi nyata: harga pangan, transportasi, dan tempat tinggal. Selain itu, cakupan bantuan sosial perlu diperluas agar menjangkau para pekerja miskin yang selama ini terabaikan.
Lebih dari itu, kita perlu membongkar narasi lama tentang kemiskinan. Tidak semua orang miskin malas. Banyak dari mereka bekerja dua kali lebih keras, tetapi sistem gagal memberi ruang untuk maju. Perubahan cara pandang masyarakat terhadap kemiskinan menjadi bagian penting dari solusi.
Sistem yang timpang, bukan moral individu, yang menjebak para pekerja dalam jurang kemiskinan. Maka, perubahan struktural bukan sekadar pilihan—melainkan kewajiban.
Sudah Saatnya Melihat dengan Jernih
Kerja keras tidak selalu menghasilkan kemakmuran. Dalam kenyataannya, kerja keras sering kali hanya cukup untuk bertahan hidup. Jika sistem tetap membiarkan ketimpangan, para pekerja miskin akan terus menopang ekonomi tanpa pernah menikmati hasilnya.
Kini, saatnya berhenti berpura-pura tidak melihat. Pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat luas harus mengakui kenyataan bahwa kerja tanpa jaminan layak hanyalah bentuk perbudakan modern.
Hanya melalui keberpihakan nyata dan kebijakan yang menyentuh akar masalah, martabat jutaan pekerja miskin bisa benar-benar terangkat. Mereka telah lama menopang negeri ini dari balik layar—sekarang, giliran kita menempatkan mereka di panggung utama.