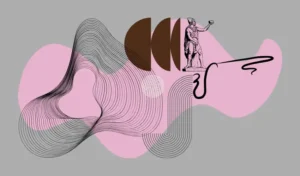Jatuh Tanpa Bunyi

Hidup tidak pernah menjanjikan jalan lurus yang mulus. Ia lebih sering tampil sebagai tikungan panjang dengan lubang-lubang tak terduga, tempat seseorang bisa terperosok dan sulit bangkit. Kita menyukai kisah-kisah kebangkitan, kisah-kisah perjuangan yang berhasil. Namun kenyataan di jalan hidup sering kali justru dipenuhi dengan kegagalan demi kegagalan, luka yang tak sempat sembuh sebelum luka lain menganga. Mari bicara soal hidup yang remuk—secara ekonomi, pendidikan, relasi, hingga kepercayaan sosial. Bukan untuk meratapi, melainkan untuk memahami bahwa banyak orang benar-benar berada di titik paling bawah.
Bayangkan seorang anak muda di kota kecil. Ia lahir dari keluarga yang patah sejak awal: ibunya pekerja rumah tangga, ayahnya entah ke mana. Pendidikan menjadi barang mewah karena uang saku saja tak tentu. Ketika masa sekolah datang, ia datang dengan seragam pinjaman dan sepatu sobek yang direkatkan dengan lem tembak. Anak seperti ini tidak masuk dalam retorika “rajin belajar pasti berhasil”. Kenyataannya, lapar membuatnya sulit berkonsentrasi, malu membuatnya enggan tampil, dan sistem pendidikan kita tidak dirancang untuk menampung anak-anak seperti dia. Tak heran, banyak yang akhirnya keluar sekolah bukan karena bodoh, tetapi karena hidup tak memberikan ruang untuk terus bertahan.
Data dari BPS menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin jauh lebih berisiko putus sekolah dibandingkan anak dari keluarga menengah ke atas. Ketika sekolah adalah satu-satunya jalan keluar, dan jalan itu sendiri rapuh, maka masa depan menjadi teka-teki yang bahkan tak bisa mulai ditebak.
Kondisi ekonomi yang sulit merembes ke seluruh aspek kehidupan. Ketika seseorang tak punya cukup uang untuk makan layak, bagaimana bisa ia memikirkan visi hidup, karier, apalagi mimpi? Gagasan untuk menjadi “versi terbaik diri sendiri” terdengar mewah. Dalam kenyataan sehari-hari, banyak orang hanya berusaha menjadi versi yang bisa bertahan hingga besok pagi.
Sebuah studi dari American Psychological Association menyebutkan bahwa tekanan ekonomi kronis dapat memengaruhi kemampuan otak dalam mengambil keputusan. Orang-orang dalam tekanan ekonomi tinggi lebih mudah membuat keputusan jangka pendek yang impulsif, bukan karena mereka bodoh, tapi karena sistem saraf mereka terkunci dalam mode bertahan hidup. Ketika hidup dalam mode bertahan, energi mental kita digunakan untuk mencari cara agar besok masih bisa makan, bukan untuk merencanakan lima tahun ke depan.
Sekarang bayangkan tekanan ini ditambah dengan relasi yang runtuh. Dalam banyak kasus, ekonomi yang buruk memicu keretakan asmara. Pertengkaran soal uang adalah salah satu pemicu tertinggi perceraian di Indonesia. Ketika dua orang hidup dalam kondisi minim, cinta yang awalnya manis bisa berubah menjadi luka yang saling menyalahkan. Bahkan pada pasangan muda, ketidakmampuan untuk mandiri secara ekonomi sering kali membuat relasi penuh dengan beban dan tuntutan, bukan kebersamaan yang menguatkan.
Aspek ini sangat jarang dibicarakan dalam ruang publik. Kita sering mendewakan cinta sebagai solusi, padahal cinta juga butuh ruang aman untuk tumbuh. Cinta yang dijepit oleh kesulitan ekonomi, oleh kurangnya pendidikan emosional, dan oleh lingkungan sosial yang tidak mendukung, akan menjadi bom waktu. Ledakannya bisa berupa kekerasan dalam pacaran, kekerasan rumah tangga, hingga hilangnya rasa percaya diri.
Pada titik ini, seseorang yang miskin secara ekonomi, putus sekolah, dan patah hati tidak hanya kehilangan harta atau cinta. Ia mulai kehilangan kepercayaan sosial. Ketika seseorang gagal di berbagai lini, masyarakat cenderung menjauh. Kita hidup dalam sistem yang mengagungkan hasil, bukan proses. Maka yang gagal dicap bodoh, malas, tidak niat berjuang. Padahal kenyataannya lebih kompleks dari itu.
Kepercayaan sosial atau social trust adalah fondasi penting dalam masyarakat. Francis Fukuyama dalam bukunya “Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity” menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kepercayaan sosial tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang lebih baik. Di level individu, kepercayaan sosial yang rendah membuat seseorang merasa dikucilkan, disalahpahami, dan akhirnya memilih menarik diri.
Kita mungkin mengenal orang seperti ini di sekitar kita: tetangga yang jarang keluar rumah, teman lama yang menghilang dari pergaulan, atau remaja yang tiba-tiba tidak lagi aktif di sekolah atau komunitas. Masyarakat sering kali menilai mereka aneh, pemurung, atau tidak tahu diri, padahal bisa jadi mereka sedang berada di titik terendah dalam hidup dan tidak melihat siapa pun yang akan memahami mereka.
Dalam psikologi, ini disebut learned helplessness—ketika seseorang sudah terlalu sering gagal atau ditolak, hingga akhirnya tidak lagi berusaha. Bahkan ketika ada peluang datang, mereka tidak mengambilnya karena merasa semua percobaan hanya akan berujung pada kegagalan. Ini bukan bentuk kemalasan, tapi bentuk luka yang mendalam dan tidak terlihat.
Kita juga harus melihat bagaimana sistem memperparah keadaan. Kebijakan pendidikan yang tidak memihak anak miskin, layanan kesehatan mental yang mahal, birokrasi bantuan sosial yang rumit—semua itu adalah bentuk pengabaian struktural. Mereka yang sedang dalam kesulitan berat tidak hanya berjuang melawan dirinya sendiri, tapi juga sistem yang sering kali tidak berpihak.
Permasalahan kompleks ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan motivasi pribadi. Motivasi penting, tapi motivasi tanpa akses dan dukungan adalah percuma. Kita tidak bisa meminta orang bangkit tanpa memberi mereka tempat berpijak. Harus ada jaring pengaman sosial yang kuat. Harus ada komunitas yang mau mendengar tanpa menghakimi. Harus ada ruang di mana orang-orang yang gagal bisa belajar ulang tanpa stigma.
Narasi sukses yang kita kenal sering kali datang dari orang-orang yang sudah punya akses tertentu. Mereka yang miskin, putus sekolah, patah hati, dan kehilangan kepercayaan sosial jarang muncul dalam cerita-cerita kemenangan karena mereka tidak sempat bangkit, tidak sempat bercerita. Mereka hidup dalam kesenyapan. Padahal dalam diam mereka menyimpan kisah tentang ketahanan, tentang luka yang tidak bisa diobati dengan kata-kata positif saja.
Mengapa penting bagi kita untuk memahami ini? Karena di balik angka kemiskinan, angka pengangguran, angka putus sekolah, dan angka kekerasan dalam rumah tangga, ada manusia. Dan manusia itu tidak hitam-putih. Mereka penuh cerita, penuh konflik batin, dan sangat mungkin merasa sendiri meski hidup di tengah kota besar. Kita perlu menggeser narasi dari “bagaimana cara sukses?” menjadi “bagaimana cara bertahan?”. Karena sebelum orang bisa mengejar mimpi, mereka harus bisa bangun dari tidur malam yang dilalui dengan cemas.
Hidup yang sulit bukan mitos. Ia nyata, dan dialami oleh jutaan orang. Kita perlu lebih jujur dalam melihat kenyataan itu. Kita perlu lebih pelan dalam memberi nasihat, dan lebih cepat dalam memberi dukungan konkret. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi penonton yang bertepuk tangan untuk mereka yang berhasil, dan menutup mata pada mereka yang tenggelam dalam diam.
Kadang hidup tidak mengajarkan siapa yang salah, tapi menguji siapa yang mau mengerti. Dalam dunia yang penuh luka, pengertian bisa jadi bentuk cinta yang paling revolusioner.