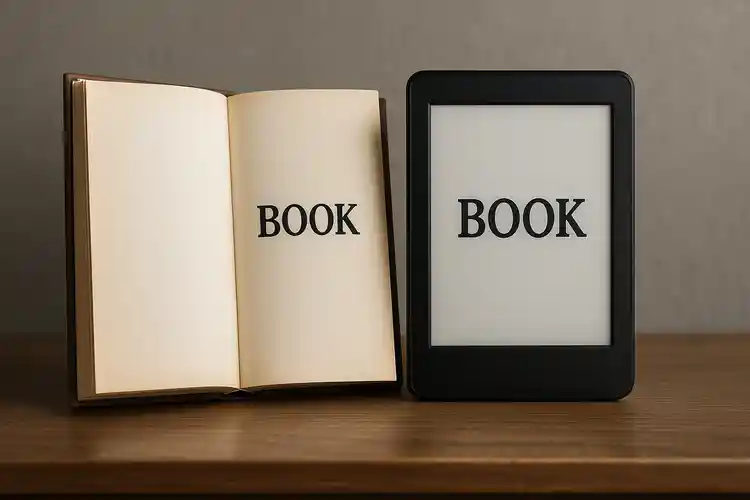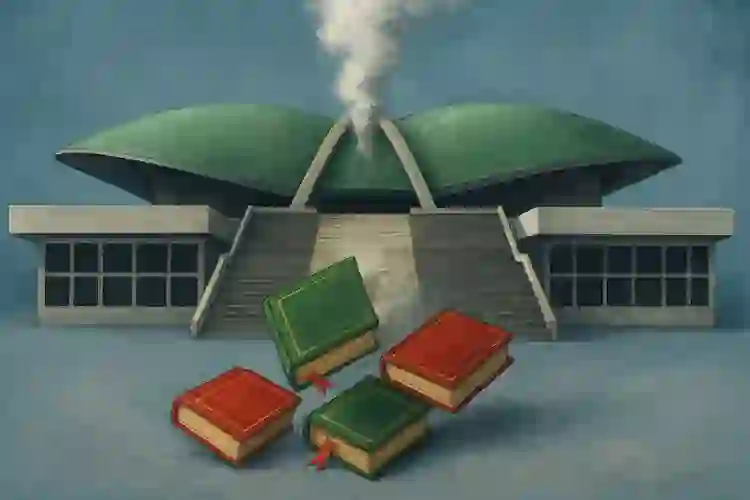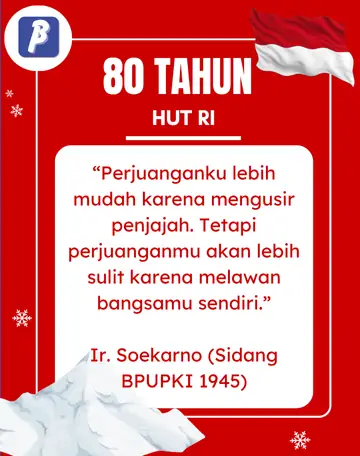Gen Z di Tengah Gelombang Stres dan Krisis Mental

Satu generasi yang kini tengah menjadi sorotan dalam diskursus sosial global adalah Generasi Z—mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Generasi ini tumbuh dalam lanskap yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya: dunia digital yang serba cepat, krisis iklim yang makin nyata, ketidakpastian ekonomi, dan pandemi global yang membekas dalam pengalaman kolektif mereka. Secara kasat mata, Gen Z tampak sangat melek teknologi, progresif secara sosial, dan vokal terhadap berbagai isu. Namun, di balik permukaan yang tampak kuat dan terkoneksi, tersembunyi kerentanan yang mendalam terhadap stres dan gangguan kesehatan mental.
Data empiris menunjukkan kecenderungan ini bukan asumsi belaka. Laporan World Health Organization (WHO) pada 2022 menegaskan bahwa masalah kesehatan mental menjadi penyebab utama disabilitas bagi remaja usia 15–19 tahun secara global. Di Amerika Serikat, data Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pada tahun yang sama menunjukkan bahwa hampir 42% remaja melaporkan merasa “sedih atau putus asa” selama dua minggu berturut-turut dalam setahun terakhir—angka tertinggi dalam dua dekade terakhir. Di Indonesia, Survei Nasional Kesehatan Jiwa oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 menemukan bahwa 1 dari 3 remaja menunjukkan gejala gangguan kesehatan mental ringan hingga sedang, terutama kecemasan (anxiety) dan depresi.
Peningkatan masalah kesehatan mental ini bukan tanpa sebab. Sebagai generasi yang tumbuh dengan ponsel pintar di tangan sejak usia dini, Gen Z mengalami eksposur konstan terhadap media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter tidak hanya menjadi saluran hiburan atau informasi, tetapi juga arena perbandingan sosial yang tiada henti. Konsep “highlight reel”—di mana orang hanya menampilkan aspek terbaik dari hidup mereka—menjadi standar tak kasat mata yang menimbulkan tekanan internal. Studi dari American Psychological Association (APA) menunjukkan korelasi signifikan antara durasi penggunaan media sosial dan peningkatan kecemasan serta ketidakpuasan terhadap citra diri.
Kondisi ini diperparah dengan budaya hustle yang merasuki dunia profesional dan pendidikan. Dalam banyak lingkungan kerja dan institusi pendidikan, produktivitas dijadikan ukuran utama kesuksesan. Banyak anggota Gen Z merasa bahwa nilai diri mereka diukur dari seberapa sibuk mereka terlihat. Laporan dari Deloitte Global Millennial and Gen Z Survey 2023 menunjukkan bahwa 46% Gen Z merasa kelelahan emosional akibat tekanan kerja dan akademik. Tekanan ini tidak hanya bersumber dari luar, melainkan juga dari internal generasi itu sendiri—yang tumbuh dengan nilai-nilai meritokrasi tinggi dan sering kali menginternalisasi ekspektasi keberhasilan instan.
Perubahan iklim juga menjadi faktor stressor tersendiri. Istilah “eco-anxiety” menjadi populer dalam satu dekade terakhir, merujuk pada kecemasan yang muncul dari kesadaran akan krisis iklim. Gen Z adalah generasi pertama yang sejak kecil disuguhi narasi krisis lingkungan secara masif, dari bencana alam yang makin sering terjadi hingga data kerusakan ekosistem yang diakses dalam sekali klik. Penelitian oleh American Psychiatric Association menyebut bahwa 67% remaja merasa sangat cemas tentang masa depan planet ini, dan ini berdampak pada motivasi mereka untuk menjalani kehidupan normal.
Krisis eksistensial yang menyertai perkembangan zaman juga tidak bisa dikesampingkan. Gen Z tumbuh dalam dunia yang sarat paradoks: teknologi membuat segalanya lebih mudah, tapi juga membuat manusia semakin tidak sabar; komunikasi semakin cepat, tetapi kedekatan emosional semakin langka. Keterasingan (alienation) menjadi fenomena yang nyata, meski secara statistik mereka memiliki lebih banyak “koneksi” dibanding generasi sebelumnya. Sherry Turkle, profesor dari MIT, dalam bukunya Alone Together mengungkapkan bahwa teknologi digital menciptakan ilusi kedekatan, padahal banyak interaksi digital bersifat dangkal dan tidak menyediakan ruang empati yang utuh.
Konflik identitas pun menjadi lahan subur bagi stres. Gen Z dikenal sangat terbuka terhadap isu gender, orientasi seksual, dan identitas budaya. Namun, dalam keterbukaan itu juga hadir kebingungan. Banyak dari mereka merasa terjebak dalam ketidakjelasan identitas di tengah tekanan untuk “menemukan jati diri” sejak dini. Tekanan ini tidak hanya muncul dari dalam kelompoknya, tetapi juga dari struktur masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberagaman. Ketika ekspresi diri dibenturkan dengan norma tradisional atau resistensi sosial, maka tekanan psikis menjadi tak terhindarkan.
Dari sisi ekonomi, Gen Z mewarisi dunia yang jauh lebih kompleks. Mereka menghadapi realitas di mana harga rumah melonjak, biaya pendidikan tinggi tak terjangkau, dan peluang kerja semakin kompetitif. Di Indonesia, misalnya, data BPS menunjukkan bahwa pengangguran terbuka pada kelompok usia 15–24 tahun mencapai angka 19,36% pada 2023—lebih tinggi dari kelompok usia lain. Kombinasi antara ketidakstabilan ekonomi dan tekanan untuk sukses menciptakan rasa tidak aman yang terus-menerus.
Tidak dapat diabaikan pula bahwa stigma terhadap kesehatan mental masih cukup tinggi di banyak komunitas. Meski Gen Z lebih terbuka untuk membicarakan isu mental health dibanding generasi sebelumnya, tidak semua lingkungan mendukung kejujuran ini. Di dunia kerja, misalnya, banyak perusahaan belum memiliki kebijakan cuti kesehatan mental atau sistem pendampingan psikologis yang memadai. Di ranah keluarga, banyak orang tua dari generasi sebelumnya masih menganggap masalah kesehatan mental sebagai kelemahan karakter, bukan kondisi medis yang perlu ditangani serius.
Peran institusi pendidikan juga patut dikritisi. Banyak sekolah dan universitas belum menyediakan layanan konseling yang memadai dan profesional. Bahkan, dalam beberapa kasus, konselor justru berperan sebagai pengendali disiplin ketimbang sebagai pendamping psikologis. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi ruang tumbuh yang tidak hanya menekankan kognisi, tetapi juga mendampingi secara emosional dan mental.
Namun, di tengah gelapnya lanskap ini, ada pula tanda-tanda perlawanan yang menggembirakan. Gen Z justru menjadi generasi yang paling aktif dalam menyuarakan pentingnya perawatan kesehatan mental. Gerakan #MentalHealthAwareness di media sosial menjadi salah satu gerakan digital paling masif dalam satu dekade terakhir. Mereka mempopulerkan terapi sebagai kebutuhan, bukan aib. Banyak pula startup kesehatan mental bermunculan, menawarkan layanan konseling daring dengan harga terjangkau.
Kita harus melihat realitas ini bukan sebagai krisis yang menakutkan, melainkan sebagai alarm untuk menata ulang struktur sosial dan nilai-nilai kita. Bahwa kecemasan dan stres bukan hanya masalah personal, tetapi cermin dari sistem yang rapuh. Jika generasi yang paling berpendidikan, paling terhubung, dan paling progresif sekalipun bisa merasa kosong dan hancur secara mental, maka ini adalah isyarat bahwa sistem kehidupan kita perlu ditinjau ulang dari fondasinya.
Menangani masalah ini membutuhkan kerja kolektif. Pemerintah harus menyusun kebijakan yang menjadikan kesehatan mental sebagai prioritas nasional. Layanan kesehatan jiwa harus mudah diakses, murah, dan bebas stigma. Kurikulum pendidikan harus memasukkan pendidikan emosional sejak dini. Media juga memiliki tanggung jawab besar dalam membingkai narasi tentang kesuksesan, kecantikan, dan eksistensi secara lebih realistis dan manusiawi.
Di tingkat mikro, keluarga harus menjadi ruang aman untuk membicarakan kegagalan dan rasa takut. Dunia kerja perlu menyediakan waktu dan ruang untuk pemulihan psikologis. Masyarakat luas harus belajar memahami bahwa mental health bukan tren generasi, melainkan kebutuhan mendasar manusia modern.
Kita hidup di zaman di mana kita bisa berkomunikasi lintas benua dalam hitungan detik, tetapi kadang kesulitan memahami diri sendiri yang ada di depan cermin. Kita bisa menyentuh langit dengan teknologi, tetapi rapuh dalam menghadapi tekanan batin. Gen Z, dengan seluruh kerentanannya, justru menjadi cermin paling jujur dari dunia yang kita bangun. Dan jika kita masih menganggap bahwa stres mereka adalah tanda lemah, mungkin sebenarnya kita sedang gagal mengenali luka kita sendiri sebagai manusia yang hidup dalam dunia yang terlalu cepat, terlalu keras, dan terlalu sepi.
Penulis: Muhammad Farhan Azizi