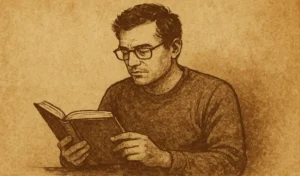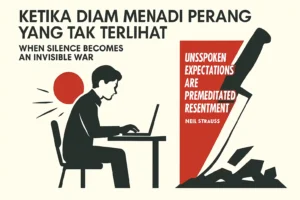Filsafat: Dialektika Kepentingan dan Ketidakpentingan dalam Epistemologi Kontemporer
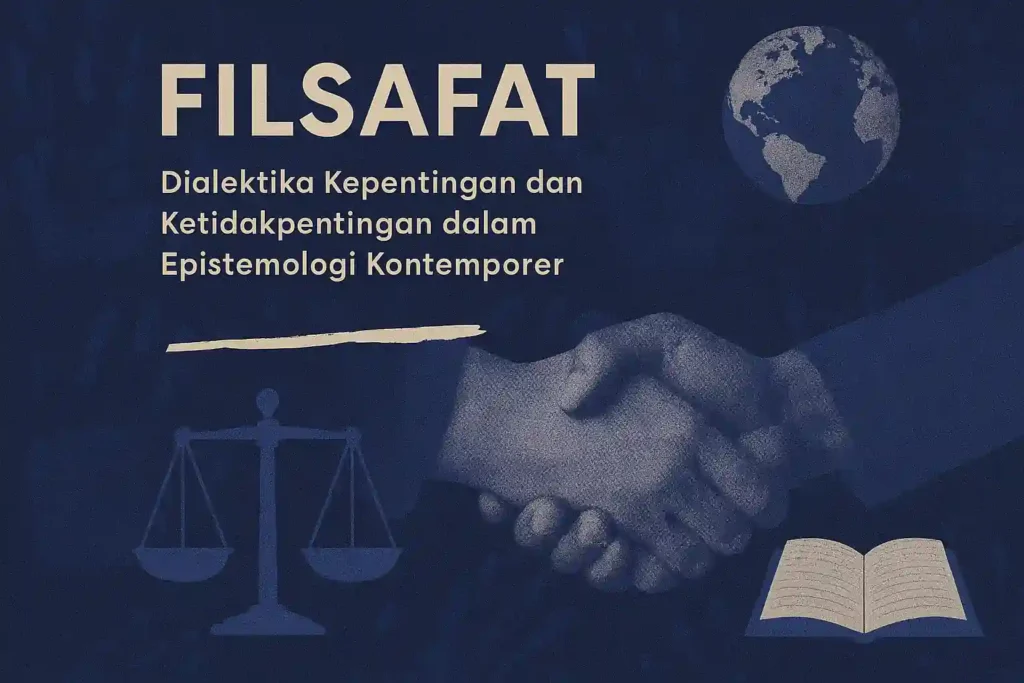
Sejak zaman Plato dan Aristoteles, filsafat dipandang sebagai upaya rasionalisasi pertama atas alam dan eksistensi manusia, berfungsi sebagai telaah transendental sekaligus kerangka konseptual sistemik bagi ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Kantian, misalnya, hubungan dialektis antara data empiris dan kategori pemahaman sangat penting. Kant menulis bahwa “Gedanken ohne Inhalt sind leer; Anschauungen ohne Begriffe sind blind” (“pikiran tanpa isi adalah kosong; intuisi tanpa konsep adalah buta”). Pernyataan ini menegaskan bahwa tanpa penggabungan antara konsep-konsep nalar dan data inderawi, pengetahuan tidak akan terwujud.
Filsafat modern juga membentuk nalar kritis dalam pendidikan dan debat sosial. Misalnya, dalam konteks teori keadilan, John Rawls memperkenalkan eksperimen pemikiran “posisi asli” dan veil of ignorance: semua individu membayangkan diri tanpa pengetahuan akan status sosialnya, sehingga mereka memilih prinsip keadilan yang benar-benar adil. Pemikiran Rawls (1971) kemudian menjadi rujukan luas dalam kebijakan publik yang mengedepankan keadilan distributif.
Dimensi Etis dan Politik Filsafat
Filsafat tidak hanya berperan dalam teori pengetahuan, tetapi juga dalam menetapkan kerangka nilai etis dan politik. Karya-karya klasik maupun kontemporer sering menekankan bahwa tanpa landasan filosofis pada martabat manusia, kebijakan hukum dan sosial dapat mengabaikan aspek kemanusiaan. Dalam konteks global, misalnya, karya Rawls mengantarkan konsep keadilan distributif berbasis veil of ignorance, yang kini banyak dirujuk dalam desain kebijakan.
Di samping itu, di ranah budaya dan politik Indonesia, filsafat kerap dipandang sebagai sumber nilai-nilai dasar. Konsep Pancasila, misalnya, sering disebut sebagai sintesis antara nilai lokal dan moral universal. Walaupun tidak selalu dikutip langsung, sejumlah sarjana berpendapat bahwa Pancasila dirumuskan dengan inspirasi nilai-nilai filsafat yang menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan bersama. Dengan demikian, filsafat tampil pula sebagai fondasi normatif dan kerangka hermeneutik bagi pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kritik Kontemporer terhadap Filsafat
Di era sains modern, filsafat juga menerima kritik tajam. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa filsafat cenderung elitis, berbelit-belit, dan jauh dari aplikasi praktis. Richard Feynman, fisikawan pemenang Nobel, pernah mengejek: “The philosophy of science is about as useful to scientists as ornithology is to birds.” Sindiran ini mencerminkan frustrasi praktisi yang merasakan filsafat ilmu terlalu abstrak untuk kebutuhan ilmu teknis.
Begitu pula para filsuf terkemuka sendiri sering menegur batas filsafat. Ludwig Wittgenstein, misalnya, dalam Tractatus menutup karyanya dengan peringatan terkenal: “Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.” Maksudnya, jika suatu hal tidak dapat diungkapkan secara bermakna oleh bahasa, lebih baik kita diam daripada berbicara tanpa makna. Teguran-teguran semacam itu menjadi bukti bahwa filsafat kadang tersandung kegagalan komunikatif dan relevansi praktis.
Filsafat dan Tuntutan Pragmatis
Seiring tantangan kontemporer seperti krisis iklim, eksploitasi digital, dan permasalahan sosial ekonomi, muncul pertanyaan seberapa banyak filsafat dapat menawarkan solusi konkret. Beberapa filsuf kontemporer bahkan menyarankan agar fokus beralih dari pencarian kebenaran mutlak ke pertanyaan kegunaan praktis. Richard Rorty (1979) menolak obsesi epistemologis tradisional dan menyatakan bahwa kita harus “menghentikan pertanyaan ‘Apa itu kebenaran?’ dan mulai menanyakan ‘Apa yang berhasil (what works)?'”. Dengan kata lain, jika filsafat terjebak terlalu lama dalam perdebatan teoretis, maka ia gagal menanggapi dunia yang membutuhkan tindakan konkret. Kritik semacam ini menegaskan bahwa filsafat perlu mempertimbangkan nilai-nilai kerja praktis dalam mengambil peran sosialnya.
Rekontekstualisasi Peran Filsafat
Meskipun demikian, para pemikir juga menunjukkan bahwa problemnya bukan semata-mata pada filsafat itu sendiri, melainkan pada ekspektasi yang dilekatkan kepadanya. Filsafat tidak berperan sebagai pencipta kebijakan atau ilmu teknik, melainkan sebagai wadah refleksi kritis dan “pra-teori” bagi disiplin lain. Para filsuf seperti Habermas dan Ricoeur pernah menyoroti bahwa filsafat kini tidak lagi memonopoli akal budi manusia, namun tetap berfungsi untuk merefleksikan dan mengkritisi batas-batas penalaran kita. Hal ini berarti filsafat patut diposisikan ulang sebagai praktik otonom yang membebaskan pola pikir, bukan sebagai paket solusi konkret.
Secara ringkas, rekontekstualisasi ini menempatkan filsafat pada peran otonomnya: sebuah medan reflektif yang membuka cakrawala interpretasi baru. Dalam batas inilah filsafat seharusnya beroperasi—mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar, memperluas horizon pemikiran, dan menyediakan kerangka konseptual bagi kajian disiplin lain—daripada berupaya menjadi teknik intervensi sosial langsung.
Paradoks Produktif Filsafat
Akhirnya, filsafat selalu menjadi ladang ketegangan produktif antara relevansi reflektif dan ketidakpraktisan aksi. Justru ketegangan inilah yang memberi filsafat kedinamisan: filsafat penting karena memampukan kita menjauh secara kritis dari aliran utama ideologi, pasar, dan kekuasaan; sekaligus tampak “tidak penting” bila dinilai dari segi hasil instan atau keuntungan pragmatis.
Dengan kata lain, apakah filsafat penting?—dalam membentuk habitus intelektual dan memperluas kesadaran kritis, jawabannya ya. Apakah filsafat tidak penting?—dalam logika praktikal dan kebutuhan hasil cepat, jawabannya juga ya. Paradoks inilah yang menjadi sumber legitimasi keberlanjutan filsafat: sebagai disiplin reflektif yang produktif justru karena mampu menjaga jarak kritis terhadap tuntutan praktis.
Referensi
Feynman, R. P. (1999). The value of science. In J. Robbins (Ed.), The Pleasure of Finding Things Out (pp. 141–150). Perseus Books. ISBN: 978-0465023950
Habermas, J. (1981). The theory of communicative action (Vol. 1–2). Beacon Press. ISBN: 978-0807015070 (Vol. 1); 978-0807014011 (Vol. 2)
Kant, I. (1998). Critique of pure reason (P. Guyer & A. W. Wood, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1781). ISBN: 978-0521657297
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press. ISBN: 978-0674000780
Ricoeur, P. (1974). The conflict of interpretations: Essays in hermeneutics. Northwestern University Press. ISBN: 978-0810104426
Rorty, R. (1979). Philosophy and the mirror of nature. Princeton University Press. ISBN: 978-0691020167
Wittgenstein, L. (1922). Tractatus logico-philosophicus (C. K. Ogden, Trans.). Kegan Paul. ISBN: 978-0486404455