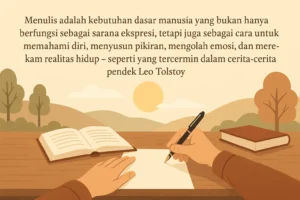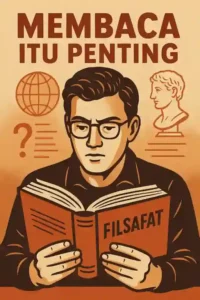DPR, Gedung Aspirasi atau Pabrik Legislasi?
“Reformasi sudah berumur 27 tahun, tapi DPR masih berperilaku seperti bayi yang doyan susu mahal dan tidur panjang. Bedanya, bayi memang lucu. DPR? Tidak sama sekali.”

Indonesia punya kebiasaan aneh: sejarah diulang-ulang, tapi bukan dalam bentuk tragedi- lalu komedi seperti kata Marx. Di sini, tragedi dan komedi sering tampil bersamaan. Kita bisa menangis dan tertawa dalam satu tarikan napas, menatap layar ponsel yang menampilkan ribuan orang berbaris di depan gedung DPR, sambil di sisi lain membaca komentar netizen yang lebih lucu daripada acara stand-up.
Demo 25 Agustus 2025 adalah salah satu babak dari panggung itu. Sebuah “seruan revolusi rakyat” yang viral di media sosial, tapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa inisiatornya. Seperti pesta kejutan, hanya saja yang diundang adalah rakyat marah, aparat bersenjata, dan para politikus yang buru-buru mencari kaca spion untuk memastikan mobil dinasnya aman dari massa.
Kita pernah melihat semua ini sebelumnya. Reformasi 1998, kerumunan mahasiswa yang memenuhi Senayan, wajah-wajah muda yang teriak lantang. Lalu tahun 2001, Gus Dur berdiri dengan wajah tenang dan mengumumkan dekrit pembubaran DPR—dekrit yang gagal, tapi meninggalkan legenda. Kini, di 2025, rakyat kembali berdiri di pintu sejarah. Pertanyaan mendesak pun muncul: apakah ini sekadar keributan musiman, atau tanda bahwa reformasi belum benar-benar tuntas?
Revolusi atau Keriuhan Digital?
Sejak awal, demo ini sudah unik. Undangan menyebar di media sosial, dengan gaya poster digital yang lebih mirip promosi konser musik daripada panggilan perlawanan. Bedanya, line-up artisnya adalah “Rakyat vs DPR”. Tidak ada panitia resmi, tidak ada orator dengan CV organisasi mapan. Bahkan, KSPSI dan BEM SI—nama besar dalam dunia gerakan—segera mengumumkan bantahan. “Itu bukan kami,” kata mereka.
Tapi rakyat sudah keburu percaya. Di Twitter (atau X, atau apapun namanya hari ini), tagar #BubarkanDPR trending. Di TikTok, yel-yel anak STM dengan teriakan “STM datang, bawa pasukan!” menjadi musik latar viral. Aneh, ironis, sekaligus heroik. Demo kali ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia tidak butuh struktur komando yang jelas untuk bergerak. Cukup satu hal: rasa muak.
Pengamanan tentu saja ketat. 1.250 personel gabungan TNI-Polri dipasang seperti pagar kawat berduri, dengan beton, kawat, dan tameng. Aparat tahu, rakyat bisa jadi massa yang lucu, tapi juga massa yang berbahaya. Di sisi lain, rakyat pun tahu, aparat bisa jadi pelindung, bisa juga jadi palu godam. Hubungan ini selalu ambigu: cinta-benci, layaknya hubungan lama yang toxic.
DPR, Gedung Aspirasi atau Pabrik Legislasi?
Tak perlu basa-basi: DPR adalah bintang utama dalam kemarahan rakyat. Dengan gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas yang bisa menembus ratusan juta rupiah per bulan, DPR seolah hidup di dimensi paralel. Sementara rakyat antri minyak goreng, mereka sibuk rapat paripurna dengan tingkat kehadiran yang sering kali mirip konser musik indie di kota kecil: sepi.
Satire terbaik justru datang dari netizen: “Kalau kerja DPR bagus, gaji segede itu enggak masalah. Tapi kalau yang dikerjain cuma tidur, ribut, atau bagi-bagi kursi, itu namanya stand up comedy dengan tiket termahal di dunia.”
Ada pula yang lebih pedas: “DPR itu kayak kos-kosan elit. Isinya penuh, tapi jarang ada yang pulang tepat waktu.”
Kritik ini bukan hal baru. Dari era Reformasi hingga kini, DPR selalu berada di garis depan ketidakpercayaan publik. Bagi sebagian rakyat, DPR bukanlah “Dewan Perwakilan Rakyat”, melainkan “Dewan Perwakilan Rentenir” atau “Dewan Perwakilan Rezim”. Perubahan singkatan ini adalah bentuk satire spontan rakyat, sekaligus peringatan keras bahwa legitimasi bukan sekadar soal kursi, melainkan soal kepercayaan.
Reformasi 1998 – Bayangan yang Tak Pernah Hilang
Ketika ribuan mahasiswa memasuki gedung DPR pada Mei 1998, itu bukan sekadar aksi mahasiswa. Itu adalah penegasan bahwa rakyat bisa mengambil alih ruang yang selama ini steril dari suara publik. Orde Baru tumbang, Suharto lengser, dan kata “reformasi” menjadi mantra nasional.
Namun, reformasi tidak pernah sepenuhnya tuntas. Ia seperti rumah yang dibangun terburu-buru: pondasinya kuat, tapi atapnya bocor, dindingnya retak, dan penghuni barunya malah memperparah kerusakan.
Kini, dua puluh tujuh tahun setelahnya, kita masih berkutat dengan masalah yang sama: korupsi, oligarki, DPR yang lebih sering jadi teater daripada forum rakyat. Bedanya, kali ini rakyat melawan dengan meme, tagar, dan video TikTok. Gerakan sosial bertransformasi menjadi gerakan digital, dengan kekuatan viral menggantikan toa kampus.
Ada yang bilang: “Reformasi gagal.” Tapi sebetulnya, reformasi tidak gagal—ia hanya dibajak. Dan demo 25 Agustus 2025 ini adalah tanda bahwa rakyat mulai sadar, bahwa mereka berhak menagih janji lama yang dikhianati elite.
Dekrit Gus Dur – Legenda yang Tak Mati
Tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur berdiri dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan: dekrit pembubaran DPR/MPR. Dengan kalimat tenang namun tegas, ia menyatakan lembaga itu kehilangan legitimasi. Indonesia tercengang. Hanya beberapa jam kemudian, politik bergerak lebih cepat dari logika: MPR menggelar sidang istimewa, Gus Dur diberhentikan, Megawati naik menjadi presiden.
Dekrit itu gagal. Tapi dalam sejarah, seringkali kegagalan justru melahirkan legenda. Gus Dur menjadi simbol perlawanan tunggal terhadap DPR yang dianggap menyimpang. Dekritnya menjadi semacam hantu yang terus bergentayangan, dipanggil kembali setiap kali rakyat muak pada DPR.
Kini, di 2025, hantu itu kembali dipanggil. Tagar tentang dekrit Gus Dur bermunculan, seolah rakyat ingin menghidupkan kembali semangatnya. Meski sadar bahwa presiden saat ini tak mungkin menirunya, memori itu berguna: sebagai pengingat bahwa legitimasi bukan milik abadi DPR. Legitimasi itu bisa hilang kapan saja, jika rakyat sudah tidak percaya.
Elite Politik – Satire Tak Pernah Cukup
Di panggung politik, para elite selalu punya bakat akting. Mereka bisa tersenyum di depan kamera, lalu tawar-menawar kursi di ruang gelap. Mereka bisa bicara tentang rakyat, sambil sibuk menulis draft RUU titipan oligarki.
Satire rakyat pun lahir:
- DPR disebut lebih rajin “mengetok palu anggaran” daripada mengetuk hati rakyat.
- Politisi dianggap lebih sibuk memikirkan “posisi” ketimbang “visi”.
- Gedung DPR dijuluki “mall paling mahal di Jakarta” karena isinya banyak yang sekadar jalan-jalan.
Kita tahu satire ini lahir dari rasa muak. Tapi dalam konteks Indonesia, satire bukan sekadar ejekan: ia adalah bentuk kritik paling demokratis. Karena ketika rakyat sudah malas bicara serius, mereka akan menertawakan kekuasaan. Dan ketika kekuasaan sudah menjadi bahan tertawaan, itu tanda legitimasi berada di titik nadir.
Sejarah yang Berulang – dari Jalan ke Timeline
Kalau Reformasi 1998 dimulai dari jalanan, Reformasi 2025 dimulai dari timeline. Bedanya, jalanan memberi ruang tubuh untuk hadir, sementara timeline memberi ruang suara untuk bergema. Dua-duanya punya risiko. Di jalan, risiko ditangkap aparat. Di timeline, risiko ditenggelamkan buzzer.
Namun keduanya sama-sama menggerakkan. Viralitas hari ini adalah bensin baru bagi gerakan rakyat. Kita bisa bayangkan, jika mahasiswa 1998 punya Twitter, mungkin Suharto lengser lebih cepat, atau justru lebih lama karena buzzer Orde Baru lebih masif.
Demo 25 Agustus membuktikan bahwa sejarah memang berulang, tapi dengan medium berbeda. Reformasi dulu lahir dengan darah, mungkin kini ia lahir dengan data.
Babak Baru atau Riak Sesaat?
Apakah demo 25 Agustus 2025 akan tercatat sebagai titik balik, atau hanya riak sesaat yang segera tenggelam dalam arus infotainment politik? Tidak ada yang tahu. Sejarah selalu tak terduga.
Tapi ada yang pasti: rakyat Indonesia punya memori panjang. Reformasi 1998 tidak mati, ia hanya tertidur. Dekrit Gus Dur tidak hilang, ia hanya menunggu dipanggil. Dan setiap kali rakyat marah, memori itu kembali hidup, menjadi senjata moral untuk mengingatkan: kedaulatan bukan milik kursi DPR, kedaulatan itu milik rakyat.
Di tengah semua ironi ini, kita hanya bisa mengucap satu kalimat satire:
“Reformasi sudah berumur 27 tahun, tapi DPR masih berperilaku seperti bayi yang doyan susu mahal dan tidur panjang. Bedanya, bayi memang lucu. DPR? Tidak sama sekali.”