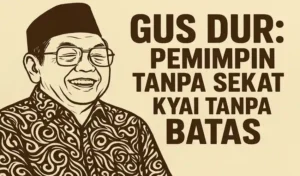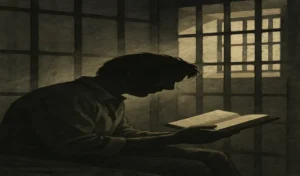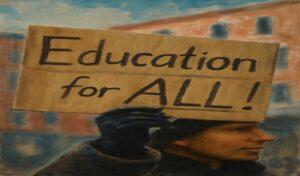Dari Desahan GBK ke Maros: Ketika Keadilan Menunggu Viral

Gelora Bung Karno adalah ikon. Tempat orang joging, tempat atlet mengejar medali, tempat kenangan berserakan antara tawa penonton dan keringat nasionalisme. Tapi siapa sangka, pada suatu pagi yang tak terlalu istimewa, ia berubah menjadi panggung dari suara yang… bagaimana menyebutnya? Mendesah. Suara desahan sensual, terdengar keras dari pengeras suara GBK, menggema di ruang publik tempat orang berolahraga sambil membawa anak-anak. Publik pun terperanjat. Sebagian tertawa geli, sebagian menunduk malu, sisanya merekam, menyebarkan, dan membuatnya viral. Dalam hitungan jam, suara yang tak lazim itu menjadi topik nasional.
Pihak pengelola GBK buru-buru minta maaf. Mereka menyalahkan sistem audio otomatis yang entah bagaimana bisa memutar suara dari playlist bebas hak cipta yang belum diverifikasi. Petugas yang bertanggung jawab langsung diberhentikan, dan sistem pemutaran audio diperketat. Sungguh sebuah ironi, ketika tempat paling megah untuk olahraga justru kalah teliti dibanding playlist YouTube anak-anak. Tapi inilah Indonesia hari ini, di mana kelalaian teknis bisa viral dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Namun jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hanya suara tak senonoh yang bisa membuat publik bergidik. Di Maros, Sulawesi Selatan, seorang pedagang wanita diduga dianiaya oleh oknum TNI AU. Kejadian ini direkam oleh warga dan kemudian menyebar di media sosial. Berbeda dengan kasus GBK yang disambut gelak tawa dan meme, kasus di Maros menimbulkan kemarahan dan kecaman. Seorang perempuan, pelaku ekonomi kecil, ditampar oleh orang berseragam negara. Tak ada playlist di sini, tak ada desahan. Hanya tangan yang terangkat, dan martabat yang terinjak.
TNI AU segera bertindak. Oknum prajurit ditahan oleh Polisi Militer, dan pernyataan resmi segera dikeluarkan. Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap institusi. Tapi seperti biasa, masyarakat bertanya-tanya: jika tidak viral, apakah kasus ini akan diproses secepat itu? Apakah keadilan harus menunggu tren algoritma?
Dua peristiwa ini, walau berbeda konteks dan skala, menunjukkan satu hal yang sama: kita hidup di zaman di mana keadilan seringkali bergantung pada seberapa cepat jempol bekerja di layar ponsel. GBK tak akan secepat itu minta maaf kalau tak ada video yang dibagikan ribuan kali. Oknum TNI mungkin tidak akan ditahan secepat itu jika wajahnya tidak terpampang jelas dalam rekaman warga.
Tentu, suara mendesah tidak bisa disamakan dengan tangan yang menampar. Yang satu kekonyolan teknis, yang satu kekerasan nyata. Tapi keduanya menegaskan lemahnya sistem pencegahan dan respon kita. Dalam kasus GBK, tidak ada SOP yang ketat untuk memeriksa isi playlist. Dalam kasus Maros, pertanyaannya lebih dalam: berapa banyak tindakan kekerasan yang tidak terekam dan karena itu tidak pernah diselesaikan?
Lucunya, kita lebih cepat bereaksi terhadap yang jenaka. Desahan di GBK menjadi candaan nasional. Akun-akun meme berlomba menyunting ulang audio tersebut dengan visual-visual absurd. Kita tertawa. Kita menyebarkan. Lalu kita lupa. Tapi kasus kekerasan? Ia tinggal lebih lama di kepala. Ia membuat kita tidak nyaman. Dan karenanya, kita enggan membicarakannya dengan nada ringan.
Namun, bukan berarti humor tidak boleh hadir. Dalam masyarakat yang letih dengan berita buruk, kadang humor menjadi selimut tipis yang melindungi akal sehat. Tapi kita harus tahu batasnya. Kasus GBK bisa kita ledek sebagai “DJ nasional kepleset playlist”. Tapi kasus Maros bukan bahan guyon. Ia adalah refleksi dari relasi kuasa yang timpang, dan bagaimana orang berseragam bisa dengan mudah mengabaikan batas antara wibawa dan arogansi.
Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, institusi publik harus bekerja lebih cepat dari algoritma viral. Jangan tunggu kasus meledak di media sosial baru bertindak. Kedua, masyarakat perlu terus mengawasi dengan cerdas. Jangan puas hanya dengan minta maaf atau tahan sementara. Proses harus tuntas. Ketiga, humor boleh, tapi jangan biarkan humor menutupi luka. Jangan sampai suara mendesah di GBK mengalihkan perhatian kita dari suara-suara jeritan yang tak sempat terekam di banyak sudut negeri.
Indonesia tidak kekurangan kejadian lucu maupun tragis. Tapi yang lebih penting dari viralitas adalah bagaimana kita, sebagai publik, belajar dari setiap insiden. Apakah kita hanya akan tertawa dan melupakan? Atau kita bisa menjadikan tiap kasus sebagai momentum pembenahan? Kadang, untuk bisa memperbaiki sesuatu, kita memang harus mendengar—entah itu suara desahan yang tak sengaja, atau suara tamparan yang terlalu sering disenyapkan. (*)