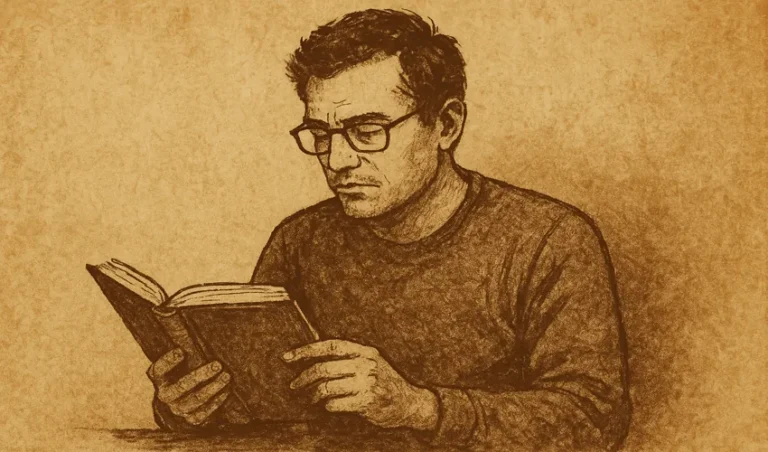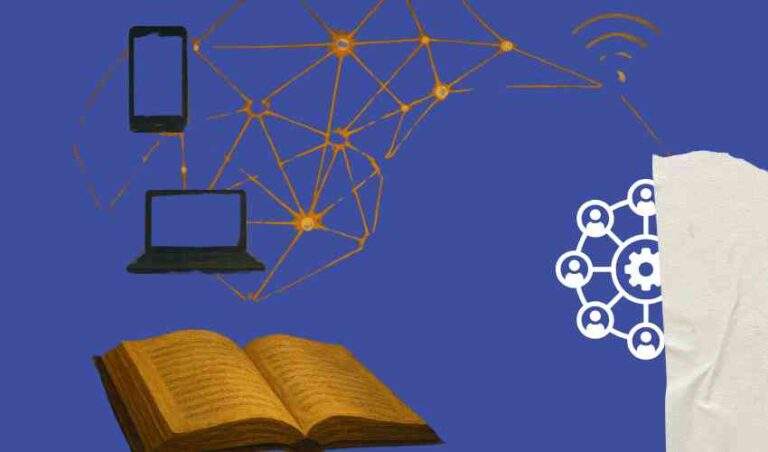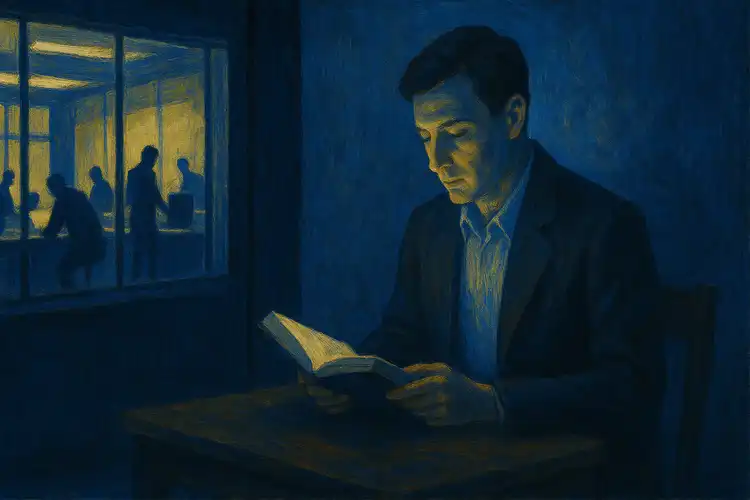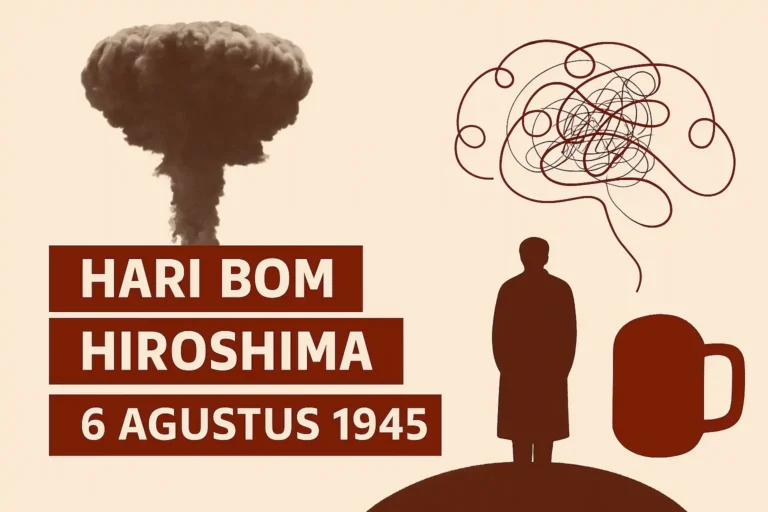Banyak Kebohongan di Gunung

Aku ingat malam sebelum pendakian pertama kali, ketika ransel terasa terlalu besar dan nyali terlalu kecil. Grup percakapan ponsel berdering tanpa henti: tautan video highlight “epic sunrise,” kutipan motivasi berbumbu kitsch—collect moments, not things—dan foto selebritas yang berdiri di bibir kawah sambil memejamkan mata, seolah‑olah menyatukan diri dengan semesta. Kata‑kata itu memompa imajinasi, tapi diam‑diam juga mengusir keraguan kritis: seberapa jujur citra gunung yang dijual di layar kita?
Di era pop culture yang serba dikemas, gunung menjelma panggung estetika. Kamera gawai menjadi juru bicara utama, mampu mengubah batu, lumut, dan kabut menjadi konten garing siap tayang. Kebohongan pertama lahir di sini: gagasan bahwa pendakian adalah paket glamor nan steril—latihan fisik secukupnya, jaket warna neon, tenda ringkas, lalu—voilà—puncak seakan membentang untuk dipijak siapa saja yang menekan tombol “unggah.” Padahal di balik satu foto matahari tersenyum oranye, ada napas terengah, sendi menjerit, kantung plastik sampah, dan kadang tangis marah karena hujan memukul wajah tanpa kompromi.
Kebohongan berikutnya meresap lewat bahasa promosi. Iklan peralatan outdoor menanamkan ilusi “petualang otentik” hanya lahir dari logo tertentu yang menempel di dada. Sementara itu produsen memperbarui katalog empat kali setahun, menciptakan percepatan tren yang membuat ganti‑gear serajin ganti cerita Instagram. Kesadaran ekologis dikutip sebagai tagline—ramah lingkungan, daur ulang, carbon neutral—namun rantai produksi global tetap menambang bahan mentah di tempat lain, meninggalkan jejak karbon menguap bersama kabut pagi yang kita kagumi.
Di pos tiga, ketika embusan angin menggigit, aku melihat sekelompok pendaki muda berebut sinyal demi menyiarkan live story. Mereka mengangkat ponsel lebih tinggi dari kepala rekan yang sedang muntah karena altitude sickness. Tidak ada yang tega mematikan kamera; rasa iba tertukar dengan peluang konten. Gunung berubah jadi studio realitas. Perasaan kagum nan sunyi, yang oleh para pendaki lawas diagungkan sebagai “keramat,” panik mencari tempat berlindung dari pusaran likes dan views. Budaya pop, seperti aliran lava virtual, mengeraskan kerak ego di jalan setapak.
Tentu, gunung selalu memuat mitos dan romansa; sejak nenek‑moyang, puncak adalah altar tempat manusia menantang diri sekaligus memohon ampun. Namun hari ini romantisme dilembagakan oleh pasar. “Mendaki adalah self‑care,” kata poster berwarna pastel. “Puncak adalah ruang healing,” lanjutnya. Jika tidak sampai puncak, apakah proses penyembuhan batal? Narasi ini menyimpan kebohongan halus: ia mendegradasi perjalanan menjadi semata medali pribadi, menutup mata pada realitas ekologi, sejarah konflik lahan, atau hak masyarakat adat yang sejak lama menjaga lereng sembari tak pernah disebut di dalam caption.
Lelah merambat, dan di pos empat kami menemukan tumpukan bungkus mi instan mencuat dari balik batu, saksi bisu janji klise “sampah turun bersama kami.” Kebohongan “leave no trace” rupanya mudah patah oleh dingin subuh dan kantuk. Aku teringat film indie yang menampilkan pahlawan lingkungan, bersih dan bercahaya, padahal di lokasi syuting kru menyisakan potongan kardus dan bekas gaffer tape. Begitu pula pendakian massal bermisi “cinta alam” tetapi diakhiri pesta kembang api—serpihan plastik beterbangan, mendarat entah di aliran sungai desa di bawah.
Ada pula kebohongan tentang maskulinitas gunung: “lelaki sejati harus menaklukkan puncak.” Kalimat itu bergaung di komentator medsos, membenarkan kepongahan. Akibatnya, perempuan pendaki kerap dihadapkan pada tatapan sinis—seolah langkah mereka sekadar pelengkap estetika. Ironisnya, sebagian brand memanfaatkan stereotip sama untuk menjual edisi “girl power” yang dangkal: warna ungu muda, potongan ketat, namun desainnya masih menomorsatukan tampilan dibanding fungsi. Gunung pun menjadi pasar identitas, tempat gender dipoles mengikuti grafik penjualan.
Pada dini hari terakhir, rombongan kami menapak kerikil beku menuju puncak. Bintang belum sempat surut ketika lampu‑lampu headlamp membentuk garis cahaya seperti ular neon. Di depanku, seorang pendaki baru mengirim pesan suara kepada kekasihnya: “Aku sudah hampir puncak; semua indah sekali!” Padahal ia gemetar, bibir biru, oksigen menipis. Keindahan dipaksa hadir sebelum waktunya, demi menepati ekspektasi feed‑media. Kebohongan tentang ketangguhan individu pun lahir—seolah rasa takut harus disembunyikan, padahal gunung lebih menghargai kejujuran tubuh yang mengaku lelah.
Tiba di puncak, matahari memang menari di ufuk, tetapi suara riuh teriakan “selfie dulu!” menenggelamkan kesunyian yang kuharapkan. Tubuh‑tubuh berdesakan mencari sudut tanpa orang lain, agar gambar terlihat sepi dan eksklusif. Di sini, kebohongan paling subtil menampakkan wajah: rindu akan keheningan yang dibunuh oleh hasrat memotret keheningan itu sendiri. Begitu foto didapat, sepi kehilangan nilai—kita turun tergesa, menolak merenung lebih lama karena baterai hampir habis.
Namun, apakah semua di gunung hanyalah kebohongan? Tidak juga. Di sela kabut, masih ada pendaki yang menanam bibit cemara, tim SAR sukarela yang berjaga tanpa pamrih, porter yang menyusuri jalur sunyi untuk memanggul air bersih sambil bersiul lagu dangdut. Mereka adalah pengingat bahwa gunung lebih luas dari lensa kamera, lebih tua dari tren, lebih tabah dari algoritma. Kita hanya perlu merendahkan suara, menekan ego, dan memberi ruang bagi kebenaran alam berbicara: derik serangga, napas tanah basah, gema petir di lembah—semuanya tidak butuh filter.
Ketika turun, lutut protes di setiap tikungan. Hujan rintik membuat jalur licin seperti cermin. Di titik inilah kebohongan boleh runtuh—aku mengakui kelemahan, meminjam tongkat dari porter, dan membagi roti terakhir dengan rekan yang pucat. Tanpa gawai, tanpa slogan, rasanya lebih ringan. Kami tersadar: pendakian bukan tentang memenangi cerita, melainkan memahami batas. Gunung tidak berutang panorama; kitalah yang berutang hormat.
Di kaki gunung, sinyal kembali penuh. Notifikasi mengalir deras: “Bagaimana sunrise‑nya?” “Jangan lupa tag!” Sesaat aku tergoda mengirim foto—mungkin tetap akan kulakukan. Tapi kali ini caption‑nya berbeda: bukan perayaan heroik, melainkan pengakuan rapuh. Bahwa banyak kebohongan di gunung, dan sebagian bersumber dari diri kita sendiri, dari ketakutan terlihat biasa‑biasa saja.
Esai ini kutulis sebagai langkah kecil menahan deras ombak pop culture yang menenggelamkan makna. Jika kita bersedia menukar kebohongan dengan kejujuran—tentang rasa letih, tentang kerusakan, tentang hakikat berbagi ruang—mungkin gunung akan kembali menjadi guru, bukan sekadar latar belakang konten. Dan barangkali, ketika suatu pagi grafis cuaca memprediksi cerah, kita memilih mendaki bukan demi foto, melainkan demi diam, demi merenungi bahwa tidak ada kemenangan yang lebih agung daripada pulang dengan membawa sampah sendiri dan hati yang lebih ringan.