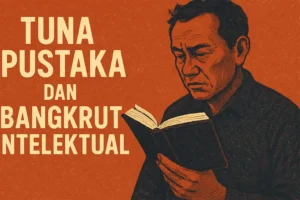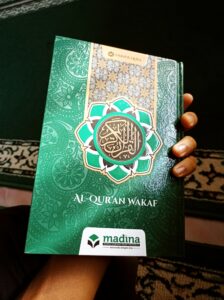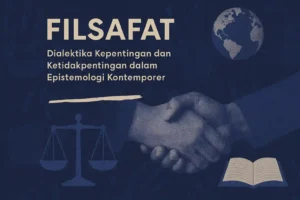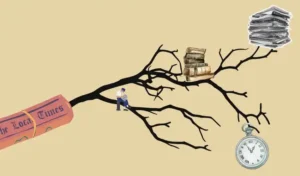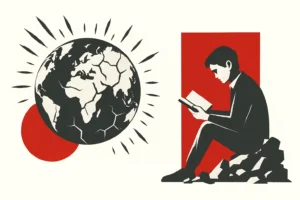AI dan Etika: Renungan Mahasiswa di Era Digital
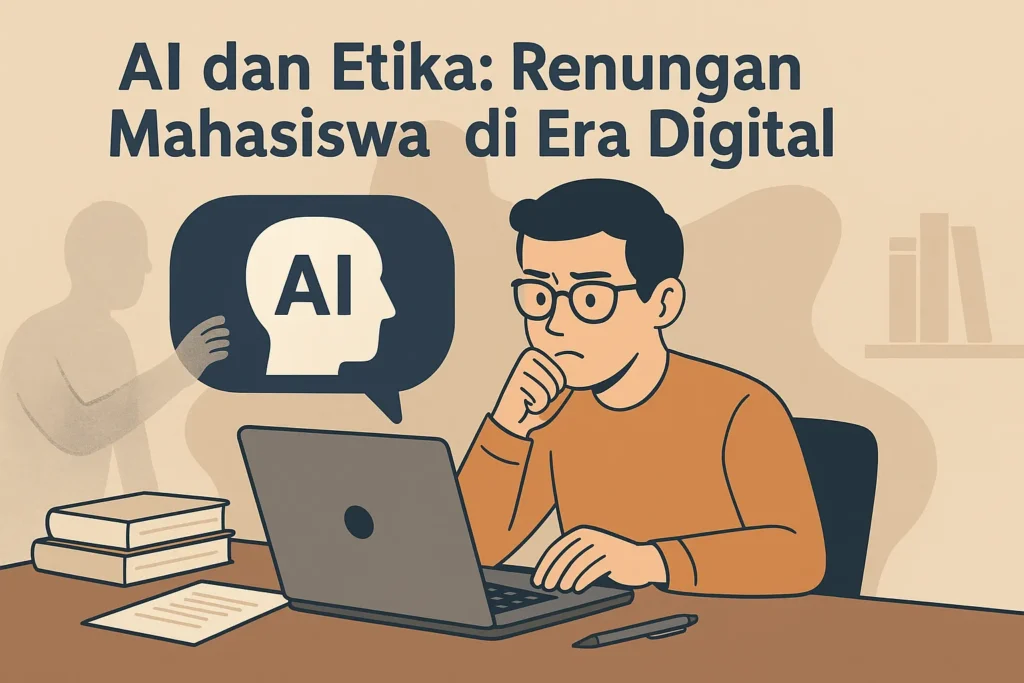
Di tengah gemuruh revolusi digital, kecerdasan buatan hadir sebagai lentera baru dalam jagat pendidikan tinggi. ChatGPT, Grammarly, dan sahabat-sahabat generatif lainnya telah menjadi teman setia mahasiswa: membukakan jalan bagi pemahaman, mempercepat pencarian referensi, merapikan kata, dan merangkai argumen.
Jika digunakan dengan bijaksana dan beretika, AI bukan sekadar alat, melainkan oase pengetahuan yang menyuburkan nalar dan membangkitkan kreativitas. Namun, di balik kemilau kemudahannya, mengintai tantangan yang tak kalah serius.
Banyak mahasiswa tergoda oleh ilusi kecepatan—menyalin mentah hasil dari AI, tanpa menyentuh kedalaman makna, tanpa mencantumkan sumber, tanpa bertanya kembali: “Apakah ini benar?” Ketika mesin bicara dan manusia diam, integritas akademik pun mulai retak.
Kejujuran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap proses belajar tergadaikan di altar kepraktisan. Jika dibiarkan, generasi pembelajar akan berubah menjadi generasi penyalin—mereka yang mengandalkan teknologi, tapi kehilangan jiwanya dalam berpikir.
Sebuah penelitian dari Universitas Padjadjaran tahun 2023 membuka mata: sekitar 60% mahasiswa menerima jawaban dari AI tanpa verifikasi lebih lanjut. Sementara di seberang benua, Profesor Antony Aumann dari Michigan University menemukan esai-esai yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI—tanpa jejak pemikiran mahasiswa. Fenomena ini menguak luka dalam pendidikan: etika perlahan terpinggirkan, digantikan oleh ketergantungan yang tak lagi sehat pada mesin pintar.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sejatinya telah memberi rambu: penggunaan AI harus berpijak pada integritas, transparansi, keamanan, dan tanggung jawab sosial. Namun prinsip-prinsip ini kerap terabaikan saat kecepatan menjadi dewa, dan proses belajar dianggap sekadar pengisi waktu.
Maka, sudah saatnya seluruh sivitas akademika bukan hanya menguasai AI sebagai teknologi, tetapi juga menanamkan etika sebagai landasan utama. AI, pada akhirnya, harus menjadi rekan berpikir, bukan pengganti pikiran itu sendiri.
Dalam buku terkenalnya Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman membagi cara kerja otak manusia menjadi dua: Sistem 1—yang cepat, reflektif, dan instan; serta Sistem 2—yang perlahan, kritis, dan menguras tenaga.
Saat mahasiswa menyodorkan pertanyaan pada AI dan menerima jawaban tanpa tanya balik, mereka menenggelamkan diri dalam kenyamanan Sistem 1. Mereka memilih jalan pintas, membiarkan otak beristirahat, dan membiarkan kemalasan berpikir merayap masuk secara perlahan namun pasti.
AI memberi kita jawaban dalam sekejap, seakan membuka tirai pemahaman. Padahal, di balik kemasan rapi itu, sering kali tersembunyi kekosongan makna.
Mahasiswa pun terjebak dalam ilusi mengerti—seolah tahu, padahal belum sungguh memahami. Jika ini terus terjadi, maka kemalasan kognitif yang disebut Kahneman akan menjadi penyakit sunyi yang menggerogoti kemampuan intelektual mahasiswa—menumpulkan pisau analisis, melemahkan daya refleksi, dan menenggelamkan mereka dalam arus informasi tanpa arah.
Pendidikan tinggi seharusnya mengasah Sistem 2: memicu refleksi, mendorong analisis, dan menumbuhkan pemahaman orisinal. Tapi jika mahasiswa terus dimanja oleh instan, maka proses berpikir akan terasa asing, bahkan melelahkan. Lambat laun, mereka tak hanya kehilangan kemampuan untuk berpikir mendalam, tetapi juga kehilangan keberanian untuk berpikir sendiri.
Namun, beban ini tak sepenuhnya harus dipikul oleh mahasiswa. Dosen, pengajar, dan institusi pun turut memegang kunci. Ketika kampus lebih memuja hasil akhir—angka, nilai, kelulusan—daripada menghargai proses berpikir dan usaha belajar, maka tak heran jika mahasiswa tergoda untuk menyodorkan tugas yang dibisikkan mesin.
Maka, paradigma penilaian pun harus berubah. Bukan hanya menilai apa yang ditulis, tetapi bagaimana mahasiswa sampai pada tulisan itu.
Dosen perlu mengajak mahasiswa untuk menjelaskan proses berpikir mereka, menulis refleksi pribadi, bahkan membuka diskusi tentang bagaimana AI membantu—bukan menggantikan—mereka.
Kampus pun perlu membekali para pengajar dengan kemampuan mendeteksi jejak digital AI, sekaligus menyusun sistem penilaian yang merangkul integritas dan menumbuhkan rasa ingin tahu.
Jika seluruh elemen akademik bersatu dalam semangat ini, maka AI tak lagi menjadi pelarian dari berpikir. Mesin itu akan berubah menjadi jembatan—menghubungkan informasi dengan pemahaman, teknologi dengan etika, dan akhirnya, kecerdasan mesin dengan kebijaksanaan manusia.
Editor: Muhammad Farhan Azizi