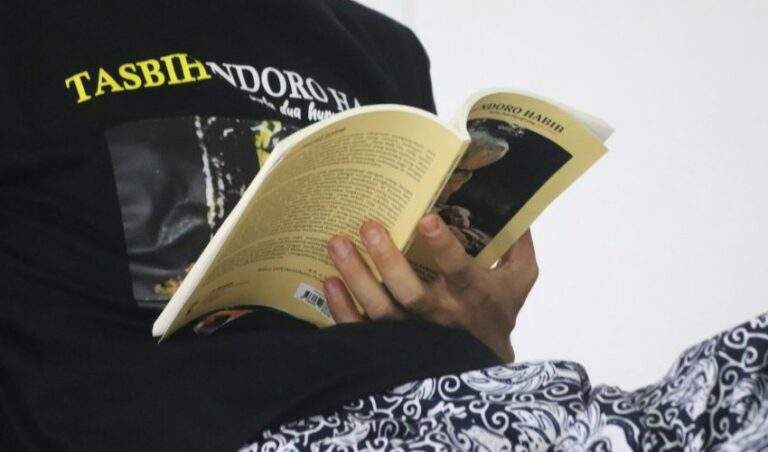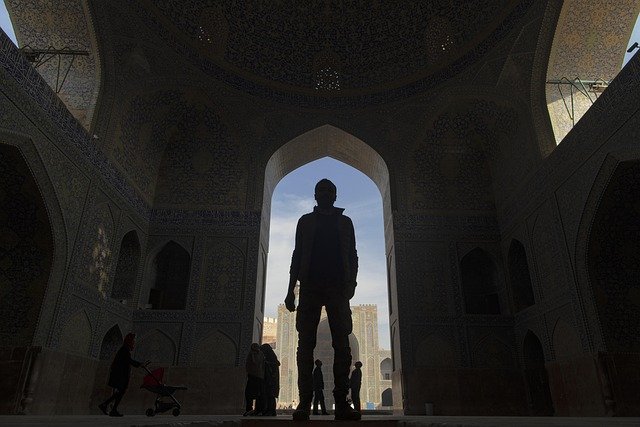Buku, Membaca, dan Kehidupan Sosial Kebangsaan
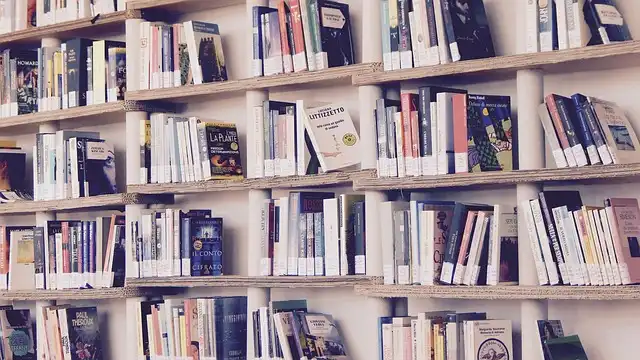
Peristiwa yang terjadi dewasa ini disadari atau tanpa disadari adalah pemutaran rekaman peristiwa masa lalu. Hanya pelaku dan waktunya yang sedikit atau signifikan berbeda. Sementara hubungan dan penyebabnya relatif atau bahkan sama sekali persis. Buku adalah ruang penyimpanan semua peristiwa, dan membaca buku adalah salah satu cara mencermati serta memahami hubungan dan penyebab terjadinya peristiwa itu.
Saat ini, kita hampir tak pernah ketinggalan segala bentuk peristiwa yang terjadi melalui pemberitaan di media massa maupun media sosial. Mulai dari demo hingga kerusuhan yang terjadi bulan lalu, keracunan MBG, sekolah rakyat, korupsi, rubuhnya gedung pesantren, boikot trans7 dan sebagainya. Sebagian atau semua pembaca pasti mengetahui seluruh peristiwa tersebut.
Namun, di antara sekian banyak peristiwa tersebut, pernahkah buku sebagai ruang menyimpan semua peristiwa menjadi perbincangan serius dalam kehidupan sosial Indonesia? Iya, pernah. Tetapi, hanya sebagai barang sitaan Aparat karena dianggap membahayakan. Sedangkan, buku yang dianggap tidak membahayakan sama sekali tidak pernah menjadi perbincangan.
Indonesia atau negara berkembang lain di seluruh penjuru dunia, di mana demokrasi menjadi barang antik sebagai wacana, tetapi tabu sebagai praktik, buku seharusnya hadir sebagai tayangan prioritas di media massa arus utama—koran, radio, dan tv. Namun, realitasnya buku seolah mayat yang dikubur dalam-dalam. Sementara membaca buku menjadi kegiatan tidak digemari, bahkan dianggap membahayakan.
Bukti tidak dianggappentingnya buku atau membacanya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperka) di daerah-daerah kerap menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) “pembuangan”. Tidak strategis, karena cenderung sangat kurang dalam anggaran. Jika cermati, sekolah tanpa perpustakaan apalagi buku hanyalah taman kanak-kanak.
Berdasarkan ulasan sederhana dalam pembukaan tulisan ini, maka membuka ruang untuk membahas buku, membaca dan kaitannya dengan kehidupan bersosial atau berbangsa setidaknya menjadi kebutuhan yang perlu diulas dalam tulisan ini. Terdapat beberapa hasil riset yang menunjukkan bahwa betapa penting membaca buku.
Di banyak sekolah dasar di Indonesia, membaca bukan sekadar materi pelajaran; ia menjadi kunci membuka pintu pemahaman, kecerdasan berbahasa, dan daya literasi yang kelak menentukan keberhasilan akademik. Penelitian di SDN Kebun 1 misalnya, menunjukkan bahwa kebiasaan membaca berpengaruh nyata terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas 4. Anak-anak dengan kebiasaan membaca yang lebih sering secara konsisten menunjukkan performa lebih baik dalam pemahaman materi, kosa kata, dan kemampuan menyusun kalimat.
Di Aceh Besar, sebuah studi yang memfokuskan pada taman baca atau “reading corner” pada pendidikan anak usia dini menemukan bahwa ruang baca interaktif dan berbasis permainan dapat meningkatkan secara signifikan keterlibatan anak dalam kegiatan literasi: mereka lebih termotivasi membaca, lebih mampu memahami bacaan, dan menunjukkan peningkatan dalam kemampuan menulis serta berhitung. Kenikmatan membaca dan rasa penasaran yang muncul di lingkungan membaca tersebut terlihat memicu proses belajar yang lebih aktif.
Penelitian tentang membaca fiksi juga menunjukkan korelasi antara kemampuan membaca fiksi dan kemampuan menulis cerpen di kalangan siswa SMP. Di SMP Negeri 1 Kecamatan Pangkalan, ditemukan bahwa siswa yang memiliki keterampilan membaca fiksi yang baik cenderung menulis cerpen dengan kualitas yang lebih baik—terutama dalam aspek ide cerita, struktur narasi, dan pemilihan bahasa. Dari hasil analisis, semakin sering membaca fiksi, semakin kuat kemampuan menulis kreatif siswa, termasuk kemampuan mereka untuk berimajinasi dan merangkai ide dengan cara yang menarik.
Di tingkat perguruan tinggi, penelitian di Universitas Hamzanwadi mengenai mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (semester 6) memperlihatkan bahwa membaca bukan hanya soal memperkaya kosakata atau memahami teks, tetapi juga memperkuat keterampilan berpikir kritis. Mahasiswa yang rutin membaca cenderung lebih mampu menganalisis teks, membandingkan sudut pandang, dan menggunakan argumen yang lebih kuat dalam diskusi akademik. Selain itu, membaca juga meningkatkan kemampuan sosial dan partisipasi—baik di ruang kelas maupun di luar kelas—karena siswa mampu berbicara lebih ekspresif, ikut berdiskusi, dan merasa memiliki landasan literasi yang cukup untuk menyumbangkan ide.
Tapi sekalipun manfaatnya jelas, banyak studi lokal mengungkap bahwa budaya membaca di Indonesia masih belum optimal. Di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, survei terhadap ratusan mahasiswa mengungkap bahwa hanya sekitar 38% mengaku memiliki kebiasaan membaca secara reguler, sementara sebagian besar sisanya hanya membaca ketika diwajibkan tugas, atau bahkan tidak yakin apakah mereka punya kebiasaan membaca aktif atau tidak. Waktu yang dihabiskan untuk membaca juga relatif singkat, seringkali kurang dari satu jam per hari.
Faktor-eksternal dan internal turut menjadi penghambat. Akses ke buku bermutu di beberapa daerah masih terbatas; motivasi pribadi terkadang lemah; perangkat digital dan hiburan instan menjadi pesaing kuat bagi waktu membaca yang lebih mendalam. Seringkali bacaan yang diakses adalah bacaan dangkal atau bacaan yang disediakan untuk tugas semata, bukan bacaan yang dipilih atas dasar minat, yang dapat memberikan kenikmatan, refleksi, dan rangsangan imajinatif.
Meski begitu, usaha‐usaha kecil dan program lokal menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Di Medan, program literasi membaca buku fiksi di SMP Negeri 11 menunjukkan bahwa literasi membaca (khususnya fiksi) membantu siswa dalam memperluas wawasan, memperkuat bahasa, meningkatkan daya imajinatif, bahkan membantu siswa dalam memahami moral dan nilai dalam teks. Program tersebut juga memberi peluang untuk siswa yang sebelumnya kurang tertarik berubah pola pikirnya terhadap membaca: bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi aktivitas yang menyenangkan dan bermakna.
“Peran minat baca” pun tidak bisa diabaikan. Di tingkat SD, studi tentang pengaruh minat membaca terhadap prestasi Bahasa Indonesia menemukan bahwa siswa dengan minat baca yang tinggi cenderung memiliki nilai yang lebih baik, baik dalam memahami bacaan, mengerjakan tugas, maupun mengikuti pelajaran di kelas. Minat baca seringkali menjadi pendorong agar siswa mau meluangkan waktu, mencari bacaan sendiri, dan terus mempraktikkan membaca di luar konteks tugas sekolah.
Metode pembelajaran juga terbukti penting. Sebagai contoh, program “morning literacy” yang diterapkan di SMP Negeri 6 Semarang berhasil meningkatkan kemampuan memahami bacaan siswa. Dengan kegiatan literasi pagi—baca bersama, diskusi singkat, atau kegiatan membaca terpandu—siswa jadi lebih siap menghadapi pelajaran hari itu, kemampuan pemahaman teks meningkat, diskusi kelas menjadi lebih hidup, dan antusiasme terhadap bacaan mulai terlihat.
Dalam konteks perkembangan empati sejak usia dini, metode dialogic reading terbukti efektif di antara anak usia 3-4 tahun. Saat guru atau orang tua membaca cerita bergambar dan secara aktif mengajak anak berdiskusi—bertanya “bagaimana perasaan karakter dalam cerita?”, “kenapa dia melakukan itu?”, “apa yang kamu lakukan kalau kamu di posisinya?”—anak menjadi lebih peka terhadap emosi orang lain, mampu memahami perspektif selain miliknya sendiri. Ini penting karena empati pada usia awal sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan moral, cara anak berinteraksi di sekolah dan di rumah.
Melihat keseluruhan temuan ini, beberapa hal penting muncul sebagai kesimpulan yang relevan untuk masa depan.
Pertama, manfaat membaca di Indonesia tidak bersifat konseptual saja; bukti empiris menunjukkan bahwa membaca memperkuat hasil belajar, meningkatkan keterampilan bahasa (membaca, menulis, kosa kata), membantu kemampuan berpikir kritis, dan membangun empati sejak usia dini.
Kedua, untuk memaksimalkan manfaat tersebut, perlu adanya dukungan sistemik: infrastruktur baca (akses buku berkualitas), waktu dan ruang membaca, budaya literasi di rumah dan sekolah, serta metode membaca yang interaktif dan reflektif (seperti dialogic reading, membaca bersama, diskusi bacaan).
Ketiga, pentingnya motivasi dan minat baca: tanpa keinginan pribadi dan kesenangan dalam membaca, kegiatan membaca bisa menjadi beban, bukan sumber kekayaan batin. Bila membaca dipaksakan sebagai tugas tanpa dipilih berdasarkan minat, efeknya mungkin kurang optimal.
Keempat, program-kecil yang baik—membaca pagi, pojok baca, pelibatan guru/orang tua—bisa menjadi katalis untuk perubahan budaya literasi yang lebih luas.
Jika penulis boleh beropini, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan membaca bukan hanya sebagai alat akademik, tetapi sebagai sarana transformasi sosial dan pribadi. Dengan memperkuat budaya literasi sejak usia dini, menyediakan bacaan menarik dan sesuai minat, serta menjadikan membaca sebagai ritual rutin (bukan sekadar tugas sekolah), kita bisa melihat generasi yang tidak hanya mampu membaca dengan baik tetapi juga berpikir kritis, menghargai orang lain lebih dalam, dan memiliki kapasitas untuk menghadapi kompleksitas dunia.
Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan kolaborasi: kebijakan pemerintah yang mendukung akses buku, kurikulum yang memberi ruang dan kebebasan memilih bacaan, guru yang terlatih untuk memfasilitasi kegiatan membaca interaktif, dan tentu rumah yang mendukung dengan menyediakan bacaan, waktu, serta contoh membaca. Jika semua elemen ini bekerja bersama, membaca akan berkembang dari aktivitas pasif menjadi denyut kehidupan budaya kita—dan dari situ manfaatnya tidak hanya terasa di sekolah, tetapi dalam keseharian: bagaimana kita berpikir, berempati, membuat keputusan, dan berinteraksi satu sama lain.
Daftar Pustaka
Aini, M., & Usman, F. (2023). Hubungan keterampilan membaca fiksi dengan kemampuan menulis cerpen siswa SMP Negeri 1 Kecamatan Pangkalan. Jurnal Kande, Universitas Malikussaleh. Diakses dari https://ojs.unimal.ac.id/index.php/kande/article/view/3409
Atma Jaya Yogyakarta University. (2024). Survei kebiasaan membaca mahasiswa di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. LATTE Journal. Diakses dari https://ojs.uajy.ac.id/index.php/latte/article/view/11658
Baylor College of Medicine. (2023). Mindful reading and mental health. Diakses dari https://www.bcm.edu/news/mindful-reading-and-mental-health
Frontiers in Public Health. (2022). Reading habits and health outcomes among older adults in China: Evidence from the Chinese General Social Survey. Frontiers in Public Health, 10, 1031939. https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2022.1031939/full
Jannah, R., & Hidayat, R. (2023). Peran pojok baca terhadap peningkatan kemampuan literasi anak usia dini di Aceh Besar. Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, UIN Sunan Kalijaga. Diakses dari https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/goldenage/article/view/213-223
Khotimah, S. (2023). The effect of reading activity on cognitive function in older adults: A longitudinal study. Alzheimer’s Research & Therapy, 14(11), 98. https://alzres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13195-022-01098-1
Lewis, D. (2009). Reading can help reduce stress by up to 68 percent. Mindlab International, University of Sussex. Dikutip melalui Mental Health First Aid England. https://mhfaengland.org/mhfa-centre/blog/reading-good-mental-health
Liu, Q., Zhang, L., & Li, X. (2024). Reading habits causally shape brain structure: Evidence from Mendelian randomization. Frontiers in Neuroscience, 18, 10953555. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10953555
Mansur, A., & Rahmawati, L. (2024). Pengaruh minat membaca terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV SDN Kebun 1. IJoBE (Indonesian Journal of Basic Education), STKIP Rokania. Diakses dari https://e-jurnal.stkiprokania.ac.id/index.php/IJOBE/article/view/693
Mental Health First Aid England. (2021). Reading is good for your mental health. https://mhfaengland.org/mhfa-centre/blog/reading-good-mental-health
Muslimah, D. (2023). Peran literasi membaca buku fiksi terhadap peningkatan kemampuan berbahasa siswa SMP Negeri 11 Medan. Jurnal Pendas, Universitas Pasundan. Diakses dari https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/29572
Nugroho, S., & Rahmatika, N. (2024). Penerapan program literasi pagi terhadap kemampuan memahami bacaan siswa di SMP Negeri 6 Semarang. EJCEEL (Educational Journal of Contemporary Education and Learning). Diakses dari https://ejceel.com/index.php/journal/article/view/197
Puspita, E., & Darmayanti, F. (2023). Dialogic reading untuk mengembangkan empati anak usia dini: Studi di Kota Malang. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Teknologi (JIPT), Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses dari https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/5212
Sari, D., & Lestari, R. (2024). Kebiasaan membaca dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Jurnal Pendidikan Indonesia (JAPENDI). https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/8547
Sungkono, H. (2024). Reading as lifelong health: Correlation between reading frequency, neurocognition, and physical health. Frontiers in Aging Neuroscience, 16, 11303134. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11303134
Taylor, M., & Mar, R. A. (2016). Reading fiction and empathy: Evidence for long-term effects. Psychological Science, 27(3), 1–9. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4733342
Verghese, J., et al. (2016). A Chapter a Day: Association between book reading and longevity. Social Science & Medicine, 164, 44–53. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5105607
Verywell Health. (2024). The science-backed benefits of reading for sleep and stress reduction. https://www.verywellhealth.com/benefits-of-reading-8723145
Widodo, B., & Putri, F. (2024). Pengaruh minat membaca terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia siswa SDN Kebun 1. JIRPE (Jurnal Inovasi Riset Pendidikan dan Edukasi), Papanda Institute. Diakses dari https://ejournal.papanda.org/index.php/jirpe/article/view/2004
Zhao, M., & Chen, H. (2024). Four reading styles and their effects on mental health and quality of life among university students. Frontiers in Psychology, 15, 11355533. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11355533