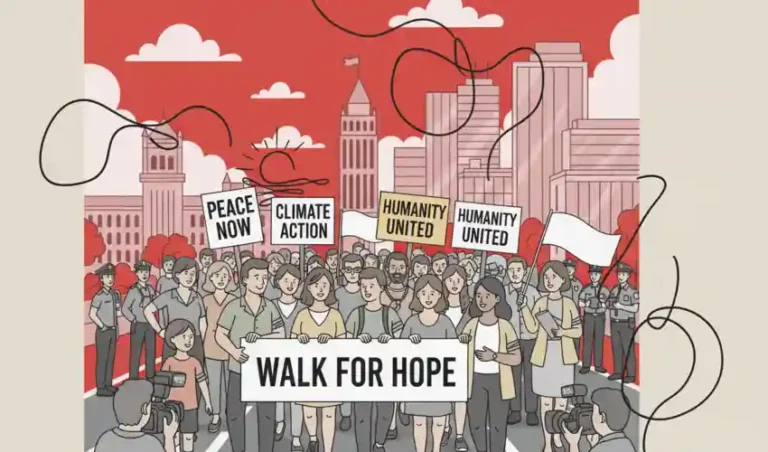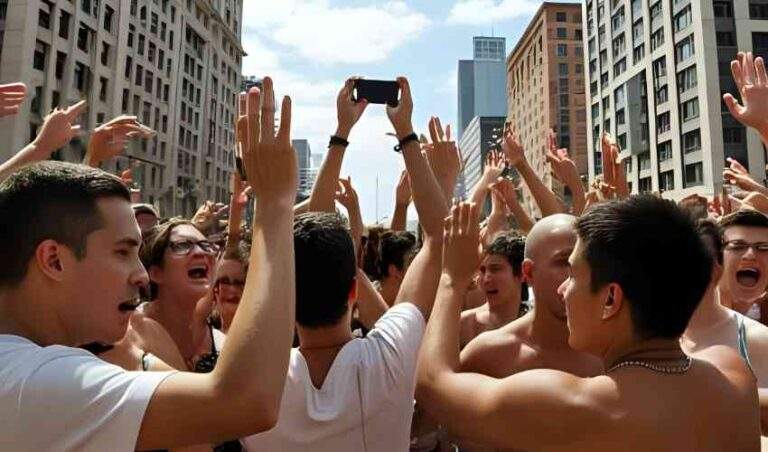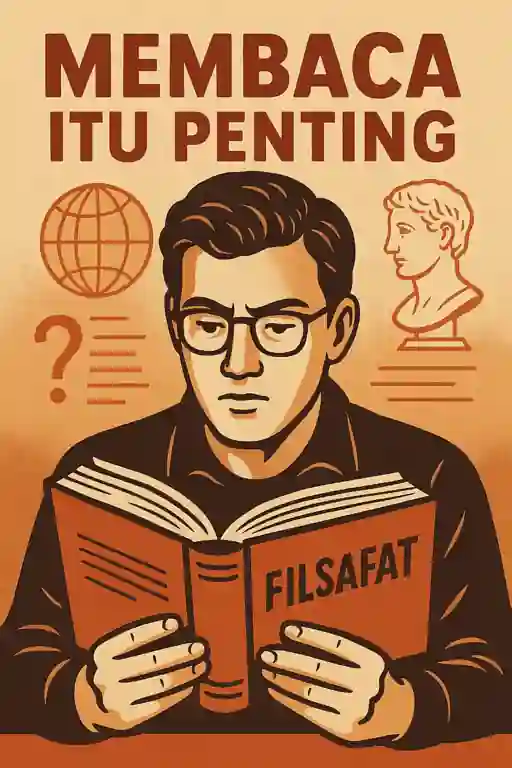Boikot Trans7 dan Martabat Pesantren

Gelombang boikot terhadap Trans7 pada Oktober 2025 menjadi cermin besar bagi relasi antara media modern dan dunia pesantren yang telah menjadi fondasi moral bangsa. Tayangan Xpose Uncensored yang menyinggung kiai dan kehidupan santri memantik reaksi keras publik. Potongan video yang menggambarkan kiai secara satir dianggap melecehkan simbol religius, sehingga memicu seruan boikot di media sosial, demonstrasi di depan gedung Transmedia, serta desakan dari berbagai organisasi keagamaan agar stasiun televisi bertanggung jawab. Bagi sebagian orang kota yang terbiasa dengan humor televisi, reaksi ini mungkin tampak berlebihan. Namun bagi kalangan pesantren, apa yang ditampilkan bukan sekadar lelucon—melainkan penghinaan terhadap tata nilai yang dijaga turun-temurun.
Peristiwa ini bukan hanya kesalahan produksi program hiburan, tetapi menunjukkan adanya krisis empati kultural dalam industri media kita. Televisi yang semestinya menjadi jembatan antarbudaya justru menjadi sumber luka simbolik. Dalam satu tayangan, terjadi benturan antara logika industri yang mengejar rating dan logika moral masyarakat yang menjunjung kehormatan. Konflik ini mengguncang kesadaran kolektif kita tentang bagaimana modernitas seharusnya dijalankan di negeri yang plural, religius, dan berakar kuat pada tradisi pesantren.
Untuk memahami kedalaman reaksi masyarakat terhadap tayangan itu, kita perlu menengok ke akar konseptual yang telah lama dijelaskan oleh Zamakhsyari Dhofier dalam karyanya Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai. Dhofier menulis bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga “subkultur” yang menanamkan sistem nilai, hierarki moral, dan tatanan sosial yang khas. Di dalam pesantren, hubungan antara santri dan kiai dibangun atas dasar adab, bukan sekadar instruksi. Kiai bukan figur administratif, melainkan simbol moral dan spiritual. Ketika kiai diperlakukan dengan nada sinis di ruang publik, komunitas pesantren merasa bahwa bukan hanya individu yang dilecehkan, melainkan seluruh sistem nilai yang menopang kehidupan mereka.
Dalam kerangka inilah, kemarahan publik terhadap tayangan Xpose Uncensored menjadi sangat masuk akal. Pesantren telah lama menjadi ruang pembentukan karakter bangsa, tempat di mana kesabaran, kesederhanaan, dan penghormatan pada ilmu menjadi pilar. Melalui ribuan pondok di seluruh nusantara, pesantren menjaga kesinambungan Islam kultural yang santun dan inklusif. Maka, merendahkan simbol pesantren sama artinya dengan menodai akar moral bangsa itu sendiri. Dalam pandangan Dhofier, otoritas kiai bukan dibangun oleh kekuasaan, melainkan oleh keteladanan. Ia adalah figur yang menghubungkan langit pengetahuan dengan bumi kehidupan masyarakat. Karena itu, penghinaan terhadap kiai menimbulkan luka sosial yang lebih dalam daripada sekadar persoalan citra di layar televisi.
Namun di sisi lain, pemikiran Nurcholish Madjid memberi dimensi reflektif yang sama pentingnya. Dalam berbagai esainya tentang Islam dan modernitas, Nurcholish menegaskan bahwa umat Islam perlu membuka diri terhadap rasionalitas dan perubahan zaman tanpa kehilangan kompas moralnya. Modernitas, bagi Cak Nur, bukan sekadar soal teknologi dan kebebasan, tetapi soal bagaimana kebebasan itu dikelola dengan tanggung jawab. Dalam konteks media, kebebasan berekspresi tidak bisa dijadikan alasan untuk menyinggung keyakinan publik. Keterbukaan yang tanpa etika justru melahirkan anarki simbolik: semua hal boleh ditertawakan, tetapi tidak ada lagi yang dihormati.
Cak Nur sering mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdialog antara tradisi dan kemajuan. Jika pesantren adalah wujud kearifan tradisi, maka media modern adalah wujud kemajuan. Konflik antara keduanya tidak perlu berakhir dengan saling curiga, melainkan bisa menjadi titik temu untuk membangun peradaban yang beradab. Sayangnya, logika ekonomi media yang terlalu menekankan sensasi sering mengabaikan prinsip ini. Tayangan dibuat bukan untuk mencerdaskan, tetapi untuk memancing emosi. Dalam situasi seperti itu, modernitas kehilangan jiwanya, dan media berubah menjadi alat konsumsi emosi massal yang dangkal.
Dari perspektif etika sosial, reaksi keras publik terhadap Trans7 adalah bentuk pertahanan diri masyarakat terhadap banalitas media. Pesantren, yang selama ini identik dengan kesabaran dan kesederhanaan, kini menunjukkan ketegasan moralnya. Mereka menegaskan bahwa ada batas antara kebebasan dan pelecehan, antara kritik dan penghinaan. Dalam masyarakat yang majemuk, garis batas ini penting untuk menjaga keharmonisan. Jika media kehilangan kepekaan kultural, maka ruang publik akan dipenuhi luka simbolik yang pada akhirnya merusak kepercayaan sosial.
Namun kita juga perlu berhati-hati agar kritik terhadap media tidak berubah menjadi sensor terhadap kebebasan. Seperti yang diingatkan Nurcholish, keterbukaan adalah syarat utama bagi kemajuan pemikiran. Persoalannya bukan pada kebebasan itu sendiri, melainkan pada cara kebebasan digunakan. Media perlu mendidik diri agar cerdas dalam membedakan kritik sosial dengan penghinaan simbolik. Kritik terhadap praktik-praktik keagamaan boleh saja, tetapi harus dilakukan dengan niat edukatif dan cara yang etis. Inilah tantangan sejati modernitas: bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
Kasus boikot Trans7 juga memperlihatkan perubahan lanskap kekuasaan dalam dunia komunikasi. Dahulu, media besar bisa mendikte opini publik; kini, publik memiliki kekuatan balik untuk mengontrol media melalui jejaring sosial. Dalam hitungan jam, seruan boikot menyebar ke seluruh negeri, menekan stasiun televisi untuk meminta maaf secara terbuka. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat pesantren bukan lagi penonton pasif. Mereka telah memasuki ruang digital dengan identitasnya sendiri, dan siap menegur siapa pun yang menistakan simbol moral mereka. Ini adalah bentuk “emansipasi kultural” yang menegaskan bahwa kekuatan moral tradisional masih sangat hidup di era modern.
Dari perspektif akademik, kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi industri penyiaran. Media yang ingin bertahan di tengah masyarakat religius seperti Indonesia tidak cukup hanya profesional secara teknis, tetapi juga harus memiliki kepekaan etis. Program pelatihan jurnalisme budaya, dialog antara pekerja media dan tokoh agama, serta pedoman representasi kelompok keagamaan menjadi keharusan. Dengan cara itu, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial. Sebab, di negeri yang plural seperti Indonesia, kesalahan simbolik sekecil apa pun bisa berimplikasi besar terhadap kohesi sosial.
Dari sisi pesantren sendiri, momentum ini bisa dijadikan refleksi untuk memperkuat literasi media di kalangan santri. Di era digital, dakwah tidak lagi hanya dilakukan dari mimbar, tetapi juga dari layar. Pesantren memiliki modal moral dan intelektual yang besar untuk menampilkan wajah Islam yang ramah dan cerdas di ruang publik. Alih-alih menjauh dari media, pesantren justru perlu masuk ke dalamnya untuk mengisi ruang-ruang yang kosong dengan nilai-nilai kebajikan. Dengan demikian, hubungan antara pesantren dan media dapat bertransformasi dari konflik menjadi kolaborasi.
Boikot Trans7 pada akhirnya bukan sekadar soal satu tayangan yang menyinggung perasaan. Ia adalah refleksi mendalam tentang arah moral bangsa. Kita diingatkan bahwa kebebasan berekspresi tanpa empati adalah bentuk lain dari keangkuhan intelektual. Kita juga belajar bahwa tradisi bukanlah penghalang kemajuan, tetapi sumber kebijaksanaan untuk menuntun arah perubahan. Dhofier mengajarkan kita pentingnya memahami kedalaman tradisi, sementara Nurcholish mengingatkan agar modernitas dijalankan dengan akal sehat dan tanggung jawab moral. Jika dua warisan pemikiran ini dijalankan bersama, Indonesia akan memiliki ruang publik yang sehat: bebas namun beradab, terbuka namun tetap menghormati akar moralnya.
Kasus ini harus menjadi pelajaran terakhir bagi media yang sering bermain-main di wilayah sensitif. Dunia hiburan boleh kreatif, tetapi tidak boleh kehilangan hati nurani. Kita semua, baik jurnalis, pendidik, maupun penonton, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga ruang publik agar tetap bermartabat. Ketika media kehilangan empatinya, maka masyarakatlah yang harus mengembalikannya. Dan dalam hal ini, pesantren sekali lagi membuktikan dirinya bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi penjaga moral yang masih relevan di tengah hiruk-pikuk modernitas.