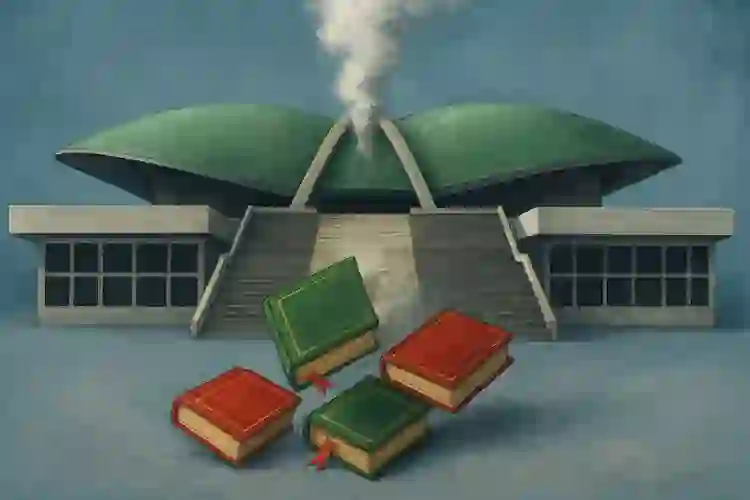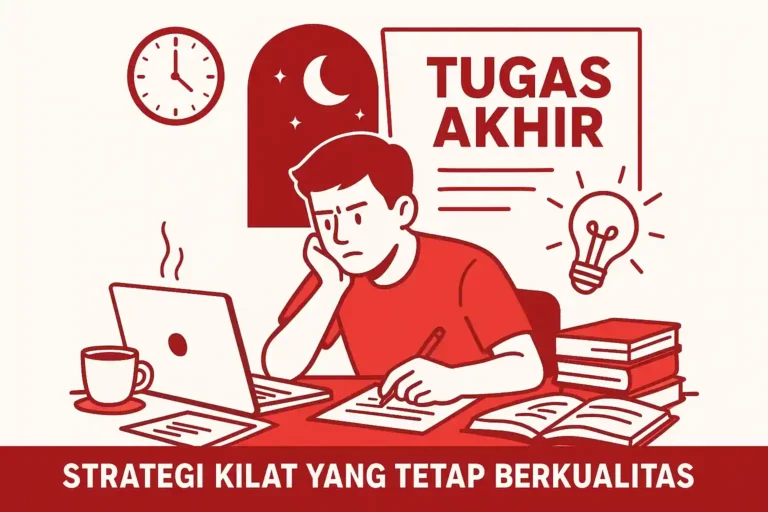Dua Wajah Tunjangan Guru: Sejahtera di Dompet, Lesu di Kelas
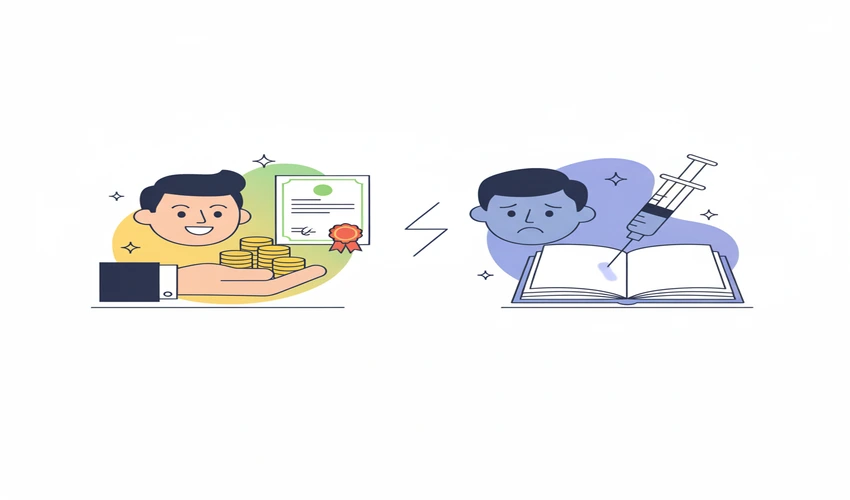
Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi sebuah tonggak sejarah dalam dunia pendidikan Indonesia. Salah satu amanat paling fundamental dari regulasi ini adalah pengakuan guru sebagai profesi yang menuntut kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi tinggi. Sebagai kompensasi atas tuntutan tersebut, pemerintah meluncurkan program Tunjangan Profesi Guru (TPG), sebuah kebijakan ambisius yang dirancang untuk mencapai dua tujuan mulia secara simultan: meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong peningkatan profesionalisme mereka, yang pada akhirnya diharapkan bermuara pada peningkatan mutu hasil belajar siswa. Setelah lebih dari satu dekade implementasinya, program yang menyerap porsi signifikan dari anggaran pendidikan nasional ini terus menjadi subjek perdebatan dan analisis. Berbagai riset dari lembaga kredibel, baik nasional maupun internasional, telah mencoba membedah efektivitas dan dampak kebijakan ini. Analisis ini akan mengupas secara naratif temuan-temuan kunci dari riset tersebut, menelusuri jejak TPG dari tujuannya yang luhur hingga realitas implementasinya yang kompleks di lapangan.
Pada tataran paling awal dan paling kasat mata, riset secara konsisten menunjukkan bahwa TPG berhasil secara signifikan dalam mencapai tujuan pertamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan guru. Sebelum adanya kebijakan ini, profesi guru sering kali identik dengan pengabdian yang berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi. TPG, yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok, menjadi angin segar yang mengubah lanskap finansial para pendidik. Studi yang dilakukan oleh lembaga seperti The SMERU Research Institute dan Bank Dunia mengonfirmasi bahwa tunjangan ini secara nyata meningkatkan pendapatan dan daya beli guru. Peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, tetapi juga pada peningkatan status sosial guru di tengah masyarakat. Motivasi dan kepuasan kerja pun terbukti mengalami peningkatan. Guru merasa lebih dihargai, tingkat stres finansial menurun, dan mereka dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas mengajarnya tanpa harus dibebani oleh pencarian pekerjaan sampingan untuk menopang ekonomi keluarga. Dari perspektif ini, TPG adalah sebuah intervensi kebijakan yang sukses besar, menjadikannya salah satu program transfer tunai bersasaran (targeted cash transfer) terbesar dan paling berdampak di Indonesia.
Namun, keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan tidak secara otomatis berjalan linear dengan pencapaian tujuan kedua, yaitu peningkatan profesionalisme dan kompetensi. Inilah titik di mana berbagai hasil riset mulai menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks dan bahkan kontradiktif. Asumsi dasar kebijakan ini adalah bahwa guru yang lebih sejahtera akan termotivasi untuk menginvestasikan lebih banyak waktu, tenaga, dan bahkan sumber daya finansialnya untuk pengembangan diri. Namun, bukti di lapangan tidak sepenuhnya mendukung asumsi ideal ini. Salah satu sorotan utama jatuh pada mekanisme gerbang masuk untuk mendapatkan TPG, yaitu proses sertifikasi guru. Pada awalnya, proses ini banyak mengandalkan penilaian portofolio, yang menurut banyak kajian, terbukti lemah dalam menyaring dan mengukur kompetensi guru secara akurat. Proses ini rentan terhadap praktik-praktik tidak jujur dan lebih bersifat administratif daripada substantif. Meskipun kemudian beralih ke model Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan kini Pendidikan Profesi Guru (PPG), tantangan untuk memastikan bahwa sertifikat pendidik benar-benar merefleksikan kualitas pengajaran yang unggul masih terus ada. Akibatnya, banyak riset menemukan tidak adanya perbedaan kinerja yang signifikan antara guru yang telah menerima TPG dengan mereka yang belum, ketika diukur melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) atau metode evaluasi kinerja lainnya.
Persoalan ini membawa kita pada pertanyaan paling krusial: apakah TPG berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas dan hasil belajar siswa? Ini adalah muara akhir yang ingin dicapai, namun sekaligus menjadi mata rantai yang paling lemah dalam argumen efektivitas TPG. Sejumlah studi kuantitatif berskala besar yang mencoba menghubungkan status penerimaan TPG seorang guru dengan nilai ujian siswanya secara konsisten menemukan hasil yang mengecewakan. Riset yang dipublikasikan oleh Bank Dunia, misalnya, menyimpulkan bahwa tidak ada bukti statistik yang kuat yang menunjukkan bahwa siswa yang diajar oleh guru bersertifikat dan menerima TPG memiliki pencapaian akademis yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang diajar oleh guru non-sertifikasi. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian lain di tingkat nasional.
Ada beberapa hipotesis yang diajukan oleh para peneliti untuk menjelaskan “keterputusan” antara peningkatan kesejahteraan guru dan hasil belajar siswa ini. Pertama, seperti yang telah disinggung, proses sertifikasi mungkin belum efektif sebagai filter kualitas. Sertifikasi lebih dilihat sebagai hak yang harus dikejar untuk mendapatkan tunjangan, bukan sebagai puncak dari sebuah proses pengembangan profesional yang berkelanjutan. Kedua, tambahan pendapatan dari TPG tidak selalu dialokasikan untuk kegiatan yang secara langsung meningkatkan kualitas mengajar, seperti membeli buku referensi, mengikuti seminar, atau mengembangkan media pembelajaran inovatif. Sebagian besar mungkin digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau investasi lain yang tidak terkait langsung dengan profesi. Ketiga, faktor-faktor lain di luar guru, seperti kurikulum, fasilitas sekolah, dukungan manajemen sekolah, dan latar belakang sosio-ekonomi siswa, mungkin memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap prestasi akademis. Dengan demikian, meningkatkan kualitas guru saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan perbaikan pada komponen ekosistem pendidikan lainnya.
Lebih jauh lagi, implementasi kebijakan TPG di lapangan juga melahirkan serangkaian tantangan dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Salah satu yang paling sering dikritik adalah persyaratan beban kerja mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu. Aturan ini, pada praktiknya, sering kali memaksa guru untuk mengambil jam mengajar di luar bidang keahliannya (mengajar mata pelajaran yang tidak linear) hanya untuk memenuhi kuota. Alih-alih mendorong fokus dan pendalaman materi, aturan ini justru berpotensi menurunkan kualitas pengajaran. Di daerah-daerah dengan jumlah siswa terbatas, pemenuhan 24 jam menjadi sangat sulit, menyebabkan guru harus “mencari” jam mengajar hingga ke sekolah lain, yang menghabiskan waktu dan energi. Selain itu, isu pemerataan juga menjadi masalah. Guru di daerah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi dan kesempatan sertifikasi dibandingkan rekan-rekan mereka di daerah terpencil. Keterlambatan pembayaran tunjangan juga menjadi keluhan klasik yang mencederai motivasi dan menunjukkan adanya kelemahan birokrasi dalam pengelolaan program masif ini.
Relevansi analisis ini menjadi semakin tajam jika dikaitkan dengan realitas terkini yang dihadapi para guru. Tantangan pemenuhan beban kerja yang sebelumnya terfokus pada 24 jam mengajar, kini berevolusi ke dalam bentuk baru. Munculnya platform digital seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), meskipun bertujuan baik untuk pengembangan profesional, dalam praktiknya sering kali dirasakan sebagai beban administratif tambahan. Guru dituntut untuk melengkapi berbagai ‘bukti karya’ dan menyelesaikan modul-modul secara daring, yang kembali mengarahkan fokus pada pemenuhan target kuantitatif di atas platform ketimbang refleksi dan perbaikan kualitas pembelajaran substantif di kelas. Hal ini menggemakan kembali kritik lama bahwa kebijakan cenderung terjebak pada aspek formalitas, mirip dengan bagaimana sertifikasi dahulu dipandang sebagai tujuan akhir. “Keterputusan” antara kesejahteraan dan peningkatan kompetensi yang disorot oleh riset terdahulu juga masih sangat terasa. Di tengah tuntutan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang menuntut inovasi tinggi, TPG yang diterima guru tidak secara otomatis membekali mereka dengan keterampilan dan pola pikir baru yang dibutuhkan. Ini menegaskan bahwa insentif finansial saja tidak cukup untuk mendorong transformasi pedagogis yang mendalam tanpa diiringi sistem dukungan dan pengembangan profesional yang efektif dan tidak memberatkan secara administratif.
Menyimpulkan dari berbagai bukti riset, Tunjangan Profesi Guru adalah sebuah kebijakan dengan dua wajah. Di satu sisi, ia adalah sebuah keberhasilan yang tak terbantahkan dalam mengangkat harkat dan martabat ekonomi guru, sebuah capaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun di sisi lain, ia belum mampu menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit kronis rendahnya mutu pendidikan nasional. Asumsi bahwa kesejahteraan akan secara otomatis bertransformasi menjadi profesionalisme dan berujung pada prestasi siswa terbukti terlalu sederhana untuk realitas yang kompleks.
Ke depan, arah kebijakan perlu berevolusi dari sekadar pemberian tunjangan berbasis status (kepemilikan sertifikat) menuju sebuah sistem yang lebih komprehensif. Riset-riset menyarankan perlunya reformasi fundamental pada proses rekrutmen dan pendidikan calon guru, serta perbaikan mekanisme sertifikasi agar lebih berorientasi pada kinerja dan dampak nyata di ruang kelas. Sistem pengembangan profesional berkelanjutan (CPD) yang efektif, terukur, dan tidak membebani guru secara administratif harus menjadi prasyarat, bukan sekadar pelengkap. Mengaitkan sebagian dari tunjangan dengan penilaian kinerja (performance-based incentives) bisa menjadi salah satu alternatif yang patut dipertimbangkan, meskipun implementasinya tentu tidak mudah. Pada akhirnya, TPG telah memberikan fondasi kesejahteraan yang penting. Kini, tantangan terbesar bagi para pemangku kebijakan pendidikan di Indonesia adalah bagaimana membangun di atas fondasi tersebut sebuah struktur kokoh yang mampu menopang peningkatan kualitas pengajaran dan benar-benar mewujudkan tujuan akhir dari setiap upaya pendidikan: masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa.