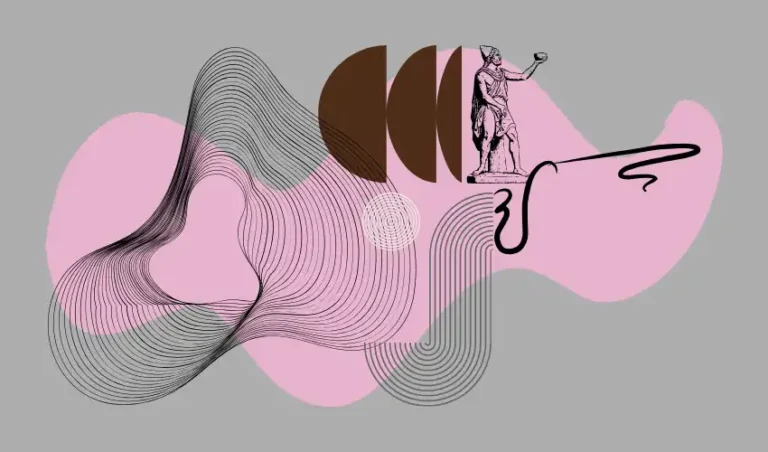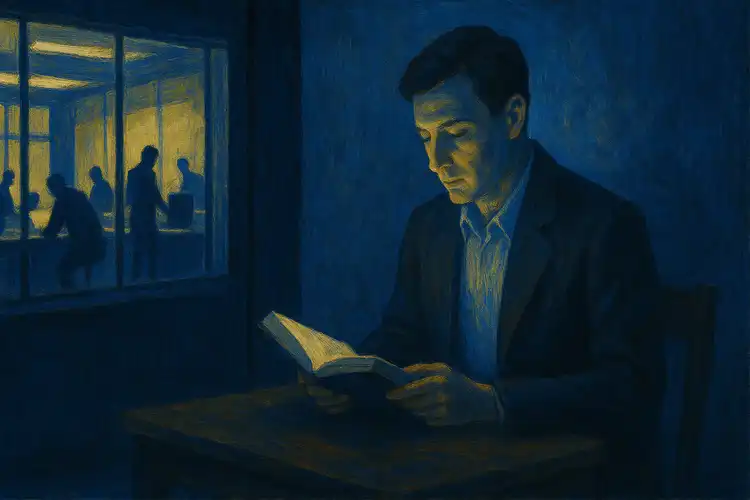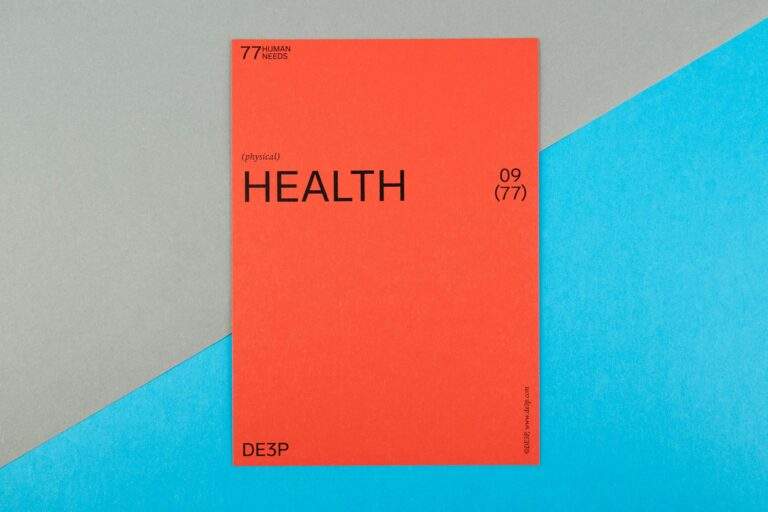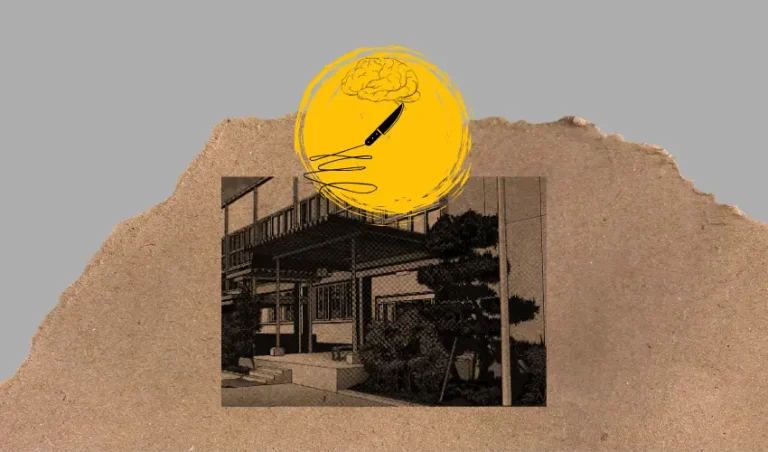Menyoal Dominasi Lembaga Fatwa di Indonesia Pasca-Orde Baru (Bagian I)

Fatwa, sebagai produk utama hukum Islam, telah lama menjadi penentu arah kehidupan sosial keagamaan umat Muslim di Indonesia. Namun, signifikansinya mengalami lonjakan drastis pasca-jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Era Reformasi membuka keran bagi ekspresi keagamaan yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama, menciptakan medan kontestasi yang intens bagi otoritas keagamaan dalam memperebutkan legitimasi publik. Institusi-institusi keagamaan besar, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, kini memainkan peran strategis yang melampaui ranah hukum agama, merambah arena sosial dan politik.
Oleh karena itu, fatwa tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai jawaban normatif-teologis atas persoalan umat. Analisis menunjukkan bahwa fatwa merupakan bagian inheren dari struktur sosial dan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian ideologi keagamaan. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang plural dalam pemikiran dan praktik, otoritas fatwa menjadi titik tarik-menarik yang kompleks antara tradisionalisme, konservatisme, modernisme, dan bahkan reformisme. Memahami fenomena ini membutuhkan pendekatan interdisipliner—sebuah lensa sosio-legal yang mencakup aspek sosial, politik, budaya, dan historis—daripada sekadar pendekatan teologis yang kaku.
Kajian mendalam mengenai fenomena ini terangkum dalam buku Fatwa in Indonesia: An Analysis of Dominant Legal Ideas and Mode of Thought of Fatwa-Making Agencies and Their Implications in the Post-New Order Period (2017) karya Pradana Boy ZTF. Pradana menggunakan pendekatan sosio-legal untuk mengkaji peran dominan ketiga institusi fatwa terbesar: MUI, Lajnah Bahtsul Masail (LBM) NU, dan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah. Argumen sentralnya adalah bahwa, meskipun memiliki orientasi ideologis yang berbeda, ketiga lembaga ini menunjukkan tendensi kuat untuk mempertahankan hegemoni pemikiran keagamaan tertentu, dengan implikasi yang luas terhadap kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia.
Reformasi Politik dan Desentralisasi Otoritas Keagamaan
Reformasi politik sejak 1998 secara fundamental mengubah konfigurasi otoritas fatwa. Sebelum reformasi, peran lembaga fatwa cenderung terkooptasi dalam sistem kekuasaan negara, di mana otoritas keagamaan berfungsi relatif terpusat di bawah kendali rezim. Pasca-Orde Baru, ruang publik keagamaan mengalami desentralisasi yang signifikan. Desentralisasi ini tidak hanya memberikan ruang bagi ekspresi keagamaan yang lebih bebas, tetapi juga menyebabkan otoritas keagamaan bersaing secara terbuka untuk memperebutkan legitimasi di mata publik dan akar rumput.
Dalam lanskap baru ini, konfigurasi otoritas fatwa sangat dipengaruhi oleh struktur ideologi dan sejarah masing-masing lembaga. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang didirikan pada tahun 1975, memiliki kedekatan historis yang erat dengan kekuasaan negara. Kedekatan ini memungkinkannya mengartikulasikan otoritas keagamaan dalam format yang sangat konservatif dan defensif. Sebaliknya, NU mengandalkan kekuatan akar rumput dan jaringan pesantren yang luas, menjadikan pendekatannya deliberatif berbasis kitab kuning. Sementara itu, Muhammadiyah merepresentasikan modernisme Islam yang berbasis pada tradisi tajdid dan purifikasi ajaran.
Ketiga lembaga ini kini bersaing tidak hanya dalam substansi produk fatwa, tetapi juga dalam konstruksi narasi keislaman yang ingin mereka dominasi di ruang publik. Fatwa beralih fungsi menjadi alat untuk menegaskan posisi masing-masing lembaga dalam peta keislaman nasional, dan dalam banyak kasus, digunakan untuk merespons isu-isu politik yang sedang berkembang.
Kerangka Analisis Dominasi: Ideologi dan Kontrol Narasi Ortodoksi
Otoritas fatwa pasca-Orde Baru bukan lagi monopoli negara, melainkan hasil negosiasi yang kompleks antara lembaga keagamaan dengan kekuatan sosial-politik sekitarnya. Dalam konteks ini, dominasi memiliki makna yang lebih mendalam daripada sekadar penguasaan keputusan hukum; dominasi berarti kemampuan untuk memengaruhi cara berpikir umat Islam Indonesia dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama mereka. Dengan demikian, konfigurasi otoritas fatwa menjadi medan ideologis yang sangat dinamis, sarat dengan tarik-ulur antara tradisi, modernitas, dan realitas politik kontemporer.
Analisis terhadap lanskap ini menunjukkan suatu dinamika yang menarik. Desentralisasi otoritas keagamaan, yang muncul seiring dengan kebebasan pasca-Reformasi, ternyata tidak selalu mendorong pluralisme. Sebaliknya, hal ini justru memperkuat tendensi konservatif pada lembaga yang paling dekat dengan negara, seperti MUI. Hal ini terjadi karena kompetisi ideologis menuntut lembaga-lembaga ini untuk menstabilkan dan menegaskan identitas ideologis mereka. Dalam pasar ideologi keagamaan yang bebas, cara tercepat bagi MUI untuk mendapatkan legitimasi moral yang luas dan bersaing dengan NU/Muhammadiyah adalah dengan mengambil peran defensif dan purifikatif terhadap akidah.
Maka, fatwa-fatwa konservatif yang menentang konsep seperti pluralisme, liberalisme, dan sekularisme (PLS), menjadi manifestasi dari respons strategis untuk mempertahankan hegemoni dalam mengontrol narasi ortodoksi. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol keberagamaan masyarakat dan menjaga “kesatuan umat” dari segala bentuk deviasi teologis. Lembaga fatwa dengan demikian berfungsi sebagai gatekeeper atas diskursus keislaman yang sah dan tidak sah, menjaga ortodoksi Islam versi mayoritas Sunni.
Penggunaan kerangka analisis sosio-legal, sebagaimana yang diusung oleh Pradana, sangat penting dalam konteks ini. Kerangka ini mengakui bahwa istinbath hukum (pengambilan hukum) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi politik dan sosial. Keputusan hukum yang paling sakral pun dibentuk oleh sejarah kelembagaan, kepentingan politik, dan tuntutan basis massa. Oleh karena itu, lembaga fatwa yang dominan tidak hanya menginterpretasikan teks, tetapi juga secara aktif mereproduksi dan menjaga tatanan sosial dan politik tertentu.
Editor: Muhammad Farhan Azizi