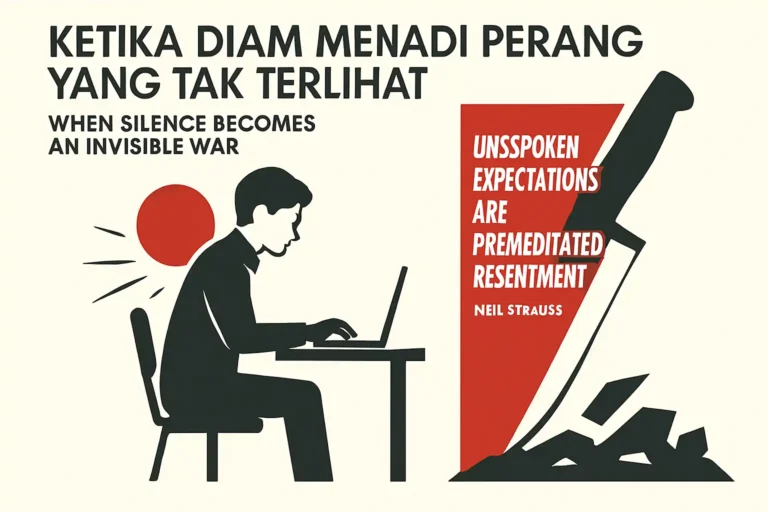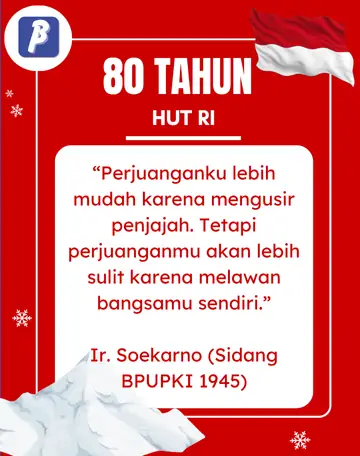Perempuan dan Hal-hal yang Belum Selesai

Di atas meja makan yang juga jadi meja kerja, meja jahit, dan altar kecil bagi cangkir-cangkir teh yang selalu setengah habis, seorang perempuan menunda mengikat benang. Jahitannya rapi tapi tidak dirapikan. Ada ujung-ujung yang sengaja dibiarkan: seperti kalimat yang belum ditutup titik, napas yang mengukur ruang. Ia tahu orang lain akan menyebutnya “belum selesai”. Namun di sela itu—celah kecil antara niat dan rampung—tersembunyi cara ia bertahan.
“Belum selesai” kerap disalahpahami sebagai kurang, sebagai kegagalan menuntaskan. Padahal, bagi banyak perempuan, “belum selesai” adalah modus hidup yang paling jujur. Hidup yang dijalani di bawah jam yang tidak pernah sepenuhnya milik sendiri; hidup yang diatur oleh tempo tubuh, siklus darah, dengung grup WhatsApp keluarga, pekerjaan yang tak dihitung sebagai kerja, dan panggilan-panggilan kecil—ibu, mbak, bu kos, bu bidan—yang menuntut hadir sekaligus. Selesai adalah kata yang, di sini, lebih banyak dipakai orang lain untuk menghakimi daripada oleh pelakunya untuk merayakan.
Mari lihat hal-hal yang katanya harus selesai. Pendidikan, misalnya. Di rapat RT, ada yang bilang: “Anak perempuan harus cepat selesai sekolah, supaya…”—kalimatnya mengapur di udara, meluruh pada logika yang menempatkan pendidikan sebagai stasiun, bukan perjalanan berlapis-lapis. Padahal bagi banyak perempuan, belajar adalah jalan memutar yang tidak punya garis finis: membaca artikel menyusui di sela lembur, belajar perangkat lunak baru sambil menidurkan bayi, menyusun proposal di antara panci dan setrika. Yang “tidak selesai” di sini bukan tekadnya, melainkan sistem yang menyangka belajar bisa dibatasi jam kantor.
Atau ambil contoh kerja rumah. Konsep selesai di sana memang tak pernah logis. Cucian selesai hari ini hanyalah prolog dari cucian besok. Panci yang mengilap pukul tujuh akan menghitam lagi pukul dua belas. Perawatan, pemeliharaan, dan pekerjaan reproduktif lain berjalan dalam ritme sirkular; ia menolak garis lurus menuju “beres” karena nilai utamanya justru pada pengulangan: memberi makan, menyapu, mengelap waktu dari permukaan meja. Menyebutnya “belum selesai” adalah menggunakan kosakata pabrik untuk menjelaskan kehidupan; ketidaktepatan yang membuat perempuan merasa selalu bersalah di depan standar yang tak dirancang untuk mereka.
Di kota, hal-hal yang belum selesai tampil dalam arsitektur. Trotoar yang tinggi buat kereta bayi, lampu jalan yang padam di gang sempit, halte yang jauh dari posyandu. Infrastruktur memanggil siapa yang dibayangkan sebagai pengguna utamanya. Ketika perempuan jalan malam hari memeluk tas seperti pelampung, problemnya bukan pada keberanian yang belum “selesai dibangun”, melainkan pada tata ruang yang belum mengakui rasa aman sebagai hak dasar. Perempuan menghafal rute yang lebih terang, menyimpan kunci di sela jari, berpura-pura sedang telepon. Ini bukan paranoia pribadi, melainkan manajemen risiko atas kerja publik yang tertunda.
Dalam dokumen, “belum selesai” hadir sebagai administrasi yang memberat: akta lahir yang tertahan karena nama ayah wajib tercantum, padahal nama ibu pun seharusnya cukup untuk mengakui keberadaan. Formulir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memantulkan struktur lama: status, “kepala keluarga”, “penanggung jawab”. Jika perempuan memilih jalan menyendiri, istilah yang tersedia cepat berubah menjadi penilaian. Di tempat kerja, kerap ada proyek yang menunggu “kapan kamu tidak sibuk rumah?” seolah rumah berada di luar ekonomi. Di ranah digital, algoritma yang dilatih pada data yang bias mempromosikan bahasa, gambar, dan struktur yang menormalisasi suara laki-laki sebagai default. Ketika perempuan bicara lantang, sistem membacanya sebagai “berlebihan”. Ketika perempuan tenang, sistem membacanya “kurang percaya diri”. Selesai, dalam sistem seperti ini, adalah target bergerak.
Tubuh sendiri adalah peta yang tak mau jadi hasil cetak final. Penuaan, kehamilan, pemulihan, sakit—semuanya proses. Perempuan menghafal terminologi yang menempel di tubuhnya: miom yang disapa seperti kerabat jauh, endometriosis yang merayap pelan di kalender, kontrasepsi yang dimodifikasi mengikuti reaksi yang berubah-ubah. “Belum selesai” di sini adalah etika merawat diri: keberanian menyesuaikan, mengulang, mengganti rencana; tahu kapan menunda, kapan memaksa; mengakui batas sebagai informasi, bukan aib.
Di ruang-ruang ibadah, “belum selesai” beresonansi sebagai tanya. Perempuan membawa pertanyaan-pertanyaan yang tak selalu mendapat ruang di mimbar: perihal tafsir yang memadat di lidah otoritas, perihal tempat berdiri yang dipisah tabir, perihal doa yang beresonansi pelan di belakang. Keimanan, bagi banyak perempuan, lahir dari kebiasaan yang setia: mencuci sajadah, mengingatkan adik wudu, melatih anak membaca, memutar zikir pelan saat lampu padam. Selesai tidak pernah jadi janji; yang ada adalah kontinuitas yang dirawat.
Di keluarga, “belum selesai” mengambil bentuk lain: percakapan yang tertunda. Perempuan menyimpan kalimat yang tidak terucap kepada ibu, nenek, putri, dan diri sendiri. Ada humor yang diwariskan, juga luka yang diturunkan seperti resep. Kerap, yang paling berat justru bukan trauma besar, melainkan serpih-serpih kecil dari hal-hal tak dibicarakan: beban anak sulung, pernikahan yang diusahakan berjalan, mimpi yang dibuat realistis demi logistik. Di sini “belum selesai” adalah warisan yang tak berbunyi, getaran halus yang memengaruhi cara mengambil keputusan.
Namun menyebut semua ini seakan perempuan adalah satu sosok homogen tentu keliru. Kata “perempuan” mencakup kelas, ras, agama, desa-kota, orientasi, disabilitas, umur. Hal-hal yang belum selesai bagi perempuan pekerja pabrik berbeda dari akademisi, berbeda lagi dari pedagang pasar, berbeda dari santri yang menyiangi waktu di sela halaqah. Tapi ada benang yang menaut: medan permainan yang dimiringkan. “Belum selesai” menjadi benang merah bukan karena perempuan kurang kuat, melainkan karena mereka dipaksa bermain di lapangan yang regulasinya berubah sesuka wasit.
Apa yang bisa kita lakukan dengan “belum selesai” selain meratapinya? Pertama, kita akui ia sebagai kategori pengetahuan, bukan sekadar status pengerjaan. “Belum selesai” mengajar kita cara membaca dunia yang tidak tergesa-gesa merapikan. Ia meminta metode yang sabar: pengamatan yang mengakui noise, kebijakan yang memberi ruang untuk iterasi, evaluasi yang menghargai proses, bukan hanya hasil. Dalam riset, itu berarti mengundang pengalaman yang tak biasanya dimasukkan: catatan harian, cerita lisan, logika dapur, peta mental rute aman. Dalam kebijakan, itu berarti indikator keberhasilan yang menghitung waktu perawatan, keselamatan perjalanan malam, dan biaya mental dari administrasi.
Kedua, kita gunakan “belum selesai” sebagai strategi. Perempuan telah amat mahir di strategi darurat: mengubah wadah jadi alat masak, mengubah ruang tamu jadi kelas TK, mengubah suara pelan jadi jaringan solidaritas. Strategi sementara bukan kompromi murahan, melainkan teknologi bertahan hidup yang canggih: membuat sistem paralel ketika sistem resmi lambat; menukar informasi lewat grup kecil; menolong dalam sunyi. Yang perlu adalah pengakuan—dan dukungan—agar strategi ini tidak terus-menerus dianggap “inisiatif pribadi” yang bisa gratis dieksploitasi.
Ketiga, kita terjemahkan “belum selesai” ke bahasa politik yang bisa menuntut. Di kantor, itu berarti perjanjian kerja yang mengakui jam fleksibel dan cuti perawatan. Di kampung, itu berarti lampu di lorong-lorong gelap dan rute transportasi yang memikirkan kereta bayi dan kursi roda. Di sekolah, itu berarti kurikulum yang mengajarkan anak laki-laki mengurus rumah sebagaimana anak perempuan diajarkan memimpin. Di ruang ibadah, itu berarti menata ulang ruang dan peran sehingga suara perempuan duduk di kursi, bukan selalu di ambang pintu.
Akhirnya, “belum selesai” adalah bentuk harapan yang lebih dewasa daripada “akan mulus”. Ia tidak menjanjikan setapak bebas hambatan; ia menawarkan kompas: arah yang bisa disesuaikan ketika cuaca berubah. Perempuan tidak menunggu gong penutupan. Mereka mencicil masa depan dengan cara yang mungkin terlihat kecil: satu pesan yang menenangkan kawan di dini hari; satu keberanian berkata “tidak” pada lelucon yang menyakitkan; satu permohonan maaf kepada anak yang tadi sore disemprot saat hari terlalu berat. Fragmen-fragmen inilah yang menyusun etika baru, bukan karena dramatis, melainkan karena tekun.
Ketika perempuan itu akhirnya mengikat benang di ujung jahitan, ia tidak menyebut pekerjaannya selesai. Ia menggulung sisa kapas, menaruhnya di cangkir teh yang belum habis, dan berpindah ke hal berikutnya. “Belum selesai” bukan tanda kalah. Ia adalah cara mengakui kenyataan: bahwa hidup tidak bergerak seperti garis lurus, melainkan seperti kain yang bertemu mesin jahit—mundur, maju, putar, balik—agar kuat. Dan barangkali di situlah kekuatan perempuan: bukan pada puncak yang sekali dicapai, melainkan pada kemampuan merawat yang berulang, melipat hal-hal kecil agar menjadi selimut bagi banyak orang. Dalam dunia yang gemar memamerkan hasil akhir, kemampuan untuk bertahan di tengah proses adalah bentuk keberanian yang paling tenang—dan, sejauh ini, paling kita butuhkan.