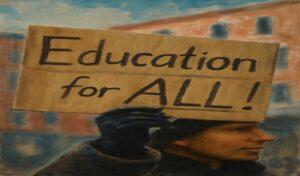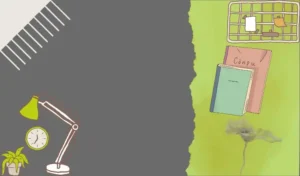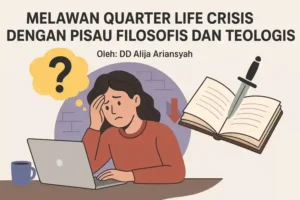Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12%: Antara Data Resmi dan Persepsi Lapangan

Di awal Agustus 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025: 5,12 persen year-on-year. Angka ini lebih tinggi dari kuartal I yang sebesar 4,87 persen, bahkan melampaui perkiraan banyak analis yang berkisar di 4,7–4,8 persen. Bagi sebagian orang, ini kabar baik. Pertumbuhan di atas lima persen sering dipandang sebagai tanda ekonomi yang sehat dan dinamis. Namun, tidak sedikit pula yang mengernyitkan dahi. Di media sosial, komentar seperti “Di lapangan lesu, kok data bisa naik?” bermunculan.
Isu ini pun melebar. Lembaga riset, ekonom independen, hingga politisi ikut menyoroti. Ada yang menyebut data BPS janggal, ada pula yang meminta klarifikasi metodologi. Singkatnya, satu angka telah memantik diskusi nasional.
Pertumbuhan ekonomi yang diumumkan BPS mengacu pada Produk Domestik Bruto (PDB), yakni total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam periode tertentu. PDB bisa dihitung dengan tiga pendekatan: produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Dalam laporan ini, BPS menyajikan pertumbuhan berdasarkan pendekatan pengeluaran.
Menurut data resmi, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97 persen dan menjadi penyumbang terbesar, yakni 54,25 persen PDB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi naik 6,99 persen dengan kontribusi sekitar 27,8 persen terhadap PDB. Ekspor barang dan jasa tumbuh 10,7 persen, sementara pengeluaran pemerintah tercatat meningkat secara moderat. BPS menegaskan perhitungan dilakukan sesuai standar internasional yang ditetapkan System of National Accounts (SNA) 2008. Data dikumpulkan dari berbagai sumber: survei, laporan industri, bea cukai, kementerian, hingga catatan perusahaan besar.
Di sisi lain, beberapa ekonom mempertanyakan konsistensi angka tersebut dengan indikator ekonomi harian atau bulanan. PMI manufaktur Indonesia pada periode yang sama berada di bawah 50, menandakan kontraksi sektor industri. Penjualan ritel mengalami penurunan, seiring fenomena “Rojali–Rohana” (beli roti, jajan sedikit, lalu hemat sisa uang) yang jadi sinyal daya beli melemah. Laporan PHK dan efisiensi di sejumlah industri pengolahan meningkat. Harga komoditas ekspor andalan seperti batu bara dan CPO cenderung melemah.
Bagi para pengkritik, indikator-indikator ini sulit dipadukan dengan gambaran pertumbuhan yang cukup tinggi. “Bisa jadi PDB naik karena faktor tertentu, tapi itu tidak berarti ekonomi di lapangan otomatis terasa lebih baik bagi masyarakat,” ujar salah satu peneliti INDEF.
Menanggapi keraguan ini, Kepala BPS menegaskan bahwa PDB tidak semata mencerminkan kondisi semua sektor secara seragam. “Ada sektor yang melambat, ada yang tumbuh pesat, sehingga rata-rata nasional tetap positif,” jelasnya. BPS juga menekankan bahwa pertumbuhan 5,12 persen mencerminkan kinerja gabungan semua komponen PDB. Misalnya, investasi besar di infrastruktur dan pertumbuhan ekspor bisa mengangkat total meski konsumsi ritel melambat.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, “Tidak ada manipulasi. Pertumbuhan ini nyata, didukung konsumsi, investasi, dan pariwisata, baik domestik maupun mancanegara.” Pihak Istana pun menambahkan bahwa metodologi BPS sesuai standar global dan hasilnya dapat diaudit.
Perbedaan antara data resmi dan persepsi publik bukanlah hal baru. Ada beberapa alasannya. Pertama, perbedaan cakupan data. PDB mencakup seluruh sektor ekonomi, termasuk yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat umum. Misalnya, ekspor jasa digital atau investasi infrastruktur yang nilainya besar, tapi tidak langsung dirasakan dalam aktivitas harian.
Kedua, efek rata-rata nasional. Pertumbuhan di satu daerah atau sektor bisa menutupi pelemahan di daerah atau sektor lain. Jika sektor pertambangan di Kalimantan tumbuh tinggi, itu akan mengangkat rata-rata nasional meski sektor ritel di kota besar sedang lesu.
Ketiga, lag waktu persepsi. Dampak pertumbuhan ekonomi sering baru terasa setelah beberapa bulan atau tahun. Proyek infrastruktur yang dikerjakan tahun ini mungkin baru memberi efek signifikan pada lapangan kerja di tahun depan.
Keempat, indikator yang berbeda. PMI, penjualan ritel, dan PDB mengukur hal yang berbeda. PMI fokus pada manufaktur, sementara PDB meliputi jasa, pertanian, konstruksi, dan lain-lain.
Polemik 5,12 persen ini memberi beberapa pelajaran penting. Transparansi metodologi perlu terus diperkuat, agar publik paham mengapa angka bisa berbeda dari indikator lain. Literasi statistik publik juga penting, karena masyarakat perlu memahami bahwa satu angka bukanlah gambaran utuh. PDB, inflasi, dan pengangguran harus dilihat bersama-sama. Perbedaan antara data resmi dan temuan lapangan tidak serta-merta berarti salah satu keliru. Diskusi terbuka membantu menyempurnakan kebijakan.
Di era informasi cepat, angka statistik sering jadi bahan perdebatan publik. Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen adalah salah satunya. Bagi pemerintah, ini adalah sinyal positif yang ingin disampaikan ke pasar dan investor. Bagi sebagian masyarakat, ini adalah angka yang perlu diuji lagi dengan realitas sehari-hari.
Yang jelas, menjaga kepercayaan pada data memerlukan dua hal: keakuratan teknis dan keterbukaan komunikasi. BPS sudah memiliki standar teknis, tetapi polemik ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi publik masih perlu diperkuat. Pada akhirnya, data adalah alat untuk memahami realitas, bukan sekadar angka di atas kertas. Memahami data dengan benar, mengkritisinya dengan dasar yang kuat, dan menggunakannya untuk kebijakan yang bermanfaat adalah tujuan akhir dari setiap rilis statistik nasional. (*)