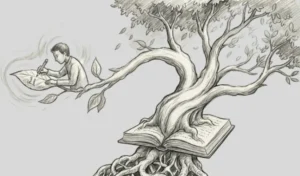Kopi dan Budaya Kelas Menengah

Dulu, kopi identik dengan minuman rakyat: hitam, pahit, dan murah. Diseduh di warung sederhana, menemani obrolan santai, gosip tetangga, hingga perdebatan politik kecil-kecilan.
Namun, di kota-kota besar, kopi telah menjelma menjadi simbol status. Gelas kopi dengan label tertentu—yang dibawa di tangan atau dipajang di Instagram—seringkali lebih penting daripada isi kopinya sendiri.
Fenomena ini mencerminkan transformasi sosial: kopi menjadi bagian dari budaya kelas menengah urban yang tumbuh pesat di Indonesia sejak dua dekade terakhir.
Kopi Sebagai Gaya Hidup
Munculnya coffee shop bergaya minimalis, lengkap dengan Wi-Fi, alunan musik jazz, dan barista berseragam apron, tidak bisa dilepaskan dari tren konsumsi kelas menengah. Di ruang ini, kopi bukan sekadar minuman, tapi pengalaman. Menikmati kopi single origin dengan metode V60 atau manual brew dianggap lebih “berbudaya” dibanding kopi instan saset.
Pierre Bourdieu, filosof Prancis peletak dasar modernisme, menyebut ini sebagai cultural capital—di mana seseorang membangun identitas melalui preferensi budaya. Pilihan kopi tertentu mencerminkan selera, pengetahuan, dan kadang superioritas simbolik.
Kopi dan Pencitraan Sosial
Media sosial mempercepat transformasi ini. Foto flat lay secangkir cappuccino di meja kayu, dengan quote bijak di caption, menjadi bagian dari pencitraan personal: “Aku produktif, aku santai, aku tahu kualitas.” Di sinilah kopi menjadi komoditas visual, bukan lagi kebutuhan harian.
Dalam banyak kasus, kopi bahkan menggantikan kemewahan yang lebih mahal. Ketika kelas menengah tidak mampu membeli mobil premium, mereka membeli gaya hidup premium versi terjangkau: nongkrong di kafe artisan. Hal ini disebut “aspirational consumption”—mengkonsumsi barang atau pengalaman yang memberi ilusi status sosial lebih tinggi.
Ironi yang Tersembunyi
Sementara kelas menengah sibuk menikmati kopi sebagai simbol gaya hidup, petani kopi di dataran tinggi seringkali tidak merasakan kesejahteraan sepadan. Mereka menjual biji kopi dengan harga rendah, bergantung pada cuaca dan fluktuasi pasar.
Ironisnya, narasi “kopi lokal” justru digunakan oleh pemilik kafe di kota besar sebagai jualan branding, meski nilai tambahnya tidak kembali ke petani. Ini menunjukkan adanya jarak antara simbolisme kopi di kota dan realitas di desa.
Kesadaran Budaya Kopi
Kopi telah menjadi bagian dari identitas kelas menengah urban: efisien, estetik, dan penuh simbol. Namun di balik busa latte dan interior kafe Instagramable, ada relasi sosial dan ekonomi yang kompleks.
Kopi bisa tetap dinikmati, tentu. Tapi menjadi konsumen yang sadar, yang tidak sekadar membeli citra tetapi juga mendukung rantai nilai yang adil, adalah langkah kecil menuju budaya minum kopi yang lebih bermakna.