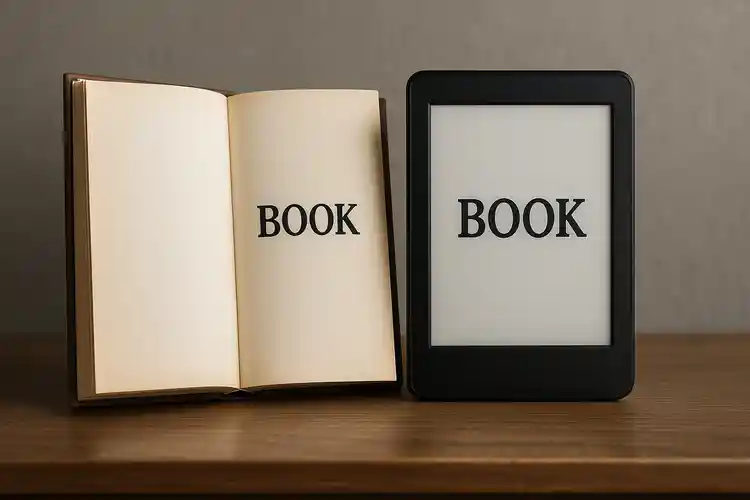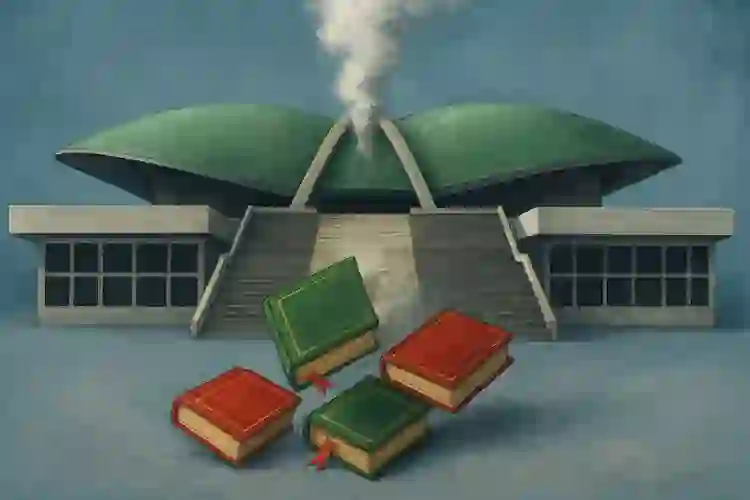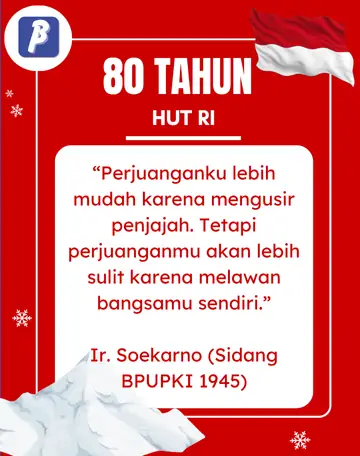Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Pesantren: Antara Kekosongan Regulasi dan Krisis Tata Kelola

Pesantren selama ini dikenal sebagai institusi pendidikan Islam yang melahirkan para pemuka agama, ulama, dan tokoh masyarakat. Namun, dalam satu dekade terakhir, citra luhur pesantren di Indonesia tercoreng oleh serangkaian kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap santri, baik laki-laki maupun perempuan. Meski bukan kasus mayoritas, skala dan kekejian beberapa kasus tersebut telah memicu keprihatinan nasional serta menggugah urgensi perbaikan sistemik dalam pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum di lingkungan pesantren.
Tulisan ini mengkaji kekerasan dan pelecehan seksual di pesantren dengan pendekatan ilmiah: berdasarkan data, argumen dari perspektif hukum, sosiologi, dan tata kelola pendidikan.
Data Empiris dan Tren Kekerasan Seksual di Pesantren
Laporan Komnas Perempuan 2022 menyebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis agama meningkat secara signifikan. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, menyatakan bahwa dalam kurun 2019–2021, mereka menerima lebih dari 20 laporan kekerasan seksual di lingkungan pesantren, dan jumlah ini diperkirakan jauh lebih kecil dari angka yang sebenarnya terjadi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat budaya tabu, relasi kuasa, dan minimnya mekanisme pelaporan internal.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menyampaikan bahwa pelaku kekerasan seksual di pesantren kerap memanfaatkan posisi sebagai “guru”, “ustaz”, atau “kyai” untuk menciptakan hubungan dominasi dan ketergantungan terhadap santri. Dalam banyak kasus, korban merasa tidak punya pilihan selain diam karena pelaku adalah tokoh yang sangat dihormati atau ditakuti dalam lingkungan tertutup pesantren.
Kekejaman yang Tidak Bisa Ditutupi
Salah satu kasus paling mencengangkan dalam sejarah pendidikan Indonesia adalah kekerasan seksual massal yang dilakukan oleh Herry Wirawan, pendiri Pesantren Madani Boarding School di Bandung, Jawa Barat.
Menurut dakwaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Herry telah memperkosa 13 santri perempuan berusia 14–17 tahun antara tahun 2016–2021. Delapan korban hamil dan melahirkan anak, dan semuanya mengalami trauma berat secara psikologis. Herry melakukan kejahatannya di ruang guru, hotel, dan asrama santri. Ia memanfaatkan kedekatan spiritual dan kekuasaan mutlaknya di lembaga pendidikan yang tidak memiliki sistem pengawasan eksternal.
Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana mati dan kebiri kimia, serta perampasan aset untuk kompensasi korban (Kompas.com, 2022).
Kasus ini bukan hanya memperlihatkan brutalitas pelaku, tetapi juga lemahnya sistem pengawasan di lembaga pesantren yang cenderung tertutup dan menormalisasi ketundukan mutlak kepada sosok kyai.
Kasus berikutnya menimpa seorang tokoh pesantren ternama di Jombang, berinisial KH E, yang juga anak dari pendiri pondok pesantren. Ia dilaporkan oleh belasan santri perempuan karena melakukan pelecehan seksual selama bertahun-tahun.
Meskipun telah dilaporkan sejak 2019, upaya hukum terhambat karena pelaku memiliki pengaruh kuat dan dukungan dari simpatisan pesantren. Bahkan pada 2022, ketika polisi berupaya menangkap KH E, massa pesantren menghadang aparat dengan aksi kekerasan dan intimidasi. Baru setelah beberapa upaya, pelaku berhasil diamankan dan kini menjalani proses hukum.
Kasus ini menyoroti dua hal krusial: kultus individu dalam kepemimpinan pesantren dan minimnya perlindungan bagi pelapor dan korban, terutama ketika pelaku memiliki jejaring politik, ekonomi, atau sosial yang kuat.
Dimensi Sosiologis: Ketertutupan, Relasi Kuasa, dan Budaya Patriarki
Banyak pesantren masih menerapkan pola pendidikan berbasis otoritas tunggal, di mana kyai atau ustaz menjadi sosok yang tidak boleh dibantah. Struktur ini memudahkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan membuat korban enggan bersuara.
Dalam bukunya Discipline and Punish, Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berasal dari hukum atau negara, tetapi juga dari pengawasan yang terinternalisasi dalam sistem tertutup. Pesantren, sebagai sistem sosial yang tertutup, menjadi ruang di mana kontrol atas tubuh, waktu, dan pikiran santri sangat kuat—dan bila tidak diimbangi dengan pengawasan eksternal, sistem ini sangat rentan terhadap penyimpangan seksual.
Sosiolog UGM, Dr. Heru Nugroho, menyatakan bahwa dalam banyak kasus kekerasan seksual di pesantren, pelaku memanfaatkan kombinasi pengaruh spiritual, kekuasaan ekonomi, dan struktur patriarkal, sehingga santri perempuan (atau laki-laki) menjadi korban dalam posisi sangat lemah.
Ketiadaan Regulasi Perlindungan Internal
UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memang memberikan status hukum bagi pesantren sebagai entitas pendidikan formal. Namun regulasi ini belum menyentuh aspek perlindungan santri dari kekerasan seksual secara eksplisit.
Laporan dari Yayasan Rumah Kitab (2023) menyebutkan bahwa 80% pesantren di Indonesia belum memiliki mekanisme pengaduan kekerasan seksual internal. Bahkan ketika ada kasus, penyelesaiannya kerap bersifat informal, kekeluargaan, atau ditutup-tutupi demi “menjaga nama baik lembaga.”
Belum adanya kewajiban pelaporan kepada lembaga eksternal seperti Komnas HAM, KPAI, atau Dinas Sosial membuat banyak korban memilih diam. Bahkan, ada korban yang akhirnya dikeluarkan dari pondok karena dianggap merusak reputasi pesantren.
Pandangan Agama dan Tantangan Interpretasi
Secara normatif, Islam sangat tegas dalam melarang pelecehan seksual dan melindungi martabat perempuan. Dalam QS. An-Nur ayat 30–31, umat Islam diperintahkan untuk menjaga pandangan dan kemaluan, serta tidak melakukan tindakan cabul. Namun, dalam praktiknya, ajaran ini sering kalah oleh struktur sosial patriarki dan interpretasi agama yang bias kekuasaan.
Beberapa pengelola pesantren menolak keterlibatan aparat dengan dalih “aib internal umat Islam harus diselesaikan secara internal.” Pandangan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip hukum positif, tetapi juga mengkhianati misi moral pendidikan Islam sebagai ruang pembinaan akhlak dan keadilan.
Upaya Reformasi: Antara Retorika dan Implementasi
Pemerintah dan organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mulai menyadari urgensi perlindungan santri. PBNU pada 2023 mengusulkan agar semua pesantren di bawah afiliasi NU menerapkan standar tata kelola berbasis good governance, termasuk membentuk satuan tugas perlindungan santri dan pelaporan kekerasan seksual.
Kementerian Agama telah menyiapkan modul Pendidikan Kesetaraan Gender dan Etika Pergaulan di Pesantren, namun belum diwajibkan secara nasional. Komnas Perempuan mengusulkan integrasi pesantren dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), tetapi respons DPR masih terbagi.
Sementara itu, beberapa pesantren independen telah membentuk tim pengawasan internal, namun jumlahnya masih sangat kecil dan tidak memiliki sanksi legal bila tidak dilaksanakan.
Rekomendasi Ilmiah dan Kebijakan
UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren perlu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Agama yang memuat kewajiban membentuk Unit Perlindungan Santri (UPS), mekanisme pelaporan rahasia dan bebas dari intimidasi, serta sanksi administratif bagi pesantren yang tidak kooperatif dalam kasus kekerasan
Selain itu, Kementerian Agama perlu melakukan audit independen terhadap tata kelola pesantren, bukan hanya soal kurikulum dan akreditasi, tetapi juga aspek perlindungan anak dan etika relasi kekuasaan.
Pun santri dan pengasuh perlu diberikan pendidikan tentang batasan relasi sehat antara guru dan murid, hak korban untuk melapor, dan perspektif Islam yang progresif dalam membela korban kekerasan
Perlu narasi kuat dari para kyai, ustaz, dan tokoh agama yang menyatakan bahwa membongkar kekerasan seksual bukanlah “membuka aib”, melainkan bentuk jihad melawan kebatilan.
Menyelamatkan Martabat Pesantren
Kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren adalah cermin bahwa kelembagaan yang berbasis moral pun bisa runtuh bila sistemnya tidak dikawal dengan transparansi dan pengawasan. Masyarakat harus berani membedakan antara penghormatan terhadap agama dan fanatisme terhadap individu yang menyalahgunakan simbol agama untuk kepentingan pribadi.
Menyelamatkan pesantren berarti menyelamatkan ribuan anak Indonesia yang menaruh harapan di tempat itu. Tidak cukup hanya dengan slogan, “Pesantren adalah benteng moral bangsa”—tetapi harus dengan langkah konkret: regulasi ketat, pendidikan etika, dan keberanian membongkar borok kekuasaan yang menyamar sebagai pengasuhan.