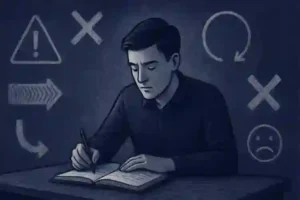Saat Perguruan Tinggi Jadi Kios Percetakan

Perguruan tinggi kita, hari ini, lebih mirip “kios percetakan” ketimbang lembaga pendidikan tinggi. Kios yang sibuk memproduksi sertifikat, lembar ijazah, kumpulan artikel ilmiah, dan foto wisuda—demi memenuhi permintaan pasar yang tak pernah habis: para calon sarjana yang mengejar legitimasi formal, bukan ilmu.
Situasi tersebut bukan semata keinginan dari institusi Perguruan Tinggi itu sendiri, melainkan kehendak sistem yang menjadikan ijazah sebagai salah satu bukti awal dari kriteria penilaian kompetensi atau kualitas SDM untuk dunia kerja.
Barang tentu, tidak ada birokrasi atau korporasi yang mau “membeli kucing dalam karung”. Boleh jadi, setiap instansi pasti memiliki standar penilaian sedari proses administrasi pendaftaran calon pekerja. Bidang disiplin ilmu yang sesuai, atau portofolio lain yang nanti dinilai mampu meningkatkan kinerja instansi, misalnya.
Namun, ekosistem tersebut juga bisa menjadi bumerang. Penilaian yang terlalu beroriantasi pada nilai akademik di ijazah atau almamater kampus justru akan mengabaikan keterampilan seseorang.
Pada sisi ini, ada bentuk ketimpangan antara masyarakat yang mendapat kesempatan dan tidak. Ada ketimpangan antara satu sektor dengan sektor lainnya. Sementara dalam dunia politik nasional, misalnya, kendati disyaratkan pada aturan pelaksanaan Pemilu, UUD 1945 tidak menjadikan ijazah sebagai syarat utama untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Alih-alih menjadi salah satu bukti kompetensi individu, ijazah sangat mungkin menjadi alat untuk merekayasa sosial. Dampaknya, orientasi para mahasiswa untuk kuliah bukan lagi menjalankan tri darma perguruan tinggi, melainkan mendapatkan sertifikat, publikasi artikel ilmiah, ijazah, dan foto wisuda. Walhasil, aktivitas plagiarisme merajalela. Mahasiswa malas atau mungkin tidak mau berpikir tentang cara mengemban gelar sarjana, yang ada di kepala hanyalah harus dapat ijazah dan bisa bekerja.
Gambaran dari penyimpangan orientasi itu bisa dilihat dari beberapa kasus plagiarisme yang terjadi, dua di antaranya: Kasus Mahasiswa S3 ITB tahun 2022 yang dituduh menjiplak sebagian besar isi disertasi dari makalah orang lain yang terpublikasi di jurnal internasional, sehingga ITB membatalkan ijazah doktor tersebut.
Contoh lain, kasus plagiarisme seorang dosen Unila tahun 2015-2016 yang menggunakan karya mahasiswa dalam jurnal nasional tanpa mencantumkan nama mahasiswa tersebut, sehingga berujung pada penurunan jabatan akademik.
Dua contoh ini hanya puncak gunung es. Ada banyak lagi praktik plagiarisme diam-diam yang lolos tak terendus: skripsi hasil beli, artikel jurnal hasil salin-tempel, bahkan disertasi ‘titipan’.
Perguruan Tinggi dengan kewenangannya untuk menganugerahi gelar akademik dan gelar-gelar lainnya rawan dengan praktik penyalahgunaan. Institusi yang menyalahgunakan wewenang inilah yang amat layak menyandang status “Kios Percetakan”.
Meningkatkan Mahasiswa Baru sama dengan Meningkatkan Pengangguran Baru
Banyak Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan segala upayanya, terus menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Mulai dari pengadaan fasilitas, pembangunan infrastruktur, peremajaan literatur, dan sejenisnya.
Namun, niat baik itu kerap diselimuti gairah yang menggelora untuk memoles citra institusi demi meningkatkan jumlah peminatnya, tanpa proyeksi dan pertimbangan yang matang terkait capaian lulusan. Yang pada akhirnya, peningkatan jumlah mahasiswa baru bersamaan dengan peningkatan jumlah pengangguran baru.
Menurut data BPS tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan Perguruan Tiggi mencapai 5,25%, lebih tinggi dari rata-rata lulusan Diploma (4,83%) dan SMP (4,11%). Sementara dalam data Dukcapil, angka status pendidikan terakhir Sarjana S1 mencapai 4,64% atau 13 juta dari 280 juta total penduduk Indonesia. Artinya, walaupun gelar sarjana kerap dianggap ‘tiket emas’, realitanya masih ada sekitar 682 ribu dari 13 juta sarjana yang masih menganggur.
TPT 5,25% sebenarnya bukan angka yang terlalu buruk. Namun, angka ini juga menunjukkan ironi, bahwa semakin tinggi pendidikan belum tentu semakin mudah bekerja. Lantas pertanyaannya, apakah penyebab hal ini terjadi?
Secara umum, problem ini kerap dikaitkan dengan satu penyebab terbesar, yakni mismatch keterampilan. Karenanya, banyak sarjana bekerja di bidang yang tidak relevan dengan jurusan yang ditempuh sebelumnya di Perguruan Tinggi. Dan secara sederhana, masalah ini menunjukkan bahwa efisiensi pendidikan belum optimal.
Ironisnya, meskipun peluang kerja tak sebanding dengan jumlah lulusan, gelar sarjana tetap dianggap bergengsi. Akibatnya, sebagian kalangan mahasiswa menganggap pekerjaan yang tidak relevan bukan sebagai sebuah pekerjaan. Kenyataan ini juga menjadi bukti nyata apabila Perguruan Tinggi hanya bekerja layaknya kios percetakan.
Sekalipun demikian, Perguruan Tinggi bukan berarti harus menjadi seperti Balai Latihan Kerja yang mengeluarkan mahasiswa siap pakai. Sistem seperti ini justru dapat membuat pendidikan tinggi akan kalah dengan workshop-workshop enterpreneur. Dengan peralatan mumpuni, pelatihan-pelatihan kerja kewirausahaan yang diadakan oleh siapapun itu justru akan lebih jitu melahirkan manusia mekanis.
Pada kenyataannya banyak lulusan Perguruan Tinggi yang saat ini menjalani pekerjaan tanpa seperangkat administrasi yang diperoleh dari “kios percetakan” itu. Misalnya admin, marketing, driver ojol, tenaga kerja kontrak, barista, content creator, atau bahkan bekerja sebagai pekerja kasar. Kerap kali, pekerjaan ini belum sepenuhnya diakui sebagai pekerjaan tetap. Alasannya sederhana tanpa harus mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi, siapapun bisa mengerjakannya.
Tuntutan Sistem yang Tak Terelakkan
Pada akhir tulisan ini, saya tidak ingin meninggalkan sedikit aspek subjektif pengalaman. Sebab tidak jarang—meminjam perumpamaan ‘menuntut ilmu seperti mengisi gelas kosong’—mahasiswa yang ketika awal masuk perguruan tinggi adalah gelas kosong setelah lulus pun tetap gelas kosong, sama sekali tidak terisi.
Para pembaca lainnya mungkin pernah menemukan hal serupa secara langsung. Sehingga, hadir penyataan: Siapa penyebabnya? Apakah karena individunya atau karena kesalahan sistem yang ada?
Tentu, kita tidak bisa menitikberatkan tanggungjawab sepenuhnya kepada individu maupun institusi Perguruan Tinggi. Pasalnya, individu mahasiswa dan institusi telah menjadi dua komponen yang saling memengaruhi. Di satu sisi mahasiswa memberikan sumbangsi berupa materi agar institusi bisa terus meningkatkan kualitasnya, di sisi yang lain Perguruan Tinggi juga terus berupaya memformulasikan kurikulum terbaik untuk mahasiswanya.
Oleh karena itu, ada sebuah unsur yang sebenarnya tidak terelakkan dari seluruh aspek kehidupan manusia, yakni tuntutan sistemik dari berbagai macam aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Mahasiswa berhadapan dengan tuntutan lingkungan untuk memeroleh penerimaan, rasa aman, dan bermacam jaminan atau keistimewaan di lingkungan sosial. Sedangkan kampus dikejar-kejar oleh ritme birokrasi dan korporasi yang semakin hari semakin menggila.
Di sinilah kampus terjebak menjadi pabrik yang melayani birokrasi dan pasar. Sementara mahasiswa menjadi konsumen yang hanya peduli hasil cetakan: ijazah, transkrip, dan publikasi, bukan proses berpikir kritis.
Kini, tuntutan sistemik itu sudah menjadi mata rantai yang terus berputar di dalam dunia Perguruan Tinggi. Maka tugas kita, hari ini, bukan sekadar melawan ‘kios percetakan’, melainkan memutus mata rantai itu dengan memutarbalikkan arah pemahaman bahwa roh Perguruan Tinggi yang sejati adalah sebagai rumah belajar, ruang berpikir kritis, dan laboratorium kemanusiaan. Sebab pendidikan di tingkat apa pun itu semestinya bukan hanya soal sertifikat, publikasi, ijazah, apalagi foto wisuda—melainkan tentang menjadi manusia yang merdeka.