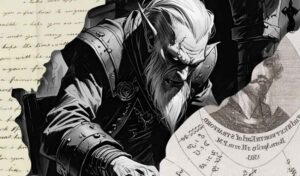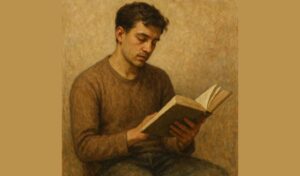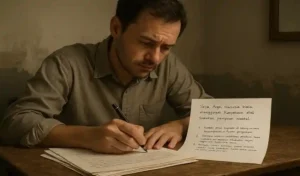Anak Alam

Di sebuah lembah yang malas muncul di peta, bernama Lembah Bisu, hidup seorang anak bernama Sema. Orang-orang memanggilnya “Anak Alam”. Bukan karena ia dilahirkan dari rahim pohon beringin atau air sungai, tapi karena ia tidak pernah duduk di bangku sekolah, tidak pernah mengeja huruf di atas kertas, dan tidak tahu bedanya titik dengan koma. Ia belajar dari angin, dari retak daun, dari peluh bumi.
“Dia tidak berpendidikan,” kata Pak Camat saat singgah ke lembah itu dalam safari literasi nasional yang lebih sering menjadi ajang selfie sambil membagikan buku-buku yang tak pernah dibaca.
“Dia tak tahu Pancasila,” kata petugas penyuluh yang tak bisa mengucapkan sila kedua tanpa melirik catatan.
“Dia bukan bagian dari masa depan bangsa,” kata guru honor yang mengajar dari WhatsApp karena bangunan sekolah telah lama menjadi kandang kambing.
Tapi Sema, yang tak berpendidikan itu, bisa menirukan suara burung hantu, memahami gerak awan, membaca jejak musang di tanah, dan tahu kapan hujan akan datang hanya dari aroma angin. Sema bisa merawat luka dengan daun, menyembuhkan demam dengan rebusan akar. Dan yang lebih hebat: Sema tahu diam lebih baik dari pidato kosong.
Ia tinggal bersama kakeknya, Mbah Waris, satu-satunya manusia di lembah itu yang mengaku pernah mencicipi sekolah—pada zaman ketika guru masih dianggap pemilik ilmu, bukan pegawai proyek kurikulum.
“Zaman dulu,” kata Mbah Waris suatu malam sambil menyalakan api unggun, “sekolah adalah tempat menumbuhkan manusia. Sekarang sekolah adalah tempat mencetak berkas—ijazah, rapor, sertifikat. Anak-anak tidak lagi belajar berpikir, mereka hanya belajar menjawab soal.”
Sema mengangguk. Ia tak mengerti banyak soal sekolah, tapi ia mengerti ketika manusia menjadi robot, dan robot menjadi guru.
Pada suatu hari, datanglah sekelompok orang dari kota, lengkap dengan seragam dan kamera. Mereka datang dalam rangka program “Menyapa Anak Bangsa di Pelosok Negeri”, bagian dari upaya untuk menaikkan citra kementerian yang baru saja tercoreng karena kasus korupsi pengadaan buku digital.
“Kami datang membawa cahaya peradaban,” kata salah satu pejabat yang berjubah safari, mengibaskan debu dari sepatu kulitnya.
Mereka mendirikan tenda, memasang spanduk, dan menyuruh Sema duduk di bangku plastik sambil memegang buku yang bahkan belum dibuka segelnya.
“Mari kita ajarkan dia membaca! Menulis! Menghitung!” seru salah satu ibu pejabat yang lebih sibuk mengatur filter Instagram-nya daripada membuka halaman buku.
“Tunggu dulu,” kata Sema, yang selama ini diam. “Apakah aku harus belajar menulis sebelum aku tahu apa yang perlu kutulis?”
Pejabat itu tertegun. Ia tidak dilatih menjawab pertanyaan yang tidak ada di modul.
“Apakah aku harus membaca buku yang kalian bawa sebelum kalian membaca diriku?”
Seorang relawan LSM nyaris tersedak air mineral kemasan.
“Aku tidak tahu angka, tapi aku tahu kalau panen makin susah karena hutan di utara dibabat untuk tambang emas. Apakah sekolah bisa mengajari aku menanam pohon yang ditebang orang-orang kota?”
Pejabat itu menoleh ke staf humas.
“Apakah menulis puisi tentang cinta tanah air lebih penting daripada merasakan luka tanah itu sendiri?”
Mereka pulang sore itu juga. Laporan kegiatan tetap dikirim ke pusat. Foto Sema memegang buku—meski segelnya belum dibuka—tetap dijadikan sampul laporan bulanan: “Pendidikan Menjangkau yang Terjauh.”
Kisah Sema menyebar seperti kabar duka yang enggan dikubur. Wartawan datang. Videografer datang. Influencer pendidikan datang.
Sema menjadi bahan berita, bukan subjek cerita. Ia diwawancarai tentang kehidupan tanpa sekolah, lalu dibingkai sebagai simbol perjuangan pendidikan—padahal ia tidak sedang berjuang, ia hanya hidup.
Salah satu media menulis: “Anak Alam Ini Butuh Sekolah.” Padahal yang Sema butuhkan adalah tanah yang tak digusur dan sungai yang tak diracuni.
“Apa gunanya sekolah,” gumam Sema, “jika hanya mengajari kita cara menjawab soal, bukan soal hidup?”
Negeri itu sedang demam ujian. Semua anak dicekoki dengan latihan soal. Bahkan anak-anak taman kanak-kanak sudah diajari cara mencongak. Hafalan dijadikan ukuran kecerdasan, bukan pemahaman. Anak-anak pintar menghapal pasal, tapi buta terhadap rasa.
Pendidikan berubah jadi proyek. Kurikulum silih berganti seperti musim, tapi tanah tetap tak pernah ditanyai. Sekolah menjadi tempat mendiamkan anak-anak agar tidak membahayakan stabilitas nasional. Tak ada ruang bertanya, karena pertanyaan dianggap gangguan. Tak ada ruang menolak, karena kritik dianggap makar.
“Negara ini takut pada anak-anak yang berpikir,” kata Mbah Waris pada Sema, “karena anak-anak yang berpikir akan menuntut jawaban.”
Pada hari kemerdekaan, pemerintah mengundang Sema ke ibu kota. Ia diminta berdiri di podium, memakai seragam putih-merah, dan membaca naskah pidato yang sudah disiapkan biro humas.
“Ucapkan terima kasih pada negara yang telah peduli padamu,” bisik salah satu panitia di belakang panggung.
Sema naik ke podium, memandangi para pejabat, para wartawan, dan deretan mikrofon yang tak menampung suara, hanya gema pencitraan.
Lalu ia buka naskah itu, dan membakarnya di depan umum.
“Aku tidak akan membaca kata-kata yang bukan milikku,” katanya. “Aku bukan hasil program. Aku bukan hasil proyek. Aku bukan produk statistik. Aku manusia.”
Ruangan hening. Kamera tetap menyala. Tapi siaran langsung dipotong iklan deterjen.
Setelah hari itu, Sema kembali ke lembahnya. Ia tetap tidak punya ijazah, tetap tidak tahu nama menteri pendidikan yang baru, dan tetap tidak tahu cara mengisi formulir bantuan sosial.
Tapi ia tahu bahwa pendidikan bukan soal bangku dan papan tulis. Ia tahu bahwa anak-anak tidak butuh dicekoki, tapi diajak bicara. Ia tahu bahwa ilmu bukan warisan buku, tapi pengalaman yang terus tumbuh. Ia tahu bahwa menjadi besar bukan berarti harus tinggal di kota.
Lembah Bisu tetap sunyi. Tapi Sema tidak lagi sendiri. Anak-anak dari desa sekitar mulai datang, duduk bersamanya di bawah pohon, mendengar cerita angin, belajar membaca rasi bintang, memahami akar sebagai kehidupan. Mereka belajar mencintai bumi sebelum diajari soal kapital.
Dan para pejabat yang dulu datang, kini hanya menonton dari layar televisi. Mereka menyebut tempat itu: “Sekolah Alternatif Berbasis Alam.” Mereka ingin menjadikannya pilot project. Mereka ingin membuat aplikasinya. Mereka ingin menstandarkan kebebasan.
Tapi Sema hanya tertawa. Karena kebebasan yang distandarkan, adalah penjara yang tersamar.
“Aku tidak ingin menjadi besar karena kalian membesarkan,” katanya, “aku ingin menjadi besar karena aku tumbuh.”
Lembah Bisu tidak ada di peta. Tapi kita semua pernah lewat sana. Kita pernah duduk di bangku yang tidak bertanya siapa kita. Kita pernah belajar untuk lulus, bukan untuk mengerti. Dan mungkin, seperti Sema, kita sedang belajar menjadi besar—bukan karena sekolah menginginkannya, tapi karena alam memanggilnya.
Penulis: Farhan Azizi