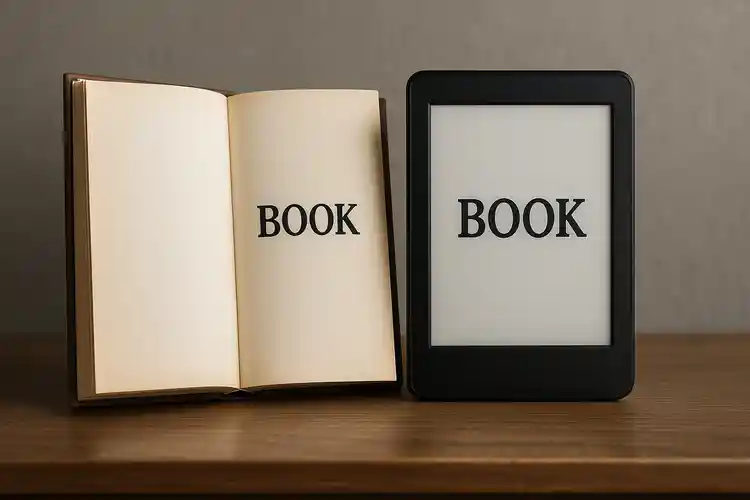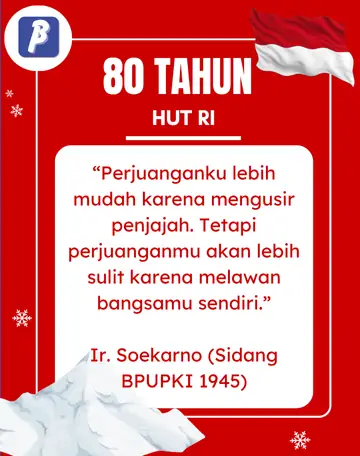Koperasi Merah Putih: Mimpi Kolektif di Tengah Pasar yang Rakus

Di tengah hiruk-pikuk pasar bebas, ketika segala sesuatu diukur dengan laba dan rugi, masih adakah ruang bagi sebuah gagasan yang lahir dari semangat gotong royong? Di antara mall-mall megah dan startup yang membakar uang investor untuk membeli loyalitas konsumen, koperasi kerap tampak seperti peninggalan masa lalu yang ketinggalan zaman. Namun, justru dalam absurditas zaman inilah koperasi menemukan relevansinya kembali—terutama ketika ia mengenakan nama yang begitu sarat makna: Koperasi Merah Putih.
Nama itu saja sudah menjadi semacam proklamasi terselubung. Ia bukan sekadar koperasi, tetapi koperasi yang hendak memanggil kembali semangat merah dan putih dalam kehidupan ekonomi bangsa—warna yang bukan hanya simbol bendera, tapi juga simbol luka dan harapan. Merah: darah yang pernah tumpah untuk kemerdekaan. Putih: niat tulus untuk hidup bersama sebagai bangsa.
Koperasi Merah Putih bukan lahir dari kekosongan, melainkan dari kegelisahan. Sebuah kegelisahan melihat bagaimana ekonomi Indonesia makin lama makin dimonopoli oleh segelintir pihak—baik lokal maupun global—yang tidak memiliki ikatan emosional maupun ideologis terhadap nasib rakyat kecil. Mereka yang hidup dari hasil bumi sendiri justru menjadi penonton dalam pesta yang digelar atas nama pertumbuhan. Petani tidak punya kuasa atas harga beras. Nelayan tak tahu ke mana ikan-ikan akan dijual. Buruh selalu bisa diganti oleh mesin atau buruh lain yang lebih murah. Dalam kondisi seperti itu, koperasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi keniscayaan.
Namun, koperasi yang dibayangkan dalam “Koperasi Merah Putih” bukan koperasi yang sekadar formalitas demi pinjaman ringan atau bagi hasil tahunan. Ia adalah koperasi sebagai gerakan, sebagai alat perlawanan terhadap ketimpangan sistemik. Ia bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan. Bayangkan, misalnya, sebuah koperasi yang dimiliki oleh petani kopi dari berbagai daerah, yang kemudian membentuk jaringan distribusi sendiri, membuka kedai sendiri, bahkan membentuk lembaga keuangan sendiri. Mereka bukan lagi sekadar produsen yang menunggu belas kasihan tengkulak, tapi pelaku aktif dalam rantai nilai, dari hulu sampai hilir.
Tapi tentu saja, membangun Koperasi Merah Putih bukan pekerjaan ringan. Ada tembok-tembok ideologis yang harus dihancurkan terlebih dahulu. Di benak banyak orang Indonesia, koperasi seringkali diasosiasikan dengan “koperasi sekolah” atau “koperasi pegawai” yang tak lebih dari toko kecil dengan harga yang tak terlalu bersaing. Atau bahkan, koperasi yang dimanipulasi oleh segelintir elite lokal demi kepentingan pribadi. Karena itu, menghidupkan kembali koperasi harus dimulai dari kerja ideologis: membongkar citra lama, dan menanamkan makna baru.
Koperasi Merah Putih harus dibayangkan ulang bukan sebagai entitas yang melayani, melainkan yang memberdayakan. Ia tak bisa berdiri sendiri tanpa pendidikan politik ekonomi bagi para anggotanya. Dalam koperasi semacam ini, setiap anggota adalah pemilik sekaligus pembuat keputusan. Transparansi dan partisipasi bukan jargon, tapi syarat mutlak. Dan justru karena itulah koperasi menjadi ruang yang sangat politis, dalam arti yang paling substantif: ruang untuk mengatur hidup bersama berdasarkan kesadaran kolektif.
Di tengah era platform digital, koperasi pun harus bertransformasi. Bayangkan jika Koperasi Merah Putih memiliki aplikasi sendiri—bukan untuk memesan ojek atau makanan, tapi untuk memesan masa depan. Aplikasi yang memungkinkan konsumen membeli langsung dari produsen tanpa perantara rakus. Aplikasi yang memungkinkan buruh membentuk koperasi pekerja dan menjual jasa mereka dengan harga yang mereka tetapkan sendiri. Di sinilah teknologi bukan alat eksploitasi, tapi medium emansipasi.
Namun, teknologi saja tidak cukup. Dibutuhkan ketekunan, kesabaran, dan militansi ideologis untuk membangun koperasi yang tahan banting. Dan lebih dari itu, diperlukan rasa cinta tanah air yang otentik. Bukan nasionalisme kosong yang hanya berkibar di momen seremoni, tapi nasionalisme yang berakar pada keinginan untuk melihat anak bangsa hidup bermartabat melalui ekonomi yang adil.
Di sinilah letak harapan Koperasi Merah Putih. Ia bukan sekadar unit bisnis, tapi ruang hidup. Ia bukan sekadar strategi ekonomi, tapi strategi kebudayaan. Koperasi semacam ini bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap individualisme ekstrem dan ketamakan kapitalisme yang menyamar dalam jargon efisiensi. Dalam koperasi, keuntungan bukan hanya diukur dari angka, tapi dari relasi sosial yang tumbuh, dari martabat yang dipulihkan, dari rasa memiliki yang tak bisa dibeli.
Jika koperasi adalah bentuk paling konkret dari semangat gotong royong, maka Koperasi Merah Putih adalah mimpi kolektif untuk membuat gotong royong menjadi relevan kembali. Di tengah dunia yang terus terpecah oleh algoritma, segregasi ekonomi, dan jurang sosial, koperasi menjadi tali pengikat yang tidak hanya menyatukan, tapi juga membebaskan.
Mungkin benar bahwa membangun Koperasi Merah Putih adalah jalan yang sunyi. Tapi jalan sunyi itulah yang pernah ditempuh para pendiri bangsa saat mereka bermimpi tentang republik. Sekarang, giliran kita menempuh jalan itu kembali—bukan dengan senjata, tapi dengan solidaritas. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keberanian untuk percaya pada kekuatan bersama. Koperasi Merah Putih adalah undangan terbuka untuk itu.