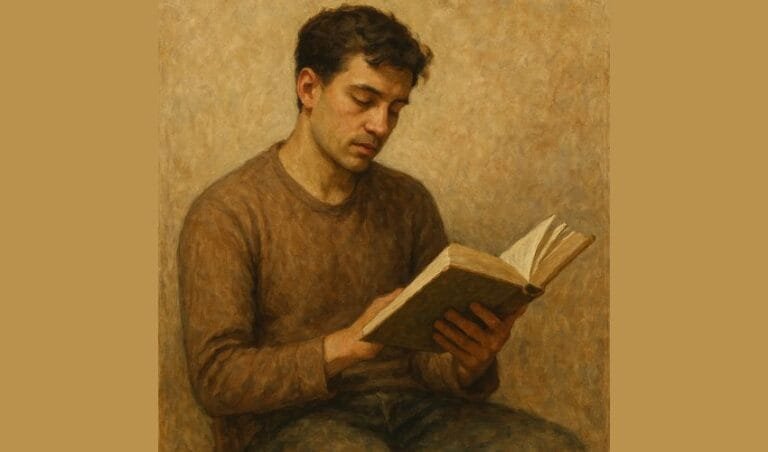Tren Kita Hari Ini: Antara Cuan, Cicilan, dan Cuan Lagi
Di negeri yang katanya “gemah ripah loh jinawi”, hidup ternyata tidak seindah feed Instagram selebgram skincare. Hari ini, tren di Indonesia sudah bukan lagi soal “apa yang penting” tapi “apa yang bisa viral”. Semua orang seolah sedang berlomba-lomba bukan untuk menjadi baik, tapi untuk menjadi terkenal. Viral jadi komoditas, cuan jadi tujuan, dan cicilan jadi gaya hidup.
Mari kita mulai dari tren paling mendasar: cuan. Anak muda zaman sekarang tidak lagi bermimpi jadi pahlawan, dokter, atau astronot. Mereka lebih realistis: jadi affiliate marketer, dropshipper, atau konten kreator. Semua kerja keras sekarang dikemas dalam kata “soft selling”, dan motivasi hidup berubah dari “ingin berguna bagi bangsa” menjadi “biar bisa beli iPhone 15 Pro Max yang warnanya titanium itu”. Semua demi cuan.
Tapi, cuan bukan datang dari langit. Ia datang dari algoritma. Dan algoritma itu tidak mengenal etika. Maka tren kita pun berubah menjadi upaya maksimal untuk menjilat algoritma. Bukan lagi soal konten bermanfaat, tapi konten yang bisa nendang—nendang ke muka orang-orang yang suka julid. Maka muncullah video 1 menit yang membahas sejarah dunia, dengan musik techno remix dan suara robotik dari aplikasi gratisan. Ilmu sejarah jadi setara dengan TikTok dance. Satu tarikan nafas antara fakta dan fiksi, antara kebenaran dan konten.
Kemudian muncul tren lain yang lebih filosofis: cicilan. Hari ini, orang tidak membeli barang karena mampu. Mereka membelinya karena tersedia di marketplace dengan cicilan 0% dan voucher cashback 20 ribu. Semua orang jadi punya kulkas dua pintu, bukan karena perlu, tapi karena bisa dicicil. Dulu ada pepatah “besar pasak daripada tiang”. Sekarang lebih cocok “besar cicilan daripada gaji”. Tapi itu tidak masalah. Yang penting, hidup harus estetik.
Tren selanjutnya adalah gaya hidup healing. Setelah seminggu bekerja sambil digas bos dan deadline tak kenal ampun, weekend harus healing. Tempat healing sekarang bukan lagi puncak atau pantai, tapi café estetik dengan harga kopi dua kali harga nasi padang. Di sana orang-orang duduk, memotret latte, lalu mengetik caption: “Self love is the best love.” Padahal, isi rekening tinggal 42 ribu dan belum isi saldo e-money buat bayar tol pulang. Tapi itu tidak penting. Yang penting: aesthetic dan inner peace.
Dalam dunia kerja, tren juga mengalami mutasi. Dulu kita disuruh kerja keras, sekarang disuruh kerja cerdas. Tapi dalam praktiknya, semua orang tetap kerja keras sambil pura-pura terlihat cerdas. Meeting lewat Zoom dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, sambil terus berkata, “Kita perlu agility dan inovasi, guys!” Tapi ujungnya tetap: kirim revisi malam ini juga. Tidak ada yang berubah kecuali bahasa dan font-nya.
Sementara itu, di dunia pendidikan, tren berubah dari “belajar untuk mengerti” menjadi “belajar untuk lulus”. Dan sekarang, dengan bantuan AI dan GPT, semua tugas bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 10 menit, tanpa harus membaca sama sekali. Mahasiswa hari ini lebih fasih mengetik prompt daripada menulis esai. Kampus pun mulai kelabakan: bagaimana caranya mengembalikan semangat literasi jika semua literasi bisa diketik dan dijawab dalam hitungan detik? Tapi tenang, solusinya akan dimatangkan dalam rapat koordinasi yang berlangsung tiga hari di hotel bintang empat dengan nasi kotak dan sesi foto bareng.
Lalu, ada juga tren “menjadi aktivis dadakan”. Hari ini, menjadi peduli itu mudah. Tinggal ganti foto profil jadi bendera Palestina, tulis caption panjang tentang kemanusiaan, dan posting di story tentang donasi online. Tidak perlu terjun langsung ke jalan, cukup terjun ke kolom komentar. Tidak perlu turun ke lapangan, cukup turun ke Twitter. Aktivisme jadi selebrasi estetika dan engagement. Yang penting terlihat peduli, urusan konsistensi bisa nanti.
Tren yang tak kalah membingungkan adalah dunia percintaan. Hari ini, pacaran bukan soal sayang-sayangan, tapi soal konten. Tiap hari harus bikin vlog bareng, review tempat makan berdua, dan posting video lucu pasangan. Kalau tidak ada konten, rasanya hubungan itu tidak sah. Bahkan, kalau putus pun harus ada kontennya. Video breakup sambil nangis dan background lagu galau jadi satu paket promosi diri: “Aku terluka tapi tetap estetik.”
Tren politik juga tidak ketinggalan. Sekarang, siapa pun bisa jadi analis politik asal punya akun X dan bisa membuat utas panjang yang dikutip media. Semua orang mendadak paham geopolitik, isu pemilu, dan rekam jejak kandidat. Tapi semua itu berubah jadi ajang saling sindir dan saling lapor. Politik berubah dari urusan ide dan solusi menjadi kompetisi siapa yang bisa memaki lebih banyak dan mendapat likes lebih banyak. Dan politisi kita, dengan lihai, ikut menari di atas panggung tren. Mereka ikut joget di TikTok, menyapa Gen Z dengan “sobat misqueen” dan “kita gaskeun ekonomi digital!”. Tak penting apakah mereka paham isinya, yang penting reach.
Sementara itu, tren fashion makin hari makin absurd. Celana gombrong, baju penuh coretan, dan topi yang terlalu kecil untuk kepala jadi bagian dari gaya “streetwear”. Dulu orang tua kita menyuruh berpakaian rapi agar terlihat sopan, sekarang anak muda berpakaian compang-camping agar terlihat kaya. Di balik kaos robek seharga satu juta, ada filosofi yang katanya anti-mainstream, padahal semua orang memakai yang sama. Anti-mainstream jadi mainstream yang baru.
Di sisi lain, tren kuliner tak pernah kehilangan momentumnya. Dari kopi susu gula aren, es boba, croffle, martabak telur asin, sampai ramen pedas level 10, semuanya datang silih berganti. Tapi ada satu pola yang sama: tren makanan di Indonesia harus pedas, manis, dan bisa di-review. Semua makanan harus bisa masuk kamera, diangkat dengan garpu, diberi suara “kresss”, dan diakhiri dengan ekspresi “hmmm, enak banget guys!”. Walaupun perut menolak, yang penting konten jalan terus.
Tren-tren ini, suka tidak suka, mencerminkan siapa kita hari ini. Kita hidup dalam zaman kecepatan. Zaman ketika kesabaran adalah kelemahan, dan perhatian hanya berlangsung 15 detik. Kita tidak lagi membaca berita, kita scroll. Kita tidak lagi berdiskusi, kita reply. Kita tidak lagi menyimak, kita hanya skip. Dalam pusaran seperti ini, tren bukan lagi soal arah, tapi soal irama. Siapa yang bisa ikut joget, dia yang menang.
Namun di tengah semua itu, kadang-kadang kita juga berhenti sejenak dan bertanya: untuk apa semua ini? Apakah tren membuat kita lebih bahagia? Atau kita hanya lelah tapi tidak bisa berhenti? Barangkali kita memang sedang menjalani hidup seperti menonton TikTok: tanpa arah, tapi terus scroll sampai baterai habis.
Dan seperti halnya semua tren, semua ini juga akan berlalu. Esok akan datang tren baru: mungkin soal AI, mungkin soal spiritualitas digital, mungkin tentang jadi digital nomad di Ubud sambil kerja dari co-working space. Kita akan terus beradaptasi. Kita akan terus mencari “yang terbaru” agar tidak ketinggalan. Sebab hari ini, ketinggalan tren adalah bentuk kemiskinan yang tak termaafkan.
Di akhir hari, mungkin yang paling penting bukan mengikuti tren, tapi menyadari bahwa hidup bukan lomba algoritma. Kadang kita butuh diam, secangkir teh hangat, dan waktu untuk benar-benar berpikir: siapa sebenarnya kita, di balik semua tren yang datang dan pergi?
Tapi ya itu tadi, berpikir tidak masuk tren. Jadi ya sudahlah, kita kembali scroll, cari diskon, dan siap-siap bikin konten lagi. Yang penting: hidup harus viral.