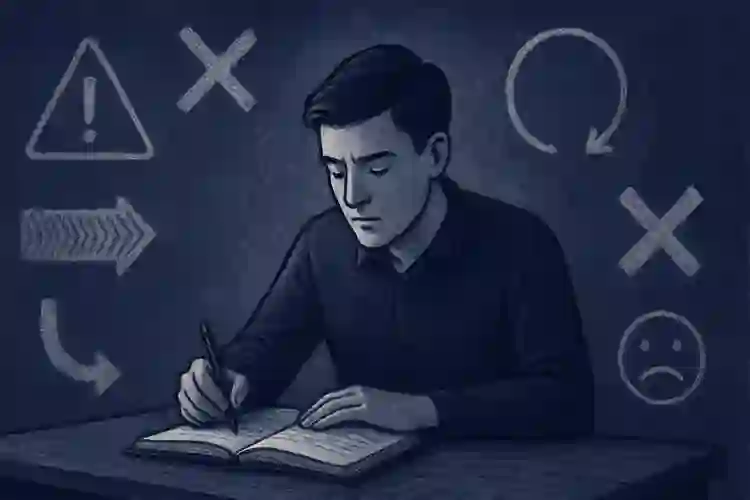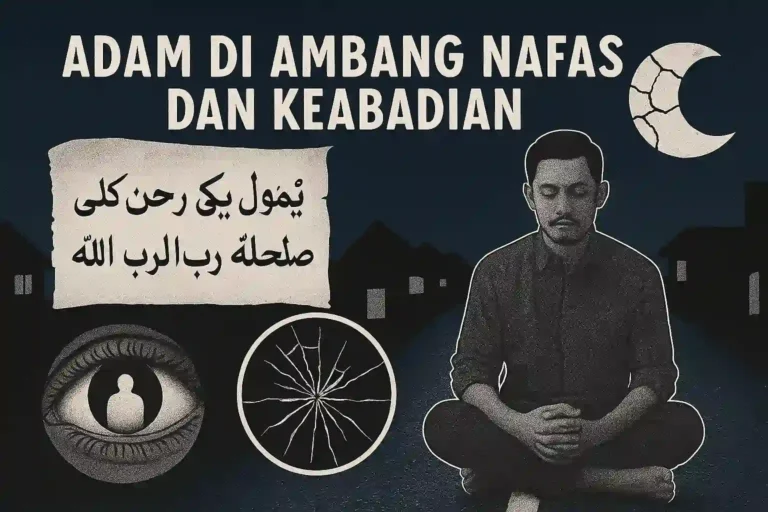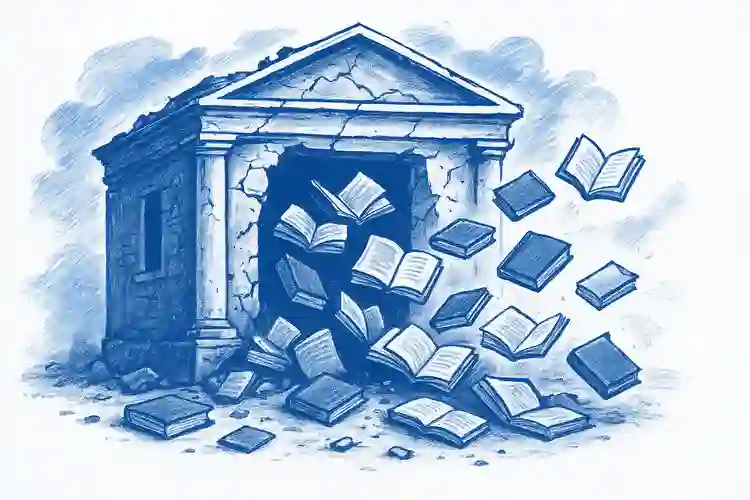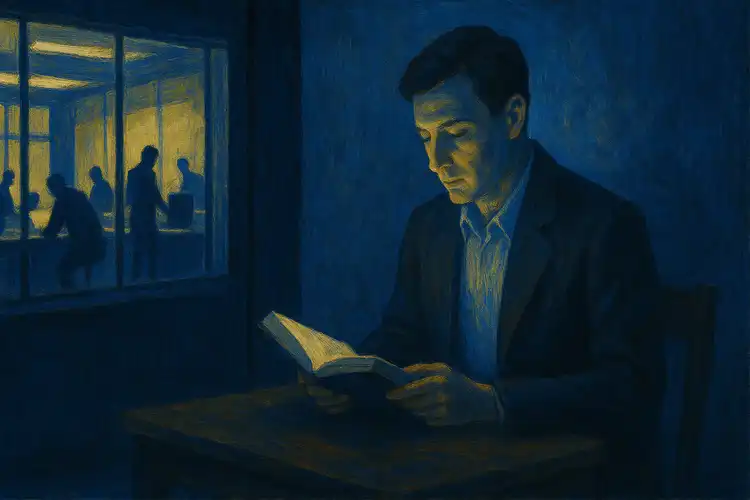Feodalisme di Pesantren: Antara Barokah dan Budak Sistem
“Feodalisme di pesantren adalah realitas yang kompleks. Ia tidak sepenuhnya buruk, juga tidak sepenuhnya mulia. Di satu sisi, ia menjaga struktur, kedisiplinan, dan kesinambungan tradisi. Di sisi lain, ia bisa menjadi jebakan yang mengkerdilkan manusia dan mematikan keberanian untuk bertanya.”

Pesantren adalah tempat di mana para santri hidup berdampingan dalam sebuah ekosistem sosial keagamaan yang memiliki hukum, ritme, dan kosmologi sendiri. Siapa yang masuk ke tempat itu harus siap menjalani hidup dalam sistem yang bukan sekadar tempat belajar agama, melainkan juga ruang reproduksi tatanan kuasa yang tak kasatmata. Di antara tatanan itu, feodalisme menjadi semacam ruh yang tidak diakui secara formal, tetapi hidup dalam perilaku sehari-hari.
Tunduk adalah nilai pertama yang diajarkan. Seorang santri tidak hanya diajari cara membaca kitab kuning, tetapi juga bagaimana menundukkan punggung dan hati saat bersalaman. Santri tidak hanya diminta menghafal ayat atau matan, tetapi juga bagaimana mencium tangan dengan penuh takzim dan tidak menatap mata guru terlalu lama. Ada semacam kesepakatan diam-diam bahwa kebenaran turun dari atas ke bawah—dari kiai ke ustaz, dari ustaz ke santri senior, dari senior ke junior.
Relasi ini bukan sekadar hormat. Ia adalah kepasrahan yang dibalut narasi spiritual. Dalam kerangka pesantren, apa yang oleh sebagian orang disebut feodalisme, dianggap sebagai jalan menuju barokah. Logika yang hidup bukan logika dialektika, melainkan logika tunduk dan patuh. Jika guru berkata puasa hari Senin, maka tidak penting apakah bulan itu ada dua Senin. Yang penting, santri ikut. Kalau guru tidak memberi izin pulang meski orang tua sedang sakit, santri diajari menahan rasa: “Barangkali ini ujian untuk naik derajat.”
Feodalisme di pesantren berjalan halus, seperti embun di pagi hari. Ia tidak memaksa, tapi melekat. Tidak menghardik, tapi menyusup lewat doa-doa dan kisah-kisah. Banyak cerita heroik tentang santri yang patuh lalu jadi orang besar. Banyak kisah tentang orang durhaka pada guru yang hidupnya hancur. Semua itu membentuk lapisan kepercayaan bahwa tunduk adalah awal dari kemenangan spiritual.
Sistem ini dianggap efektif. Dalam pesantren yang besar, struktur komando harus kuat. Kiai adalah pusat semesta. Ia bukan sekadar guru, tetapi juga pemimpin, penentu keputusan, dan penjaga moral. Dalam banyak kasus, satu kata dari kiai bisa menghentikan keributan, membatalkan rencana, bahkan mengubah sikap kolektif santri. Para pengagum sistem ini percaya bahwa feodalisme justru menjaga tradisi tetap hidup. Tanpa struktur seperti ini, pesantren akan porak-poranda oleh ego santri modern yang sok kritis.
Para pembela sistem ini pun sering membandingkannya dengan dunia pendidikan formal yang katanya terlalu liberal. “Di luar sana, murid bisa mendebat guru, orang tua bisa menggugat sekolah. Apa hasilnya? Anak-anak kehilangan adab,” begitu argumen yang kerap terdengar. Di pesantren, adab adalah harga mati. Ilmu bisa dicari belakangan, tapi kalau tidak punya adab, maka akan tersesat bahkan sebelum sampai halaman depan kitab.
Di luar aspek spiritual, ada pula faktor sosial dan ekonomi yang membuat feodalisme tetap lestari. Banyak pesantren hidup dari jejaring alumni yang merasa berkewajiban memberi bantuan, baik dalam bentuk uang, proyek, atau dukungan politik. Kedekatan dengan kiai menjadi semacam “saham sosial”. Alumni berlomba membangun relasi dengan pusat otoritas karena itu akan berdampak pada status sosial di kampung halaman. Feodalisme, dalam hal ini, tidak lagi sekadar soal barokah, tapi juga kapital simbolik.
Namun di balik semua kelebihan yang didengungkan itu, ada pula suara-suara lain yang perlahan mulai muncul—meski kadang masih dibisikkan di bawah bantal atau ditulis di catatan harian yang disembunyikan di bawah ranjang besi.
Ketika Hormat Menjadi Ketakutan dan Kritik Menjadi Dosa
Ada saat-saat di mana santri tak lagi bisa membedakan antara adab dan ketakutan. Mereka takut bertanya karena takut dianggap lancang. Mereka takut berpikir berbeda karena takut dicap tidak mendapat barokah. Dalam situasi seperti ini, feodalisme menjelma menjadi alat penjinak akal sehat.
Jika santri hanya diajari untuk tunduk tanpa bertanya, bagaimana mungkin pesantren melahirkan pemikir besar? Jika setiap perbedaan dianggap pembangkangan, lalu untuk siapa sebenarnya pesantren berdiri?
Kritik terhadap feodalisme di pesantren bukan berarti menolak penghormatan kepada guru. Justru sebaliknya, kritik itu lahir karena penghormatan terlalu suci untuk dijadikan alat manipulasi. Banyak yang mulai melihat bahwa struktur hierarkis yang terlalu kaku membuat santri tidak tumbuh menjadi manusia merdeka, melainkan menjadi pengikut pasif yang takut salah langkah. Dalam dunia pendidikan, ini adalah bahaya besar.
Ketika santri dilarang bertanya “kenapa”, maka pesantren bukan lagi tempat belajar, melainkan tempat indoktrinasi. Ketika keputusan kiai dianggap selalu benar tanpa ruang diskusi, maka pesantren kehilangan fungsi kritisnya. Feodalisme yang dijustifikasi dengan alasan adab dan barokah bisa berubah menjadi kekerasan simbolik yang menggerogoti jiwa para pencari ilmu.
Apalagi, tidak semua kiai memiliki kualitas moral atau intelektual yang tinggi. Dalam sistem yang feodal, otoritas tidak bisa dikritik, bahkan ketika ia keliru. Ini berbahaya. Ketika manusia diberi kuasa absolut tanpa pengawasan, sejarah sudah berkali-kali membuktikan, yang lahir bukan kebijaksanaan, tapi penyimpangan. Bahkan dalam konteks pesantren pun, beberapa kasus pelecehan, manipulasi keuangan, atau kekerasan psikis tak lepas dari sistem yang tidak memungkinkan santri untuk bersuara.
Ada juga dampak sosial yang tak kalah penting: ketimpangan kelas. Santri senior dipandang lebih tinggi dari junior. Santri yang dekat dengan kiai mendapat akses istimewa. Mereka bisa makan lebih enak, tidur lebih nyaman, bahkan mendapat peran penting dalam organisasi internal. Yang lain? Harus pasrah dengan kasur tipis dan jadwal piket kamar mandi. Dalam struktur seperti ini, pesantren bukan rumah ilmu, melainkan semacam miniatur kerajaan.
Namun suara-suara ini tidak serta-merta bisa menggoyang tatanan yang sudah mapan. Setiap kali ada yang menyuarakan kritik, jawaban yang muncul seringkali bernada spiritual: “Kalau kamu tidak ikhlas mondok, ya jangan harap ilmunya manfaat.” Kritik dilawan dengan retorika keikhlasan. Diskusi dianggap hilangnya adab. Ini adalah jebakan retoris yang membuat siapapun yang berpikir kritis langsung terpojok.
Ironisnya, sebagian pesantren yang menolak feodalisme secara lisan, justru memperkuatnya dalam praktik. Kiai yang menyebut dirinya “demokratis” tetap memilih menegur santri secara searah. Ustaz yang katanya terbuka pada kritik tetap menyebar kisah-kisah mistik tentang santri yang berani bertanya lalu hidupnya hancur. Feodalisme, dalam hal ini, bukan hanya struktur, tetapi mentalitas.
Kritik terhadap feodalisme di pesantren seharusnya tidak dipahami sebagai penghinaan terhadap tradisi. Justru sebaliknya, ini adalah bagian dari upaya menjaga pesantren tetap relevan dengan zaman. Pesantren yang sehat adalah yang mampu membedakan antara adab dan ketundukan, antara penghormatan dan ketakutan, antara cinta pada ilmu dan kepasrahan tanpa nalar.
Menghormati guru adalah prinsip mulia. Tapi menghormati guru bukan berarti mematikan akal. Tradisi yang hidup adalah tradisi yang mau membuka ruang dialog. Kiai bukan dewa. Santri bukan budak. Ilmu bukan hasil dari tunduk buta, tapi dari proses panjang berpikir, mempertanyakan, dan mencari kebenaran bersama.
Feodalisme di pesantren adalah realitas yang kompleks. Ia tidak sepenuhnya buruk, juga tidak sepenuhnya mulia. Di satu sisi, ia menjaga struktur, kedisiplinan, dan kesinambungan tradisi. Di sisi lain, ia bisa menjadi jebakan yang mengkerdilkan manusia dan mematikan keberanian untuk bertanya. Jalan tengahnya bukan menghancurkan, tapi mereformasi. Bukan menggugat untuk menghina, tapi menggugat untuk menjaga nyala ilmu tetap hidup.
Pesantren perlu terus menjadi taman ilmu yang menghargai guru, tapi juga memanusiakan santri. Karena pada akhirnya, barokah itu bukan milik mereka yang patuh tanpa berpikir, tapi milik mereka yang berjalan dalam cinta, nalar, dan kesadaran.