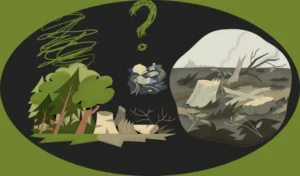Indonesia di Simpang Jalan

(unsplash.com/@fuzlan)
Gelombang protes #IndonesiaGelap ternyata bukan sekadar seruan simbolik; ini adalah refleksi krisis demokrasi dan makin melemahnya kepercayaan publik terhadap keberpihakan pemerintah. Sepanjang Februari 2025, aksi yang dimotori BEM SI ini menyentuh lebih dari 20 kota besar—Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, bahkan Aceh dan Bali—dengan total massa protes fase pertama mencapai hampir 10.000 orang, serta menimbulkan korban: setidaknya 48 terluka, 161 ditangkap, dan ribuan lainnya terdampak—termasuk 18 jurnalis dan 3 petugas medis. Aksi ini memperlihatkan retakan legitimasi demokrasi yang cukup dalam.
Rangkaian 13 tuntutan yang dipampang mahasiswa bukan retorika kosong. Mereka menuntut pencabutan Inpres No. 1/2025 — instrumen efisiensi anggaran APBN/ APBD yang justru memotong belanja penting seperti pendidikan dan kesehatan—serta menolak revisi UU TNI dan UU Minerba yang berpotensi menutup ruang kritik akademik. Dalam puncaknya pada 20 Februari, demonstran menekankan penolakan terhadap multifungsi TNI, pemberantasan mafia tanah, dan ancaman impunitas institusi keamanan .
Langkah pemerintah merespons tuntutan ini sebagian diwarnai retorika represif. Aparat mengepung gedung DPR, menerjunkan ribuan personel keamanan, membubarkan protes dengan water cannon, gas air mata, bahkan beberapa kasus kekerasan fisik dan penangkapan massal. Di saat bersamaan, elit politik seperti Wakil Ketua DPR Adies Kadir mendeskripsikan protes ini sebagai “ciri khas mahasiswa” yang sah secara konstitusi—namun kritik ini justru mengandung kontradiksi jika diimbangi tindakan keamanan yang represif.
Fase kedua yang terjadi di Maret, bernuansa #TolakRUUTNI, menyoroti revisi UU TNI yang memungkinkan militer menduduki posisi sipil hingga 14 persen, mengancam supremasi sipil, dan dikhawatirkan membuka jalan bagi dwifungsi ala Orde Baru. Banyak kampus—termasuk UGM dan Trisakti—bergabung, dengan pola protes simbolik seperti black flag, payung ala Hong Kong, bahkan aksi teatrikal bak ruwatan Jawa di Yogyakarta. Eskalasi ini menunjukkan fragmentasi aspirasi mahasiswa dan warga sipil bahwa demokrasi sedang diuji.
Paralel dengan protes tersebut, fenomena #KaburAjaDulu berkembang sebagai bentuk kepanikan kaum milenial dan Gen Z terhadap masa depan di Indonesia. Tagar ini viral sejak Februari—didorong oleh kegelisahan atas lapangan pekerjaan yang terbatas, pengangguran tinggi (mengacu BPS: ~7,5 juta), biaya hidup tinggi, dan kualitas layanan publik yang rendah. Analisis Indef dan tokoh seperti Irwan Prasetiyo menekankan bahwa gerakan ini adalah cerminan nyata kekhawatiran sistemik, bukan sekadar cita-cita estetis migasi ke luar negeri.
Hashtag ini juga menjadi platform berbagi informasi konkrit: cara melamar kerja luar negeri, tips beasiswa, peluang magang, serta diskusi soal prosedur legalitas emigrasi dan implikasinya terhadap loyalitas nasional. Bahkan sejumlah penulis Kompasiana dan Metrotv menyuarakan bahwa tren ini menggugah FOMO (fear of missing out) serta menuntut pemerintah hadir dengan solusi: reformasi pendidikan tinggi, insentif talenta, dan penciptaan iklim bisnis yang kompetitif.
Data resmi dari BPS dan peringkat Indeks Modal Manusia ASEAN memperlihatkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam dalam indikator kualitas SDM . Potensi “brain drain” ini jika dibiarkan bisa meruntuhkan basis pembangunan jangka panjang: inovasi, penelitian, dan daya saing global melemah.
Pada aspek infrastruktur dan lingkungan, banjir besar Jabodetabek pada awal Juli 2025 memberikan gambaran lain dari krisis tata kelola: meski sudah diperingatkan BMKG, saluran tersumbat dan respons pemerintah daerah lamban menyebabkan isolasi ratusan RT—menandakan bahwa mitigasi bencana masih sebatas reaktif, bukan proaktif. Kasus ini memperparah narasi bahwa aparatur sipil negara tidak siap menghadapi tekanan perubahan iklim secara sistemik.
Jika kita dekati dari perspektif kelembagaan, jelas terlihat ada distorsi fungsi antara pemerintah pusat, daerah, DPR, dan TNI/Polri. Intervensi politik dalam kebijakan ekonomi (efisiensi budget), peradilan (UU Minerba), dan pendidikan (pengurangan anggaran pendidikan) memperlihatkan bahwa elit pemerintahan mengambil keputusan tanpa konsultasi publik. Sehingga wajar jika mahasiswa menuntut pembatalan beberapa instrumen hukum serta perombakan kabinet “Merah Putih”.
Dilema fundamental muncul: apakah pemerintah serius mengangkangi aspirasi rakyat atau menutupinya lewat alibi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan? Investor memang menikmati IPO gemilang (CDIA, COIN, MERI), tetapi narasi ekonomi makro tidak sejalan dengan realitas rakyat—inflasi tinggi, PHK massal, kemiskinan stagna—yang menjadi pemicu utama protes dan exodus bak elit muda.
Sementara elite militer pensiunan pun mulai bersuara: forum purnawirawan TNI menuntut pencopotan wapres Gibran Rakabuming dan perombakan politik militer sipil. Ini menunjukkan ketegangan elit bukan hanya antara pemerintah dan mahasiswa, tetapi juga internal kelompok kekuasaan. Demokrat Kompasianya menganggap hal ini sebagai tanda geopolitik domestik sedang dipengaruhi kekuatan paralel yang sulit direspons rakyat biasa.
Semua peristiwa ini—protes #IndonesiaGelap, penolakan UU TNI, exodus #KaburAjaDulu, krisis iklim, eksodus talenta, dan fragmentasi politik elit—menunjukkan bahwa yang sedang terjadi bukan fenomena insidental. Ini adalah fase kritis reformasi Indonesia: fase redefinisi nilai demokrasi, supremasi sipil, integritas kelembagaan, dan strategi pembangunan berkelanjutan.
Apa yang harus dilakukan, dan oleh siapa?
Meski dapat dibilang utopia, adalah keniscayaan untuk tetap meletakkan harap pada mereka yang menjadi roda penggerak negara ini. Itu sebabnya adalah 6 harapan yang barangkali bisa menjadi pesan dalam tulisan ini.
- Dialog inklusif dan transparan, dimana pemerintah dan DPR membentuk forum konsultasi nasional, melibatkan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan cendekiawan untuk menuntaskan tuntutan 13 poin — evaluasi Inpres, transparansi anggaran, dan revisi nama lainnya.
- Reformasi kelembagaan TNI/Polri melalui pemisahan peran yang jelas, seleksi karier yang berbasis meritokrasi, dan pembatasan intervensi dalam pemerintahan sipil.
- Strategi Pembangunan SDM: kucurkan anggaran penelitian ke perguruan tinggi, perluas program beasiswa riset internasional, dukung wirausaha muda lewat insentif pajak, sekaligus dorong riset wilayah dengan keunggulan lokal (teknologi pangan, energi terbarukan, budaya kreatif).
- Perbaikan infrastruktur adaptif: sinergikan data BMKG‑LPB dengan pemerintah daerah, optimalkan anggaran mitigasi banjir, dan buat sistem respons cepat; jangan jadikan bencana hanya bahan berita sesaat.
- Reformasi birokrasi dan anti‑korupsi: jalankan penerapan e‑budget open data, audit belanja publik, dan tegakkan UU Perampasan Aset. Ini akan memberi tanda percaya kepada masyarakat bahwa elite politik berbicara serius soal keadilan.
- Retensi talenta: buat kebijakan ‘diaspora bonding’ yang memberi insentif pajak, beasiswa lanjut, dan kesempatan penelitian di dalam negeri—mengubah #KaburAjaDulu menjadi #BalikAjaSekarang.
Dengan perbaikan ini, bukan tidak mungkin momentum protes dan eksodus talenta akan berubah menjadi semangat inovasi, demokrasi yang langsung dirasakan, dan pembangunan yang inklusif. Namun kegagalan menjawabnya dengan serius hanya akan memperparah kemandegan demokrasi, krisis SDM, dan konflik sosial yang bersifat laten.
Indonesia di 2025 bukan lagi sekadar negara berkembang. Ia berada di simpang jalan — antara mengukuhkan demokrasi berbasis rakyat atau kembali ke fiksi legitimasi retorik yang hampa makna.