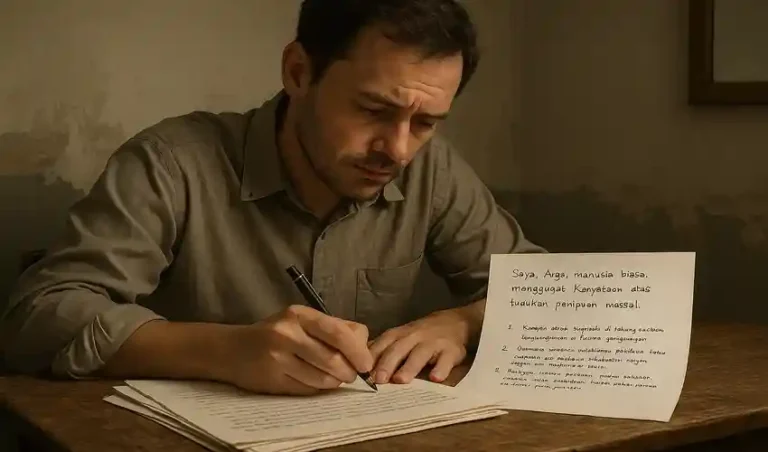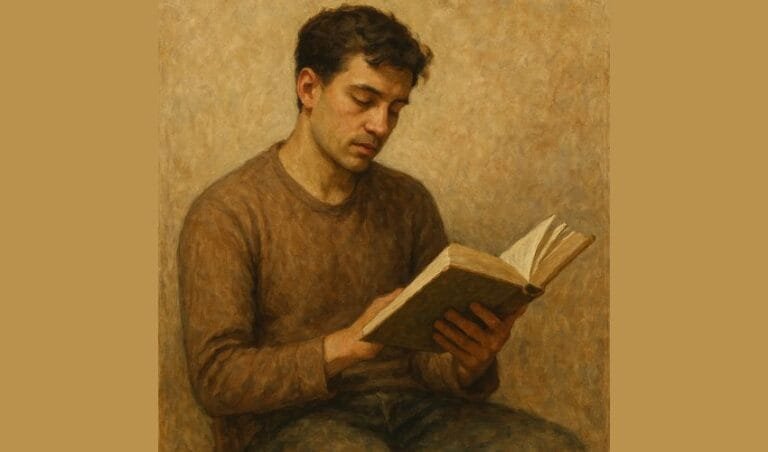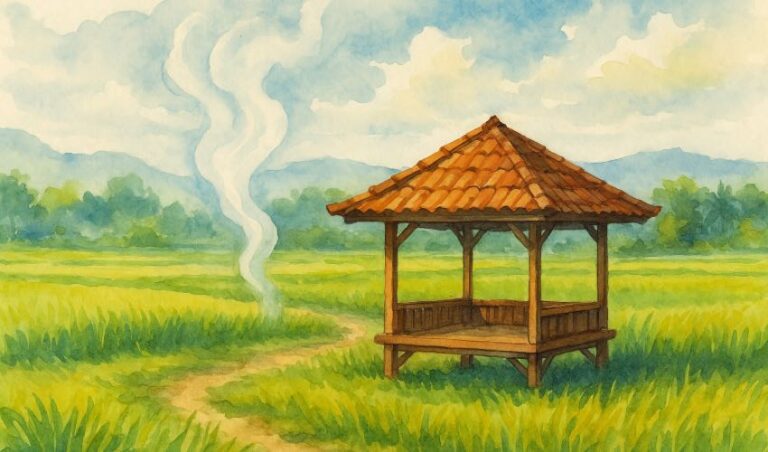Meja Laptop
“Negeri ini terlalu terbiasa duduk di kursi empuk sambil membiarkan meja rakyat bergoyang tak stabil. Tapi setiap kita yang pernah menulis di atas meja ringkih tahu: kebohongan tak akan lama berdiri, jika papan bawahnya sudah retak.”

Aku membeli meja laptop itu pada suatu sore mendung di Pasar Mawar—pasar loak yang baunya seperti ingatan lama bercampur hujan. Penjualnya lelaki separuh baya, rambutnya pirang-berdebu, mengenakan kaus kampanye kusam yang masih memamerkan senyum politisi yang kini mendekam di penjara korupsi. “Meja lipat, Mas,” katanya sembari mengetuk pelat aluminium tipis di atas pangkuannya. “Ringan, praktis, bisa dipakai ngetik sambil tiduran.” Ia tidak tahu, atau mungkin tak peduli, betapa kalimat barusan telah menantang seluruh hidupku yang selama ini terpaku di kursi kantor kementerian, mengetik laporan tanpa makna di bawah lampu neon yang berdesing seperti nyamuk.
Meja itu remeh—hanya kerangka alumunium anodisa dengan engsel plastik dan permukaan kayu lapis berpola karbon palsu—tetapi dalam renggang jarak antara kedua kakinya yang ringkih, aku menangkap sesuatu: kemungkinan tempat baru bagi kata‑kataku yang selama ini terkurung. “Berapa?” tanyaku. “Seratus dua puluh, Mas.” Kujawab dengan menawar setengah, akhirnya sepakat di enam puluh ribu rupiah, lalu pulang mengayuh motor bebek tuaku, meja terikat di jok belakang bergoyang‑goyang seperti sayap patah.
Di kamar kos petak tiga kali empat, aku membuka laptop, meletakkannya di atas meja baru itu, dan mengetik satu kalimat yang sudah lama berputar di kepalaku: “Kita hidup di negeri yang menukar keadilan dengan kuitansi.” Kalimat itu mengejutkanku sendiri, seperti ledakan kecil di lorong sepi. Selama bertahun‑tahun aku mencongkel angka demi angka di laporan realisasi anggaran, tahu betul bagaimana sebuah proyek jembatan bisa menyusut 30 persen panjangnya demi menaikkan 300 persen keuntungan pejabat. Tetapi tak pernah mampu menuliskannya secara terang. Kini, di atas papan kayu palsu, huruf‑huruf itu muncul dan menuntut cerita.
Aku bekerja di Direktorat Fasilitasi Sarana Digital Desa, nama mentereng untuk meja‑meja kusam penuh map cokelat. Setiap awal bulan, atasanku—Pak Drajat—mengirimkan berkas SPJ ke mejaku: lembar‑lembar fotokopi kuitansi pembelian server, router, kabel fiber, dan segala hal yang bahkan tak sempat keluar dari kardusnya sebelum dijual kembali di toko daring. Tugasku sederhana: memeriksa kecocokan nominal, menandatangani, memindai, lalu memasukkannya ke sistem. “Santai saja, Din,” kata Pak Drajat suatu kali. “Kalau semua dicek terlalu cermat, kapan selesainya? Negara kita butuh percepatan.” Ia selalu memakai kata percepatan untuk menamai kemalasan, dan efisiensi untuk menutupi korupsi.
Aku menandatangani karena aku pengecut—atau mungkin karena aku masih membayar cicilan kuliah adik bungsuku dan obat darah tinggi ibu. Tetapi tiap malam, selepas absen daring, aku membuka dokumen pribadi berjudul “Meja Laptop”—sebuah kumpulan catatan tentang bagaimana uang negara menguap lewat lubang‑lubang kecil: honor rapat palsu, perjalanan dinas fiktif, konsultansi rangkap. Aku menulis dengan gaya setengah fiksi, menukar nama dinas menjadi “Kementerian Bayang‑Bayang,” mengganti para pejabat dengan tokoh wayang: Dursasana, Sengkuni, Rahwana. Karena konon, bila kebenaran terlalu telanjang, orang menutup mata; tetapi bila kebenaran menyaru dongeng, ia merasuki darah.
Namun aku sadar, catatan digital itu tak ada gunanya bila hanya tersimpan di hard‑disk. Aku ingin cerita ini keluar, menjerat para pencuri bersafari gelap. Keinginan itu seperti api kecil yang makin membara setiap kali aku melihat berita: Anggaran Bantuan Laptop Desa 5 Triliun Akan Selesaikan Kesenjangan Digital. Aku tahu betul berapa persen dari triliun itu yang sungguh‑sungguh menjadi laptop. Sisanya? Menguap dalam bundaran komisi.
Malam‑malam di kosku makin larut. Pukul satu dini hari, suara hujan menggesek atap seng, dan jari‑jariku menari di atas papan ketik. Meja laptop—rapuh tetapi setia—menahan seluruh beban cerita yang semakin berat. Aku merasa seperti tukang kayu menatah peti mati untuk rahasia pemerintah.
Suatu Selasa, kami kedatangan Inspektorat Jenderal. Mereka akan audit sampel proyek, katanya. Ruang rapat disemprot pengharum ruangan berlebihan, meja diganti taplak baru. Pak Drajat membagi‑bagi amplop cokelat tipis kepada staf. “Bonus lebaran dini,” ujarnya sambil berkedip. Aku membuka amplopku: lima lembar ratusan. Katanya, agar kami “kompak” ketika ditanya auditor.
Di lorong, kutemui Sari, rekan kerjaku yang pandai diam. Sambil melipat amplopnya, ia berbisik, “Din, kalau Inspektorat tanya soal pankalan data, jangan sebut ‘servernya belum sampai’, ya.” Aku mengangguk, tetapi dalam kepalaku muncul kalimat lain: “Kita hidup di negeri yang menukar diam dengan ketenangan palsu.”
Audit berjalan seperti teater: auditor duduk, menulis tiga atau empat catatan, kemudian menerima sajian lemper dan susu kedelai, lalu berlalu dengan cengkeramam jabat tangan lebih erat pada Pak Drajat. Esoknya, di grup kantor, muncul pesan: “Alhamdulillah, clear.”
Aku pulang, hujan deras menampar aspal. Di kos, listrik padam—trafo terendam air. Aku menyalakan lilin, menaruh laptop di meja, dan menulis menggunakan baterai yang menyala seadanya. Aku menulis tentang pertemuan hantu—tentang lembaga audit yang berjalan menembus dinding, memeriksa tanpa menyentuh, menilai tanpa membuka mata. Kata‑kataku meluncur seperti anak panah, tepat menuju sasaran yang tak berwajah.
Tiba‑tiba kusadari sesuatu: meja laptopku bergoyang lebih hebat dari biasanya. Kuteliti: salah satu baut engsel hilang. Sepele, tetapi seperti metafora; bila satu baut kejujuran longgar, seluruh struktur ambruk. Kubiarkan, berpikir akan membelinya besok, tetapi malam itu engsel retak menimbulkan bunyi kresak halus—suara yang sempurna melatarbelakangi kalimat‑kalimatku.
Aku menulis sampai baterai tinggal lima persen. Saat layar meredup, aku menatap meja yang nyaris roboh, lalu bertekad: aku pun akan menjadi engsel yang patah—penyambung yang pecah agar meja panik dan orang menoleh.
Aku mengirim naskah pendekku ke beberapa media maya dengan nama samaran “Nahariah Dini”—menyaru perempuan agar lebih kebal dari serangan personal. Satu situs sastra penerbit independen memuatnya keesokan minggu, judulnya kupersingkat: “Meja Laptop.” Kukirim link ke Sari, tanpa komentar. Lima menit kemudian, ia membalas emoji mata terbelalak.
Dua hari berlalu, artikel itu viral kecil—seribu share di media sosial, dibahas di forum penulis diaspora. Komentarnya beragam: “Ini fiksi? Atau kisah nyata?”; “Kementerian mana nih, mirip banget kasus laptop desa;” hingga, “Penulis berani, salut!” Aku merasa campur: bangga sekaligus takut.
Ketakutanku terbukti. Pada Senin pagi, Pak Drajat memanggilku ke ruangannya. Di depannya terbuka layar tablet, menampilkan tulisanku. “Kamu tau ini?” tanyanya pelan, seolah ayah mendapati anak mencuri kue. Darahku merayap dingin. Ia mengetuk meja kayu jati, kemudian berujar, “Fiksi, ya? Bagus, sangat imajinatif. Tapi kamu mengerti, imajinasi bisa menyesatkan publik.”
Ia lalu mencondong, nada suaranya mendadak lembut seperti sirup di racun tikus. “Kamu kreatif, Din. Aku usul kamu pindah ke Subdit Konten Edukasi Digital. Di sana, kamu bebas menulis modul, membuat cerita positif tentang desa. Kami butuh orang sepertimu.” Tawaran promosi, tapi aku dengar nada ancaman terselubung: Bergabung atau minggir.
Aku tersenyum kaku, berpura: “Terima kasih, Pak. Saya pertimbangkan.” Keluar ruangan, napasku tercekat. Sari menunggu di lorong, matanya khawatir. “Gimana?” Aku tak menjawab, hanya berjalan cepat ke toilet, membasuh muka.
Di cermin, kulihat diriku seperti meja laptop: engsel longgar, tapi belum runtuh. Keberanianku setengah matang—aku kira aku siap, ternyata belum. Tetapi mundur berarti selamanya diam.
Pada malam berikutnya, listrik kembali padam. Di tengah gelap, aku menyalakan lilin dan memperbaiki engsel meja menggunakan paku payung—darurat, tapi cukup kokoh. Lalu kumulai tulisan baru, lebih panjang, lebih tajam. Kali ini kutolak samaran, kutulis dengan inisial asli: A.D. Aku menelusuri dokumen, kontrak, foto gudang kosong tempat “server” seharusnya dikirim. Kukonfirmasi kebocoran lain: di delapan kabupaten, saldo anggaran menguap sebelum proyek dimulai. Kumenyusun semuanya dalam satu narasi: “Negara Tanpa Baut”.
Setelah selesai, aku menahan tombol Enter lama‑lama sebelum akhirnya memutuskan: kuposting di blog pribadi, lalu kubagikan anonim di grup jurnalis investigasi. Aku tahu—sumber dokumen bisa dilacak, tapi kubuat beberapa langkah pengaburan—cukup untuk menunda, meski tak sepenuhnya menghapus jejak. Saat tautan itu mulai beredar, aku merasakan sesuatu berbeda: bukan lagi rasa bangga, tapi ketenangan, seperti saat seseorang akhirnya memutuskan berhenti berbohong pada dirinya sendiri.
Esok paginya, berita pecah. Tajuk utama portal daring nasional menulis: “Data Kebocoran Laptop Desa: Menguap 2,1 Triliun.” Beberapa kanal talkshow membahas, mengundang analis kebijakan. Menteri membuka konferensi pers dadakan, berjanji “evaluasi menyeluruh.” Foto Pak Drajat muncul di feed televisi—dia berdiri di belakang menteri, wajahnya pucat. Aku berada di kantor, menatap layar sambil pura‑pura membuat tabel pivot. Suara detak kompresor AC seperti degup jantung.
Sari mengirim pesan: “Hati-hati.” Kubalas: “Selalu.” Tetapi bagaimana seseorang berhati‑hati di dalam bangunan yang seluruhnya rapuh?
Siang harinya, ruang kantor diselimuti kabut cemas. Pak Drajat tak muncul; kabarnya dipanggil ke Menara Pemerintah. Obrolan bisik‑bisik menyesaki pantry. Aku menunduk, menahan gemetar. Setiap bunyi notifikasi ponsel membuatku refleks menoleh.
Pukul empat, teleponku berdering: nomor tak dikenal. Suara di seberang berat, formal, memperkenalkan diri sebagai penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka mengundangku ke kantor lembaga itu esok pagi sebagai “narasumber klarifikasi.” Sejenak aku berpikir: betapa cepat segalanya bergerak. Aku menjawab singkat: “Baik, Pak.”
Kututup telepon, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kupikir tentang meja laptop itu. Betapa benda remeh di pasar loak menyeretku hingga ke ruang yang memisahkan takut dan keberanian. Seperti senjata berkarat yang tetap bisa menggugurkan tirani.
Sampai sini kuakhiri bagian pertama catatan panjang ini. Di layar, kata‑kata terakhir yang kububuhkan malam itu berbunyi: “Jika kau melihat negara tergeletak tanpa baut, jangan sibuk mengetuk kayu jati; gantilah engsel yang patah meski tanganmu berdarah.”
Penyambung yang Retak
Hari berikutnya, aku berangkat ke kantor Komisi dengan ransel kecil berisi fotokopi dokumen, catatan pribadi, dan satu salinan pendek tulisan “Meja Laptop” yang telah kusebar itu. Sebelum berangkat, aku memandangi meja tempat aku menulis setiap malam. Meja itu nyaris roboh, satu kakinya kuganjal dengan kamus bahasa Sanskerta warisan dosenku dulu—simbol ironis dari negeri yang melupakan warisannya sendiri demi proyek digitalisasi berbau fulus.
Aku duduk di ruang tunggu selama dua jam, ditemani AC yang terlalu dingin dan kopi sachet yang terlalu manis. Akhirnya dipanggil. Di ruangan berukuran kecil, tanpa jendela, aku duduk berhadapan dengan dua penyidik: satu berkacamata bulat, satu lagi lebih muda, wajahnya mirip kasir minimarket. Mereka tak membentak, tak mendesak. Mereka mendengar.
Aku bercerita, pelan-pelan, dari awal: bagaimana kuitansi fiktif bertebaran, bagaimana gudang kosong dilaporkan penuh, bagaimana laptop hanya angka di atas anggaran. Aku tunjukkan bukti-bukti. Mereka menandai. Tak ada dramatisasi seperti di serial televisi. Ini justru lebih sunyi. Sunyi yang terasa menggigil.
Salah satu penyidik akhirnya berkata, “Kami sedang menyusun skema pembuktian. Keterangan Anda akan sangat penting.” Aku mengangguk. Dalam hati, kutanya: akankah kebenaran yang kuutarakan ini punya ujung, atau hanya menjadi berita yang cepat basi di algoritma?
Malamnya aku pulang ke kos. Di meja laptop, kusambungkan kembali kabel charger. Lampu kecil menyala. Aku membuka halaman baru, dan menulis satu kalimat: “Penyambung yang retak tak selalu tanda kehancuran, bisa jadi pintu rahmat.”
Tulisan itu kuberi judul: “Kesaksian Engsel”.
Tangan-Tangan Tak Terlihat
Malam setelah klarifikasi itu, aku bermimpi didatangi seorang lelaki tua dengan kepala terbakar. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya meletakkan sebuah obeng di tanganku, lalu menunjuk meja laptop di sudut ruangan yang terus bergoyang, hampir runtuh. Ketika kutanya, “Bagaimana cara memperbaikinya?”, lelaki itu menghilang. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup seperti sirene. Sebuah mimpi buruk? Atau pesan yang terlalu simbolis untuk sekadar ditertawakan?
Keesokan paginya, ancaman pertama datang dalam bentuk paling sederhana: amplop putih tanpa nama, diselipkan ke bawah pintu kos. Di dalamnya hanya satu lembar kertas: “Keluarga itu segalanya. Jangan korbankan mereka untuk sesuatu yang kamu sebut kebenaran.” Huruf-hurufnya dicetak rapi, tak ada sidik jari, tapi baunya: amis ketakutan.
Kupandangi amplop itu lama sekali. Lalu kubakar. Api kecil di asbak menyala seperti lidah setan yang tengah bersenandung. Aku mulai memahami: kebenaran tidak hanya mengusik para pelaku, tapi juga menggoyang tiang rumah orang-orang biasa yang memilih diam demi hidup normal. Dan diam, aku sadari, adalah mata uang paling berharga di negeri ini.
Sore harinya, aku ditelepon Ibu. Suaranya serak. “Tadi ada orang nyari kamu ke rumah. Nggak ngaku siapa. Bilangnya teman kantor. Tapi kenapa wajahnya kayak… preman, Din?”
Aku tercekat. “Bu, maaf. Kalau bisa jangan terima siapa pun yang datang. Bilang saya kerja di luar kota.” Ibu mengangguk, lalu suaranya lirih, “Kamu kenapa, Nak? Jangan macam-macam.”
“Aku nggak macam-macam, Bu. Aku cuma nyoba jujur.”
Diam di ujung telepon terasa lebih keras dari teriakan.
Aku mulai merasa diawasi. Sepulang kantor, motor bebekku dua kali hampir diserempet. Di halte bus, seseorang duduk terlalu dekat dan berbisik lirih, “Tulisan bisa berbalik jadi peluru.” Bahkan di kantor, Pak Drajat—yang biasanya santun—tiba-tiba mengirim pesan:
“Saya sarankan kamu cuti. Istirahat. Jangan terlalu capek mikirin negara.”
Dan benar saja, dua hari kemudian SK cuti “dengan alasan pemulihan mental” terbit atas namaku. Aku tertawa pahit. Mereka mencoba membuatku tampak gila. Mungkin itu cara termudah menghabisi kebenaran: mencapnya sebagai halusinasi.
Aku pulang ke kos. Duduk di depan meja laptop. Meja itu kini semakin ringkih. Terdapat goresan-goresan halus di atas permukaannya, seperti luka kecil yang tak kunjung sembuh. Tetapi di sanalah, di atas papan palsu itu, aku menemukan satu-satunya ruang di mana aku masih bebas menjadi manusia yang tak berbohong.
Di sela hari-hari cuti itu, aku menyempurnakan naskah panjangku: laporan setebal 97 halaman berjudul “Engsel Negara: Investigasi Fiktif tentang Proyek Fiktif”. Di dalamnya, aku memetakan alur uang, mencocokkan dokumen pengadaan dengan catatan lapangan, menyisipkan foto-foto, bahkan membuat rekonstruksi visual menggunakan data terbuka.
Tulisan itu kulengkapi dengan kata pengantar:
“Ini bukan fiksi. Tapi karena kebenaran begitu asing di negeri ini, maka aku menyamar sebagai fiksi agar kalian mau membacanya.”
Dokumen itu kukirim ke tiga redaksi media independen, dua LSM antikorupsi, dan satu kanal YouTube investigatif yang sering membuka kasus besar. Kali ini aku pakai nama asliku: Adinara Dwi.
Kali ini, aku ingin mereka tahu: bahwa seorang staf biasa pun bisa jadi penyambung yang retak—dan bisa juga menjadi keretakan yang memulai reruntuhan.
Keretakan yang Membuka Jalan
Dua hari setelah naskah “Engsel Negara” tersebar, dampaknya meledak seperti luka yang dibuka paksa: tak tertahankan dan menjijikkan. Media-media arus utama mulai mengutip paragraf demi paragraf, meski berhati-hati: “Sumber anonim mengungkap pola pengadaan fiktif di sejumlah kementerian teknis.” Kanal YouTube investigatif memuat potongan narasi visual dari dokumenku: grafik alur uang, wajah-wajah pixelated para pelaku. Nama Adinara Dwi disebut sekilas, tanpa foto, hanya: “Diduga mantan pegawai di salah satu direktorat teknis.”
Namaku mulai bergema, bukan sebagai pegawai rendahan seperti dulu, tapi sebagai pengungkap skandal. Itu membuatku lebih takut dari sebelumnya. Karena dalam sistem yang busuk, orang baik bukan dihargai, tapi dimusuhi.
Di hari keempat sejak publikasi, aku resmi dinonaktifkan dari kementerian. Suratnya dikirim via email, berjudul kering: “Keputusan Penonaktifan Pegawai atas Dasar Etik dan Keseimbangan Institusi.” Aku tak tertawa, tak menangis. Aku hanya menatap layar, lalu menoleh ke meja laptop. Di situlah semuanya dimulai.
Hari yang sama, sebuah mobil hitam berhenti di depan kosku. Tiga orang turun. Dua berpakaian sipil. Satu berbadan besar. Mereka menenteng map dan dokumen. Mereka menyebut diri dari “Satuan Tindak Pidana Siber”. Tuduhannya: penyebaran informasi yang meresahkan dan manipulasi data pengadaan. Dengan kalimat panjang dan datar, mereka berkata: “Anda kami bawa untuk pendalaman.”
Interogasi bukan sekadar tanya-jawab. Ia adalah seni menyayat perlahan. Selama enam jam aku ditahan di ruangan ber-AC dingin, mereka memainkan banyak peran: dari yang sok bersahabat, lalu menjadi agresif, kemudian kembali lunak. Mereka tidak marah, tapi memelintir kata-kataku sendiri.
“Jadi, Anda mengaku bahwa Anda bukan pakar pengadaan?”
“Tidak. Tapi saya membaca dan mengamati cukup lama.”
“Lalu, kenapa Anda berani menyimpulkan ada korupsi?”
“Karena datanya saling menyambung.”
“Tapi apakah Anda tahu betul prosedur audit?”
“Apakah mereka tahu cara membedakan server dan kardus kosong?”
Suasana mengencang. Mereka mencoba memaksa mengakui bahwa naskahku adalah rekaan jahat, provokasi, bukan hasil pengamatan. Aku bertahan. Di antara jeda, aku hanya ingat satu hal: Meja Laptop itu. Seandainya aku roboh, semua yang kutulis akan ikut tumbang. Aku tak mau jadi bagian dari generasi yang melunakkan lidah karena takut kehilangan pekerjaan.
Setelah jam ketujuh, aku dilepaskan “sementara”, dengan syarat wajib lapor dan tidak boleh keluar kota. Mereka belum punya cukup alasan hukum menahanku. Tapi pesan itu jelas: “Kami bisa kapan saja.”
Malamnya, aku kembali ke kos. Lampu sudah padam. Di atas meja laptop, ada surat kecil yang ditinggalkan Sari—ia satu-satunya yang masih sering datang diam-diam:
“Din, aku tahu kamu takut. Tapi takutmu itu tulus. Dan ketulusanmu menular. Aku dan beberapa kawan berencana mengungkap lebih banyak. Jangan mundur. Kau engsel, tapi bisa jadi pintu.” —Sari
Aku menangis pelan malam itu. Di luar, hujan turun. Suara rintiknya seperti langkah kaki banyak orang yang akhirnya bergerak bersama.
Minggu berikutnya menjadi seperti arus balik yang tak bisa dicegah. Komisi resmi memanggil lima pejabat teras untuk diperiksa. LSM mendesak pembekuan dana program digitalisasi desa. Satu demi satu laporan pengadaan diminta ulang. Nama-nama fiktif terbongkar. Sebuah jembatan di Flores yang tak pernah dibangun tapi menghabiskan dana miliaran akhirnya jadi sorotan nasional.
Tapi yang paling mengejutkan: Pak Drajat ditangkap. Bukan hanya karena korupsi, tapi juga intimidasi saksi dan pemalsuan laporan. Ia diborgol saat hendak kabur ke negara tetangga. Berita itu viral. Salah satu kanal menyebut: “Penangkapan ini dimulai dari satu artikel fiksi berjudul ‘Meja Laptop’.”
Di momen itu aku sadar: kata-kata ternyata bisa jadi peluru. Tapi peluru yang menembus bukan tubuh, melainkan sistem. Dan meja itu, benda murah dari pasar loak, menjadi monumen kecil dari perlawanan senyap.
Sisa-Sisa Papan Palsu
Tiga bulan sejak tulisan itu tayang dan menggemparkan, hidupku tidak kembali normal. Tapi, aku juga tidak menyesal.
Aku kini tinggal sementara di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kos lama terlalu banyak disusupi jejak. Meja laptop kubawa, meski kini satu kakinya benar-benar patah. Kutopang dengan tumpukan buku hukum dan anggaran negara. Meja itu tak lagi bisa dilipat, tak bisa dibawa ke mana-mana, tak praktis seperti dulu. Tapi aku tak mau membuangnya. Ia seperti saksi bisu dari pertarungan sunyi yang akhirnya meledak menjadi arus kebenaran.
Kadang-kadang aku berpikir, jika tidak membelinya di pasar loak sore itu, mungkinkah semua ini tak terjadi? Tapi seperti kata dosen filsafatku dulu: “Segala yang tampak kecil bisa jadi pangkal kekacauan besar. Atau keadilan yang tak direncanakan.”
Aku kini tak punya penghasilan tetap. Tapi beberapa organisasi media dan lembaga antikorupsi memintaku menulis, menjadi narasumber, bahkan merancang sistem transparansi anggaran berbasis komunitas. Aku menolak beberapa tawaran yang terlalu bersponsor. Aku ingin tetap berjalan tanpa dikendalikan.
Sari kini bekerja di NGO yang memantau proyek digitalisasi desa. Kami masih sering bertukar dokumen, kadang obrolan tentang harga tomat, kadang juga tentang rasa rindu terhadap hidup biasa—yang kini terasa seperti kemewahan.
Kami sepakat: ini bukan tentang jadi pahlawan. Ini tentang menolak ikut diam. Karena dalam sistem yang membusuk, hanya ada dua pilihan: menjadi bagian dari bau busuk itu, atau menjadi tangan yang mencoba membuka jendela agar udara masuk.
Suatu malam, aku duduk sendiri. Di hadapanku, meja laptop yang sudah tak bisa dilipat. Di atasnya: laptop tua, segelas teh, dan draft tulisan baru berjudul “Negara yang Tak Bisa Duduk Tenang”.
Aku menulis:
“Negeri ini terlalu terbiasa duduk di kursi empuk sambil membiarkan meja rakyat bergoyang tak stabil. Tapi setiap kita yang pernah menulis di atas meja ringkih tahu: kebohongan tak akan lama berdiri, jika papan bawahnya sudah retak.”
Aku berhenti sejenak. Mendengar suara jendela diketuk angin. Hujan turun perlahan. Tidak seperti badai sebelumnya. Kali ini seperti rintik doa.
Aku menoleh ke meja. Dan untuk pertama kalinya, aku menyentuhnya bukan sebagai alat, tapi sebagai teman.
Teman yang diam-diam telah membawaku menuju jalan yang tak pernah kutahu bisa kulewati: jalan kejujuran.
Berliku. Dingin. Sepi. Tapi tak pernah membuatku ingin mundur.
Karena sekarang aku tahu, meja yang ringkih pun bisa menampung keberanian.
Dan dari sanalah semua bermula.
Penulis: Farhan Azizi (Fans MU)