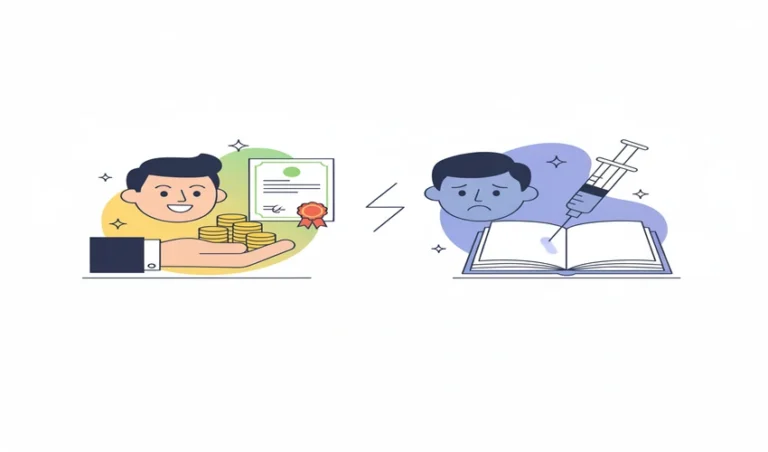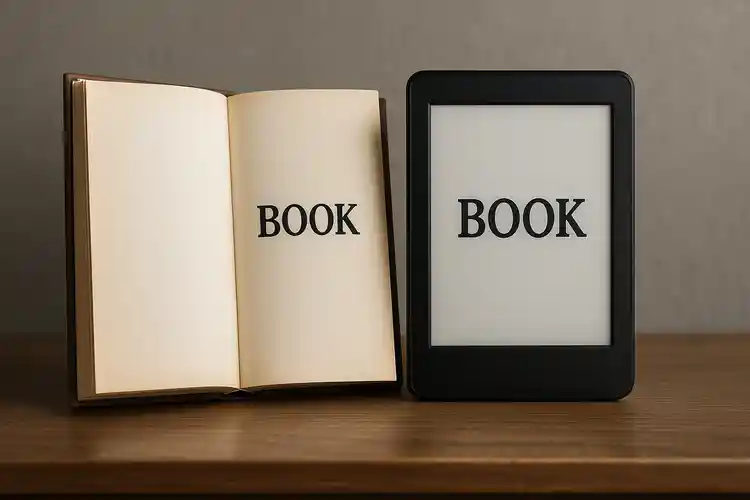Indonesia di Mata Orang Bodoh

Indonesia, di mata orang bodoh, tak lebih dari sepetak tanah yang basah oleh hujan, berdebu oleh kemiskinan, dan berisik oleh kebisingan kendaraan dan pasar tradisional. Di pandangan mereka yang malas membaca, negeri ini adalah tubuh tropis yang digerayangi korupsi, didefinisikan oleh pantai-pantai eksotis, dan dikutuk oleh kebodohan kolektif yang tak selesai-selesai. Mereka menyebut nama Indonesia seperti menyebut kata yang hanya muncul dalam iklan perjalanan murah atau laporan tahunan lembaga donor internasional. Tapi siapa yang sebenarnya bodoh?
Orang bodoh adalah mereka yang menyamar dalam jas akademik dan berdasi diplomatik, namun melihat dunia dari lembaran statistik buta dan grafik pembangunan ekonomi yang tak pernah menyentuh tanah. Mereka membaca Indonesia dari atas Google Maps, lupa bahwa yang tampak dari langit hanyalah garis-garis patah yang menyembunyikan sejarah luka, perjuangan, dan daya tahan. Di balik garis itu ada Sriwijaya yang tenggelam dalam sunyi, ada Majapahit yang dipecah kolonialisme, dan ada republik yang dibangun dari bara kemerdekaan, bukan dari resep demokrasi instan.
Mereka mengira Indonesia adalah satu kota bernama Jakarta. Mereka menyangka seluruh rakyatnya memakai sarung di pagi hari dan menari di malam hari, padahal mereka tak tahu betapa kerasnya para nelayan di Pantai Selatan bertarung dengan ombak yang mengabaikan upah minimum, atau bagaimana petani di lereng Merapi hidup dalam ketakutan karena letusan yang tak pernah diumumkan oleh media internasional.
Mereka berbicara soal Indonesia hanya saat ada gempa bumi atau kasus korupsi besar. Mereka lupa—atau sengaja lupa—bahwa setiap kali ada bencana, warga Indonesia membangun tenda bukan karena negara absen, tapi karena masyarakatnya belajar sejak lama: bertahan hidup bukan soal menunggu negara hadir, tapi soal gotong royong yang tumbuh dari trauma sejarah.
Jika Indonesia dianggap gagal, maka ukuran keberhasilan yang dipakai hanyalah salinan dari buku teks yang ditulis oleh mereka yang pernah menjajah dan kini mengaku peduli. Mereka menyebut pemerintahan sehat hanya jika mengikuti resep reformasi ekonomi IMF, padahal lupa bahwa “kesehatan” di sini bukan soal anggaran defisit atau surplus, melainkan kemampuan untuk bertahan hidup tanpa menyerah pada kepalsuan.
Indonesia bukan citra eksotis dalam brosur turis atau studi kasus lembaga think tank. Ia adalah wajah perempuan di Papua yang tetap sekolah meski jarak dari rumah ke kelas adalah lima jam berjalan kaki. Ia adalah buruh pabrik yang berteriak menolak upah murahan, sementara dunia hanya ingin tahu apakah pabrik itu bisa mengirim barang tepat waktu. Ia adalah petani Kendeng yang menyemen kaki mereka demi mempertahankan tanah dari mesin semen yang diberkati izin resmi.
Mereka menertawakan demokrasi Indonesia, menyebutnya teater murahan, lupa bahwa panggung yang mereka banggakan di negara sendiri pun penuh aktor korporat dan skenario kapitalis. Mereka bicara soal keterbelakangan, padahal tak pernah membicarakan siapa yang memperlambat: siapa yang menghisap nikel tanpa transfer teknologi, siapa yang mencaplok hutan dan menggantinya dengan janji kerja yang tak pernah tetap.
Indonesia yang mereka lihat hanyalah siluet yang dipantulkan oleh televisi dan statistik. Mereka tak melihat kompleksitasnya, karena mereka hanya mau melihat kekacauan. Mereka tak peduli pada keanekaragaman 700 bahasa, karena tak ada algoritma yang bisa menterjemahkan solidaritas, ritual, dan nilai-nilai komunal yang tak kapitalistik. Mereka tak bisa memahami kenapa orang Indonesia tetap tertawa di tengah krisis, karena mereka tak kenal budaya yang memelihara harapan bukan dari kenyamanan, tapi dari keteguhan.
Mereka menilai Indonesia dengan ukuran negara-negara yang pernah mengklaim membawa pencerahan, tapi lupa bahwa pencerahan juga bisa berarti pembakaran rumah, pencurian rempah, dan penghilangan nama-nama lokal dari peta sejarah. Mereka ingin Indonesia tunduk pada satu jenis modernitas, padahal Indonesia sedang menciptakan modernitasnya sendiri: yang tak membunuh adat, yang tak menghapus gotong royong, yang tak menjadikan manusia sebagai angka dalam sistem pinjaman internasional.
Orang-orang bodoh yang memandang rendah Indonesia sejatinya sedang menertawakan diri mereka sendiri. Karena yang mereka tak mampu lihat adalah bahwa negeri ini tidak sempurna, tapi punya arah. Bahwa rakyatnya marah, tapi tak menyerah. Bahwa pemerintahnya bermasalah, tapi juga sedang berproses. Dan bahwa negara ini bukan tentang kecepatan mengejar indeks, tapi tentang bertahan hidup dalam sejarah panjang yang belum selesai.
Mereka menyebut Indonesia “negara berkembang”, seolah negeri ini sedang mengejar ketertinggalan. Padahal, siapa yang sedang tertinggal sebenarnya? Mereka yang tak mampu memahami negeri sebesar dan seberagam ini, atau Indonesia yang terus mencoba menyatukan ribuan pulau dengan satu nyanyian dan seribu cerita?
Indonesia di mata orang bodoh adalah wajah yang mereka tempelkan sendiri: penuh cemooh, dipoles prasangka, dan dicetak dalam bingkai kolonial yang belum pecah. Tapi Indonesia yang sejati tidak menunggu dipahami oleh mereka. Ia terus berjalan, dengan kaki yang luka, dengan tangan yang penuh tanah, dengan kepala yang kadang bingung, tapi tetap mendongak ke langit. Dan langit itu, meski mendung, tetap milik mereka yang tak pernah menyerah menyebut diri mereka sendiri: orang Indonesia.